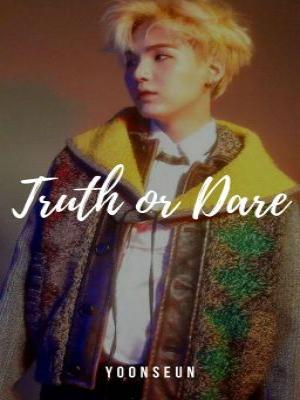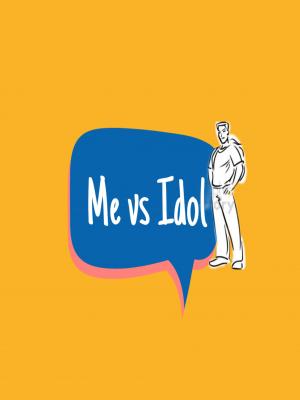Part 19. Dua Part Akhir
Untung aja Bu Widi kemarin kasih kabar bahagia. Membuatku setidaknya masih punya sedikit semangat hidup. Bulan depan akan menjadi bulan dimana salah satu impian terbesarku terwujud. Tapi, fakta tentang Nino tadi, masih terasa menyesakan dada.
Sepulang dari Mall, aku menuju rumah Gina.
"Lo kenapa, Lun??" Udah nggak sesenggukan sih, cuma mataku sembab memerah.
"Lo sih, nggak ikut gue tadi!"
"Yaaah... Lo kan tahu situasi gue. Kenapa sih? Nino lagi??"
Aku mengangguk. "Lho, katanya lo udah damai sama dia?"
"Salah gue sih ya, tolol banget gue masih ngehubungin dia!" Air mataku di ujung mata mulai kembali menetes.
"Hmm... Lo masih ada rasa ya sama Nino? Dan Nino, nggak? Gi-tu?"
"Sampe tadi gue abisin burger gue, iya, gue masih sayang sama Nino. Tapi, setelahnya... Huft!" Aku menghela nafas.
"Hah? Apaan si? Kok segala burger dibawa- bawa?"
"Si Nino bawa itu cewek, Gin. Hanny namanya. Semalem juga, dia yang angkat handphone-nya Nino."
"Semalem? Jadi, tadi Lo itu ke Mall, dan ketemuan ama Nino, gitu?"
Aku mengangguk. "Kata lo cuma kita berdua yang bakal ngerayain novel lo?" Ketawan deh sama Gina kalau aku bohong.
Aku nyengir. "Au ah! Salah lo sih ini, mutlak! Lo yang sengaja cari perkara duluan, dengan ngontak dan ngajak Nino ketemu."
"Iyaaaa, Gin, iya. Yaa... Habis, gue pikir Nino udah berubah, udah nggak ngeselin lagi. Eeeh! Mana gue tau bakal ada itu cewek."
Gina diam dan mendelik ke arahku.
"Gue pikir juga, gue cukup setrong dan sanggup ketemuan sama cewek itu..."
"Hanny?"
"Ho’oh"
"Sebut dong namanya! Cewek itu, cewek itu mulu. Udah! Sekarang gue nggak mau denger lagi tentang lo sama Nino! Dan lo, biasain sebut namanya Hanny! Biasain diri lo, kalau Nino sekarang udah punya cewek lain! Oke?!"
Aku diam sesaat. "Masalahnya, mereka udah berhubungan semenjak gue sama Nino masih Nikah, Gin..." Ucapku lirih.
Sabahatku yang berambut pendek sekuping itu kemudian mendongak kaget ke arahku.
"You sure?" Jawabnya juga lirih.
"No, I'm not." Aku menggeleng. "Tapi gue punya alasan buat menduganya. Lagipula, kalau iya pun, mana ada sih maling ngaku." Lanjutku. Sekarang gantian Gina terdiam.
"Gin, Sorry ya, kalau masalah hidup gue, malah jadi beban lo. Gue curhat mulu kerjaanya..."
"Iya, hidup lo pelik amat, sih." Tutur Gina sembari ikut bengong.
Setelah beberapa menit kita saling diam. Karena bingung juga kali ya mau ngomongin apa lagi. Aku pun mending pamit pulang, sudah hampir gelap juga langit di luar sana.
"Eh, Lun! Kalau temen Bule lo yang di Bali itu, apa kabar?"
Hadeuuh... Gina! Pake tanya soal Charlie lagi. Bikin nambah patah hati deh.
"Charlie?"
"Yes! The bakery man."
"Pastry! Dia, lagi! Udah kelaut, Gin. Udah beberapa bulan ini handphone-nya mailbox terus." Jawabku sambil menahan gagang pintu kamar Gina.
"Oh." Gina cuma manggut-manggut.
Lalu aku kemudian pulang.
***
Ayah sedang nonton TV bersama adiku saat aku pulang. Sembari mengambil makan malam. Kubuka sedikit pembicaraan.
"Kapan jadwal kontrol ke rumah sakit lagi, Yah?"
"Minggu depan. Kamu anterin Ayah, ya?"
"Iya."
"Eh, kata Ayah, novel lo mau terbi,t ya?" Kata Karin tiba-tiba.
"He’em." Aku sibuk mengunyah.
"Selamat yaa... Nanti gue dapet dong gratisanya?"
"Beli lo! Gratisan mulu!" jawabku.
"Hahahaha... Iya, nanti ayah sama Karin beli ya. Terus, next plan kamu apa?" Kata ayah.
"Nanti kalau udah terbit, biasanya akan launching ke toko buku di beberapa kota. Paling setelahnya, Luna akan lanjut nulis lagi.
"Kamu nggak mikirin akan cari pengganti Nino?"
GUBRAK! Buset, Yah! Baru aja mencapai satu target. Udah disuruh nyari target pasangan hidup yang baru lagi. Yaa... Begitulah dia, ayahku, hidupnya tidak pernah tanpa target. I guess, I get use to it.
"Belom kepikiran, Yah. Luna lagi seneng nulis dulu aja. Ngejalanin pekerjaan yang Luna suka." Padahal, alasan sebenarnya adalah, Luna baru tau penyebab utama kenapa Nino menceraikan Luna. Dan, Luna baru aja ketemua sama selingkuhannya, Yah.
"Nanti, kalau kamu sudah kepikiran. Semoga awet, cari yang benar-benar bisa menerima kamu. Dan kamu juga harus bisa menerima dia apa adanya."
Aku manggut-manggut.
Families forgive. Karena keluarga itu layaknya drugs. Dan kita semua di dalamnya adalah pecandunya. Seberapa benci kita pada obat itu, seberapa jauh kita lari dari pengaruhnya, kita tidak akan pernah bisa benar-benar bersih dan lepas dari statusnya.
***
Hari ini aku mengantar Ayah kontrol. Katanya gips di kakinya bulan depan sudah bisa dilepas. Dengan memaksakan dirinya menggunakan tongkat yang lebih kecil, membuat proses penyembuhannya lebih cepat, sepertinya. Aku dan ayah kemudian sekarang sedang berada di dalam mobil. Beberapa teman bilang, gaya menyetirku seperti laki-laki. Ngebut, selap-selip. Aku tetiba ingat, karena memang ayahlah yang mengajariku dulu. Saat aku berhasil menjadi juara kelas sesuai dengan keinginannya.
“Mau mampir makan siang dulu, Yah?”
Aku jadi merasa lebih melayaninya ketimbang menjadi anakanya. Mungkin aku tidak pernah tahu bagaimana cara bersikap yang baik dengan pasangan ataupun orang tua. Karena aku merasa tidak pernah mendapatkan contoh yang cukup.
“Boleh. Nasi padang aja, mau?”
“Iya, boleh.”
Aku membelokan mobil, parkir di salah satu restoran masakan padang di pinggir jalan. Seperti rumah makan padang lainnya, hampir semua lauk tersaji di meja. Ada cumi, macam-macam balado, rendang, dan lainnya. Ayah mengambil rendang dan telor dadar. Aku memilih gulai otak dan daun singkong. Makan masakan padang pakai tangan itu nikmat sekali
Kita tidak banyak bicara. Tapi, kalau ayahku sedang tidak ceramah menyinggung masalah pribadiku, aku merasa kalau kita sedang berdamai. Memangnya, kita sedang perang? Iya, aku merasa kita sedang dalam perang ego. Ego sebagai ayah dan ego sebagai anak. Seusai makan, kita pun melanjutkan perjalanan pulang.
“Ayah udah ada rencana kapan mau masuk kantor lagi?”
“Dua minggu lagi mungkin. Habis kontrol selanjutnya, kalau kata dokter boleh, ya Ayah ngantor.”
“Ayah nanti kalau pensiun mau ngapain?”
Dia diam sesaat. “Belum tahu.”
Aku juga kemudian diam. Bingung mau bahas apa lagi.
“Mau gendong cucu sih enaknya, ya.” Kalimatnya nyebelin sih ya. Tapi dia mengucapkannya dengan nada yang ringan dan sedikit senyuman di bibirnya.
“Cucu?? Dari Karin apa Luna?” Aku menimpali jokes-bapak-tua itu sebisanya.
“Yaa... siapa aja yang duluan, deh.”
Aku tersenyum.
Ketika seorang anak merasa sedih, tersinggung, atau bahkan tersakiti oleh orang tua. Mereka tidak menginginkan banyak. Mereka cuma butuh mendengar satu kata, maaf. Tapi ketika mungkin satu kata itu saja tidak bisa mereka dengar, mereka tetap tidak dapat membenci. Karena dengan niat baik mencairkan suasana saja, pelan-pelan, hati mereka akan ikut mencair. Pelajaran tersulit bagi seorang anak adalah, memaklumi yang dulu menjadi pahlawan mereka, idola mereka, ternyata juga manusia, yang punya kelemahan dan keburukan. Then they have to deal with it.
***


 Eno_wid
Eno_wid