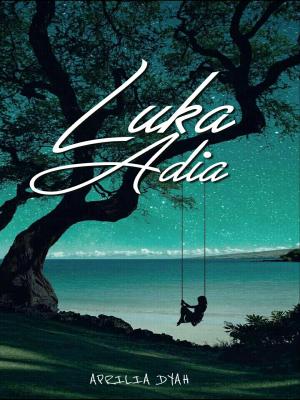Part 18. I’m Ready to Fly
1. Judul, coret! Ganti pakai bahasa Inggris. Remember, harga french fries lebih mahal dari pada kentang goreng.
2. Bab 3, halaman 20, paragraf 8, ganti dengan adegan yang lebih realistis.
3. Perhatikan setiap tanda baca di tiap dialog. Harus sesuai dengan nada bicara aslinya.
4. Bab 8, halaman 90, paragraf 3, dihapus, dirubah. Jangan kasih tahu perasaan tokoh, tapi kasih lihat lewat adegan.
5. Karakter orang ketiga kurang, lebih di perkuat lagi.
And so on... And so on... Ada belasan koreksi kurang lebih yang Bu Widi corat coret dari naskahku. Sudah seminggu ayah pulang dari rumah sakit. Aku sekarang sama sekali sedang tidak menyambi menulis artikel. Ya, karena aku sama sekali tidak punya bahan. Aku hanya sedang fokus merampungkan koreksi yang diminta oleh Bu Widi, ASAP. Si Ibu ASAP ini minta semua revisi kelar dalam tiga hari. Yaa, masih untung juga sih, setelah dua bulan aku menghilang, kemarin dia masih ingat padaku saat aku datang ke kantornya.
Kreeek.
Suara pintu kamar mandi ku dengar terbuka. Aku menunggu beberapa detik. Lalu terdengar suara kayu berbantalan karet bersentuhan dengan lantai.
"Mbaak!" Bener kan suara Ayah.
"Iya, Pak." Jawab si Mbak. Aku masih memantau keadaan lewat suara yang kudengar dari dalam kamar.
"Tolong ambilin handuknya Bapak, di jemuran. Mau mandi, lupa bawa handuk." Tak ada jawaban dari si Mbak. Pasti dia sedang lari mengambil handuk di jemuran belakang.
Lalu, KLOTAAK.
Aku sontak keluar kamar. "Kenapa, Yah?" Dia tidak menjawab. Ternyata hanya suara tongkat yang jatuh. "Bisa sendiri, Yah?" Tanyaku lagi. "Bisa." Jawabnya mantap.
Mendengar egonya. Aku pun memilih kembali masuk kamar. See? Orang yang pertama dipanggilnya itu si Mbak. Bukan aku, anak pertamanya. Tidak ambil pusing. Aku melanjutkan mengetik. Besok aku sudah harus balik lagi ke Kanayas. Bersiap-siap di corat-coret lagi naskahku. Tidak lama kudengar pintu kamar mandi terbuka lagi. Ayah memilih memakai tongkat tunggal berbahan kayu yang bentuknya menyeruapi kait setinggi pinggangnya. Padahal, dokter menyarankanya memakai tongkat besi setinggi pundaknya untuk membantunya berjalan. He forces his self as alwaysl. Whatever! Up to him.
Kemudian, KLOTAAK! Lagi.
Aku tidak langsung keluar kamar. Ayah terdengar menggerutu, memaki-maki. Perasaanku tidak enak. Setengah terpaksa aku keluar kamar, ingin tahu. "Kenapa lagi, Yah?" Dia tidak menjawab. Ternyata tongkatnya jatuh lagi di kamar. Dia kayaknya sedang mau mengambil pakaian, dan tidak bisa membungkuk ke lantai untuk mengambil tongkatnya yang jatuh. Kalau aku orangnya gengsian, tahu kan darimana nurunnya?
Aku mengambilkan tongkatnya. Sedangkan dia duduk di kasur. Aku juga lalu mengambilkannya baju di lemari.
"Yang ini?"
"Iya, boleh. Makasih, ya." Aku kemudian mengangguk, dan kembali ke kamar.
Hampir semua aktifitas ayah lakukan di kamar. Dia makin murung. Dia seperti menyesali keterbatasannya setelah jatuh kemarin. Keluarga Omku kemarin sempat datang menjenguk. Lumayan, dia ada teman ngobrol seharian. Bukannya aku tidak mau membantunya ya, tapi, dia lebih sering memanggil Mbak ketimbang aku. Atau kadang adikku. Rasanya, untuk apa menolong, kalau kehadiranmu saja seperti tidak dianggap. Bayangan harimau itu sedang datang menghampiriku.
Aku tahu, dia ayahku. Ayah kandungku. Apa aku anak yang durhaka? Ah, mana kutahu. Aku hampir lupa rasanya memiliki harimau yang kapan saja siap membelaku, siap menyemangatiku, siap memujiku. Sekarang harimau itu sudah renta dan sedang dimakan ego kejantanannya sendiri. Yang mungkin, jika egonya nanti habis, dia juga akan memakanku.
Tidak ada perceraian yang mudah. Begitupun dengan kasusku dan mantan suami. Kadang kubayangkan, apa yang telah ayah lalui dengan perceraiannya dan dia harus membesarkan dua anak perempuan. Padahal dia adalah seorang laki-laki tulen. Mungkin dia hanya tidak bisa membayangkan rasanya jadi perempuan. Dan dia termakan ketakutannya sendiri untuk gagal. Padahal tanpa ketakutannya, kedua putrinya sudah baik-baik saja.
Seharusnya dia menghapus dendamnya terhadap Ibu. Dia merasa dicampakan, merasa dibohongi, oleh Ibu. Aku juga merasakan hal yang sama dengan mantan suamiku. Tapi aku bisa memaafkannya. Karena aku sadar, dengan membenci, I got nothing. Aku lebih memilih melupakan dan memulai semuanya dari awal, ketimbang bersaing dengan egoku.
"Luna!" Ayahku teriak dari kamarnya. Nadanya tinggi, tapi aku malah senang. Aku dipanggil olehnya. Dia sadar aku ada. Dia mungkin membutuhkanku.
"Iya, Yah?" Langsung kutinggalkan tulisanku dan berlari ke kamarnya.
"Tolong ambilin remote TV, dong. Tadi kesenggol, jatoh ke kolong kasur."
"Oooh... Bentar." Aku langsung nungging, lalu tiarap, meraba-raba kolong kasur.
"Ini."
"Makasih, ya."
"Ada lagi?"
Ayah menggeleng. Aku tersenyum. Lalu kembali ke kamar. Melanjutkan menulis.
***
"Oke, udah lebih bagus, nih. Tinggal ini di bab terakhir, kamu yakin ending-nya mau gini?" Kata Bu Widi. Serasa sedang asistensi skripsi deh jadinya.
"Iya, Bu. Emang bagusnya gimana, ya?"
"Hmm... Gini juga nggak apa-apa sih. Cuma menurut saya, kamu nggak main aman di sini. Pembaca biasanya lebih suka kalau si tokoh utama balikan dengan cinta lamanya ketimbang menemukan cinta baru. Tahu Cintapucino, kan? Yaa... biasanya yang macam begitu yang disukai pembaca. Makanya dulu, dia laris kan novel sama filmnya."
Aku manggut-manggut. "Apa mau saya rubah lagi aja, Bu?"
Dia menggeleng datar. "Satu pertanyaan lagi. Kenapa kamu milih ending-nya kayak gini?"
Aku terdiam. Entah kenapa malah kutekan-tekan kuku jariku. Bu Widi menaikan alisnya, menanyakan kembali jawabanku.
"Because, this is my story. And that is what I’ll do for end up my story."
Bu Widi tersenyum. "OKE! Kita buat cover, buat blurb, terus nanti kita diskusi buat pemilihan cover-nya. Bulan depan lah, kita launching."
***
Aku menyampaikan kabar gembira ini ke ayah yang sore itu sedang ngopi di teras depan sepulang aku dari Kanayas.
"Selamat ya! Semoga laris novelnya. Nanti ayah beli." Satu kalimat yang membuatku lebih damai berada di rumah.
"Gina! Lo dimana? Jalan yuk!" Aku langsung menelepon Gina. I need a little celebration!
"Di rumah. Minggu depan gue kawin, Gila lo masih ngajak gue jalan!
"Masih jaman lo dipingit? HAHAHA..."
"IYE! Lo aja sini ke rumah gue."
"Males ah! Dikupingin nyokap lo nanti obrolan kita. Udah, Mall deket rumah ya, besok jam makan siang!"
"E, eh! Ntar dulu! Maen ngemol aja. Nggak janji ya gue."
"Telepon yang anda tuju di luar...." Aargh!! Damn you, Charlie! Ini orang kemana sih?! Oke, kalau dia punya pacar baru, its oke. Tapi, nggak perlu ganti nomor, kan. Aku cuma ingin menceritakan kabar baik ini. Aku hanya terlalu bahagia. Rasanya ingin kutelepon semua orang, mengumumkan bulan depan novelku akan terbit dan muncul di toko-toko buku. Mengalihkan adrenalinku dengan mencoba bercerita kepada semua teman, ketimbang macam orang gila yang lompat-lompat di atas kasur.
Kupikir tadi Bu Widi masih akan memberiku revisi lagi. Tak kusangka secepat itu dia meng-ACC naskahku. Hanya dengan dua kali asistensi, eh revisi maksudku.
"Hallo, Nino..." Nino pernah bilang kan kalau aku boleh meneleponnya kapan saja. Dan aku hanya ingin mengabari dia, betapa bahagianya aku.
"Hallo..." Hampir kututup teleponya saat seketika kudengar suara perempuan malah yang menjawab.
"Eh, ini nomor hape-nya Nino, kan?" Takutnya aku salah pencet tombol tadi.
"Iya. Ninonya lagi mandi. Ada pesen?" What?? Ini udah malem gitu loh. Setahuku Nino jarang mandi sepulang kerja. What have they do?
"Ini... Hanny, ya?" Kuberanikan bertanya. Walau nada suara si perempuan itu selembut sutra, tapi buatku lebih mirip suara petir di tengah malam.
"Iya. Luna, ya?" Nino ternyata masih menyimpan namaku di phonebook-nya. Nggak tahu juga ya, namaku disimpanya dengan nama apa. Cukup 'Luna' saja. Atau, 'Mantan Istri.' Atau, 'Awas anjing galak.' Atau, 'Mantan terindah.' Oke, Whatever tentang namaku.
"Iya." Nino lagi ngapain ama Hanny ampe malem-malem mandi?? Come on Luna, you slept with Charlie. Terus kenapa kalau Nino ngelakuin hal yang sama. Inget! no more drama kan, janjinya.
"Kenapa, Lun? Ada yang bisa gue sampein ke Nino?" Nih cewek tenang banget ya. Kemudian selintas terngiang, "She changed me" yang Nino pernah bilang. Dengan pembawaan setenang ini angkat telepon dari mantan istri pacarnya, I guess, she did can changed Nino.
"Oh. Nggak. Cuma mau ngajakin kumpul aja besok di Mall deket rumah. Tolong bilangin, da Gina juga kok. Yaa... Reunian kecil, gi-tu-lah."
"Oh, oke. Jam berapa acaranya?"
"Jam makan siang."
"Siap. Nanti pasti gue sampein ke Nino, ya.”
Telepon kututup. Oh Tuhan, kenapa sesak ini muncul lagi.
***
Aku ijin pakai mobil Ayah lagi. Kujemput Gina ke rumahnya. Ayah beruntung, di usianya yang mendekati pensiun, dia diijinkan dengan mudah untuk tidak masuk kantor beberapa bulan. Jadi, mobil nganggur ini, kumanfaatkan saja.
"Gina, ayo doong. Pliisss!! Itung-itung ngerayain keberhasilan gue. Gue traktir deh..." Bujukku.
"Duh, sorry banget, Lun... Nggak bisa keluar gue. Kalau abis nikah, minggu depan, malah bisa gue. Ama Ical mah, bebas. Lagian, kan masih bulan depan novel lo terbit. Minggu depan abis gue nikah aja, gimana?"
Aku bete. Sebetulnya bukan masalah Gina nggak bisa sih. Tapi lebih gengsi mau ngebatalin janji ke Nino. Mana nanti kalau nelepon lagi, belum tentu Nino langsung yang angkat, kan. Nino emang nggak pernah ngerahasiain handphone-nya ke pasangan sih. Dulu juga dari waktu kita pacaran, sampai nikah, aku bebas membuka-buka handphone-nya.
Aku maju dari rumah Gina dengan mulut manyun. Aku tidak bilang ke Gina kalau aku semalam menelepon Nino-setelah sadar aku telah melalukan hal bodoh itu, dan aku nggak mau jadi bahan ledekan Gina.
Akhirnya, aku melajukan mobilku ke Mall tersebut. Bukan Mall besar. Aku mulai memesan makanan cepat saji saja. Berharap Nino tidak akan datang. Satu paket burger, french fries dan Cola siap kulahap di hadapan. Lumayan, buat makan siang juga, lah. Seketika handphone-ku berdering. Perasaanku berubah tidak enak, agak panik dan tetiba saja jadi kenyang.
"Aku udah masuk Mall nih, di lantai dasar. Kamu dimana?" Bener kan, Nino. Dia emang nggak pernah nggak tepat janji sih. Sama persis seperti ucapanya saat mengajak kita bercerai. Dia tepati itu dengan baik.
"Aku di BK. Sama, di lantai dasar juga. Ke sini aja."
Dua gigitan burgerku terhenti setelah melihat dua pasang sejoli itu berjalan ke arahku. You stupid, Luna! Pakai jadi dateng segala ke Mall! Makiku pada diri sendiri. Nino dengan kaos dan celana pendeknya, menggandeng Hanny dengan setelan jins serta kemeja ngatungnya. Bedanya, kali ini Hanny hanya memakai flat shoes. Kenapa sih, kemejanya harus selalu ngatung. Yang, kalau dia menyibakan rambutnya doang aja, dua senti perut rata-putihnya kelihatan!
"Hai... Mana Gina?" Sapa Nino duluan. Dia sepertinya masih orang yang sama saat terakhir kali kulihat di rumah sakit. Lagi pula, ada Hanny juga, rasanya aku tidak perlu takut untuk bertengkar dengan Nino, ada pawangnya ini. Yeah, si 'Miss Changed Me' ini, kayaknya megang Nino banget, deh.
"Nggak jadi dia. Lagi dipingit." Kataku.
"Hai, Luna..." Aku menyodorkan tanganku
"Hanny..." Aku dan Hanny bersalaman. Agak malu sih, kalau inget waktu itu aku nyiram Nino pake es kopi di depan dia.
"Han, mmh... Sorry ya, waktu..."
"Ooh... It's okay. Santai aja. I know, Nino emang kadang nyebelin, sih." Jawabnya santai. Memotong kalimat maafku. Dan, kalimat akhirnya itu, seolah membuatnya lebih mengenal Nino ketimbang aku. Mantan istrinya sendiri.
Nino mulai agak kikuk. "Mmh, gini sih, tadinya emang gue ngajakin Gina, Ical, Doni juga. Yaa... Mantan anggota genk kita dulu gi-tu, buat kumpul-kumpul aja. Ada kabar bahagia, dikit..." Kataku. Soal mengajak Ical dan Doni itu sih cuma, bualan doang.
"Oh ya, kabar apa?" Tanya Nino.
"Insyaallah bulan depan novelku launching. Yaa... tadinya mau ngerayain gitu. Tapi, karena pada nggak bisa dateng. Yaudah, makan sendiri aja deh di sini, hehehe..." Garing nggak sih aku?
"Wow? Congratulation ya... Apa judulnya?" Tanya Hanny. Nino sendiri cuma senyam senyum aja sedari tadi kulihat dari ekor mataku.
"Sweet Escape." Jawabku.
"It must be so sweet..." Lanjut Hanny. Kerasa banget sih, Hanny kayak berusaha mendekatiku. Berbuat baik padaku. Seperti mengibarkan lebar-lebar bendera damai diantara kita. Padahal, perangnya sendiri saja tidak jelas karena apa, atau dimulai sejak kapan.
Lima-sepuluh menit aku melanjutkan makanku dengan sedikit paksaan-yang eneg juga ya makan di depan mereka. Setelah Nino memesan makanan serupa. Aku akhirnya mulai meng-ACC bendera damai yang Hanny kibarkan.
"Ngomong-ngomong, kalian kenal dari kapan?" Tanyaku pada Hanny.
"Mmh, lumayan lah ya... Dari awal gue masuk law firm, Nino udah ada."
"Oooh... " What a stupid answer, Hanny! Aku menyadari sesuatu. Aku menghentikan sesapanku di sedotan soda yang sedang kuminum. Aku melirik Nino. Nino menyadari sesuatu juga. Dia melihat balik mataku. Dia menggeleng kecil. Tapi itu semua sudah terlambat bagiku. Aku menarik nafas panjang. Persetan dengan 'no drama'!
Hanny belum menyadari apapun. Aku lalu berdiri.
"Congratulation, No! You made it! You made it perfectly!" Aku tidak dapat menahan air mataku yang mengambang seketika begitu saja. Hanny langsung bingung. Stupid Hanny!
"Luna! No drama, pleaaasee..." kata Nino lirih sambil ikut berdiri mencoba menenangkanku. Aku sendiri hanya fokus agar kali ini tidak menyiramnya lagi dengan sisa sodaku. Aku memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Kali ini, serius, amarahku tidak memuncak. Aku hanya sedih sekali. Sakit sekali di dada ini. Nino mengejarku dengan mudah.
"Luna!" Dia menahan tanganku. Menanggil namaku. Tapi tidak memberikan penjelasan apapun.
"Bilang kalau kita cerai buka gara-gara dia, No!" Aku bicara sambil sesenggukan mengusap air mataku sendiri. Bodo amat dilihat orang-orang juga. Hanny masih tetap duduk manis di kursi restoran cepat saji tadi.
"It wasn't." Nino berucap lirih sambil menggeleng.
"But now, for me, YES IT WAS!" Aku mendekatkan tubuhku ke tubuh Nino. Dengan berbisik, pasti, tegas, aku mengucapkannya.
"And now I'm leaving! Thank's." Aku menepuk pundaknya, menyeka air mataku yang kesekian kali, lalu beranjak pergi. Nino bengong, kaget. Macem orang bego.
***


 Eno_wid
Eno_wid