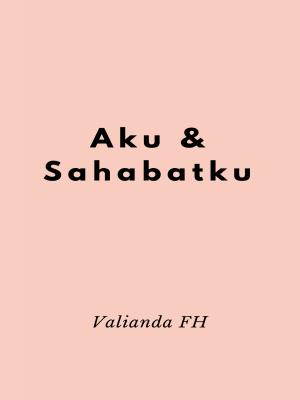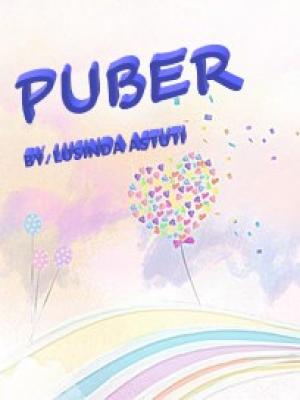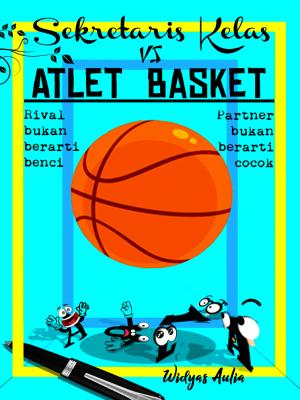Part 14. Obliviate!
Malam itu rasanya lebih gelap. Hujan yang turun dari sore baru mulai reda. Kesekian kalinya aku mendengar suara gaduh itu. Aku mengurung diri di kamar. Ibuku menggendong seorang balita, menenangkannya dari tangis yang tumpah bersamaan dengan air matanya juga. Aku tidak tahu persis dimana posisi mereka berdua. Tapi aku yakin, beberapa menit lalu ada sebuah benda berbahan beling yang baru saja pecah.
Kata ayahku, ibuku salah. Kata ibuku, ayahku peselingkuh. Oh, really, I don't give a care! Terserah siapa yang salah. Aku hanya ingin keluar dari semua hal ini. Bahkan, aku juga tidak pernah memikirkan si balita itu. Aku hanya peduli sama hidupku.
Sepuluh tahun saja aku belum. Tapi air mataku melebihi orang yang patah hati. Lalu, beberapa tahun setelahnya, aku tidak pernah menangis lagi. Karena tidak ada gunanya menangisi orang terkasih yang sudah tidak ada di sampingmu lagi. Hilangnya air mataku, seiring dengan hilangnya bagian dari hidupku juga.
Lalu, kita bertiga menjalani hari-hari yang-biasa aja. Tapi, Ayah adalah pahlawanku. He was my hero. Dia memberi makan aku dan adikku. Dia membantuku mengerjakan PR. Dia mendoktrin aku dan adikku agar menjadi orang yang kuat. Dia membayar uang sekolah, jajan, main, les dan lain-lainya. Dia menampung kami. Anak-anak yang tak beribu.
Kemana ibu? Aku tidak tahu pasti. Kata ayah, mereka bercerai. Sudah itu saja. Jadi ibu harus pergi dari rumah. Sungguh, aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada hidupku. Kemudian aku memiliki pacar. Seiring juga kudengar di telinga, ibuku juga punya pacar-dan kemudian mereka menikah-dan punya anak, lagi. Kecewa? Nggak. They had their choice! And I really don't care about their choice! Sekali lagi, aku hanya peduli dengan pilihanku sendiri.
Aku ketawa-ketiwi dengan teman-temanku, melakukan yang anak-anak lain lakukan. Bolos sekolah, nonton di Mall, ikut ekskul, pontang-panting di ujian kenaikan kelas, ke salon, pacaran, pelukan, ciuman, cemburu, bertengkar dengan pacar, terus baikan, dan masih banyak lagi. Aku pikir, aku baik-baik saja, sama seperti yang lainnya.
Aku selalu jadi ingin seperti yang ayahku mau. Sayangnya, aku tidak sekuat dirinya, mungkin. Aku suka mengeluh, aku suka melemah. Tapi setidaknya, aku tidak pernah mengeluhkan atas apa yang dia lakukan. Tapi, dia tidak sadar, mungkin. He did a lot. Tidak usah kusebutkan satu persatu. Karena aku, tidak peduli. Sifat ketidak-pedulianku lalu menjadi pahlawanku juga. Karenanya, aku selamat dari lembah narkoba, rokok, atau free sex anak-anak broken home lainnya. Aku hanya peduli, pada mimpi-mimpiku.
Ah! Ternyata aku tidak baik-baik saja. Banyak kok mimpiku yang tercapai. Tapi, untuk tidak menjadi seperti apa yang orang tuaku alami, aku gagal. Aku bercerai. Satu kegagalan itu, membuat semua hal yang pernah kucapai, seperti sampah. Perkara lama yang kembali kuingat saat mataku panas terkena radiasi laptop, dan pegalnya punggung akibat mengetik sambil tiduran. Ayolah Luna, ini sudah hampir duapuluh tahun lalu. Do you still want to blame it?
Tidak ada yang perlu kuusap dari mataku. Aku tidak gampang meneteskan air mata. Tapi, detik ini aku sangat rindu si Bule itu. Dan dia tidak bisa dihubungi. Si Mbak-Mbak itu masih bilang teleponya tidak aktif. Rese’ banget, kan! Kemudian, aku melanjutkan menatap radiasi itu.
Punggungku yang pegal tidak kupedulikan, ditempel koyo saja nanti, sudah sembuh paling. Ada yang menarik pikiranku seketika. Dari rasa penuh terjejal di kepala, menjadi sebuah rasa lega. Aku ingat bola mata itu. Rasanya bisa kucium aroma pagi, dingin dan sejuk di kampus dulu. Saat kesentuh jemari dinginnya. "Nino..." Jawabnya dengan senyum semanis gulali.
Tidak ada rasa paling indah, saat dua orang insan yang saling malu dan bertabrak pandang. Itu namanya jatuh cinta. Saat pertama laki-laki berambut lurus itu bilang, "Besok kamu ada acara nggak?" Di depan kantin kampus.
Itu adalah saat, dimana aku merasa menjadi manusia paling beruntung sedunia. Tidak mendapat belaian lengkap kedua orang tua, tidak masalah! Mau dapet nilai D di salah satu mata kuliah, bodo amat! Aku jatuh cinta padanya, pada pandangan pertama. Eh, kita. Mungkin. Nggak tau juga sih.
"Mmh, besok nggak ada acara, kok." Jawabku malu-malu tai kucing. Besok malamnya, dia menjemputku. Kita malam mingguan layaknya ABG labil lainnya. Jalan ke Mall, ketawa-ketawi, nonton, makan, pura-pura tabrakan tangan, terus gandengan, liat-liatan. Lalu berciuman di dalam mobilnya, di tengah-tengah lampu merah. Kemudian, malu-malu saling buang muka saat lampu berganti hijau.
Kissing in the first date? Iya, kenapa? I'm tottaly madly in love with him. Bodo amat, walau ada sepuluh missed call ayah di handphone-ku yang ku silent. Ayah pasti marah-marah karena waktu itu sudah melewati jam sepuluh malam dan aku masih belum pulang. Tapi, sekali lagi, bodo amat! Tidak ada yang lebih penting ketimbang bersama Nino, bahkan untuk omelan ayah sekali pun.
I was eighteen, and that wasn't my first kiss. Owh, come on! Ciuman pertamaku-yang kata sebagian orang harus menjadi momen paling indah, aku habiskan saat masih di SMP. Waktu itu lagi main Truth or Dare. Dan aku lebih memilih Dare. Melakukan tantangan yang diberikan dengan senang hati dengan salah seorang teman laki-laki. Anak basket, kecengan bagi sebagian siswi di sekolah. Dari sekedar Dare, di detik pertama yang kaku, kita berdua malah kebablasan dan melakukannya berulang-ulang di lain waktu. Oke, that was my first kiss. Cuma karena penasaran, saat nafsu lebih cepat di definisikan ketimbang sebuah perasaan.
Tidak ada kata tembak-menembak. Nino makin dekat denganku. Aku tidak tahu persis kenapa dia bisa mendekatiku. Dia memang bukan cowok terkenal di kampus. Tapi, cukup ganteng-dalam versiku. Tinggiku yang pas sedagunya, membuat kami terlihat sangat serasi. Lalu, dengan latar sama-sama dari keluarga jawa-which is richer, dia berhasil merebut hati ayah. Setelah sekian banyak cowok yang tidak ayah sukai, Nino berhasil membuat hubungan kita didukung penuh olehnya. Apa lagi yang kurang saat itu. Aku-adalah orang terberuntung sedunia.
Seketika awan-awan di atas kepalaku tertarik lagi, ke suasana Lombok sore itu. Redup-redup, antara senja yang jingga dan malam yang menggelap, kita berbaring di balkon kamar, di atas hammock yang bergoyang pelan. Tapi lalu, kurasakan panas di mata ini. Perihnya tenggorokan yang kehabisan suara karena berteriak-teriak memaki. Telapak tangan yang memanas karena habis menampar pipi yang selalu ingin kubelai. Pertengkaran itu, di dapur, di ruang tamu. Seperti dobel dejavu. Saat ini, saat aku mengingatnya. Dan saat itu, saat aku mengalaminya, pengulangan dari apa yang kulihat hampir duapuluh tahun silam.
Dibalik semuanya, satu hal yang paling kukecewakan pada diriku sendiri adalah bercerai. Karena, sakitnya itu dobel. Saat dulu, aku pernah menyumpah-serapahi orang tuaku atas perpisahannya-yang membuatku merasa tidak adil, merasa seperti anak malang yang tak beribu. Lalu sekarang, aku mengulanginya, dengan versi yang sedikit lebih simpel, tanpa anak. Membencinya tapi melakukannya. Aku masih saja berkutat di situ. Menyalahkan keluargaku, yang membuatku melakukan hukum tarik-menarik itu sendiri. Seperti, kamu takut kecurian, lalu kamu akan memasang semua alarm dan CCTV di rumahmu. Tapi ternyata, kamu malah benar-benar kemalingan. Paham nggak?
Apa yang menjadi ketakutanmu itu, malah akan terjadi, biasanya. Karena kamu terlau memikirkan soal kemalingan, sehinga, keparnoan itu terus berputar di kepalamu, dan itu malah terjadi. Kekuatan pikiran. Makanya, ada pepatah bilang, berpikirlah seperti orang sukses, maka kamu akan sukses. Ya itu, kekuatan pikiran. Aku terlalu takut bernasib sama seperti orangtuaku. Membuatku jadi posesif, parno tingkat dewa. Dan benar, sekarang, aku menyandang gelaranya.
Aku adalah orang yang logis. Semua yang kuinginkan selalu masuk akal. Tapi sangat disayangkan, kali ini aku sedang tidak ingin masuk akal. Aku butuh satu mantra untuk bisa melupakan semuanya. Menghilangkan semua rasa dan ingatan masa lalu itu, agar besok bisa kembali ceria sediakala. Mantra yang dikarang J.K Rowling, untuk setiap novel fantasinya. Obliviate!
***.


 Eno_wid
Eno_wid