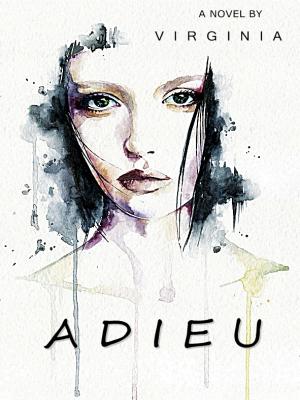Part 1. Charlie
Part 1. Charlie
"He wish me like a Tony Stark!”
“Smart, sexy, rebel, and an asshole! In woman version, of course.” Dia tertawa melihatku menjelaskan.
"I’m serious! Don't laugh!" Kucubit tangan berkulit pucatnya.
"So what happen to you?" tanyanya sembari cengar-cengir.
"Here I am! Being a dumb writer, trap in ton of ideas but never blowing up!"
"HAHAHA... Come on Luna, kamu itu pintar kok.
"Thank's for cheering me up, Charlie." senyum paksa kulemparkan padanya.
"Look, you can write your story. Your own life story. Karena setiap kamu cerita tentang hidupmu, I enjoy it. Stop telling them fiction!" Saran lak-laki itu.
"Telling people about how mad I am with my Dad? Let everybody knows, kalau aku selalu kurang baginya? Lalu sekarang, sedang mencari simpatik pembaca? Is that really what you mean!?"
Charlie tersenyum. "Let get out of here." Lalu dia mengajaku keluar dari kafe.
Aku bertemu dengan Charlie di Bali. Dan sekarang pun kita masih di Bali. Dia warga negara Australia yang memiliki visa usaha di Bali. Dia membuka toko pastry di sekitaran Seminyak. Walau tidak sampai disebut obesitas, tapi tubuhnya tinggi dan besar. Beberapa bagian kulitnya merah terbakar matahari akibat sering berjemur di Kuta. Tangan dan punggungnya bertato. Aku yakin sekali, orang yang sekilas melihatnya tidak akan percaya kalau dia suka cake. Dan cake buatannya memang enak, 9 dari 10.
Sudah hampir dua tahun dia menetap di Bali. Perbendaharaan bahasa Indonesianya sudah lumayan, tapi aksennya masih kental. Lalu, aku? Sedang apa aku di Bali? Escape. Yap, aku sedang melarikan diri. Dari rutinitas ibukota tercintah, Jakarta. Bagaimana aku bisa berkenalan dengan Charlie? Oh, sudahlah, tidak perlu dibahas. That was just a simple moment.
Aku sudah hampir satu bulan di sini. Mengontrak rumah mungil dekat Kuta. Aku penulis, katakanlah begitu. Biasanya aku menulis lepas beberapa artikel di situs online dan majalah. Berharap pelarianku bisa menghasilkan sebuah mahakarya yang-setidaknya, bisa membuat hidupku lebih berarti. And Charlie is my only friend in Bali. I have no other.
I just love writing. Walaupun aku berpengalaman dalam menulis artikel, tapi sesungguhnya aku lebih menyukai fiksi. Wondering something that impossible to be happen, happened. Atau mungkin, aku tidak menyukai cerita hidupku sendiri. Sehingga menyenangkan saja ketika bisa membayangkan masuk dalam sebuah cerita orang lain yang bisa kukarang seenak jidatku. Yang aku tahu, menulis itu penyembuh. Menyembuhkanku dari banyak sakit hati dan emosi yang tak terungkap karena keterbatasan keadaan.
And my Dad? Oh, He is a totally random and a perfectionist man. Trust me, He got a high standard for everything. Mungkin itu juga yang membuat ibuku tidak tahan hidup dengannya. Memutuskan meninggalkannya saat aku masih duduk di bangku Sekolah. Meninggalkan juga aku dan adikku yang saat itu masih balita. I don't know, I just feel, I never be good enough for him.
***
Jadi ceritanya nih, sedari kemarin aku sedang membenamkan diri di dalam kamar. Segitunya? Iya, cuma gara-gara satu telepon masuk dari Ayah, aku langsung gelagapan merampungkan satu novel yang sedang kugarap. Katanya, "Mana hasil karyamu? Udah mau sebulan kok belom ada update-nya, sih?" Lo pikir nulis novel kayak orang buang hajat apa, langsung cemplung keluar gitu aja.
"Belomlah, Yah. Tenang aja, nanti kalo udah terbit pasti Luna kabarin kok. Sabar aja." Alih-alih ngeles, aku malah menjanjikan hal yang tidak pasti ke si Mr. Perfectionist.
Terbit? Dilirik sama penerbit aja belum tentu. Ayahku yang tidak tahu proses suka duka kepenulisan-atau tepatnya, lebih banyak dukanya itu, membuatnya menganggap menulis itu hal yang mudah. Menurutnya, hal yang sulit nan keren itu adalah menjadi seorang engineer, alias tukang insinyur-kalau di dalam film Si ‘Doel Anak Sekolahan.’ Kerja di lapangan, menghitung banyak angka dan berkutat dalam rumus.
Ya kalo anaknya laki-laki sih mending ya. Sayangnya aku dan adikku adalah perempuan tulen. Bedanya, dia lebih berani, lebih cuek dan lebih tahan terhadap ayahku. Lebih pintar? Hmm, tunggu dulu, terakhir kali aku lihat, hasil test IQ-ku itu lebih tinggi dari dia, lho. Tes IQ yang kita lakukan saat masih TK dulu. Itu artinya, sudah duapuluh tahun lebih. Mungkin saja kalibrasinya sudah kadaluarsa. Faktanya, banyak kejadian dan perubahan selama duapuluh tahun-an yang malah membuat IPK nya sekarang jauh lebih tinggi dibanding IPK-ku dulu sewaktu kuliah.
Aku pernah berusaha menjadi apa yang ayahku mau. Kalau soal ambisius, ya, aku ini orang yang ambisius. Apa yang aku mau, harus kudapatkan. Itulah yang membuat ayahku pernah menyukaiku ketimbang adikku, dulu. Sampai aku menemukan, apa yang aku tidak mau, tidak akan bisa kudapatkanya. Dan apa yang ayahku mau, ternyata tidak melulu sama dengan apa yang kumau.
"... Lalu dia memandangi si wanita tersebut, seperti seekor harimau yang-"
TOK TOK TOK!
Astaga! Bikin kaget aja. Kubukakan pintu depan yang jaraknya hanya enam langkah dari kamar. Rumah ini kukontrak selama tiga bulan, dan ini masih bulan pertamaku. Pemiliknya cukup baik hati dengan memberikanku harga miring. Karena sepertinya dia memang tidak sedang butuh uang. Hanya agar rumahnya ada yang merawat saja selama suaminya mutasi kerja ke Jakarta. Haha, lucu ya, disaat aku ingin sekali tinggal di Bali, tapi ada satu keluarga yang justru malah pindah ke Jakarta.
Sudah kuduga, pasti Charlie. Entah kenapa, tidak pernah tiga hari pun ia lewatkan tanpa bertemu denganku. Dia suka padaku? Oh, no! Itu tidak mungkin. Satu, wujudku tidak seperti wanita-wanita Indonesia yang berkulit hitam-kejemur dan bewajah eksotis-versi Bule. Kedua, bentuk badanku tidak montok, semok, dimana pantat dan payudara saling bersaing ingin menunjukan kelebihannya. Bisa dikatakan, aku bukan tipenya Bule banget lah. Kalau secara deskripsi, aku malah lebih cocok dengan tipe cowok-cowok ibukota negara. Iya, Jakarta. Dengan tinggi 160-an dan bobot 48 kilo, agak tipis ya, dengan rambut panjang terurai lurus sepunggung, berpakaian feminim, berkulit kuning langsat, dengan logat gue-lo yang fasih. Tapi, sayangnya. Aku juga tidak bernasib baik dengan cowok-cowok ibukota, sepertinya.
"Hai, Lun! Where have you been?"
"I am all here!"
Lalu Charlie masuk dan langsung duduk di kursi tamu. Kursi kayu berbahan jati yang ditinggal oleh pemiliknya. Aku menempati rumah kontrakanku itu full furnished.
"Lagi serius nulis, nih?" kata Charlie yang dalam posisinya bisa langsung melihat isi kamarku dengan laptop di atas kasur.
Aku mengangguk.
"Nggak makan siang?"
"Delivery aja. Atau paling, ke warung nasi seberang."
"Oh, oke! So... You want me to leave you alone?" Pria Bule itu mengangkat kedua tangannya.
Aku diam berpikir. Kok kayaknya, garing juga ya, udah dua hari nggak ngomong sama siapa-siapa.
"Hmm... What if, you stay here, but don't bother me. Just stay here. You can watch TV, or... anything. But just, don't talk to me."Alisku kuangkat, senyumku kulebarkan.
Laki-laki itu diam sebentar. Lalu, "All right!" katanya.
Dua jam kemudian, aku dan dia malah asyik duduk di kursi yang sama, menertawakan adegan "Bend and Snap" Reese Witherspoon dalam film Legally Blonde yang sedang di putar di TV kabel.
“Is that really work?” tanyaku heran kepada Charlie.
***


 Eno_wid
Eno_wid