BAB XIII
Aku sudah keluar dari rumah sakit. Hari ini aku akan menemani Wanda jogging sebagai bentuk terapinya. Kami mengikuti kegiatan Car free day yang pada waktu itu sedang digandrungi masyarakat Jakarta. Lokasi Car free day dimulai dari Bunderan Ratu Plaza ( Jend. Sudirman) sampai Patung Arjuna (Jl. MH Thamrin) dengan titik sentral di Bundaran Hotel Indonesia. Jakarta yang biasanya disesaki kendaraan kini penuh dengan lautan manusia. Peserta yang ikut waktu itu sangat ramai dan beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa?entah itu datang sendiri, bersama keluarga, atau mewakili organisasi tertentu. Para pedagang juga menggunakan kesempatan ini untuk menjajakan barang dagangannya. Suasana pagi itu sangat sejuk sekaligus meriah. Setelah cukup lama berputar-putar mengelilingi jalanan, kami duduk di bundaran hi. Aku memperhatikan wanda yang mengenakan kaus tim softballnya dan celana pendek. Ia sibuk memegangi lututnya yang dibalut pelindung lutut.
“Bagaimana lututmu? sudah tidak terasa sakit?” tanyaku.
“Memang tidak terasa sakit,” jawab Wanda sambil mengatur nafas. “tapi aku sudah lama tidak berlari jadi rasanya tidak seperti biasanya.”
Aku menyeka keringatku dengan handuk. “Baguslah jika tidak terasa sakit.”
“Kau sendiri bagaimana?” tanya wanda.
“Aku memangnya kenapa?”
“Barusan semalam benar kan kau baru dibolehkan pulang."
“Sedikit capek sih.”
“Tuh kan! kau masih butuh istirahat. Aku tidak ingin memaksamu, kau sendiri yang memaksa ikut.” celoteh Wanda. “Kalau kau jatuh memangnya aku mau menggendongmu ke rumah sakit?”
Aku menertawainya karena ia bertingkah seperti anak kecil. “Kau ini suka melebih-lebihkan! Aku capek karena sudah jarang berolahraga.” kataku menenangkan.
“Tetap saja itu berbahaya.” kata wanda sambil memalingkan wajahnya.
Sepertinya ia marah padaku karena aku tidak terlalu peduli pada diriku sendiri. Sifat wanda yang terlalu peduli pada hal-hal kecil memang terkadang menjengkelkan, namun di sisi lain tingkahnya sangat manis.
Wanda memegang perutnya, terdengar bunyi keroncongan. “Nif, aku lapar. Pedagang makanan di pinggir jalan sungguh menggodaku.” katanya sambil menunjuk ke arah gerobak makanan.
“Bubur disana sepertinya enak, kau mau mencobanya?” tanyaku
Wanda setuju dan kami makan disana. Setelah mengantri cukup lama akhirnya bubur yang kami pesan disajikan. Rasanya memang enak, tapi harganya sangat menguras kantong. Hari semakin terik dan orang-orang mulai meninggalkan jalanan, begitu juga kami.
*
Sore ini Angga menelponku. Ia menanyakan apakah aku bisa berbicara empat mata dengannya. Aku menyanggupi permintaannya. Ia bilang padaku untuk menemuinya malam ini di rooftop apartemen melati?letaknya dekat kampusku. Aku menekan tombol lantai paling atas pada lift. Sembari menunggu lift bergerak mencapai puncaknya aku bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Angga, mungkinkah ini tentang Wanda? pintu lift terbuka dan aku menginjakkan kakiku keluar. Seorang laki-laki berdiri termenung dibalik pagar pembatas rooftop. Aku berjalan menghampiri dan berdiri disampingnya. Ia sendiri menyadari kedatanganku, tapi tidak menunjukkan reaksi apapun.
“Ada apa?” kataku sambil mencengkram pagar besi.
Ia tidak menjawab, matanya masih sibuk mengikuti mobil-mobil yang lewat. Wajahnya dibayang-bayangi sinar rembulan?sekilas menunjukkan keresahan. Sebelumnya Angga belum pernah seserius ini, dia itu orang yang sangat ekspresif.
“Wanda bukan?” kataku
Air mukanya tidak menunjukkan perubahan sedikitpun.
“Kalau ini tentang Wanda. Aku minta maaf.” Aku berusaha mencari kata-kata yang tepat. “Aku tidak bermaksud merebutnya darimu.”
Ia menghela nafas. menengadahkan wajahnya ke bulan. Bulan yang hampir sempurna, hampir purnama.
“Bukan, bukan tentang wanda.” ia menyulut sebatang rokok. “Wanda itu cerita lama, sesuatu yang lebih serius menimpaku.”
Aku lega bahwa ia sudah melupakan wanda, tapi apa yang masalah yang membuatnya sampai seperti ini?
“Ini tentang Grace.” sambungnya. “Kau ingat dia?”
Aku ingat-ingat lagi nama itu. “Ah, wanita yang kita temui di kelab malam itu kan?”
“Tepat sekali.” katanya tenang.
“Grace yang malang. Ia pasti marah setelah mengetahui kau tidur dengan banyak wanita ya?” kataku mencairkan suasana.
Ia mematikan rokoknya yang masih separuh, menginjak puntungnya seolah-olah puntung tersebut adalah masalah yang sedang ia hadapi.
“Dia hamil.”
Aku langsung meliriknya dengan tatapan tajam.
“Jangan bilang kau..”
“Aku yang menghamilinya.” sela Angga. “Hasil tesnya positif.”
“Astaga, memangnya kau tidak pakai pengaman?”
“Aku tidak tahu, aku terlalu mabuk saat itu.”
“Tapi belum tentu kau ayah dari bayi itu kan??maksudku wanita itu bisa saja tidur dengan banyak pria.” kataku penuh harap.
“Ia menantangku dengan tes DNA. kurasa menyangkal sudah tidak ada gunanya.” katanya sambil menjambak rambutnya sendiri. “Ia memaksaku menikah dengannya, kalau sampai orangtuaku tahu bisa bisa aku bisa celaka! ibu bisa langsung terkena serangan jantung dan ayah akan menembakku bila tahu semua ini terjadi.”
Aku sendiri belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Persoalan ini sudah sering terjadi, dan penyelesaiannya pun tidak ada yang sederhana?harus ada yang dikorbankan. Sejenak aku membantunya berpikir mencari jalan keluar, tapi tidak juga terlihat titik terang.
“Apa aku harus menggugurkan bayinya, atau sekalian saja membunuhnya” kata Angga sambil tertawa. Ia kelihatan serius dengan perkataannya.
“Angga! sadarlah!” aku mengguncang-guncang badannya. “Kita harus berpikir jernih. bukan seperti itu caranya!”
“Bukan kau yang mengalaminya, tapi aku. Kau tidak akan pernah mengerti.” nadanya terdengar getir. Ia melepaskan cengrakaman tanganku dan turun dengan lift.
Mungkin ia hanya butuh waktu sendiri
Aku pun masih bertahan dengan hembusan angin malam dan deru kendaraan yang melintas dibawah apatermen ini. dunia memang tidak pernah berhenti berputar.


 rayhan_khalid
rayhan_khalid





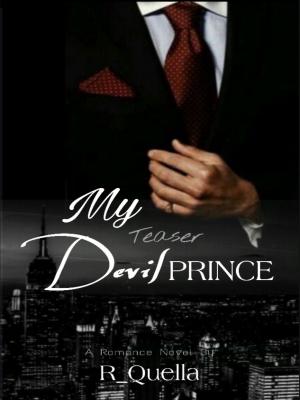




"Aku tidak pernah menghisap apapun selain udara"
Comment on chapter BAB IIOke, mungkin kalimat itu bakal nempel dikepalaku sampai besok :))