Masih ingatkah kau? Kita pernah menikmati hari-hari bersama. Mengisi waktu dengan canda dan tawa. Tidak peduli terhadap orang-orang yang mencibir ‘gila’ karena kita tertawa sepuasnya, dimana pun dan kapan pun. Acuh pada mereka yang menatap geli melihat tingkah kita yang –terkadang– kanak-kanakan. Indah bukan? Melebihi indahnya cerita-cerita yang tertera di novel best selller. Lebih romantis dibandingkan kisah yang ditulis para pujangga.
Aku pernah berteman baik dengan toilet karenamu, Zella. Kau meracunku, bersekongkol dengan pedagang mie ayam, menabur cabe semaunya –tanpa sepengetahuanku. Demi melihatmu yang bersemangat, aku menghabiskan mie ayam super pedas itu. Pura-pura kuat walau bibirku serasa terbakar, perutku panas layaknya gunung api yang siap menyemburkan isinya. Sambil menahan tawa, kau terus menyemangati, mengagapku peserta yang sedang mengikuti lomba makan, antusias sekali melihat lelakimu dibanjiri keringat.
“Aduh sayang, kamu pasti menderita ya nongkrong di toilet,” kau seakan cemas padaku, “lain kali ajak temen-temenmu ya biar rame nongkrongnya hahaha,” lanjutmu.
“Kalau gitu besok kamu traktir temen-temenku mie ayam. Supaya bisa nongkrong bareng.”
Kita tertawa bahak membayangkan toilet yang disulap menjadi tempat nongkrong.
Mendengar tawamu di ujung telepon, semua rasa kesal pun hilang. Andai saja yang meracunku itu bukan kamu, tentu saja aku akan balas dendam. Bermalam di toilet menjadi pengalaman yang mengerikan. Nyamuk bernyanyi ria, seakan mereka berpesta. Sesekali ia hinggap di sembarang tempat; kaki, tangan, dahi, pipi, hingga bokong. Menyebalkan. Gemercik air memperkeruh suasana. Seketika memoriku mengeluarkan bayangan valak –hantu yang kita tonton kemarin. Bulu kuduk berdiri. Bagaimana jika ia menghampiriku di saat aku sekuat tenaga mengeluarkan isi perut? Aku tidak bisa kabur. Sial.
Aku tahu meskipun kau terlihat cuek dan seakan tertawa di atas penderitaanku, tapi, kau mencemaskan diriku. Tidak mungkin membiarkan lelakimu “menderita” begitu lama. Pagi itu Ibu berteriak. Memberi tahu jika ada seorang perempuan berambut ombak menjengukku. Memberikan obat sakit perut dan sebungkus bubur ayam sebagai menu sarapan. Tak lupa kau pun mengucapkan maaf. Aku hanya mengacak-ngacak rambutmu, gemas sekali dengan “kenakalanmu.”
***
Kenapa hari-hari yang penuh warna itu berubah menjadi kenangan manis yang terasa pahit? Ya, Zella, setiap kali aku mengingatnya, bibirku tersenyum menyadari betapa konyolnya tingkah kita, namun mataku malah berair, karena semuanya telah berakhir dan hanya menyisakan luka. Kalau saja lelaki itu tidak pernah ada, mungkin kita akan bersama hingga tua. Tidak Zella, aku tidak menyalahkanmu. Kau berhak memilih siapa saja menjadi pendampingmu. Memilih kebahagiaanmu. Tetapi bukan dengan cara seperti ini!
“Maaf aku tidak bisa meneruskan hubungan kita.”
“Kenapa?” Aku bertanya layaknya anak kecil yang tidak mau ditinggalkan ibunya ke pasar.
“Kita sudah tidak cocok,” kau berkata pendek. Buliran air berguguran dari matamu.
Hah, tidak cocok? Kau bilang kita tidak cocok setelah ratusan hari kita lewati bersama. Apanya yang tidak cocok? Bukankah kau sendiri yang bilang “aku sangat bahagia bersamamu, berjanjilah untuk setia padaku dan tanpa kau minta aku akan setia padamu.” Dan sekarang kau bilang kita tidak cocok?
“Ada yang lebih baik darimu.” Sempurna kau bersandiwara lewat air matamu, lantas pergi meninggalkanku yang termangu.
Sial, kau tega membakar kenangan kita oleh api yang dibawa lelaki itu. Api yang mampu membakar keberadaanku di hatimu. Padahal susah payah untukku masuk ke sana. Butuh perjuangan, keberanian, hingga pengorbanan. Bodohnya, lelaki itu sangat mudah untuk menggantikanku. Ya, hanya dengan api kecil saja, sempurna dia menghanguskan semuanya.
Andai saja aku tidak bisa mengendalikan emosi. Boleh jadi aku langsung mencari lelaki yang merebutmu. Mengajak teman-temanku untuk memukulinya.
Aku keliru Zella. Lelaki itu tidak merebutmu. Kau sendiri yang menginginkannya. Aku menyesal tidak menyadarinya sedari dulu, saat hubungan kita baik-baik saja. Saat kita masih memakai seragam yang sama. Rupanya kau tersiksa dengan jarak yang memisahkan kita. Perlahan tapi pasti kau berubah. Tidak ada lagi rintihan rindu, yang ada hanya makian karena aku tidak bisa memberi waktu.
Benar Zella, kau pantas melakukannya. Tapi, salahkah jika aku pergi jauh, menyibukkan diri, larut dalam perkerjaan yang menuntut banyak waktu? Salahkah jika aku melakukan semua itu demi janji masa depan yang lebih baik, demi kita, demi dirimu? Bukankah di hari kelulusan, kita sepakat untuk saling memercayai. Tapi kenapa kau menuduhku menghabiskan waktu dengan wanita lain, hingga lupa mengabarimu.
Kau tahu Zella, bohong jika aku berkata tidak sakit hati. Kendatipun aku menyibukkan diri, peluh membanjiri tubuh, tersenyum setiap kali ada yang menyapa, tertawa saat teman-temanku bercanda, hatiku tetap saja sakit. Siang memberiku kebebasan, namun malam mengurungku dengan luka.
Pada titik ini aku merasa bodoh Zella. Di sini aku ditemani oleh luka. Mengingat kembali hal-hal indah yang pernah kita lewati bersama. Otakku terlalu lambat untuk berpikir, kalau kau tidak pantas untuk dicintai. Hatiku terlalu munafik, masih menyimpan dirimu. Di tempat lain, boleh jadi kau sedang berbahagia dengan lelaki sialan itu. Lelaki yang merebut warna yang selalu mewarnai hari-hariku. Merebut senyummu yang teramat manis. Merebut janji masa depan yang pernah kita ikrarkan. Menghancurkan semuanya.
***
“Maaf.” Perkataanmu mengaburkan lamunanku. Mencairkan kebekuan di antara kita. Setelah empat tahun berlalu, kau menemuiku lagi.
Bibirku kelu untuk merangkai kata. Otakku terlalu banyak dirasuki pertanyaan. Kenapa aku di sini? Kenapa aku menerima ajakanmu? Kenapa kau hadir di saat aku berhasil berdamai dengan masa lalu? Ke-na-pa?
“Aku minta maaf, Gar. Dulu aku keliru,” matamu berkaca-kaca, “ternyata lelaki itu tidak lebih baik darimu.”
Selama ini aku menahan diri untuk tidak membencimu. Tapi saat kau berkata seperti itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Kenapa kau begitu mudah berkata “lebih baik”. Tidak kah ingat, dulu kau mengatakan hal yang sama. Mengakhiri kisah kita karena lelaki yang –menurutmu– lebih baik dariku.
“Kamu mau kan mengulangi lagi hubungan kita dari awal? Anggap saja kita tidak pernah bertemu sebelumnya.” Kau memberi tawaran, menganggapku layaknya anak kecil yang menangis, lantas kau beri uang jajan.
Dari banyaknya lelucon yang pernah aku dengar, lelucon ini yang paling lucu, Zella. Ingin sekali aku tertawa bahak, sayangnya bibirku terkunci rapat.
Dering telepon memecah kebekuan.
“Hallo, Tegar, kamu di mana?” Suara seorang perempuan terdengar dari ujung telepon.
“Aku lagi di Bandung… Sama temen, Ta...”
“Kapan balik ke Jakarta? Oh iya nanti minggu jadi, kan? Ayolah Gar, mumpung ada film bagus.”
“Malem ini aku Ta.. Hmm iya aku usahakan..”
“Ayolah Gar… jadi yaa, jadii.”
“Iya bawel.”
“Hahahaha.. oke, aku tunggu Gar. Kalau bisa bawakan aku oleh-oleh yaa hehe... Udah dulu Gar, ada si boss. See you beb, haha. Tutt tutt tutt.”
Aku baru sadar, kalau minggu ini ada janji dengan seseorang.
“Siapa?” Kau bertanya dengan raut penasaran.
“Pacarmu?” sekali lagi kau bertanya, tanpa sempat aku menjawab pertanyaan pertamamu.
Aku memperlihatkan sebuah foto di layar handphone.
“Oh, kalau gitu semoga hubungannya langgeng. Ditunggu surat undangannya.” Kau tersenyum tipis, meski pipimu basah.
Dengan sisa buliran air mata, kau pergi meninggalkan aku yang membeku. Sedari tadi tidak ada sepatah kata pun yang mampu keluar dari bibirku untukmu. Aku menghela napas. Kenapa aku tidak bisa jujur pada perasaanku sendiri?
***
Terima kasih Sinta, kamu menyelamatkan hidupku. Kamu meneleponku di waktu yang sangat tepat.. Jujur otakku tidak bisa berjalan dengan baik, kala dia meminta untuk menjalin hubungan lagi denganku. Beruntung, sebelum hatiku mengambil alih, kau hadir. Kau memang sahabat terbaikku. Maaf, maaf aku mengaku sebagai pacarmu. Doakan, semoga besok lusa aku bisa lepas dari titik kebodohan ini.


 NasrulM.Rizal
NasrulM.Rizal









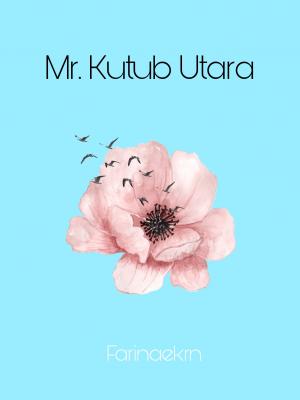
manteb nih gan, permainan emosi yg pas dan tidak main stream