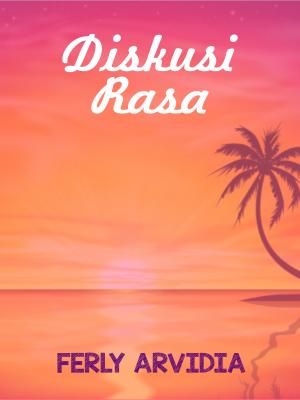Ketika istirahat, biasanya aku sangat jarang bersama Gerald karena dia cepat untuk berbaur dan mendapat teman. Yah, sepertinya aku jadi agak dilupakan kalau dia sudah bersama teman laki-lakinya. Jam istirahat selalu aku habiskan di dalam kelas, entah kenapa aku takut untuk ke kantin—mati-matian menahan perut keroncongan—demi agar tidak bertemu kakak-kakak kelas. Senioritas di sekolah ini aku rasa cukup tinggi, makanya aku cari aman saja. Sejujurnya sih, aku sudah dapat teman, tapi tidak terlalu akrab. Aku masih canggung jika harus mengajak ke kantin bersama, atau sekedar jalan-jalan keliling sekolah. Eh, tunggu dulu. Jalan-jalan keliling sekolah sepertinya bukan ide yang buruk, daripada aku terus berdiam diri—membisu di kelas ini. Aku coba keluar kelas dulu, deh. Untungnya, lorong lantai dua ini tidak terlalu ramai.
"Sera, tumben keluar dari kandang?" Seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh. Ah, ternyata Hanny, anak kelasku.
"Iya," aku tertawa renyah, "pengap juga di kelas terus."
"Oh, begitu. Ya sudah, aku ke kelas dulu." Dia tersenyum tipis. Aku balik tersenyum.
Kira-kira seperti itu hubunganku dengan teman-teman perempuan di kelasku. Biasa-biasa saja. Hanya sekedar tegur sapa. Ya sudahlah, aku lanjut lagi keliling-keliling. Aku mau ke lantai tiga, karena cukup jarang ke daerah itu. Aku naik tangga dan memasuki lorong lantai tiga, untunglah sepi. Karena disana hanya ada ruangan-ruangan laboratorium, perpustakaan, dan ruangan sekretariat ekstrakulikuler. Aku melanjutkan langkah dan akhirnya terhenti karena suara petikan gitar. Aku mencari dari mana asal suara tersebut. Ternyata dari ruang band—lebih tepatnya ruang sekretariat ekskul band. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Aku mengintip dari pintu yang sedikit terbuka, dan kudapati seseorang sendirian disana. Orang itu membelakangiku. Rambut dan postur badannya tidak asing. Siapa, ya?
Tiga menit aku menonton—lebih tepatnya mengintip orang itu bermain gitar, aku kagum sekali dengan permainan gitarnya. Dan tanpa kuduga, tiba-tiba dia menengok ke arah pintu. Astaga! Aku langsung sembunyi dibalik pintu lainnya yang tertutup. Aku langsung berjalan cepat-cepat, menghindari ruangan itu. Tapi...
"Bagus tidak?" Seseorang menyentuh lengan kiriku. Aku menoleh dan mendapati Sylvester—teman sekelasku—alias yang tadi kuintip.
Ah, bodoh! Jantungku seperti keluar dari tempat seharusnya. Jujur, meskipun sekelas, aku tidak akrab sekali sama Silva—itu nama panggilannya. Dia bisa dibilang anti-sosial, atau sedikit sosiopat, atau entahlah! Pokoknya, orang itu tidak banyak bicara sama sekali. Aku bingung sekali mau jawab apa, dan bisa-bisanya aku tidak menyadari kalau dia mengejarku dari belakang. Bodoh sekali kamu, Ser!
"Ke..keren, kok!" Aku terbata-bata, mukaku mungkin sama warnanya dengan kepiting rebus sekarang.
"Kamu lancang sekali, ya. Kalau mau jadi penggemar rahasiaku itu jangan sampai ketahuan." Dia melengos pergi begitu saja, meninggalkanku yang mematung. "Dasar."
Sekarang dia resmi membuatku memberi impresi pertama yang buruk padanya. Aku kesal. Kesal sekali. Siapa yang penggemar rahasiamu? Bodoh!
Untungnya bel tanda istirahat selesai sudah berbunyi, dan aku segera masuk kelas. Tapi, di kelas aku akan bertemu si sialan itu lagi. Ah, pokoknya, aku sangat menyesal sudah keluar kelas.
***
Kalau kalian penasaran sekali dengan muka Sylvester atau Silva itu, tahan saja. Aku agak kesal juga membicarakannya, sangat tidak sopan. Tapi, biar aku ceritakan sedikit mengenai fisiknya. Pertama, aku dengar-dengar dari desas-desus di kelas, bahwa Silva ada keturunan Inggris. Masa bodo, aku tidak peduli. Karena dia tidak baik denganku, aku juga tidak akan baik dengannya. Terserah kalau kalian mau bilang dan menebak-nebak aku akan suka padanya, itu tidak akan terjadi!
Aku lihat-lihat muka dia seperti orang-orang Anglo-Saxon, tapi bedanya rambut dan warna matanya hitam. Tidak jelas. Dasar orang aneh. Maaf bila aku terlalu penuh dengan api kekesalan kalau bicara tentangnya. Tapi sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang dirinya, sih. Aku hanya tahu kalau urutan absennya tepat di bawah namaku. Huft, karena teramat kesalnya memikirkan kejadian tadi, aku tidak sadar bahwa Gerald dari tadi sudah menunggu di parkiran, karena sekolah sudah bubaran.
"Heh, bodoh. Kenapa, sih? Mukamu sudah cukup jelek, jangan ditambah-tambahin lagi jeleknya." Gerald menyalakan mesin motornya.
"Berisik kau!" Aku tambah muram. "Hei, apa kamu akrab dengan si Silva Silva itu?"
"Sepertinya tidak. Kurang akrab." Gerald menaikkan alisnya sebelah, "memang kenapa?"
"Pernah bicara dengannya?" Aku mengalihkan.
"Pernah. Memangnya kenapa, sih?"
"Apa bicaranya kurang sopan? Atau bagaimana?"
"Ya, biasa saja. Memang kenapa, sih, bodoh?" Gerald mulai tidak sabar.
"Tidak." Aku langsung naik ke motornya.
"Dasar tidak jelas. Jangan naik ke motorku." Gerald melotot kepadaku lewat spion.
"Ini bukan motormu, sial. Ini motor ayahmu." Aku menggetok kepalanya yang memakai helm. Gerald hanya tertawa sebentar, lalu menarik gas motornya.
***
"Tumben ibumu pulang cepat?" Tanya Gerald setelah sampai di depan gang rumahku—melihat mobil ibu terparkir di depan rumahku. Ya, ibu pulang pada sore hari adalah keajaiban dunia ke delapan. Ada apa ini?
"Keajaiban dunia ke delapan. Aku juga tidak tahu kenapa ibu pulang cepat. Dia juga tidak mengabari aku dulu." Aku mengatakan yang ada di pikiranku. "Kamu mampir saja dulu, salam sama ibuku. Jarang-jarang bertemu."
"Iya." Gerald memarkirkan motornya di depan rumahku, tepat di belakang mobil ibu.
Aku dan Gerald masuk ke rumahku. Aku melihat sepatu heels ibu yang tertata rapi di rak sepatu. Pintu rumah sudah tidak dikunci dan sudah terbuka, berarti ada ibu di dalam, kalau Bang Stev sudah pasti belum pulang sore-sore begini.
"Eh, aku lepas sepatu?" Tanya Gerald dengan tampang cengonya. Bodoh sekali, sih. Pintar-pintar bodoh.
"Boleh kamu pakai sepatumu sampai dalam rumah, tapi kamu harus membantuku mengepel rumah ini selama seminggu." Aku tersenyum paksa. Gerald membuka sepatunya dan menaruh di rak sepatu.
"Bu?" Aku memanggil ibu, memastikan dia ada dimana.
"Iya? Sera sudah pulang?" Ibuku menyahut tapi entah dia ada di ruangan mana.
"Iya, Bu. Ada Gerald nih, mau salam."
Ibu turun dari lantai dua dengan menggerek koper travel-nya. Aku kaget sekali. Dia juga sepertinya baru sampai rumah. Blazer hitamnya—yang biasa ia kenakan ketika bekerja tidak ia ganti dan make up-nya juga belum di hapus.
"Ibu abis packing baju-baju dan barang, nih." Dagunya menunjuk koper disampingnya.
"Oh..." Aku kaget dan tidak menyangka, tidak tahu mau jawab apa.
"Tante," Gerald menyapa ibuku dan mencium punggung tangannya. "Tante mau kemana, Tan?"
"Biasalah, Ger." Ibuku tersenyum tipis. "Jadi kamu antar-jemput Sera, ya? Wah, saya berhutang budi sama kamu, Ger."
Aku tidak mengerti maksud "biasa" bagi ibuku. Aku juga tidak menyangka kalau dia pulang hanya untuk beres-beres barang saja. Memang, aku tidak bisa berharap lebih sih, dari orang sibuk seperti dia. Tapi, terserah dia sajalah, dia juga seperti ini demi menghidupi anak-anaknya. Kalau dilihat untuk relasi ibu dan anak-anaknya, ini tidak wajar. Ibuku sangat tertutup kepada Bang Stev dan aku. Tidak seperti orang tua lainnya, yang membimbing atau minimal bersedia menjadi tempat curhat anak-anaknya—ibuku mana pernah seperti itu. Iya, aku sekarang sedang membandingkan ibuku dengan ibu-ibu lainnya. Entahlah, intinya aku tidak bisa memaksa dan berbuat banyak. Aku pasrah saja.


 ynx
ynx