Musim panas, 2015
Peintures dan café-café di area Majestic Theaters ramai, tawa-tawa riuh rendah, dengan pesanan yang hampir serupa di atas mejanya, chocktail dengan es batu kotak yang terlampau penuh, minuman sempurna untuk mengawali musim panas di Broadway. Di pojok sebuah peniture ala 70-an, seorang lelaki duduk serius di hadapan laptopnya, mana peduli pada berbagai pasangan muda-mudi yang bercengkerama mesra, ia duduk seorang diri, bahkan tidak dengan seorang sanak saudara pun yang menyapa singkat di ponselnya yang dibiarkan tergeletak di sebelah tangan kanannya yang terluka. Ah, luka itu masih memerah rupanya.
Lelaki itu berkulit putih, sama seperti kebanyakan American lainnya, rambutnya sewarna pasir, namun biji matanya bulat coklat mahoni, pinggirannya kekuningan, sempurna bagai coklat tertuang madu jati. Tetapi ia sungguh bukan seorang pribumi, barang kebetulan saja kulitnya tampak pucat kini. Keadaannya belum stabil, luka-lukanya masih basah dan memerah, tertutupi blues berpatron lurik yang tampak pudar, energinya juga belum pulih, wajar saja kecepatan goting the root keahliannya menurut drastis. Beberapa laman yang ia telusuri sejak tadi belum memberikan secercah titik terang. Kedatangan Nunsius itu memang menyusahkan, pikirnya.
Baru tadi malam ia mendapatkan luka-luka itu, sebagian besar akan kering sendiri dengan berjalannya hari-hari, sebagian kecil, seperti jenis luka yang dihatinya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Seorang chambermaid berpakaian minimalis menghampiri, membawakan pesanannya sekaligus menawarkan wine merah berharga miring dengan extra dektrosa impor asal Asia secara berlebihan, senang mengoda lelaki tampan. Namun lelaki itu menolak halus, ia tidak meminum bir, ia seorang muslim.
***
“Ini tidak adil, Hans”
“Dunia memang tidak pernah bisa menjadi seadil pikiranmu, Jules”
Lalu sunyi, sepasang manusia itu terdiam, menatap seonggok tubuh gempal yang tidak lagi bernyawa. Pria tua berusia hampir setengah abad yang kian serakah, seorang eksekutif, middle manager sekaligus seorang bandar. Oleh karenanya ia terbunuh. Darahnya masih segar, tampak pekat di suasana malam yang gelap, matanya terbuka, menatap nanar terkejut, mungkin tidak menyangka bahwa nyawanya akan berakhir malam ini.
Mereka berdua kembali terdiam, yang perempuan merapikan anak rambutnya yang ikal mencuat-cuat, yang lelaki masih terus mematung. Ia tidak pernah melihat pembunuhan terjadi di depan matanya secara langsung. Padahal sejak kecil ia terbiasa melihat pembantaian, bukahkah itu penyebab ia yatim piatu seperti saat ini? Suasananya juga sama, teriakan ketakutan, peringatan-peringatan nyaring berbahasa asing, roket-roket kecil yang membakar udara serta senapan angin yang melesat tanpa suara. Nyaris tanpa perbedaan. Hanya saja senapan itu bukan lagi berada di tangan tentara berbaju hijau malam, senapan itu berada ditangannya. Ia yang baru saja membunuh pria bertubuh gempal itu.
Kejadian pembunuhan itu sudah menjadi memori yang terlampau tua, mungkin empat atau lima tahun silam. Toh, buat apa di ingat-ingat, ia juga sudah berubah. Walau ia masih ingat persis bau mesiu dan pertikaian, ia sungguh sudah berubah. Hanya saja seakan dunia terlalu rendah hati untuk membiarkannya hidup tenang. Seperti kata pepatah, hidup bagai replika roda terkadang berada di atas atau di bawah. Malam tadi merupakan titik balik kehidupannya. Semua ketenangan seakan sirna dalam hitungan detik. Kemudian pertikaian, senapan, baku hantam juga pengkhianatan mengambil alih seluruhnya. Kembali mengusik-usik memorinya. Ia hampir lupa cara menarik pelatuk pistol semalam. Tubuhnya luka-luka, tetapi ia berhasil melarikan diri. Hanya ada satu masalah, ia bukanlah si pengkhianatan dalam cerita ini.
Semilir angin muson barat menerpa rambutnya yang berwarna pasir, memainkannya riang di sore hari begini. Lalu ia merindukan rumahnya, kampung halamannya, dahulu ia senang duduk di pelataran rumah bermain angin seperti ini. Lantas ia mencari-cari minatur itu dikantongnya. Ukurannya kecil saja, sebesar jari telunjuk ras kaukasoid, berwarna keemasan dengan motif-motif yang serupa dengan bangunan Amerika manapun. Tapal kuda Umayyah, pola geometris Murabitun yang bercorak senada dengan garis-garis tegas Muwahhidun beserta tulisan kecil yang nyaris kasat mata. Namun terpatri kokoh pada sanubari lelaki itu “wa la ghalib ilallaha”. Rupanya, benda itu sakral peninggalan moyangnya. Suku Nasrid dari golongan bani Kharaj di Granada, pertahanan terakhir ummat muslim di benua itu dari genggaman kristendom dahulu. Kali ini, replika itu tidak hanya kan menjadi symbol bekas kejayaan seperti zaman ia di bangun, replika mungil itu merupakan replika keteguhan sang lelaki. Itu monument Al-Hambra’ persis nama belakangnya. Angin sore membuat musim panas di Broadway menjadi lebih bersahabat. Bunga-bunga hortensia mungil juga bermekaran cantik. Hans menyentuh luka-luka di tangannya yang mulai mengering, masih sangat perih. Lalu ponselnya bergetar pelan, sebuah pesan singkat masuk, dari Jules.
“Hans, kau harus pulang sekarang”
Hansa segera tahu, ini mengenai Nunsius itu lagi.
******


 Hf.Anisa
Hf.Anisa









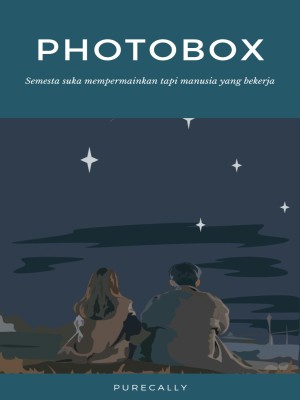

Ide, plotting dan style seleraku banget.
Comment on chapter Pulanglah, HansMampir ke tulisanku juga ya.