Kicauan burung terdengar bak lantunan lagu di pagi hari yang menyejukkan itu. Awalnya Aya berencana untuk menikmati aroma pagi dengan berjalan kaki, tapi Farel bersikeras untuk mengantarnya ke rumah sakit dengan mobil.
“Tangan lo masih kerasa sakit gak, Ya?” tanya Farel memecah hening, menatap lengan kiri Aya yang kini tertutup gips. “Sudah hampir seminggu kan.”
Aya menoleh lantas menggeleng mendengarnya. “Cuma ngilu aja kok.”
“Waktu itu dokternya ngejelasin ke gue kalo tangan lo cuma retak, bukan patah,” jelasnya selagi menunjukkan lengannya, memberikan penjelasan pada Aya bagian tulangnya yang retak. “Jadi gak terlalu parah, bisa sembuh sebulanan lagi.”
“Sebulan, ya,” bisiknya mengerti.
Perjalanan menuju rumah sakit pun berujung sunyi, Aya lebih banyak memusatkan perhatian pada jalanan yang macet. Sopir mobil kadang kali menceletuk kesal ketika ada satu dua pemilik kendaraan bermotor yang seenaknya menyelip jalannya.
Keadaan berubah menjadi tegang ketika mobil menepi di rumah sakit, membuat dada Aya sesak mengingat akan berjumpa kembali dengan Ayahnya. Lega dan takut bercampur menjadi satu.
“Kenapa Ya?” tanya Farel ketika dia menyadari kebisuan gadis itu.
“Engga, cuma aneh aja ke RS melulu,” jawabnya dengan singkat, tidak ingin membuat lelaki itu khawatir. “Ayo masuk.”
Dengan langkah berat Aya memasuki rumah sakit, suasananya yang kelam pun menyambutnya. Terdapat banyak suster yang berjalan cepat mengantarkan pasien ke kamarnya atau sekedar berjaga menunggu panggilan.
Yang membuatnya memilukan adalah pemandangan pasien-pasien, banyak di antaranya mengeluh kesakitan atau terduduk diam menahan penderitaan mereka.
Inilah sebabnya Aya tidak pernah menyukai rumah sakit semenjak kecil.
“Oh ya, lo gak manggil Lily?” ucap Aya ketika dia teringat akan temannya, sudah sewajarnya mereka mengajaknya untuk menjenguk Ayahnya bersama.
Melihat dari wajah terkejut Farel, sudah jelas bahwa lelaki itu lupa mengabari pacarnya tentang kunjungan ini. Dengan cepat dia segera menghubungi Lily, berharap gadis itu tidak memarahinya.
Tidak butuh waktu yang lama bagi Lily untuk menyusul, segera diantar oleh sopirnya menuju rumah sakit dengan kecepatan penuh. Ketika akhirnya tiba gadis itu menatap Farel dengan kesal selagi menghirup napas lelah, kecewa dilupakan.
“Gitu ya sekarang, lupain gue.” Lily mendesis jengkel terutama pada pacarnya itu. “Jadi sekarang cuma kalian berdua ya yang jalan bareng.”
“Duh Ly, jangan ngambek dong.” Aya berusaha menangani, tidak ingin menambah pelik masalah.
Mendengarnya hanya membuat gadis itu semakin memberengut, mimik kesal karena ditinggalkan tertanam jelas di wajahnya.
“Yaudah ayo jenguk om.” Lily melambaikan tangannya, menyuruh keduanya untuk segera mengikutinya. “Semoga om udah sadar.”
Aya yang mendengarnya lantas menyadari keanehan akan keadaan Ayahnya.
“Katanya keadaan Ayag gue gak bahaya, tapi kok belum sadar juga?” tanyanya dengan curiga selagi mengikuti Lily dari belakang, berusaha menjajari langkahnya.
Lily menghentikan langkahnya ketika mereka berada di depan pintu kamar rawat inap, gadis itu membukanya selagi membisu.
“Sebenernya,” ujarnya dengan ragu, kini menatap Farel untuk menunggu izin. “Kondisi Ayah lo bukan sekedar luka bakar doang, Ya. Tapi lebih serius.”
Mendengarnya membuat Aya tersentak.
“Maksudnya?”
“Ayah lo kritis.” Kini Farel yang menyambung penjelasan Lily, membuat Aya semakin yakin mereka saling bertukar rahasia di belakangnya. “Dia sempat beberapa kali koma.”
Betapa terkejutnya Aya ketika mendengarnya, bagai sisa-sisa harapan dalam hidupnya menguap bersamaan dengan kepercayaan dirinya untuk berjuang.
Dalam hati Aya berpikir dengan gelisah akan alasannya untuk hidup. Untuk apa dia bersusah payah mempertahankan kehidupan menyakitkannya tanpa tujuan.
Kenapa dia hidup? Untuk apa?
Betapa mudah persoalannya jika dia mati saja, karena yang tersulit adalah hidup. Tidak ada yang lebih sulit dari hidup. Terutama kehidupan tanpa arti.
“Ya, sori kita ngerahasiain-“ Ucapan Lily terpotong oleh helaan napas Aya.
“Gue gak apa-apa kok.” Aya menolehkan kepalanya pada kedua temannya, memaksakan senyuman. “Mending gue ke cafe aja sekarang, sabtu gini pasti rame.”
Tapi Lily menahan langkahnya, digenggamnya tangan Aya. “Ya, lo boleh kok marah atau nangis! Jangan maksain diri buat senyum.”
Mendengarnya hanya semakin membuat hati Aya teriris. Dia sudah berusaha untuk memaksakan diri untuk tidak terlarut dalam kesedihan terutama di hadapan Lily. Kenapa gadis itu tidak membiarkannya pergi saja?
“Cukup, Ly.” Farel menengahi, melepaskan genggaman Lily dari Aya. Membiarkan gadis dengan nasib malang itu melangkah keluar dengan perasaan hancur.
***
“Sialan! Tamu tadi nyebelin banget!”
Aya hampir terlompat kaget mendengar teriakan Lidia dari balik tempat penggorengan, dia sedang menghangatkan kentang dengan emosi. Diambilnya segenggam kentang lantas dilemparkannya dengan cepat ke tempat penggorengan.
“Aduh, jangan marah-marah dong Lidia,” tegur Pak Rio sambil tertawa. “Kenapa sih?”
“Dia minta uangnya dibalikin gara-gara gue telat ngehidangin makanan.” Lidia mencibir selagi memperagakan perilaku pelanggannya tadi. “Padahal pesenannya emang butuh waktu!”
Mendengarnya Pak Rio hanya tertawa renyah, memaklumi emosi Lidia.
“Kan hal kayak gini emang biasa, Lidia,” ujarnya dengan ramah. “Pasti ada sesuatu, kan?”
Lidia hanya menghela napas menanggapi pertanyaan pemilik cafe. Dengan malas dia melanjutkan pekerjaannya menggoreng sisa kentang yang belum tersentuh api.
Melihat Lidia yang sudah kembali tenang membuat Aya melanjutkan pekerjaannya membawa nampan berisi es krim pesanan pelanggan. Lengan kanannya yang masih sehat dengan cekatan meletakkan gelas es krim.
“Ini ya.”
Selama bekerja sejujurnya pikiran Aya tetap terpaku pada suatu perkara. Tentunya dia selalu memikirkan Ayahnya, kemungkinan keselamatannya yang tidak diketahuinya.
Tapi mayoritas waktunya digunakannya untuk memikirkan kehidupannya ke depannya. Aya masih SMA, tapi dia sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan Ayahnya.
Kadang kala juga di sela-sela lamunannya dia memikirkan Farel. Tentang betapa pedulinya dia kepadanya dulu, ketika dirinya sempat membuat jantung Aya sedikit berisik.
Tapi kepedulian Farel sekarang hanya untuk Lily.
“Aya, sini lo!” panggil Lidia dengan nada yang menimbulkan kekhawatiran pada Aya.
Dengan cepat Aya berjalan ke arahnya, dia sedang berkacak pinggang di depan dapur.
“Liat Radit gak? Bocah itu harusnya ikut kerja di sini.” Lidia memberengut memikirkan lelaki itu, tampang kesal terpampang jelas di wajahnya. “Pasti keluyuran lagi.”
“Gue gak liat sih, Mbak.” Aya dengan hati-hati berujar, takut menyinggung perasaan Lidia.
Mendengarnya hanya membuat wanita itu semakin kesal.
“Gue bisa minta tolong lo suruh Radit kerja, gak?” tawarnya dengan gaya pasrah, bagai memaksa kerja lelaki itu adalah perkara hidup mati. “Seret gitu.”
Walaupun Aya ingin membantunya tapi dalam hati dia tahu akan sulit baginya untuk bertemu lagi dengan Radit. Pertemuan pertamanya tidak berjalan dengan baik, lelaki itu menatapnya bagai elang pada mangsa.
Sepertinya Lidia menyadari keengganan Aya, maka dia memikirkan hal lain.
“Gini deh,” ucapnya. “Kalo lo bisa buat dia kerja, setengah gaji gue bulan ini bisa buat lo.”
Mendengarnya membuat Aya sedikit antusias, dia memang sedang membutuhkan uang.
Maka dengan cepat gadis itu menyetujuinya tanpa pikir panjang.
Lokasi pertama yang menyeruak dalam pikiran Aya tentunya adalah gang dekat cafe mengingat itulah tempat pertama ketika mereka bersua.
Dengan langkah cepat Aya segera meninggalkan cafe sebelum terlebih dahulu meminta izin pada Pak Rio, kemudian beranjak menuju gang.
Ditiliknya lokasi tersebut dengan hati-hati, menyadari sampah rokok yang berserakan bagai bir di rumahnya dulu. Mengingatnya hanya membuatnya sesak.
“Gak ada,” gumamnya sedih. Dia hanya pernah berjumpa dengan Radit sekali itu pun berakhir buruk. Bagaimana mungkin Aya bisa mengira-ngira lokasi orang asing?
“SIALAN!” Bulu kuduk Aya lantas berdiri ketika didengarnya teriakan itu, entah kenapa terasa familier di telinganya. “Enak banget ninggalin orang pas bokek, dasar temen ada butuhnya doang!”
Ketika Aya sudah mengenali sosok Radit dalam balutan seragam yang samar-samar tercium bau rokok dan alkohol, lelaki itu menatapnya tajam seketika.
“Um, lo disuruh sama Mbak Lidia buat kerja.”
Radit memutar matanya dengan kesal bagai mendengar lelucon garing. Ditatapnya Aya dengan ekspresi malas yang membuat gadis itu tidak berkutik.
Tapi tiba-tiba, suatu ide terpampang dalam otak lelaki itu saat seringai mulai menghiasi wajahnya.
“Gini deh,” ujarnya selagi melangkah mendekati Aya, membuat gadis itu menelan ludah. “Kalo lo minjemin gue duit, gue mau kerja di cafe sialan itu.”
Mendengarnya hanya membuat kaget, entah kenapa jantungnya berdegup dengan takut.
“Pinjemin gue 500 ribu aja!”


 DyaPrim
DyaPrim




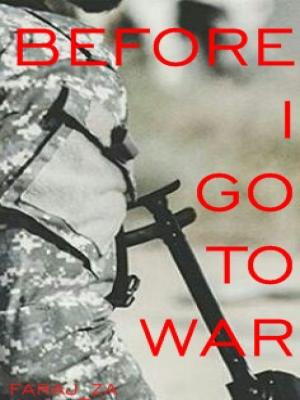









Awal bca lgsg tertarik
Comment on chapter Hidup yang Membosankan:D