Dani masih tidur. Dia tidak enak badan sejak semalam. Panasnya tinggi sekali. Ajat dan Asep segera mencari pak Wasid. Tempat kami mengadu dalam segala masalah. Biasanya Pak Wasid selalu bisa melakukan apa saja. Dia serba tahu. Kadang bisa menjadi guru, dokter, bahkan orang tua bagi kami.
Aku diam di rumah kardus menjaganya. Ajat dan Asep belum datang juga. Aku kesal. Padahal jarak dari rumah kardus ke rumah Pak Wasid tidak terlalu jauh. Hanya tersekat beberapa rumah saja dari sini.
“Jang, aku mau minum.” Dani menepuk lenganku.
Aku segera mengambilkannya minum. Sengaja aku membeli air minum dalam kemasan agar lebih higienis. Sesekali kami memang harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Karena selama ini kalau tidak dari sisa orang lain, kami terbiasa meminum air hujan yang diendapkan.
“Ajat dan Asep ke mana?” matanya melihat setiap sudut rumah kardus.
“Mereka sedang mencari Pak Wasid. Semoga dia bisa mengobatimu.”
Dani hanya mengangguk, lantas kembali tertidur.
Aku takut. Aku takut dia kenapa-kenapa. Baru kali ini Dani yang biasanya selalu terlihat riang, sakit parah. Entahlah, kemarin dia masih baik-baik saja. Bercanda dan bermain bersama kami di sungai. Memulung di bawah teriknya panas matahari. Berlarian mengikuti angin sore.
Pak Wasid datang.
Aku segera mempersilakannya masuk. Dia membawa kotak obat. Wajahnya terlihat sangat cemas. Ajat dan Asep membawakan buah-buahan yang beragam. Kami memang mungkin memerlukan asupan gizi yang baik. Bukan hanya Dani. Kami jarang makan makanan yang sehat seperti buah-buahan.
“Kenapa kalian tidak bawa saja dia ke dokter?” Pak Wasid bertanya sambil menatapku.
“Kami takut tidak bisa membayarnya. Bukankah biaya pengobatan itu mahal?” Aku balik bertanya.
“Kau rela membiarkan temanmu dalam keadaan seperti ini? Ini gejala tifus! Banyak yang sampai meninggal karena tifus. Sekarang kita bawa saja dia ke dokter, sebelum terlambat.”
Aku tersentak. Apalah artinya uang untuk nyawa seorang teman. Ternyata aku masih bodoh. Kenapa bukan sejak tadi aku bawa saja Dani ke dokter? Pak Wasid mungkin serba tahu. Tapi untuk masalah kali ini, kenapa aku tega membiarkan Dani terbaring lemas?
Pak Wasid menggendong Dani, membawanya ke dokter terdekat. Kami semua ikut mengantarnya. Aku mungkin menjadi orang yang paling khawatir dengan keadaan Dani. Perasaan bersalah menghinggapiku sejak mendengar apa yang dibicarakan Pak Wasid padaku.
“Geus, teu nanaon da, tong dipikiran teuing.” (Sudah, tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan). Ajat berusaha menghiburku.
“Benar, ini bukan hanya salahmu. Ini salah kita juga. Sudah…” Asep menepuk pundakku.
Aku tersenyum pada mereka.
-----
Kami sampai di klinik 24 jam. Antreannya penuh sekali. Kami terpaksa menunggu lama. Pak Wasid sempat membujuk petugas klinik untuk bisa masuk lebih dulu. Tapi pasien lain malah memarahinya. Dia mengalah. Tapi tetap saja wajahnya terlihat sangat cemas. Keringatnya bercucuran. Kakinya tidak bisa diam. Di saat seperti ini aku merasa memiliki orang tua. Aku bersyukur.
“Bu, antreannya masih lama?” Pak Wasid kembali bertanya.
“Sebentar ya Pak, pasien lain juga sama-sama menunggu sejak pagi. Bahkan ada yang menginap.” Jawab si Ibu yang berpakaian putih-putih.
“Saya tidak bertanya tentang itu Bu, saya tanya apa antreannya masih lama?” Pak Wasid terlihat kesal dengan jawabannya.
“Bapak pegang kartu nomor berapa?”
“Saya dapat antrean nomor 124 Bu.”
“Sebentar lagi Pak. Ini sudah nomor 122 ternyata. Sabar ya Pak.”
Aku merasa lega mendengar antreannya sudah dekat.
Keadaan Dani sangat mengkhawatirkan. Badannya terlihat lemas. Wajahnya pucat pasi. Sambil duduk, dia bersandar, tidak bisa tegak. Kami terpaksa menunggu di luar klinik, semakin lama semakin banyak saja pasien yang berdatangan. Biarlah, Dani akan aman bersama pak Wasid.
Suara perut Ajat terdengar jelas. Kami tertawa. Sejak pagi, belum satu pun makanan masuk ke dalam perut kami. Asep mengeluarkan uang lima ribu rupiah dari saku celananya.
“Beli gorengan, biar dapat banyak.” Aku berusul.
“Jangan, beli nasi saja biar kenyang. Lauknya, kuah saja.” Tukas Ajat.
“Jadi mau beli apa? Gorengan atau nasi?” Tanya Asep kesal.
“Ya sudah, beli nasi saja. Biar kenyang sekalian.” Aku mengalah.
Asep berlari ke tempat warung nasi di seberang jalan. Kelihatannya warung nasi itu penuh sekali. Akan sedikit lama kami menunggu untuk makan.
“Jang,” Ajat memanggilku.
“Apa?” Aku menoleh padanya.
“Lihat, banyak yang parkir, tapi tidak ada tukang parkirnya. Kita jadi tukang parkir dulu saja di sini. Siapa tahu mereka bayar kita,” ucap Ajat sambil tersenyum sinis. Masalah peluang uang dia memang jagonya.
“Boleh, ide bagus.” Aku menyetujuinya.
Motor yang terparkir semakin banyak. Yang pulang pun banyak. Setiap yang keluar area parkir kami bantu untuk memasuki jalan raya. Mereka memberi kami uang dua sampai lima ribu. Banyak sekali. Setimpal dengan apa yang kami lakukan. Setiap motor lain masuk, kami rapikan parkirnya. Mereka tidak marah motornya dipegang oleh anak jalanan yang kotor seperti kami.
“Nah bagus dek, di sini memang tidak ada tukang parkir. Bagaimana kalau kalian jadi tukang parkir saja di sini? Lumayan kan uangnya.” Ucap seseorang dengan berpakaian dokter yang keluar dari klinik.
“Memangnya boleh ya Pak?” Tanya Ajat kegirangan.
“Boleh, besok saya kasih seragam tukang parkirnya, oke?”
“Oke Pak!” Kami menjawab bersamaan.
Setelah berbicara pada kami, dia lantas masuk ke warung makan di seberang jalan. Asep masih di sana. Malah, mereka terlihat berbincang-bincang ketika Asep hendak keluar dari warung, kemudian Asep kembali masuk ke warung. Tak lama, dia keluar lagi, menyebrangi jalan sambil berlari. Wajahnya terlihat senang.
“Kita dapat lauk yang layak, lihat!”
Asep membuka bungkusan nasinya. Ada tiga bungkus, lengkap dengan ayam, tempe, dan sambal. Aku senang melihatnya. Ajat langsung memakannya tanpa banyak basa-basi.
“Kamu punya uang dari mana Sep?” Tanyaku menyelidik.
“Tadi ada dokter baik yang membelikannya. Tadinya dia mau mengajakku makan di sana, tapi aku bilang kalau teman-temanku sedang menunggu di depan klinik. Dia lalu menyuruh pemilik warung untuk memberiku makanan lagi dengan lauk yang lebih layak. Dan uangku pun utuh.”
“Ah, dokter itu, tadi dia…”
“Sudah, nanti saja ceritanya, kita makan saja dulu.” Ajat memotong ucapanku.
Aku mengangguk. Hari ini kami mendapat banyak keberuntungan. Uang dari hasil parkir lumayan banyak. Dan kami bisa makan enak dengan gratis. Sayang, ketika kami mendapat ini semua, Dani sedang sakit. Dia tidak ikut merasakannya. Biarlah, semoga saja ketika dia sembuh, kami bisa membelikan makanan serupa untuknya.
Tak jarang ketika makan, kami terganggu oleh motor yang hendak keluar dari parkiran. Aku harus meninggalkan alas makanku sebentar, membantunya, lantas medapat uang dari si pemilik motor.
“Sejak kapan kau menjadi…”
“Nanti saja kujelaskan.” Tukasku ketika Asep hendak bertanya.
-----


 AyPurnama
AyPurnama








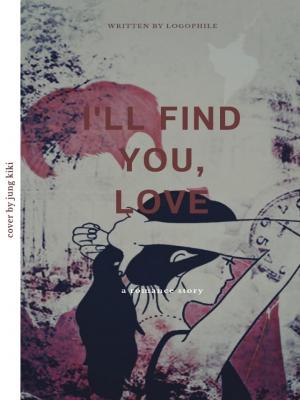

@Itikittiy aku masih muda kok kwkwk
Comment on chapter Rongsokan