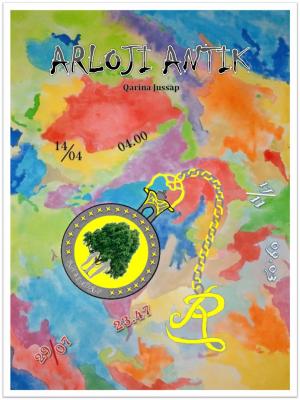Kursi rotan di teras rumah itu sudah miring ke kiri. Salah satu kaki rotannya patah setengah, dan bunyinya selalu berdecit ketika seseorang duduk. Tapi anehnya, tak satu pun dari kami tega membuangnya. Bukan karena sayang pada benda, tapi karena... ada tawa yang masih tinggal di sana.
Aku ingat betul, dulu kursi itu adalah tempat rebutan. Entah kenapa, meskipun kami punya bangku panjang dan beberapa kursi plastik, kursi rotan itu selalu jadi primadona. Mungkin karena letaknya di pojok teras, tepat di bawah jendela ruang tamu, tempat angin sore paling rajin mampir.
Atau mungkin karena di sanalah Ayah duduk setiap sore, dengan teh manis hangat di tangan kanan dan koran di tangan kiri—yang jarang benar-benar dibaca, karena lebih sering tertawa mendengarkan celotehan kami.
“Kalau Ayah duduk di situ, itu tandanya pintu rumah boleh dibuka,” kata Dira suatu sore. Kami berdua sedang menata pot tanaman. Ia memindahkan pot lidah mertua ke dekat pilar, dan aku menyapu dedaunan kering.
“Kenapa?” tanyaku.
“Soalnya kalau Ayah lagi duduk di kursi itu, suasana rumah tuh kayak... lagi nerima tamu. Padahal ya cuma kita-kita aja yang ribut,” jawabnya sambil terkikik.
Aku mengangguk, lalu menepuk-nepuk kain lap di tanganku. “Iya ya. Rasanya rumah kayak hidup kalau kursi itu keisi.”
Dulu, setiap sore, kami biasa mengelilingi Ayah yang duduk di sana. Kadang sambil makan pisang goreng, kadang cuma duduk-duduk sambil cerita. Dira sering menyanyi lagu-lagu iklan TV. Aku membacakan puisi yang tak berima. Dan Ayah akan tertawa—tawa yang khas, sedikit berat tapi penuh kehangatan.
Dan di momen itulah, entah kenapa, segala masalah jadi terasa ringan.
Ada satu hari yang tak pernah bisa kulupa. Saat itu aku pulang dari sekolah dengan wajah murung. Aku dapat nilai jelek di ujian Matematika, dan guru sempat menyindirku di depan kelas. Waktu aku masuk ke rumah, aku langsung melewati dapur dan masuk ke kamar. Tapi Ayah tahu. Ayah selalu tahu.
Sore harinya, ia duduk di kursi rotan itu, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya, bukan koran. Melainkan... kertas ujian milikku, yang entah bagaimana bisa sampai ke tangannya. Dan bukannya marah, ia malah menulis angka 100 besar-besar di belakangnya dan menunjukkan padaku sambil tersenyum lebar.
“Ini nilai yang Ayah kasih karena kamu pulang tepat waktu dan nggak nyerah,” katanya.
Aku cuma bisa melongo, lalu ketawa. Tertawa sambil setengah menangis. Dan Ayah, di kursi rotan itu, hanya mengangguk-angguk seolah berkata: "Kamu nggak harus selalu berhasil, Nak. Tapi kamu harus selalu pulang."
Sejak saat itu, kursi rotan itu punya arti baru buatku. Bukan hanya tempat duduk. Tapi tempat kembali. Tempat menaruh semua kesedihan, dan menukarnya dengan tawa.
Tapi seperti semua benda yang terus ditempati waktu, kursi itu pun mulai rapuh. Anyamannya mulai longgar. Warnanya kusam. Tapi kami tak pernah menggantinya. Tak ada yang bisa mengganti suara ‘kreekk’ khasnya yang muncul setiap kali seseorang duduk.
Dira bilang, suara itu seperti salam sapa.
“Dia tuh kayak bilang ‘eh, kamu balik lagi ya?’” kata Dira sambil duduk di kursi itu beberapa hari yang lalu. Kami sedang minum teh sore, seperti dulu.
“Tapi kalau kamu duduk terlalu lama, bisa kesangkut di waktu,” jawabku.
“Maksudnya?”
Aku menatap daun-daun mangga yang bergoyang pelan tertiup angin. “Di kursi itu... kita bisa tiba-tiba inget Ayah ketawa. Inget Ibu bawa teh. Inget kamu nyanyi ‘sirop marjan, sirop marjan’. Dan... lupa kalau sekarang udah tahun 2025.”
Dira tertawa, tawa yang seperti dulu. Lalu ia diam sejenak, memeluk lututnya. “Kamu tahu nggak, kadang aku masih berharap, kalau duduk di kursi ini cukup lama, Ayah bakal datang keluar dari rumah, duduk di sebelahku, dan bilang: ‘Mbak, korannya mana?’”
Kami tertawa. Tapi tawa itu sedikit tercekat.
Karena memang, kadang harapan tidak butuh masuk akal. Cukup jadi nyala kecil di dalam dada, supaya hari tidak terlalu gelap.
Beberapa minggu lalu, keponakan kami—Anya—yang baru berumur lima tahun, datang bermain ke rumah. Ia berlari-lari ke teras, dan seperti tertarik magnet, langsung duduk di kursi rotan itu. Kursinya berdecit, dan ia tertawa geli.
“Ini kursinya lucu banget, Bun!” katanya pada ibunya.
Kami yang mendengar hanya saling pandang dan tertawa kecil. Mungkin kursi itu tahu, waktunya belum habis. Masih ada generasi lain yang akan duduk di sana, membawa cerita dan tawa baru.
Hari ini, aku dan Dira memutuskan untuk memperbaiki kursi itu. Bukan untuk dijadikan baru. Tapi cukup diperkuat, supaya masih bisa menampung cerita.
Kami membeli paku baru, lem rotan, dan cat cokelat tua. Kami duduk di teras, seperti dulu, dan bekerja pelan-pelan. Di sela-sela memperbaiki, kami bercerita. Tentang Ayah, tentang masa kecil, tentang hal-hal yang dulu dianggap biasa tapi sekarang terasa mahal.
Setelah selesai, kami duduk berdua di sana. Kursinya masih berbunyi, tapi sedikit lebih stabil. Dan di situlah, saat senja mulai turun, kami tertawa.
Tawa yang tidak keras. Tapi cukup hangat untuk membuat kami merasa: rumah ini, kursi ini, dan kenangan ini... masih hidup.
Dan mungkin, benar kata Dira: Beberapa tawa memang tidak hilang. Ia hanya tersangkut sebentar di kursi rotan.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_