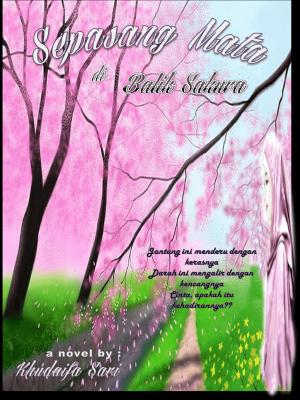Aku membaringkan badanku di atas sofa yang sangat empuk ini, setelah melempar tubuh Rafa keatas kasurku. Ya, kuputuskan untuk membawanya ke dalam kamarku di lantai atas, kemudian aku tidur di lantai bawah.
Aku memasukkan tanganku kedalam kantong. Ingin mengambil HPku…HILANG!. Apa mungkin jatuh di atas ya, aku segera kembali kekamarku untuk mencari HP dengan Rington noraknya itu. Namun ketika kubuka pintu kamar.
Rafa dengan posisi duduk melihatku. Masih setengah sadar “Yud, kamu mau dengan ceritaku, nggak?” tanyanya.
Aku duduk di meja kerja yang tepat berada di samping kasur, aku tau anak ini masih sedang mabuk, tapi akan kudengarkan ceritanya “Mau banget Rap, gimana tuh?” ucapku sok asik, aku udah siap untuk mendengar ceritanya, tapi kalo tiba-tiba ia malah cerita tentang mantan, aku akan lansung lompat ke jendela saat itu juga.
Rafa menundukkan kepalanya, tangannya mencengkeram ujung selimut, seperti sedang mencoba menahan sesuatu. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara, suaranya sedikit serak.
“Makasih ya, Yud…” suaranya pelan, hampir tenggelam di antara desahan napasnya sendiri. “Aku tuh… capeek banget.”
Dia mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang sedikit merah. “Kerja sebagai sales ini… aku bener-bener nggak suka. Aku benci sama kerjaanku, aku benci sama hidupku sekarang. Aku benci sama keputusanku dulu.”
Aku terdiam, membiarkan dia melanjutkan.
“Aku dulu pengen banget gap year, belajar lebih serius biar bisa jadi dokter. Tapi aku terlalu takut buat ambil resiko, terlalu takut buat melawan. Jadinya ya…” Rafa terkekeh kecil, tapi nadanya pahit. “Aku milih kuliah aja, meskipun bukan di jurusan yang aku mau. Dan sekarang, aku cuma bisa kerja kayak gini, jualan rumah yang aku sendiri nggak mampu beli.”
Dia menengadah ke langit-langit, mendesah panjang. “Kadang aku mikir… kalau aja dulu aku lebih berani, mungkin hidupku bakal beda.”
***
Rafa Azaela duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop yang menampilkan pengumuman seleksi universitas. Tangan kanannya menggenggam ponsel erat, sementara ibunya di seberang sana berbicara dengan nada penuh harap.
"Rafa, alhamdulillah kamu keterima, Nak! Mama bangga banget sama kamu. Ini kesempatan yang nggak boleh disia-siain."
Rafa tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada nama universitas yang tertera di layar—bukan fakultas kedokteran seperti yang selama ini ia impikan, melainkan jurusan yang ia pilih karena keadaan. Jurusan yang ia paksakan masuk, hanya karena dia takut kehilangan kesempatan untuk kuliah.
"Tapi Ma… Rafa masih pengen coba lagi tahun depan."
Ibunya terdiam sesaat. Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Sayang, kamu tahu kan, mama nggak bisa biayain kamu buat coba lagi? Lagipula, kuliah itu bukan soal jurusan, tapi soal usaha dan rezeki. Kamu pasti bisa sukses, Nak, nggak peduli di mana pun kamu belajar."
Dan di situlah Rafa menyerah. Ia menekan tombol “terima” pada pengumuman, mengabaikan gejolak di dadanya.
Tahun-Tahun yang Berlalu.
Empat tahun berlalu dengan cepat. Rafa lulus dengan predikat baik, mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya menikah dengan seorang pria yang awalnya ia kira bisa menjadi teman hidup yang tepat.
Namun, kenyataan jauh lebih pahit dari bayangannya.
Hari itu, Rafa pulang lebih awal dari kantor. Tangannya lelah membawa dua kantong belanjaan yang ia beli dengan gajinya sendiri. Saat membuka pintu apartemen kecil mereka, ia mendapati suaminya—Fajar—duduk santai di sofa dengan rokok terselip di bibirnya, matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan situs judi online.
Di atas meja, botol-botol minuman berserakan, bersama dengan tiket lotre yang entah sudah berapa banyak.
"Kamu udah di rumah?" Fajar meliriknya sekilas, sama sekali tidak berniat membantu membawa belanjaan.
Rafa hanya mengangguk. Ia berjalan ke dapur, menaruh barang belanjaan dengan hati-hati. Saat ia membuka kulkas, hanya ada sisa lauk dingin dari kemarin.
"Kamu nggak beli makanan?" tanyanya sambil menatap suaminya.
Fajar menghela napas panjang, lalu menendang meja kecil di depannya hingga botol-botol itu berguling ke lantai.
"Aku lagi sibuk, Rafa! Duitmu kan banyak, yaudah beliin aja sendiri!" suaranya meninggi.
Dada Rafa sesak. Ini bukan pertama kalinya. Fajar tidak pernah bekerja serius sejak mereka menikah, selalu beralasan sedang mencari peluang, selalu menunggu ‘keberuntungan’ yang tak pernah datang. Rafa tahu, ia yang membiayai semuanya—sewa apartemen, makanan, bahkan kebiasaan buruk suaminya.
Suatu hari, ketika pulang lebih larut dari biasanya, ia mendapati Fajar duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam.
"Uang di rekening kita tinggal segini! Kamu kemana aja seharian!?" teriaknya, sambil melempar ponselnya ke meja.
Rafa menahan napas. Dia tahu.
"Aku kerja, Fajar. Mencari uang buat kita." suaranya lelah, tapi tetap tenang.
Fajar tertawa sinis. "Kerja? Nggak cukup! Harusnya kamu tahu cara cari uang lebih cepat!"
Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Fajar menamparnya.
Rafa tidak bisa bergerak selama beberapa detik, wajahnya panas dan berdenyut. Matanya menatap pria yang dulu ia pikir bisa menjadi pendamping hidupnya—seseorang yang seharusnya melindunginya, bukan menyakitinya.
Saat itu, Rafa sadar. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri.
Ia memilih untuk tidak mengejar mimpinya. Ia memilih menyerah pada keadaan. Dan sekarang, ia terjebak dalam hidup yang tidak pernah ia inginkan.
Malam itu, Rafa duduk di dalam kamar gelap, meraba wajahnya yang memar. Bagaimana jika dulu ia lebih berani? Bagaimana jika dulu ia memilih untuk tetap berjuang?
Namun saat itu Rafa masih tidak menyerah, ia percaya suaminya akan berubah nantinya jika ia memperlakukannya dengan baik. Akhirnya Rafa kembali kerja keras bahkan lebih keras dari sebelumnya, tentu saja ia melakukan itu meskipun ia tidak menyukainya.
Setelah Rafa bekerja bekitu keras, bagaimana dengan suaminya? Tentu saja tabiatnya semakin buruk, bukannya berubah seperti yang diharapkan, suaminya malah tambah parah. Suatu hari suaminya kehabisan uang karena bermain slot, dan itupun uang yang ia pinjam dari pinjol, siapa yang akan membayarnya? Ya, benar. Rafa lah yang membayar semua utang pinjol suaminya.
Pada suatu hari di pagi-pagi buta seorang deptcollector mendatangi rumah kecilnya.
“Assalamualaikum, apa benar ini rumah pak Fajar?”
Ekspresi Rafa yang tadinya tersenyum seketika berubah, ia tau jika ada orang mencari suaminya tentu saja untuk menagih utang, “Benar pak, saya istrinya.”
“Oh, kebetulan sekali ibu, ini pak Fajar sudah mengutang dengan kami sebanyak 120 juta bu, dan sudah menunggak selama 3 bulan, kami telpon tidak pernah di jawab oleh beliau.”
“Minggu depan akan saya bayar pak!” Rafa segera menutup pintunya.
“Baik bu, saya tunggu minggu depan, ini kesempatan terakhir! Jika tidak saya akan mengambil rumah ini!” ucap pria itu sebelum akhirnya pergi.
Mata Rafa mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap menahannya. Tangannya mencengkeram tepi pintu, berusaha menjaga tubuhnya agar tidak goyah.
120 juta.
Lebih dari yang ia bayangkan. Lebih dari yang ia sanggupi.
Napasnya memburu, tapi ia harus tetap tenang. Kalau dia panik, semuanya akan makin berantakan.
Ia menggigit bibir, menoleh ke arah suaminya yang tertidur pulas di atas kasur. Tidurnya begitu nyenyak, seolah tak ada beban sama sekali. Seolah tidak ada rumah yang nyaris disita. Seolah tidak ada rentetan masalah yang sudah ia timbulkan.
Bagaimana bisa?
Rafa menarik napas dalam-dalam, tapi dadanya tetap terasa sesak. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa semua ini akan membaik. Bahwa kalau ia cukup sabar, cukup bekerja keras, cukup mencintai... suaminya akan berubah.
Tapi kenyataannya?
Semakin ia berkorban, semakin hancur hidupnya.
Jari-jarinya mengepal. Ia tidak bisa terus begini. Ia tidak bisa terus menjadi satu-satunya yang berusaha.
Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat ke tempat tidur. Tangannya terulur, menyentuh bahu suaminya. Kali ini, ia tidak akan membiarkannya menghindar.
“Sayang,” Rafa menggoyangkan badannya pelan.
Tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya—kali ini, suaranya terdengar tegas.
“Hah, kenapa? Aku masih ngantuk Rap, kalo mau pergi kerja pergi lah sana, gak usah pake salim-salim segala, lebay.” Ucap suaminya masih memeluk gulingnya dengan erat.
Ia tidak tahan. Bagaimana bisa suaminya begitu santai? Seolah 120 juta hanyalah angka di udara. Seolah hidup mereka tidak di ambang kehancuran. Seolah Rafa akan tetap jadi tameng untuk semua kesalahan yang ia buat.
“Fajar…” suara Rafa bergetar, tapi ia menelan ketakutannya. “Kamu sadar gak sih? Kita… kita hampir kehilangan rumah ini!”
Akhirnya, Fajar membuka matanya. Bukan dengan ekspresi kaget atau peduli—tapi dengan tatapan kesal.
“Kenapa sih ribut pagi-pagi? Aku kan masih ngantuk.”
Rafa mencengkeram seprei, tangannya gemetar. “Kamu udah utang 120 juta! Tiga bulan nunggak! Debt collector tadi datang ke rumah! Mereka bilang kalau minggu depan kita gak bayar, rumah ini bakal diambil!”
Fajar mengerutkan kening, lalu tertawa sinis. “Hah? Ya bayar aja lah. Kamu kan kerja.”
Jantung Rafa seperti ditusuk. Ya bayar aja? Seakan 120 juta itu bukan apa-apa. Seakan Rafa tidak lebih dari sapi perah yang harus menyelesaikan semua masalahnya.
“Aku gak bisa, Fajar…” Rafa menarik napas dalam. “Aku gak bisa terus kaya gini. Aku gak bisa terus kerja mati-matian buat nutupin semua kesalahan kamu. Aku gak mau lagi!”
Fajar mendadak bangkit. Matanya kini berkilat marah.
“APA MAKSUDMU?!”
Rafa tersentak mundur, tapi belum sempat ia menjelaskan, tangan Fajar sudah mencengkeram lengannya keras.
“Maksudmu apa, hah? Kamu mulai kurang ajar ya?!” suara Fajar semakin tinggi, napasnya memburu. “Udah kubilang, kamu tinggal bayar aja! Udah kerja tapi gak bisa apa-apa?! Dasar gak berguna!”
Rafa berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman itu makin kuat.
“Fajar… lepasin!” suaranya mulai panik.
Tapi Fajar tidak mendengarkan. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rafa.
Keningnya terasa panas, pandangannya berkunang-kunang. Tapi belum sempat ia bereaksi, tangan suaminya kembali terangkat—lebih keras, lebih kejam.
BRAK! Rafa terjatuh ke lantai. Punggungnya menghantam meja kecil di sisi ranjang. Sakit.
Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak.
“DASAR PEREMPUAN GAK TAU DIRI!” Fajar berteriak, mencengkeram rambut Rafa dan menariknya ke atas.
Air mata Rafa mengalir deras. Ini bukan pertama kalinya Fajar memukulnya… tapi kali ini, ia merasa akan mati.
Dan di titik ini, di tengah rasa sakit yang membakar tubuhnya, sesuatu dalam dirinya hancur.
Aku tidak bisa terus di sini. Aku tidak akan bertahan jika aku tetap di sini.
Dengan sisa tenaga, Rafa mendorong Fajar sekuat tenaga dan merangkak ke belakang. Matanya kini bukan hanya penuh dengan air mata, tapi juga dengan tekad.
Ini akhirnya. Aku harus pergi. Sekarang.
Fajar masih berteriak di belakangnya, tapi Rafa tidak mendengar apa pun lagi. Ia bangkit dengan susah payah, menahan nyeri di tubuhnya, tapi ia tidak peduli.
Ia berlari.
Keluar dari kamar.
Keluar dari rumah.
Keluar dari neraka ini.
Udara malam menusuk kulitnya yang memar, tapi ia tidak berhenti. Rafa berlari tanpa menoleh ke belakang.
“RAFA! BALIK SINI KAMU!”
Suara Fajar menggema, tapi untuk pertama kalinya, Rafa tidak takut.
Rafa melepas cincin kawinnya dan menjatuhkannya ke tanah.
Tanpa ragu, ia terus berlari—menuju kebebasan.
Dua tahun berlalu.
Rafa menghabiskan waktu dengan berpindah-pindah pekerjaan, mencoba bertahan hidup dengan sisa tabungannya, di kota yang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Ia mencoba menjadi asisten, kasir minimarket, hingga pegawai administrasi—tapi tidak ada satupun yang terasa tepat.
Hingga akhirnya, sebuah tawaran datang. Sales properti.
"Komisinya gede," kata seniornya saat wawancara. "Tapi ya gitu, kalau nggak bisa jualan, nggak ada gaji pokok."
Rafa menghela napas. Ia tidak punya pengalaman, tidak punya jaringan, bahkan tidak punya kemampuan berbicara yang meyakinkan. Tapi apa pilihan lain yang ia punya?
Jadilah, ia menerima pekerjaan itu.
Hari pertama bekerja, Rafa sudah ingin resign.
Hari kedua, ia mulai melirik lowongan pekerjaan lain.
Hari ketiga, ia duduk di sudut kantor, menatap layar laptop dengan tatapan kosong.
"Dua unit rumah dalam sebulan atau dipecat," ucapan bosnya masih terngiang di kepala.
Sial. Kenapa dia malah memilih pekerjaan ini? Dia bahkan benci berbicara dengan orang asing.
“Sori, sori! Permisi dulu, numpang lewat!”
Sebuah suara menginterupsi lamunannya. Rafa menoleh tepat waktu untuk melihat seorang pria nyaris menabrak printer kantor dengan gelas kopi di tangan. Kopinya tumpah sedikit ke kemejanya, tapi alih-alih panik, pria itu malah tertawa sendiri.
“Ah, nggak apa-apa, kemeja ini juga udah ketumpahan nasib buruk,” gumamnya sambil mengusap noda kopi itu dengan tisu.
Rafa menatapnya tanpa ekspresi.
Seorang pegawai baru?
Pria itu tiba-tiba berbalik, melihat Rafa menatapnya.
“Lho, kok ngeliatin Akunya gitu banget? aku ganteng banget ya?” tanyanya santai.
Rafa mengerutkan kening. “Hah?”
Pria itu menyeringai. "Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Kadang mukaku tuh memang terlalu menawan untuk diproses otak manusia biasa."
Rafa menatapnya lebih lama. "Kamu idiot, ya?"
Pria itu mendadak tertawa. "Kurasa iya, tapi sejauh ini aku belum dapat diagnosa resmi."
Rafa menghela napas panjang. "Kamu pegawai baru?"
"Betul banget! Namaku Yudhis!" katanya sambil mengulurkan tangan.
Rafa ragu sejenak, tapi akhirnya menyambut uluran tangannya. "Rafa."
Mereka berjabat tangan.
"Hmm," Yudhis menatapnya lama. "Rafa... Namamu kayak nama cowok."
Rafa langsung menyipitkan mata. "Mulai hari ini, tugasku adalah bikin hidupmu di kantor ini jadi neraka."
Yudhis mundur selangkah. "Hahaha, becanda, becanda! Ayo kerja sama yang baik, partner!"
Rafa hanya mendengus, tapi di dalam hati, dia merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, ada satu orang di kantor ini yang lebih berantakan dari hidupnya.
Dan mungkin, hanya mungkin, pekerjaan ini tidak akan seburuk yang ia kira.
***
Hari ini Rafa pasrah. Sudah seminggu mereka berusaha, tapi belum ada satu pun rumah yang terjual.
Sementara Yudhis? Dia malah sibuk mencoba menyeimbangkan pulpen di hidungnya.
"Yud, kita dipecat dalam tiga minggu kalau nggak jual dua unit rumah," ujar Rafa, menatap pria di sebelahnya dengan penuh kebencian.
Pulpen di hidung Yudhis jatuh. "Santai, Rap. Peluang selalu datang di saat yang tak terduga."
"Apa?"
"Kita cuma perlu bersabar. Mungkin hari ini bakal ada keajaiban."
"Keajaiban apaan?"
TING!
Pintu lift terbuka.
Sebuah suara berat terdengar dari dalam. "Permisi, bisa tolong tunjukkan unit premium terbaru kalian?"
Rafa langsung membeku. Klien VIP.
Bahkan sebelum pria itu melangkah keluar, aroma parfum mahalnya sudah lebih dulu menguasai udara.
Ini dia momen yang mereka tunggu!
Tapi sebelum Rafa bisa buka mulut—
"Silakan, Pak!" Yudhis malah melangkah masuk ke dalam lift.
TING! Pintu lift menutup. Yudhis dan klien VIP terjebak di dalam. Pintu lift menutup tepat di depan wajah Rafa. Astaga, Yudhis!!
Rafa menoleh ke samping, baru sadar ada tanda besar di dekat lift bertuliskan: “MASIH SEDANG DALAM PERBAIKAN.”
Rafa Hanya bisa melongo dan panik setengah mati. TIDAAAKKKK!!
Lima belas menit kemudian…Teknisi akhirnya berhasil membuka lift. Pintu terbuka perlahan. Yudhis keluar dengan wajah sumringah, sementara klien VIP di sebelahnya tertawa terbahak-bahak.
Klien VIP itu sambil mengusap air mata berkata “Wah, perjalanan yang luar biasa! Saya belum pernah terjebak di lift dan justru merasa terhibur!” Rafa masih Syok dengan apa yang barusan terjadi, menjadi lebih syok lagi, A-apa?
Klien VIP merangkul bahu Yudhis, masih tertawa “Anda benar-benar punya cara melihat dunia dengan santai, anak muda. Saya suka! Anda mengingatkan saya pada diri saya sendiri saat muda.” Rafa menatap Yudhis tak percaya. Yudhis hanya mengangkat bahu santai.
Yudhis dengan gaya sok bijak berucap “Kadang hidup mengurung kita di tempat sempit, Pak. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngobrol asik dan menikmati perjalanannya.”
Rafa berbisik “Kamu serius tadi ngobrolin filosofi di dalam lift?!”
Yudhis mengangguk mantap dan beliau setuju.
Klien VIP menepuk bahu Rafa, kemudian dengan santai berkata “Kalau semua pegawai di sini seasyik anak ini, saya rasa perusahaan ini punya masa depan cerah. Ayo, kita langsung ke rapat.”
Rafa hanya bisa membeku. Yudhis tersenyum lebar, melangkah santai mengikuti mereka. Rafa mengusap wajahnya lelah.
Rafa hanya bisa memasang wajah tersenyum canggung “Kenapa... kenapa setiap kekacauan yang dia buat malah jadi keuntungan?!” ucapnya dalam hati
Yudhis baru aja ngejual rumah gara-gara KEJEBAK di lift!?
Setelah semua itu terjadi ketika klien sudah pergi dengan meninggalkan tanda tangannya di kertas kontrak, Yudhis dengan bangganya menepuk dadanya. "Tuh kan, kubilang juga apa. Peluang selalu datang di saat yang tak terduga."
Rafa ingin menonjoknya.
Tapi di sisi lain, mereka baru saja berhasil menjual satu unit rumah!
Satu langkah lebih dekat dari nggak dipecat.
Dan Rafa, meskipun sebal, tak bisa menahan senyum.
"Baiklah, Yud," katanya akhirnya. "Kamu masih idiot, tapi untuk kali ini... kamu idiot yang berguna."
Yudhis mengangkat alis. "Idiot yang sangat berbakat, maksudnya?"
"Jangan macem-macem. Ayo kerja lagi sebelum kubanting mukamu ke lift lagi."
Mereka tertawa.
Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, Rafa merasa ada harapan.
***
“Makanya aku masih bisa bertahan di sini Yud, tapi sekarang kita bakal di pecat kalau gagal menjual 2 unit rumah dalam waktu sebulan” Rafa masih melanjutkan ceritanya, namun kali ini ia sudah sangat terlihat lelah.
Ooooooohh, jadi gitu ceritanya. Ternyata Pak Bos udah sering ngancam kami buat di pecat toh. Ternyata ada gunanya juga nih anak mabuk “Kamu tenang aja Rap, bersama Yudhis si seles nomor satu sealam jagat, jangankan 2 rumah. Satu komplek pun bisa kujual” ucapku membayangkan diriku yang berhasil menjual satu komplek beneran.
…
…
Kok sepi ya. Aku melirik ke arah kasur. Sialan ternyata Rafa sudah memeluk gulingku dengan erat. Aku padahal sudah mendengarkan ceritanya hampir 2 jam-an, begitu aku bicara nggak nyampe 5 menit, nih anak udah tidur aja.
Aku hanya bisa terdiam, dan malu sendiri karena baru saja bertingkah seperti anak TK sebelum kembali ke lantai bawah untuk beristirahat. Maka kubaringkan tubuhku kembali ke sofa. Waaahh nikmat banget, baring di sofa setelah duduk hampir dua jam mendengar ocehan Rafa. tapi setelah kupikir-pikir, hidup Rafa lumayan berat juga ya. Yaudah lah, udah terjadi juga. Kalau di kehidupan ini aja Rafa masih bisa bertahan meski terjebak di jalan yang dia nggak suka, kenapa aku harus terus takut sama pilihanku?
Akhirnya aku mulai memejamkan mataku. Menurut pengalamanku sebelumnya, setelah bangun nanti aku akan kembali ke zamanku yang asli.


 saputera
saputera