Julie yang melamun tiba-tiba terhenyak saat Irgie menghampiri bangkunya dan memberinya selembar kertas.
Ujiankah?
Bukan ternyata!
Rupanya, lembar itu berisi foto kucing Persia berwarna abu, di atasnya tercetak tebal tulisan berbunyi "kucing hilang." Terdapat penjelasan karakteristik kucing, kapan terakhir hilang, nomor kontak, dan iming-iming imbalan bagi yang bisa menemukannya dengan selamat.
"Namanya Kuro, hampir 48 jam dia ngilang dari rumah," kata Irgie. "Siapa tahu kamu liat di jalan atau di mana Jul. Aku udah cari kemana-mana, udah pasang poster ini di sudut-sudut komplek rumah, upload di sosmed, tapi belum ada kabar juga."
"Oh," balas Julie singkat.
"Kemana ya?" wajah Irgie terlihat frustrasi. Dia pun meninggalkan Julie dan kembali duduk di bangkunya dan mengecek media sosial. Dia sangat berharap ada info tentang kucing peliharaan yang sudah jadi bagian dari keluarganya selama hampir tujuh tahun.
Julie menatap foto kucing di hadapannya. Entah kenapa foto kucing itu seperti magnet yang menarik pusat perhatiannya. Dia seperti tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Dan tiba-tiba ada semacam energi yang menghantam isi kepalanya sehingga seluruh tubuhnya membeku seketika dan pandanganya gelap gulita. Sesaat kemudian penampakan kucing abu muncul. Cuplikan kucing berjalan, makan, bermain, tidur datang silih berganti dengan kecepatan tinggi layaknya rekaman video yang dipercepat tanpa suara.
Begitu penampakan di kepalanya berhenti, keringat dingin seperti membanjiri tubuhnya, napasnya sedikit tersenggal seperti orang yang mendadak terbangun dari sebuah mimpi buruk.
Setelah tenang, dia beranjak dari kursi dan berjalan menghampiri bangku Irgie. "Punya foto lain kucing itu?"
Irgie yang sedari tadi fokus melihat layar ponsel sedikit tersentak melihat Julie tiba-tiba ada dihadapannya.
Sebenarnya bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba yang membuat cowok itu kaget, tapi sungguh di luar kebiasaan Julie menghampiri seseorang bahkan mengajaknya bicara. Sepanjang yang dia ingat, anak itu selalu duduk diam di bangku pojoknya.
Ezra yang sedang duduk di barisan bangku samping juga heran dengan pemandangan langka itu.
"Foto terbaru kalau bisa," pinta Julie.
"Oh bentar," Irgie kemudian membuka galeri foto di ponselnya dan memperlihatkannya ke Julie. "Ini paling."
Julie mengambil ponsel itu dan perlahan matanya tenggelam menatap foto yang terpampang di layarnya.
"Dalam lemari, di gudang belakang rumah," kata Julie sambil mengembalikan ponsel Irgie.
"Eh?" cetus Irgie bingung.
"Kucing itu ada di situ."
"Gudang rumah siapa? Aku?"
Julie mengangguk.
Irgie tiba-tiba mengelus-elus tengkuk lehernya. "Kamu taHu dari mana?" tanyanya dengan tatapan curiga.
"Cek aja," Ezra tiba-tiba menepuk pundak Irgie dari belakang. "Ikuti sarannya."
Irgie menatap Ezra beberapa saat kemudian mengalihkan pandangannya ke Julie.
"Oke. Aku hubungi orang rumah," katanya sambil memencet-mencet tombol di ponselnya, membuat panggilan. Setelah tersambung, dia berjalan keluar kelas.
"Kamu bisa lacak keberadaan kucing itu dari sini?” tanya Ezra. "Ngeri!"
Julie menghela napas sambil berpikir keras. Ia setuju yang barusan itu mengerikan.
Kelainan apalagi ini? Tiba-tiba saja penampakan kucing muncul di kepalanya begitu dia fokus melihat fotonya. Dan seperti dugaannya, cuplikan yang dilihatnya menunjukkan memori kucing itu berdasarkan hari di mana foto itu diambil.
"Ini yang pertama kalinya," balasnya.
"Kamu bisa lacak kucing hilang dari fotonya ya?" mata Ezra tiba-tiba memicing. "Berarti kemungkinan melacak orang hilang juga bisa?"
Sejenak kemudian, Irgie kembali dengan raut wajah pucat pasi.
"Kamu bener Jul, Kuro ada dalem lemari di gudang belakang rumah," ucapnya kemudian menarik napas dalam, "tapi dia udah gak bernyawa."
Julie sudah tahu itu. Menjelang kematiannya, kucing biasa nyari tempat gelap dan tersembunyi. Seolah tak ingin diganggu dan ditemukan. Karena itulah Kuro ada dalam lemari di dalam gudang.
Irgie sibuk memasukan buku-bukunya ke dalam ranselnya. "Duluan Jul ...makasih."
"Zy duluan," kata Irgie, menepuk pundak Ezra.Ia langsung melengos keluar tanpa peduli bel pulang belum berbunyi.
Ezra kembali duduk di bangkunya. Raut wajahnya seperti orang yang sedang berpikir keras.
Julie pun kembali ke bangkunya bukan untuk duduk melainkan membereskan barang-barangnya. Dia juga ingin pulang. Tubuhnya lelah sekali. Sepertinya memproses cuplikan-cuplikan yang muncul di kepalanya menguras banyak energi.
Untungnya bel pulang berbunyi tepat dia berjalan menuju gerbang sekolah. Kali ini dia memesan Ojek Online, matanya sudah begitu berat dan ingin segera istirahat.
******
Ezra membuka pintu kamar yang hampir dua tahun tak berpenghuni. Dengan berat dia melangkah masuk dan duduk di tepi tempat tidur.
Setelah sekian lama, dia baru berani masuk kembali ke kamar itu. Dia sangat merindukan suasana kamar itu saat penghuninya masih ada.
Meski kecil, kemungkinan dia kembali ada. Harapan itu ada, itulah yang dia percaya atau mungkin itulah yang ingin dia percaya.
Ezra menjatuhkan kepalanya di atas bantal, dan memejamkan matanya. Mencoba mengumpulkan kembali kepingan-kepingan memori masa kecilnya bersama kakaknya yang entah sekarang ada di mana.
Sudah hampir dua tahun kakaknya—Alexis menghilang tanpa jejak dan kejelasan.
*****
Alexis atau biasa disapa Al hanya berbeda dua tahun dengan Ezra, bisa dibilang mereka sebaya. Tapi seringnya dia berlagak lebih tua satu dekade dengan adiknya. Dia sering sok-sokan mengajari Ezra macam-macam mulai dari naik sepeda, berenang, macam-macam olahraga, bahkan berkelahi.
Tapi Ezra merasa kakaknya begitu bukan karena peduli tapi karena dia mau unjuk gigi. Ia ingin menciptakan ilusi kalau dia lebih superior darinya.
Meskipun begitu, Ezra tetap kagum dengan kekuatan fisik dan kemampuan atletik kakaknya yang melebihi anak-anak seusianya. Imbasnya, dia juga bisa banyak hal yang anak seusianya belum bisa.
Ezra masih ingat pelajaran pertamanya naik motor bersama kakaknya yang waktu itu masih duduk di kelas 5. Seperti biasa awal pelajaran merupakan ajang kakaknya untuk pamer kebolehan. Ezra hanya disuruh memperhatikan dengan seksama gerak-geriknya.
“Pertama nyalain nih…” kata Alexis memutar kunci.
“Checked!" Sahut Ezra yang duduk di belakang.
“Terus gas deh, maju…gampangkan?”
“Checked!”
Motor pun melaju.
“Pegangan yang bener Zy,” pinta Alexis sebelum menambah kecepatan. Sebenarnya dia hanya mengendarai motor matic tapi lagaknya seolah sedang mengendarai motor balap di sirkuit.
“Woy Al! Jalan raya! Puter balik!" Ezra menepuk-nepuk pundak Alexis.
“Santai aja Zy, aku udah jago kok,” balas Alexis tanpa menurunkan kecepatan.
“Bukan itu!”
Ketakutan Ezra pun menjadi nyata. Polisi datang dan motor mereka pun ditilang. Pak Polisi juga menyita ponsel Alexis dan melemparkan beberapa pertanyaan. Alexis menjawab semua pertanyaannya itu dengan cengengesan dan wajah tanpa dosa.
Adik-kakak itu pun digiring ke dalam mobil seperti seorang tahanan.
Di dalam mobil, Alexis celingak-celinguk penasaran sementara Ezra gigit kuku, tegang.
“Wah Zy, kita bakalan di penjara!” Ekspresinya tidak jelas antara tak menyangka atau bangga. Mungkin campuran keduanya. Melihat Ezra yang pucat pasi dia pun tersenyum kemudian mengalungkan lengan di pundaknya. “Kamu nggak usah takut, kakakmu yang jagoan ini pasti jagain kamu di sana.”
“Bodoh! Kita nggak bakalan dipenjara. Palingan juga diantar pulang ke rumah.”
Alexis langsung mengintip ke jendela. Dan benar, jalan yang ditempuh merupakan rute jalan menuju rumah. “Terus kenapa kamu tegang?”
“Teganglah! Bentar lagi kita dibantai Mama Papa.”
“O iya,” raut wajah Alexis memucat. Dia pun mulai menggigit kukunya.
Setelah polisi-polisi itu pergi, ayah dan ibu mereka sibuk berdiskusi.
Alexis dan Ezra hanya duduk di kursi menunggu dieksekusi. Dan sebagai dari strategi, Alexis mulai menangis berharap bisa diampuni.
“Zy, ikutan nangis dong! Jangan diem!” bisik Alexis menarik baju Ezra.
“Gak ah, buang-buang energi!”
“Uh!” Alexis menyikut perut Ezra keras sampai dia meringis kesakitan. Wajahnya merah karena kesal.
“Nah gitu!” Alexis puas.
Namun semua itu percuma karena kedua orangtua mereka benar-benar murka. Aksi mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi orang lain. Nyawa jadi taruhannya!
Mereka pun didakwa dengan pasal berlapis tiga.
1. Mengendarai motor di bawah umur di jalan raya!
2. Berkendara tanpa menggunakan helm pelindung kepala!
3. Membawa motor diam-diam tanpa seizin orangtua!
Semua terbukti bersalah dan hukumannya menjadi tahanan rumah selama liburan sekolah tanpa ponsel, internet, komputer, bahkan TV.
Ezra pasrah sementara Alexis tidak terima dan mengajukan banding. Baginya menikmati liburan merupakan hak asasi manusia. Dan perampasan hak asasi manusia merupakan tindakan kriminal berat.
Banding ditolak. Liburan tidak termasuk hak asasi manusia. Hanya anak manja yang berpikir demikian.
Ezra yang hobinya tidur siang dan bermalas-malasan bisa menjalani hukuman ini dengan biasa-biasa saja. Waktu luangnya banyak dia habiskan di perpustakaan ayahnya, membaca macam-macam buku. Namun bagi Alexis yang super aktif, hukuman ini benar-benar membuatnya frustrasi. Dia paling tidak suka berdiam diri, dia butuh beraksi dan berinteraksi.
Dia tidak terlalu suka membaca buku. Buku seri Harry Potter yang ibunya belikan saja hanya dijadikan pajangan di rak kamarnya, jarang tersentuh. Setiap ada kesempatan, dia suka memelas kepada ayah dan ibunya agar setidaknya dia diizinkan latihan renang, sepakbola atau bahkan Jiu Jitsu. Dia berdalih sebentar lagi ada kejuaraan. Ayahnya mulai goyah namun ibunya tetap kokoh. Baginya kesalahannya begitu fatal dan harus diberi pelajaran agar jera.
Alexis hanya bisa pasrah. Tiga hari pertama perilakunya masih normal tapi di hari ke empat dia mulai aneh. Dia sering melewatkan sarapan bersama dan saat makan malam dia banyak diam. Padahal biasanya dia paling banyak bercerita dan jadi sumber hiburan keluarga di meja makan. Sekarang kerjaannya hanya menatap ke luar jendela tanpa kata-kata.
Menyaksikannya, ibunya Adel mulai khawatir. Anak yang biasa penuh energi tiba-tiba menjadi sunyi. Anak itu biasanya tidak bisa diam kok sekarang bisa betah duduk di depan jendela berjam-jam. Jangan-jangan?
“Jangan-jangan dia depresi Ma?” kata Ezra mengagetkan ibunya yang sedang fokus mengamati Alexis dari meja makan.
“Denger dari mana kamu kata itu?” tanya Adel, resah. Baginya kata “depresi” terlalu tabu untuk diucapkan anak sekecil Ezra.
“Oh jadi bener? Dia bakalan masuk asylum dong?"
Mata Adel membelalak. “Tahu apa kamu tentang asylum?"
Ezra meneguk segelas susunya sampai habis. “Kalau nggak mau masuk asylum harus cepetan diterapi.”
“Terapi?” Adel memijit-mijit salah satu pelipisnya, mulai stress sendiri.
“Kira-kira mending dibawa ke psikolog atau psikiater?”
Adel menghela napas dalam. “Zy, udah nggak usah ngomong lagi.”
Dia mulai panik dan bingung. Di satu sisi dia merasa hukum harus senantiasa ditegakkan tapi di sisi lain dia tidak mau membiarkan anak-anaknya linglung gara-gara kelamaan dikurung.
Setelah berpikir matang-matang, dia putuskan untuk menghentikan hukuman kedua anaknya. Dia meyakinkan dirinya bahwa lima hari sudah cukup membuat anak-anaknya jera dan menyesali perbuatannya.
Adel mendudukan kedua anaknya di kursi kemudian mengumumkan kalau mereka mendapatkan diskon masa hukuman besar-besaran. Mulai hari berikutnya mereka bebas menggunakan gadget mereka kembali dan bermain di luar.
“Untuk liburan masih dibicarakan mau kemananya.”
Ezra tersenyum lebar tetapi Alexis tetap datar.
“Kamu mau kemana Al, ada ide?” tanya Adel, berharap mendapatkan reaksi.
Alexis hanya tersenyum samar. “Terserah."
Dia bangkit kemudian tanpa kata-kata berjalan menuju kamarnya.
“Tenang Ma, diajak ke pantai atau mendaki gunung juga dia bakalan normal lagi,” kata Ezra.
Adel menghela napas. “Ya udah, coba kamu ajak ngobrol, tanyain dia maunya apa.”
Ezra mengangguk dan beranjak menuju ke kamar Alexis yang berada di lantai dua. Saat membuka pintu kamar, dia melihat kakaknya sedang loncat-loncat sambil jumpalikan di kasurnya.
“Kita berhasil Zy,” Alexis loncat dari kasurnya kemudian mulai joged-joged. “Berhasil! Berhasil! Hore!” serunya dengan suara pelan.
“Ide siapa dulu.”
“Itu karena akting aku yang keren, ya gak?”
“Yakin itu akting? Selangkah lagi juga kamu bakal betulan kayak gitu.”
Alexis tertawa sambil mengunci leher adiknya. “Kamu pikir aku selemah itu huh?” Ezra megap-megap tidak berkutik. “Belum pernah denger pepatah, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya?”
Alexis melepas cengkramannya dan kembali berjoget.
“Berhasil! Berhasil ! Hore!”
Ezra tersungkur di lantai sambil mengusap-ngusap lehernya. Dia lupa Alexis sedang sibuk menekuni ilmu bela diri Brazilian Jiu Jitsu. Awalnya kakaknya sendiri tidak tertarik karena kelihatannya kurang asyik, hanya guling-guling di lantai, tidak ada bumbu punch maupun kick. Namun setelah dengan mudahnya dia dikalahkan oleh orang yang tubuhnya jauh lebih kecil darinya, dia langsung terobsesi dan latihan hampir setiap hari. Dan Ezra selalu jadi korban malprakteknya, tiap kali ada teknik baru yang dipelajari.
Setelah memulihkan kekuatan, Ezra menendang kaki Alexis yang sedang jingkrak-jingkrak hingga terjatuh.
“Dasar megalomania!” sahutnya sambil menyeringai puas melihat kakaknya ambruk. Mumpung masih terjatuh, Ezra pun coba-coba mengunci leher Alexis dengan teknik yang sama namun dengan mudah kakaknya meloloskan diri.
“Zy, siap mati?” kali ini Alexis yang menyeringai.
Kalau sudah begini Ezra biasanya cepat-cepat lari tapi sayang sekali dengan cepat tangan kakaknya mencengkram pergelangan tangannya dan tahu-tahu lengannya sudah menempel di punggungnya. Dengan bobot tubuhnya Alexis menekan tubuh Ezra ke lantai. Ia tak bisa bergerak tapi masih bisa berteriak. “Mamaaa!”
“Tuh keluar aslinya,” Alexis tertawa. “Anak mami!”
Alexis mengampuni adiknya dan melepaskan cengkramannya. Namun tanpa disangka, Ezra langsung menyikut perutnya sampai ia meringis. Dia pun membalasnya dan mereka berdua saling serang sampai ibu mereka datang.
Melihat mereka berkelahi, Adel bernapas lega. Berarti kondisi sudah normal kembali.
Bagi Adel, Alexis dan Ezra merupakan paket kombo yang saling melengkapi. Alexis yang super energik dan senang jadi pusat perhatian merupakan kebalikan dari adiknya yang santai dan cuek dari bawaan lahir. Waktu bayinya saja, Ezra jarang menangis dan seringnya anteng sendiri dengan mainannya. Untungnya, Alexis aktif mengajaknya berinteraksi, kalau tidak adiknya akan asyik dengan dunianya sendiri.
Bagi Ezra, Alexis itu kebanyakan gaya dan drama tapi karena itu hidupnya penuh warna. Dia sendiri sampai kecipratan. Hidupnya yang tenang jadi banyak tantangan gara-gara ulahnya.
Pernah waktu Ezra kelas empat, ada teman sekelasnya yang suka membuli : Arka, Danny, dan Riko. Sebenarnya tidak bisa dikatakan membuli juga. Anak-anak itu hanya suka mencontek hasil kerja Ezra tanpa permisi.
Baru juga ia datang, anak-anak itu langsung menghadang—meminta buku PR-nya. Tiap ujian, baru juga beres mengerjakan, Arka yang duduk di depannya langsung menyambar kertas ujiannya dan menyalinnya tanpa basa-basi tanpa terima kasih.
Saat tak sengaja memergoki aksi Arka dan kawan-kawannya lewat kaca jendela, Alexis heran kenapa bisa-bisanya adiknya santai. Ezra sendiri memang tidak peduli karena merasa tidak dirugikan oleh tindakan konyol Arka dan kedua temannya yang pemalas. Namun, Alexis berpendapat lain.
Menurutnya, tindakan Arka dan kawan-kawannya bisa dikategorikan sebagai bentuk penjajahan. Dan sesuai undang-undang dasar yang sering ia dengar tiap upacara bendera, penjajahan di atas dunia harus dimusnahkan. Untuk kasus ini, dia percaya tidak bisa lewat jalur diplomasi tetapi harus lewat agresi.
“Kamu harus lawan mereka!” kata Alexis, tegas.
“Apaan buang-buang energi. Cuma nyontek doang!”
“Hari ini nyontek, besok-besok apalagi?”
“Kalau sudah keganggu ya tinggal lapor guru.”
Alexis hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, prihatin. “Lapor guru cuma nambahin masalah. Orang kayak mereka gak butuh dilaporkan tapi dikasih pelajaran.”
“Ya udah kamu ajah yang lawan mereka.”
“Eits jangan ngarep! Kamu harus beresin mereka sendiri.”
Ezra menyilangkan kedua tangannya di dada. “Terus apa gunannya punya kakak yang katanya jagoan.”
Alexis tersenyum simpul sambil menepuk-nepuk pundak adiknya. “Bentar lagi kakakmu yang jagoan ini mau SMP, jadi kamu harus mandiri.”
“Ya udah berarti jangan ikut campur urusan orang.” Ezra menepis tangan Alexis yang menempel di pundaknya. Dia pun berjalan ke kelasnya namun dihadang oleh kakaknya.
“Jangan bilang kamu takut?”
“Hah?”
“Kalau kamu takut bilang aja, aku nggak akan maksa kamu lawan mereka.”
“Aku nggak takut.”
“Kalau gitu lawan mereka. Jangan biarin mereka seenaknya terus.”
Ezra tertegun sejenak. “Okay, liat aja.”
“Inget teknik-teknik yang sering aku praktekin,” kata Alexis, kembali menepuk pundak adiknya. “Good luck!”
Ezra kemudian meneruskan langkahnya dan sebelum masuk kelas dia menarik napas yang cukup dalam. Karena hari ini ada PR, seperti biasa tubuh besar Arka sudah siap menghadangnya. Tanpa permisi, dia langsung merampas tas Ezra dan mengambil buku di dalamnya. Ezra melirik ke jendela, di sana Alexis sedang mengintip sambil senyam-senyum. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia bisa jadi bahan olok-olokan kakaknya entah sampai kapan.
“Balikin bukunya!” kata Ezra tegas dan keras.
Arka menoleh dan menatap Ezra tajam seolah menantangnya. “Nanti juga dibalikin!”
Ezra maju satu langkah sambil menjulurkan tangannya. “Balikin sekarang!”
Riko dan Danny sibuk menyalin tak memperdulikan Ezra. Tapi Arka merasa terganggu dengan sikap Ezra yang tidak seperti biasanya. Dia pun menaruh buku dan pensilnya di meja kemudian mendorong Ezra. “Dibilangin nanti juga dibalikin!”
Dengan cepat Ezra mendorong balik. “Balikin sekarang!”
Arka tersentak dia tidak menyangka Ezra yang biasa diam kini melawan.
Anak-anak lain yang melihatnya pun sama kagetnya dan mulai fokus memperhatikan mereka.
Arka tidak mau reputasinya sebagai ‘preman kelas’ hancur gara-gara sikap perlawanan Ezra yang bisa saja kemudian diikuti anak-anak lainnya. Dia pun mulai melemparkan ancaman. “Nantangin kelahi yah? Oke! Pulang sekolah jangan kemana-kemana!” gertak Arka.
“Kenapa nunggu pulang sekolah? Sekarang aja! Di sini kalau berani!”
“Kamu sinting? Bentar lagi ada guru!”
“Biarin, emang kenapa kalau ada guru. Aku siap dikeluarin sekolah buat lawan kalian! Asal tahu aja aku nggak akan segan-segan!”
Mata Arka membelalak belum pernah dia melihat Ezra sepercaya diri ini. Jelas sekali anak itu siap bertarung dengan segala konsekuensinya.
Riko dan Danny berhenti menulis, terperangah.
“Jangan bilang kalian takut dikeluarin dari sekolah?” Ezra tersenyum. “Cuma segitu nyali kalian? Cuma berani main di belakang?”
Anak-anak yang menonton mulai tegang, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka.
“Aku emang jarang berkelahi, tapi kalau berkelahi aku nggak akan berhenti sampai ada yang mati.”
Ezra maju selangkah, matanya tajam menghunus Arka yang mulai memucat.
“Bohong banget!” Arka tertawa gugup.
"Aku serius!” Ezra maju selangkah lagi. “Kalau kalian yang mati, aku siap ditangkap polisi, kalau aku yang mati, kalian siap nggak berurusan sama polisi?”
“Polisi?”
Dengan penuh percaya diri Ezra memasang kuda-kuda siap bertarung. “Silakan maju satu-satu?”
Arka dan kawannya diam mematung.
“Kalau kalian nggak maju, aku yang maju. Aku hitung mundur. Lima…empat…”
Danny panik sambil menarik-narik lengan Arka. “Mundur aja Ka, tu anak udah gak waras!” bisiknya.
Arka pun mundur.
“Ini bukunya kita balikin,” kata Riko, tidak menyerahkan bukunya langsung ke tangan Ezra melainkan di taruh di meja di dekatnya.
Ezra mengambil bukunya kemudian duduk di bangkunya. Dia tidak habis pikir sebegitu mudahnya bocah-bocah itu termakan omong kosongnya. Apa ekspresi wajahnya sebegitu meyakinkan?
Sebagian teman sekelasnya pasti sudah menganggapnya sinting. Semua ini gara-gara Alexis.
Ezra melirik ke jendela, dilihatnya kakaknya sudah tidak ada.
Memasuki masa SMP, Alexis lebih sering menghabiskan waktunya bersama dua sahabatnya, Jeremy alias Jem dan Nathan alias Nato. Mereka bertiga merupakan penyerang andalan di tim sepakbola Maristela.
Saat di meja makan, Alexis sering menceritakan kehebatan dirinya dan kedua temannya di lapangan. Tentu saja banyak didramatisir di sana-sini.
“Aku tuh ibaratnya Messi, si Jem itu Suarez dan si Nato itu Neymar,” tutur Alexis. “Begitu kita serang pertahanan lawan langsung porak-poranda, dan tembakan-tembakan pun melesat tepat ke gawang.”
Ezra hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap narsistik kakaknya yang menjadi-jadi bahkan sampai ke tahap halusinasi sampai-sampai menyandingkan dirinya dengan Messi. Namun harus diakui bahwa prestasinya di bidang olahraga terutama sepakbola dan Jiu Jitsu cukup cemerlang. Sekolahnya cukup bangga atas kontribusinya dalam memenangkan kejuaraan.
Waktu kelas tujuh, Ezra kembali satu sekolah dengan Alexis. Saat itu dia baru sadar kalau kakaknya sangat popular di sekolah. Entah karena prestasinya di bidang olahraga atau karena tampangnya yang sedikit di atas rata-rata. Kemungkinan besar sih karena pembawaanya yang seru, percaya diri, dan mudah bergaul.
Saat anak-anak lain tahu kalau mereka adik-kakak, mereka tak menyangka dan mulai membanding-bandingkan. Mereka heran Alexis yang ramah dan easy going bisa punya adik yang cuek dan serius. Awalnya mereka kira Irgie-lah adik Alexis mengingat mereka sama-sama easy going dan atlet.
Guru-guru pun sama herannya.
“Kamu beneran adiknya Al?” tanya seorang guru matematika.
Ezra mengangguk.
“Saya dulu wali kelasnya,” guru itu menghela napas kemudian menyerahkan hasil ulangan Ezra, tersenyum. “Syukurlah kamu gak ikut-ikutan badung kaya kakakmu.”
Rupanya, ketenaran Alexis di kalangan guru-guru tidak ada hubungannya dengan prestasinya di bidang olahraga. Kemana pun Alexis berada, drama senantiasa mengikutinya. Ada saja yang bisa jadi bahan pembicaraan tentang anak itu. Entah karena kehebatannya di lapangan, keseruannya di kelas, atau kehidupan sosialnya di sekolah.
Kadang Ezra juga kena imbasnya karena harus meladeni pertanyaan-pertanyaan konyol seputar kakaknya.
“Kakak kamu beneran lagi deket sama Silvanna, ketua Klub Sains, kelas 9-B?”
“Gak tahu.”
“Tadi kita lihat mereka sibuk liatin gorong-gorong sekolah. Kayak yang akrab gitu.”
“Oh.”
“Kayaknya mereka lagi nyari bahan eksperimen deh. Si Silva ini ‘kan terkenal suka bikin eksperimen yang aneh-aneh sama kayak orangnya.”
“Hmm.”
“Denger-denger sih, dia juga pernah bikin ledakan di rumahnya sendiri pas eksperimen. Tampang boleh imut-imut tapi mainannya bom! Kamu nggak takut kakak kamu jadi korban eksperimennya?”
“Biarin.”
“Eeeh!”
Di lihat dari sudut pandang mana pun, hidup Alexis bisa terbilang lengkap dengan segala lika-likunya. Karena itu, Ezra sedikit kaget waktu kakaknya justru bilang sebaliknya.
Pernah dia melihat Alexis yang waktu itu masih kelas 9 sedang merokok di beranda kamarnya sambil menerawang jauh ke atas langit.
"Merokok membunuhmu!” Ezra membangunkan lamunan Alexis.
“Klasik…” Alexis nyengir.
“Bilang Mama Papa ah!”
“Janganlah! Aku ‘kan anak kebanggaan mereka. Harapan mereka satu-satunya. Paling disayang!”
“Nggak ada yang mikir kayak gitu.”
Alexis tertawa. “Pura-pura nggak tahu.” Ia kemudian mengisap rokoknya dan menghembuskannya ke udara. “Aku ngerokonya jarang kok Zy. Kalau lagi pengen aja kayak sekarang.”
“Terserah sih. Tapi kamu tahu ‘kan resikonya sebagai atlet?”
“Iya tahu, makanya cuma sesekali aja,” Alexis kembali menghisap rokoknya. “Ini edisi galau aja.”
“Oh.”
“Kamu nggak penasaran, aku galau kenapa?”
“Nggak.”
Alexis geleng-geleng kepala sambil terkekeh.
“Bukan karena cewek ya.”
“Nggak nanya.”
Hening sesaat.
Alexis melempar puntung rokoknya jauh-jauh. “Dari kecil aku suka ngerasa kayak gini,” raut wajah Alexis berubah, “nggak tahu kenapa Zy.”
“Maksudnya?” Ezra berusaha terlihat santai padahal penasaran. Jarang-jarang sekali melihat kakaknya melodramatik seperti ini.
“Kadang aku ngerasa ada yang kurang, Tapi aku bingung kurangnya di sebelah mana coba?” Alexis kembali mengambil satu batang rokok dari bungkus yang tergeletak di sampingnya. “Kayak ada sesuatu yang hilang tapi nggak tahu apaan.”
“Pantes caper terus.”
“Tuh kamu paham!” Alexis tersenyum, asap kembali mengepul dari mulutnya. “Rokok ini bisa bikin keresahan aneh itu lenyap Zy.”
“O ya? Sehebat itukah efek nikotin?” Ezra menjulurkan tangannya ke hadapan kakaknya.
“Apaan?”
“Nyoba.”
Kaget, Alexis mundur sambil terbatuk-batuk. “Bocah ingusan jangan coba-coba deh! Bahaya!”
Ia kemudian mengambil bungkus rokok di lantai dan menyodorkannya ke hadapan Ezra.
“Tuh lihat bungkusnya, horror ‘kan? Makanya!”
Ezra mengambil ponsel di sakunya dan menyalakan kameranya. “Ya udah siap-siap ya.”
“Ngapain tuh?”
Ezra hanya tertawa. “Barang bukti.”
Alexis mengela napas, melempar rokoknya kemudian meregangkan jari-jarinya. “Siap mati?”
******
“Siap mati?”
Ezra membuka matanya kemudian membelalak saat melihat angka-angka yang ditunjuk jarum jam. Selama itu dia tertidur?
Pandangannya kemudian beralih ke sebuah foto di dinding. Dia bertekad akan menemukannya. Bagaimanapun caranya.


 galilea
galilea





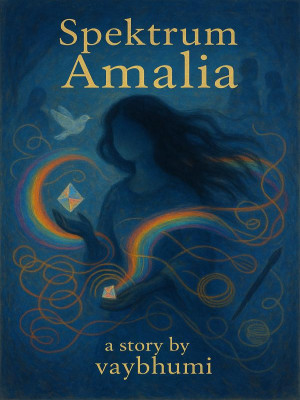




Ini nggak ada tombol reply ya?
Comment on chapter Bab 6@Juliartidewi, makasih kak atas masukannya, nanti direvisi pas masa lombanya selesai. Thank youu...