Nilam menekuni goresan demi goresan pensil di atas kertas gambarnya. Udara dingin dan kabut sedikit menghalangi pandangan, tetapi ia masih bisa berkonsentrasi. Suara jangkrik menemaninya dalam kesendirian, sementara ia terhanyut pada lukisan malam berbintang dengan bulan di tengahnya. Bau asap samar terhidu di indera penciumannya, mungkin berasal dari api unggun di bawah sana. Entah berapa lama waktu berlalu, ia tak lagi memedulikannya.
Kegiatan padat yang sudah dilakukan sejak pagi sudah selesai dan ini saatnya acara bebas. Seharian, mereka sudah melakukan berbagai macam kegiatan tanpa ada jeda. Mereka harus bangun pukul lima, shalat berjemaah, senam bersama, kemudian mengantre mandi, dan sarapan. Setelah itu, materi tentang kepemimpinan dan wawasan kebangsaan silih berganti diadakan. Pembicaranya beragam: ada pembina OSIS, mantan ketua OSIS yang sudah menjadi alumni, bahkan tentara yang dulu pernah mengenyam pendidikan di sekolahnya. Otak Nilam seolah ‘ngebul’ karena begitu banyak informasi yang masuk, tetapi paling tidak ia tak merasa sendirian karena kesibukan.
Sepanjang hari, ia hanya sempat bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Bahkan, Naura hanya menyapanya selintas saja saat berpapasan di depan prasmanan di jam makan siang. Hatinya semakin teriris saat sahabatnya itu tidak mengajaknya ikut berkumpul bersama di api unggun dengan teman-teman barunya. Bahkan, di depan mereka, dia bersikap seolah tak mengenal Nilam. Dia juga membiarkan Gisel dan yang lain menyindirnya perihal kejadian di bus kemarin.
“Dia, mah, nggak suka kumpul-kumpul, Kak. Senengnya sendirian, atau ngumpul sama anak cowok!” sindir Zahra saat kakak kelas yang sekamar dengannya mengajak ia ikut berkumpul. “Iya, kan, Naura?”
“I–iya. Nilam biasanya suka sendirian,” jawab Naura masih terngiang di telinga Nilam.
Sekarang, di sinilah ia. Duduk sendirian di atas sebatang kayu yang sudah ditebang, ia melampiaskan kegelisahan hatinya di atas kertas. Letak tempatnya duduk yang berada lebih tinggi dari lapangan membuatnya dapat melihat kerumunan yang mengitari api unggun. Mereka bersenda gurau bersama, menghangatkan diri sambil membakar marshmallow. Suara tawa mereka bahkan terdengar ke telinganya, bersama dengan bunyi jangkrik yang bernyanyi menyambut malam.
Pandangan Nilam perlahan kabur tertutup air yang menggenang di pelupuk mata, terus meluncur turun hingga membasahi buku gambarnya. Memang salahnya yang tidak bisa bergaul, tidak bisa memiliki teman, tidak bisa bercakap-cakap dengan orang baru. Kedinginan dan sendirian membuatnya ingin cepat-cepat pulang dan menyudahi kegiatan yang membuatnya tertekan ini. Toh, alasan Naura mengajaknya hanya karena dia tak punya teman, bukan? Sekarang dia sudah punya, buat apa Nilam ada?
Sesaat embusan udara membelai tengkuk Nilam, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengusap tengkuknya, tetapi hawa dingin semakin terasa. Bergidik, Nilam baru menyadari hal yang tadi terlupakan olehnya. Dia, seorang gadis yang bahkan tak berani melihat iklan berhantu, berani-beraninya duduk sendirian di tengah kabut gelap! Jantungnya mulai berdegup tak keruan, tangan dan kakinya menggigil kedinginan. Ia menelan ludah dan bersiap kembali ke kamar.
Napas Nilam seolah terhenti saat terdengar bisikan di telinganya. Ia memekik saat melihat sebuah api melayang di dekat matanya. Seketika ia jatuh terduduk dan tampak bayangan tinggi seolah menyelubungi tubuhnya.
“Argh!”
Suara tawa membahana di kesunyian malam. Jantung Nilam terasa akan lepas dari tempatnya. Sesosok tinggi dengan rambut keriting tampak berkecak pinggang di depannya.
“Dora, ngapain lo sendirian di sini?”
Nilam terbelalak demi melihat manusia yang sudah nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. “Kak Tara?”
“Kenapa? Kaget lihat orang keren?” tanyanya menaikkan sebelah alis. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Nilam berdiri. “Gue dari tadi di sini, lo malah sibuk nangis.”
“Ah, i–itu, saya nggak nangis, kok,” kilah Nilam sambil menyeka air mata.
“Emang gue nggak lihat? Dari tadi gue nongkrong di sono, lo malah sesenggukan,” ujar Kak Tara telak menembus hati Nilam. Satu tangannya memegang puntung rokok yang masih menyala, satu lagi memungut buku gambar yang kini basah terkena embun. Dahinya mengernyit kala mengamati guratan pensil yang sudah memenuhi sebagian besar halaman. “Ini lo yang gambar?”
Spontan Nilam merebut buku itu dari tangan Kak Tara. “Jangan dilihat!”
“Kenapa? Bagus, kok!” Cowok itu membanting tubuh di atas kursi batang kayu. “Udah terusin, gue temenin!”
Nilam menggeleng. “Nggak usah, Kak. Saya mau balik ke kamar,” pamitnya seraya berjalan melewati Kak Tara. Seketika ia terhenti saat cowok itu menarik tangannya.
“Santai aja napa, sih! Udah duduk sini. Gambarin gue. Bikin yang ganteng!” paksanya.
Mata Nilam terbelalak. Hatinya sedang gundah, Kak Tara malah menambah buruk suasana. Ia berupaya melepaskan genggamannya, tetapi cowok itu menahan hingga pergelangan tangannya terasa sakit.
“Aku … ehm, saya, mau balik ke kamar, Kak,” isak Nilam tak kuasa menahan tangis yang kembali turun. Uh, bodoh sekali! Masa ia menangis di depan Kak Tara?
“Hei, Dora. Kalo lo pergi sekarang, entar disangka gue ngapa-ngapain lo. Udah, sini duduk dulu,” ujar Kak Tara. “Gue nggak bakal nagih lo gantiin baju gue yang robek kena cakaran kucing, deh! Gue cuma minta lo duduk di sini temenin gue.”
Kali ini Nilam tersentak. Aliran panas seolah memenuhi wajahnya teringat kejadian tempo hari. Benar juga, ia tak memikirkan bagaimana nasib seragam cowok itu setelah terkena serangan kucing yang dilancarkan Kak Orion. Bahkan, selama ini ia berusaha menghindari cowok itu karena takut. Namun sekarang, ia malah terjebak berdua dengannya di tengah kegelapan malam.
Bintang-bintang yang bertaburan di angkasa terlihat begitu memesona, seperti berlian yang dibiarkan menghampar luas di permadani hitam. Kalau saja ia bersama Kak Orion, pasti cowok itu sudah menjelaskan secara detail suhu inti bintang, reaksi fusi, atau bahkan jarak antara matahari dan bintang lain terdekat. Meskipun tak sepenuhnya paham, celoteh cowok itu mampu mengisi hari-harinya yang sepi dan sunyi. Namun sekarang, kenapa harus Kak Tara?
Tak punya lagi alasan untuk pergi, Nilam akhirnya mengalah. “Ya udah. Aku duduk di sini, tapi Kakak matiin rokoknya.”
Kak Tara terkesiap, mungkin tak menduga kalau Nilam akan mengajukan penawaran. Bibirnya naik sebelah ke atas, kemudian melepaskan batang rokok yang sudah tinggal setengah ke tanah dan menginjak-injaknya. “Fine, udah gue buang, tuh! Sekarang, duduk sini. Bikin gambar gue yang bagus!”
Nilam menurut. Dengan canggung, dia duduk di sebelah cowok yang masih menguarkan bau asap. Oh, ia baru sadar. Bau yang sejak tadi tercium bukan bau api unggun, melainkan rokok. Ternyata itu berasal dari Kak Tara dan bodohnya ia tak menyadari keberadaan cowok itu tadi.
“Lo kenapa nggak gabung sama mereka?” tanya Kak Tara saat pandangan Nilam terpaku pada kerumunan di sekitar api unggun.
Gadis itu menunduk, meremas-remas jemari tangannya. “Nggak, aku lebih suka sendiri,” bisiknya pelan. Entah mengapa ia merasa dustanya terasa menyesakkan. Memang benar ia suka sendiri, tetapi di tengah acara seperti ini, ia tak benar-benar ingin sendirian.“Kalau Kakak sendiri, kenapa nggak gabung sama mereka? Ia memberanikan diri balik bertanya.
Desahan pelan keluar dari mulut Kak Tara. Dia menyandarkan tangannya pada batang pohon hingga badannya condong ke belakang.“Gue nggak cocok sama mereka.”
“Kenapa?” Nilam memusatkan perhatian pada cowok di sebelahnya, penasaran.
“Yah … lo tau sendiri, kan? Mereka, anak-anak OSIS itu, tergolong ‘anak-anak baik’, sedangkan mereka melihat gue masuk golongan ‘anak-anak nakal’. Mereka cuma mandang gue, dan anak-anak futsal lain, sebelah mata. Jadi, mana bisa nyambung, kan?”
Nilam mengernyitkan dahi, tak percaya dengan kesimpulan yang dicetuskan Kak Tara.“Oh, ya? Masa, sih?”
Cowok di sebelahnya terkekeh-kekeh.“Lo sendiri, pertama ngelihat gue, yang ada di pikiran lo, gue anak apa? Pasti anak nakal, kan?”


 yfsiska
yfsiska

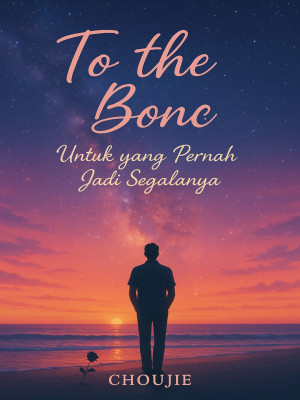








Makin lama makin seru, Kak. Semangat 💪
Comment on chapter Chapter 10