Kata orang, mengulang adalah cara belajar. Tapi bagiku, mengulang adalah cara bertahan. Menghapus, menggambar lagi, menyusun ulang barang-barang kecil di meja. Bukan karena salah, tapi karena ada yang terasa tidak tepat. Bukan di kertas, tapi di dalam kepala
**
Beberapa hari terakhir, aku mulai menghitung langkah dari gerbang kampus ke gedung fakultas. Dua puluh tujuh jika lewat tangga barat, dua puluh sembilan kalau belok lewat taman kecil. Dan itu harus sama setiap hari. Harus.
Aku tidak tahu sejak kapan kebiasaan itu mulai. Awalnya mungkin hanya iseng. Tapi suatu pagi, aku menghitung dua puluh delapan. Langkahku terhenti di tengah jalan. Dadaku langsung sesak seperti dicekik. Rasanya seperti ada yang salah dengan seluruh hariku. Aku menoleh ke belakang, lalu kembali ke titik awal. Mengulang dari nol. Dan kali ini, menghitung lebih pelan. Lebih hati-hati.
Di kelas, aku masih tersenyum saat dosen melontarkan lelucon. Masih tertawa bersama Dita saat dia mengeluh soal tugas maket yang belum disentuh. Aku masih duduk di barisan depan, mencatat dengan teliti setiap poin dari slide presentasi. Dari luar, tidak ada yang berubah.
Tapi ada hal-hal kecil yang mulai mengusikku. Suara gesekan kursi yang terlalu nyaring membuatku menggertakkan gigi. Ujung lembaran kertas milik teman sebelah yang sedikit terlipat membuatku ingin merapikannya sendiri. Dan setiap kali catatanku terasa kurang lurus, atau margin tak seimbang, bisikan itu datang. “Kalau kamu lupa menulis ulang nanti malam, nilainya akan jelek. Sangat jelek.”
Aku tidur makin larut. Bukan karena sibuk, tapi karena aku harus memastikan semua tugas selesai dengan benar. Aku bangun lebih awal, bukan karena rajin, tapi karena aku harus mengecek ulang: garis sketsa harus lurus, catatan harus bersih, jadwal harus diikuti tanpa meleset satu menit pun.
Setiap kesalahan kecil terasa seperti bom waktu yang akan menghancurkan. Setiap halaman yang kurang rapi seperti dosa besar. Kadang aku sampai tidak sadar sudah menghapus dan menggambar ulang satu sketsa empat kali, hanya karena satu garis terlihat miring setengah derajat. Semua itu kulakukan karena ada sebuah kalimat yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia Berputar. Dan terus mengulang di kepala. Kadang datang dalam bentuk kalimat lengkap. Kadang hanya desakan samar yang membuat perutku mual. Tapi selalu ada.
Seperti tadi siang, saat aku lupa membawa stabilo warna peach, warna yang biasa kupakai untuk menandai istilah penting di catatan. Rasanya seperti ada yang hancur. Aku mencoba tenang, tapi di kepalaku muncul bayangan: kalau aku tidak menandai bagian itu sekarang, nanti aku tidak bisa mengingatnya, dan kalau aku lupa, aku akan gagal. Dan kalau aku gagal… maka semua yang kulakukan selama ini akan sia-sia. Pikiran itu terus berputar. “Ulangi. Betulkan. Periksa lagi.”
Aku jadi lambat merespons orang lain. Saat Dita bercerita tentang drama yang sedang ia tonton, aku tersenyum dan mengangguk, tapi pikiranku sibuk menghitung: berapa kali aku sudah mengulang menggambar denah ruang tidur? Apakah lembar keempat sudah aku cek margin-nya? Apakah folder tugas sudah disusun sesuai urutan mata kuliah?
Aku mulai mencatat hal-hal yang harus kulakukan di selembar sticky note, lalu menggandakan di buku catatan, lalu salin lagi di aplikasi to-do-list di ponsel. Tiga salinan. Karena kalau cuma satu, nanti kalau hilang? Kalau terhapus? Kalau aku lupa?
Dan setiap kali aku berhasil menyelesaikan semuanya… ada rasa lega yang menggantung. Tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, suara itu datang lagi. “Coba cek ulang. Pasti ada yang terlewat.”
Malam-malamku jadi panjang. Mataku perih, tapi tanganku tetap bekerja. Kadang aku berdiri dari tempat tidur hanya untuk mengecek apakah pintu kamar sudah benar-benar terkunci. Dua kali. Tiga kali. Kalau belum yakin, aku ulang dari awal.
Aku tahu ini melelahkan. Tapi entah kenapa, aku juga merasa... aman. Seperti semua ini perlu dilakukan agar dunia tetap berjalan dengan baik. Agar tidak ada yang salah. Agar tidak ada yang terluka karena kelalaianku. Dan mungkin, agar aku sendiri tetap utuh.
Malam itu, setelah makan malam, aku membantu Mama membereskan dapur. Tanganku sibuk menyusun piring, gelas, sendok, semuanya harus rapi. Piring putih ditumpuk sesuai ukuran. Sendok menghadap ke arah yang sama. Serbet dilipat tiga kali, lalu satu lipatan ke kanan. Seperti biasa. Mama memperhatikanku sekilas sambil mengeringkan tangan dengan handuk kecil.
“Kamu rajin banget, Ra.” komentarnya sambil tersenyum lelah.
Aku hanya mengangguk kecil. “Biar rapi aja, Ma.”
“Besok kuliah pagi?”
“Iya, jam delapan,” jawabku sambil merapikan botol bumbu di rak, diam-diam menyusunnya berdasarkan tinggi dan warna label.
Mama tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menatapku beberapa detik, lalu berbalik mengaduk kuah sup yang masih menyisakan aroma di dapur. Aku tahu tatapan itu. Bukan marah, bukan juga kecewa. Mungkin hanya lelah. Atau bingung harus bicara apa kepada anaknya yang terlihat baik-baik saja, padahal tidak sepenuhnya.
Aku kembali ke kamar tanpa banyak suara. Duduk lagi di depan meja belajarku, membuka catatan yang tadi belum sempat disentuh. Pena di tanganku bergerak, tapi pikiranku tertinggal di ruang makan.
Papa baru pulang sekitar jam sembilan malam. Aku masih duduk di meja belajar saat kudengar langkah kakinya melewati lorong. Tak lama, pintu kamarku diketuk dua kali.
“Udah tidur?”
“Belum, Pa.”
Pintu terbuka sedikit. Papa menjulurkan kepala, menatap ruangan yang terang dan meja belajarku yang penuh kertas.
“Masih ngerjain tugas?” tanyanya singkat.
Aku mengangguk. “Tinggal revisi gambar.”
Papa mengangguk pelan. “Jangan begadang, ya. Besok kuliah pagi, kan?”
“Iya, Pa,” sahutku. Suaraku tetap stabil. Senyumku juga.
Dia menutup pintu tanpa banyak komentar. Aku kembali ke bukuku.
Tapi suara di kepalaku masih belum diam.
Revisinya belum selesai. Kertas halaman kedua masih ada bayangan garis yang terlalu tebal. Tadi penggarisnya agak goyang. Harus dicek lagi. Harus diperbaiki. Harus…
Aku menghela napas. Tanganku bergerak mengambil kertas baru. Sekali lagi. Karena kalau aku berhenti sekarang, rasanya seperti akan terjadi sesuatu yang buruk. Entah apa. Entah kepada siapa. Tapi pasti buruk. Dan suara-suara itu… belum mau diam.
Malam makin larut. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul sebelas lewat lima belas. Tapi aku belum bisa berhenti. Aku sudah menyalin ulang sketsa denah itu dua kali. Garis-garis margin sudah sejajar, simbol sudah sesuai standar, tapi entah kenapa… tetap terasa tidak pas. Seolah ada sesuatu yang miring, yang tidak terlihat, tapi mengganggu. Tanganku kembali mengambil penggaris. Perlahan, aku mengukur ulang tepi bawah halaman. 0,5 cm. Sesuai. Tapi aku mengulang lagi. 0,5 cm. Sekali lagi. 0,5 cm.
Aku baru berhenti saat telunjukku gemetar pelan karena terlalu lama menahan napas. Akhirnya, aku memaksakan diri untuk menutup map tugas itu, menyusunnya sejajar dengan buku gambar dan kotak alat tulisku. Lalu beralih ke tempat tidur. Tapi… aku belum bisa langsung tidur. Bantal harus diletakkan tepat di tengah. Selimut harus menutupi kasur hingga garis pinggir. Kaki meja belajar harus sejajar dengan kaki tempat tidur. Satu per satu aku periksa. Baru kemudian aku berbaring. Memejamkan mata. Menarik napas. Tapi suara itu tetap datang.
Kalau tadi penggarisnya sedikit meleset? Kalau kertasnya ada debu dan bikin tinta nggak meresap sempurna? Nanti nilainya turun. Nanti dosennya kecewa. Nanti semua sia-sia.
Aku membuka mataku. Lalu duduk lagi di meja belajar. Cek sekali lagi. Baru setelah itu aku benar-benar tidur. Tapi bahkan dalam tidurku pun, mimpiku penuh ruang kelas yang kacau, kertas berserakan, dan dosen yang berkata, “Tugasmu tidak bisa saya terima.”
Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari alarm. Jam lima lewat sepuluh. Pertama-tama, kulipat selimut. Empat lipatan. Kanan dulu, baru kiri. Kemudian kucek jadwal kelas hari ini. Kuatur pakaian: jaket almamater, kemeja putih, celana panjang kain, semuanya digantung rapi berdasarkan panjang lengan. Dan saat Mama mengetuk pintu untuk mengingatkan sarapan, aku sudah berdiri di depan cermin.
“Lima menit lagi turun, Ma!”
Tapi sebelum keluar, aku memeriksa ulang map tugasku. Kulihat dari atas. Rata. Dari samping. Tidak ada kertas mencuat. Sticky note di dalamnya… miring sedikit. Aku perbaiki. Dua kali. Sampai lurus.
Di meja makan, aku duduk berseberangan dengan Mama. Dia sibuk dengan ponsel, membaca berita pagi.
“Mau roti atau nasi goreng?” tanyanya tanpa menatap.
“Nasi goreng aja, Ma. Makasih.”
Aku makan perlahan. Mengunyah sepuluh kali sebelum menelan. Tangan kiri di paha, tangan kanan pegang sendok. Posisiku harus stabil.
Mama sesekali melirik, tapi tidak berkata banyak.
“Nanti kuliah jam berapa?”
“Jam sembilan. Tapi aku mau ke kampus lebih pagi.”
“Ya udah. Hati-hati, ya.”
“Iya.”
Setelah cuci piring, aku masuk ke kamar lagi. Kupastikan semua lampu mati, meja bersih, tirai ditutup rapi. Lalu baru aku berangkat.
Di dalam kereta, aku membuka buku catatan. Sekilas memastikan semua lembar tidak terlipat. Tiba-tiba, satu halaman terlipat kecil di ujung bawah. Sangat kecil. Tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku lipat halaman itu ke belakang. Tapi lipatannya tetap terasa. Aku mencoba merapikannya dengan jari. Gagal.
“Tenang. Nanti sampai kampus, salin ulang aja halaman itu.” Bisikku pada diri sendiri
Mataku terpejam sesaat. Aku menarik napas pelan. Penumpang lain tak menyadari apapun. Mereka melihatku sebagai mahasiswa yang rapi, siap, dan tenang. Dan itu sudah cukup.
Sesampainya di kampus, aku langsung menuju perpustakaan. Masih sepi. Suara sepatu di lantai keramik menggema samar saat aku berjalan menuju sudut biasa, dekat rak arsitektur. Di meja kayu yang dingin, aku membuka map tugas dan mulai menyalin ulang halaman yang terlipat semalam.
Garis-garisnya kubuat ulang seteliti mungkin. Tanganku bergerak otomatis, meski mataku masih terasa berat. Tapi setidaknya, kertas itu sekarang terlihat seperti belum pernah salah. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi dari ponsel mengingatkanku: waktu masuk studio tinggal sebentar lagi. Aku menggulung kertas hasil salinan dan memasukkannya ke tabung gambar, lalu bergegas keluar dari perpustakaan.
Studio Gambar Dasar pagi itu sedikit riuh. Pensil, penggaris, dan penghapus berserakan di meja panjang. Cahaya matahari menembus jendela besar, menyinari potongan kertas kalkir dan cetakan tugas minggu lalu.
Aku duduk di barisan depan, menghadap meja gambar. Aku sudah memegang pensil teknik dan mulai menggambar garis bantu untuk denah tugas mingguan. Tangan kiriku menjaga agar kertas tidak bergeser setitik pun. Penggaris T aku tekan dengan sangat hati-hati.
“Garis harus lurus. Presisi. Jangan goyang sedikit pun, kalau goyang, nanti harus ulang dari awal” batinku.
Di sisi lain meja, Dita menyapaku, “Ra, kamu udah mulai ngerjain? Aku baru selesai bikin sketsanya doang, belum masuk ke detail.”
Aku melirik dan tersenyum cepat. “Aku tadi pagi udah nyicil. Tapi garisnya agak miring, jadi ulang lagi.”
“Ulang?” Dita tertawa kecil. “Padahal kamu yang kemarin dibilang paling presisi sama Pak Damar.”
Aku ikut tertawa, tapi hanya sebentar. “Iya, tapi presisinya belum cukup.”
Di depanku, garis-garis tipis mulai membentuk ruang demi ruang: foyer, ruang tamu, dapur. Tapi begitu aku sadar bahwa jarak antara dua jendela di gambar tak sepenuhnya simetris, dadaku terasa sesak. Aku menghapusnya pelan. Kemudian menggambar ulang. Lalu menghapus lagi. Tiga kali. Empat kali. Goresan penghapus mulai menipiskan kertas.
“Kalau nggak pas, nanti seluruh proporsinya rusak,” pikirku. “Kalau rusak, nilainya turun. Kalau nilainya turun, nanti semuanya sia-sia.”
Di meja sebelah, Dita sudah mulai menggambar bentuk utama. Sementara aku, masih berusaha menyempurnakan satu ruang.
“Kayaknya kamu terlalu perfeksionis, Ra,” komentar Dita sambil melirik.
Aku tersenyum lagi, kali ini lebih kecil. “Nggak bisa kalau nggak rapi. Nggak tenang”
Dan meski dari luar aku tampak biasa saja, mataku mulai lelah. Tapi tanganku belum berhenti. Belum bisa. Dan belum cukup.
Jam dinding di sudut ruangan berdetak pelan, tapi setiap detiknya seperti bergema di kepalaku. Goresan pensilku tetap halus, hampir tak bersuara. Aku memperhalus detail furnitur ruang keluarga, memastikan bayangan jatuh ke arah yang tepat, garis meja tidak bersinggungan dengan dinding, dan dimensi pintu sejajar sempurna dengan jendela yang aku hitung berkali-kali.
Sementara itu, sebagian besar teman sekelas sudah mulai mengemas alat gambar mereka. Beberapa berdiri sambil bercanda, beberapa lain menunggu asisten dosen memeriksa hasil pekerjaan.
“Lima menit lagi kumpulin ya,” seru salah satu asisten dosen dari ujung ruangan.
Dita menguap kecil. “Ya ampun, mana sempat aku ngarsir detail pintunya. Bodo ah, aku kumpulin aja.”
Aku masih menggambar.
“Ra, kamu udah belum?” Dita melongok ke arah gambarku, lalu mengerutkan alis. “Ra, kamu belum juga ngumpulin tugas? Tugasmu udah kayak brosur properti. Apanya yang kurang?”
Aku tak langsung menjawab. Aku menekuk sedikit ujung kertas gambarku, memeriksa teksturnya. Ada noda kecil, hampir tak terlihat, di pinggir kertas. Seukuran kepala semut. Tapi mataku langsung terpaku.
“Bentar ya, aku bersihin dulu ini. Sedikit lagi.”
Dita menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. “Oke. Tapi jangan sampai telat ngumpulin. Kamu kan yang paling siap…”
Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Tapi tanganku mulai panik, meski wajahku terlihat tetap tenang. Aku menyobek kertas tisu, membasahkannya sedikit dengan air minum dari botol, lalu mengusap noda kecil itu. Pelan. Berkali-kali. Sampai kertasnya mulai terlihat tipis dan basah di bagian bawah.
“Sedikit lagi… Sedikit lagi…” gumamku.
Tanganku mulai gemetar. Hatiku berdegup tak wajar. Tapi wajahku masih sama—tenang, fokus, seperti biasa. Seperti mahasiswi yang memang dikenal teliti dan rajin. Dan ketika satu menit sebelum batas waktu pengumpulan tugas, akhirnya aku menyerahkan gambar itu, aku masih sempat tersenyum pada asisten dosen, membungkuk sopan, dan berkata, “Terima kasih, Kak.”
Tidak ada yang tahu bahwa saat itu, napasku terasa pendek. Tidak ada yang tahu, bahwa pikiranku belum bisa berhenti menghitung berapa milimeter yang tadi mungkin terhapus terlalu keras.
Aku membereskan alat gambar dengan gerakan pelan. Tanganku sempat diam beberapa detik di atas penggaris. Napas terasa berat, tapi tak terdengar. Suara-suara di studio mulai menipis, satu per satu orang berkemas dan pergi, mengucap “sampai besok” tanpa benar-benar menunggu jawaban. Kupasang kembali tutup tabung gambar dan menggantungkannya di bahu.
Langit sore mulai memerah saat aku melangkah keluar dari gedung fakultas. Angin membawa bau semen hangat dan suara lalu-lalang sepeda motor dari arah gerbang utama.
“Ngopi bentar yuk?” Dita menyejajarkan langkahnya. “Ada tempat baru di belakang kampus, katanya tempat duduknya enak buat gambar.”
Aku mengangkat wajah. Mataku sedikit merah, tapi senyum di bibir tetap ku ukir semanis mungkin. “Kayaknya aku langsung pulang aja deh. Mau nyicil revisi tugas desain ruang keluarga.”
Dita memutar mata kecil. “Kamu serius banget, Ra. Tugasnya baru dikumpulin tadi.”
“Iya,” Aku terkekeh pelan, “tapi aku ngerasa ada yang kurang proporsinya. Mau coba ukur ulang.”
Dita membuka mulut, hendak membalas, tapi urung. Ia hanya menepuk pelan bahuku. “Jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Kita nggak lomba siapa paling rapi.”
Aku tersenyum lagi, lebih tipis kali ini. “Aku nggak niat lomba kok. Cuma pengen… ya, semuanya sesuai.”
“Sesuai?” Dita menaikkan satu alis.
“Ya… sesuai aja. Sama ukurannya. Sama fungsinya. Sama… yang seharusnya.”
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan aku sendiri tidak tahu kenapa ada dorongan di dada yang begitu kuat untuk memastikan semuanya pas. Bukan hanya baik. Tapi pas. Presisi. Tidak meleset. Tidak salah. Karena kalau salah, rasanya seperti... dunia bisa bergeser satu inci dari porosnya.
Dita mengangguk ragu, lalu berpamitan. “Oke deh. Hati-hati ya. Jangan lupa makan.”
“Iya, kamu juga.”
Aku menunggu sampai Dita menghilang di tikungan, lalu menarik napas panjang. Aku tidak langsung pulang. Sebaliknya, aku berjalan lambat ke arah perpustakaan kampus yang mulai sepi. Duduk di bangku paling pojok. Mengeluarkan penggaris, catatan, dan salinan gambar tadi. Aku membuka lembar demi lembar, mencari… apa yang salah. Bukan karena dosennya menyuruh. Bukan karena siapa-siapa. Tapi karena kalau tidak aku ulangi, aku tahu malamnya aku tidak akan bisa tidur. Dan suara itu akan terus berdengung tanpa jeda—menghitung, mengecek, memastikan. Mengunci kepalaku dari dalam.
Di luar jendela, langit sudah berpindah warna, menyisakan jingga yang enggan benar-benar pergi. Di dalam ruangan, aku masih menggambar dan menghapus. Masih membenarkan garis yang sebenarnya sudah lurus. Tertunduk di bawah cahaya lampu yang menguning, tanganku gemetar halus. Dan di antara bayangan garis-garis itu, aku mulai bertanya—apa yang sebenarnya sedang kucari?


 bunca_piyong
bunca_piyong





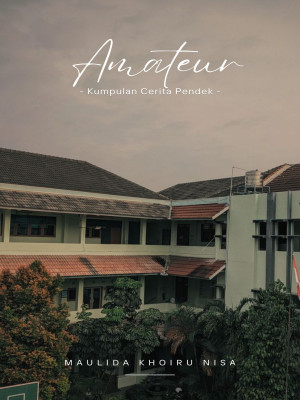






ga ada typo, bahasanya puitis tapi ringan, setiap bab yang di baca dengan mudah membawa masuk ke cerita. ceritannya juga unik, jarang banget orang mengedukasi tentang KESEHATAN MENTAL berbalut romance. dari bab awal sampe bab yang udah di unggah banyak kejutannya (tadinya nebak gini taunya gini). ini cerita bagus. penulisnya pintar. pintar bawa masuk pembaca ke suasananya. pintar ngemas cerita dengan sebaik mungkin. pintar memilih kata dan majas. kayaknya ini bukan penulis yang penuh pengalaman...
Comment on chapter PROLOG