Dunia terasa lebih mudah dikendalikan saat segalanya rapi, teratur, dan sesuai. Tapi apa jadinya jika sedikit kekeliruan saja membuat napas terasa sesak?
**
Langit pagi tak lagi terasa berat seperti dulu. Aku berdiri di depan gerbang universitas dengan jantung berdegup pelan namun mantap. Seragam putih abu-abu sudah diganti jaket kampus berwarna biru dongker, dan di punggungku tergantung ransel penuh buku dan harapan. Hari pertama sebagai mahasiswi. Hari pertama dari janji yang aku buat dalam diam.
“Mahasiswi baru, ya?” sapaan satpam kampus membuatku menoleh, lalu tersenyum kecil.
“Iya, Pak.” Jawabku.
Langkahku ringan, tapi di dada rasanya penuh gelombang. Bukan karena takut, tapi karena tekad yang begitu kencang berdesir. Aku tahu, ini bukan cuma tentang kuliah. Ini tentang menambal luka-luka lama dengan keberhasilan yang bisa membuat Mama tersenyum lagi, membuat Papa pelan-pelan menoleh, dan siapa tahu…bisa membuat Bara bangga dari jauh.
Hari pertama bukan hanya soal kelas baru, tapi tentang pembuktian diam-diam. Di kelas itu, aku duduk di barisan depan. Mataku tajam menyimak, tanganku lincah mencatat. Saat dosen meminta mahasiswa satu per satu memperkenalkan diri, aku berdiri. Suaraku sempat bergetar, tapi senyum kecilku bertahan.
“Nama saya Nara Ayu Prameswari. Dari SMA Negeri 5. Saya memilih Arsitektur karena saya ingin belajar menata ulang sesuatu yang kacau, agar bisa kembali punya bentuk dan arah.”
Beberapa mahasiswa mengangguk pelan, ada juga yang sekadar sibuk dengan ponsel.
Dosen mengangguk, lalu melanjutkan giliran.
Di sekitarku, suara-suara memperkenalkan diri silih berganti—penuh tawa, cerita prestasi, dan harapan tinggi. Tapi telingaku hanya menangkap sebagian. Pikiranku melayang, masih terjebak pada kalimatku sendiri. Aku sempat melirik ke kanan dan kiri, tapi tak ada satu pun wajah yang benar-benar menyapa. Bukan karena mereka tak ramah, mungkin hanya karena belum waktunya.
Jam pelajaran pertama akhirnnya berakhir dengan suara tawa kecil dan rencana nongkrong yang tidak kuikutkan. Di luar kelas, aku duduk sendirian di bangku taman kecil dekat kantin. Di tanganku ada buku catatan berwarna ungu yang sudah penuh coretan, dan di depanku selembar kertas peta kampus yang mulai lecek.
“Sendirian aja?” tanya suara cewek yang entah sejak kapan sudah berdiri di sebelahku. Seorang mahasiswi berambut pendek dengan ransel warna kuning.
“Iya. Masih nyari-nyari tempat enak buat makan,” jawabku sambil tersenyum tipis.
“Wah, sama dong” katanya, seraya duduk “Oh ya, kenalin namaku Dita. Kita satu jurusan, tadi kamu yang duduk di depan, kan?” Lanjutnya sambil menjulurkan tangan.
Aku menjabat tangannya, lalu mengangguk kecil. “Iya, aku Nara.” Jawabku ramah.
“Eh, Nara, kamu rajin banget, deh, nyatet. Tulisanmu rapi banget, aku sampai minder,” ujarnya sambil menunjuk bukuku.
Aku tertawa kecil. “Kalau enggak nyatet, kayaknya otakku langsung reset.”
Dita ikut tertawa. “Relate banget! Tapi tetap aja, tulisanmu kayak font—rata, bersih, enak dibaca. Pantas kamu kayaknya selalu fokus pas kelas.”
Aku mengangkat bahu, sedikit canggung. “Fokus sih iya, tapi kadang terlalu fokus. Sampai lupa istirahat.”
Aku mengangkat bahu, sedikit canggung. “Fokus sih iya, tapi kadang terlalu fokus. Sampai lupa istirahat.”
“Wah, hati-hati, lho. Jangan sampai tumbang sebelum UTS.”
Aku hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis.
Obrolan kecil itu tumbuh menjadi tawa ringan. Lalu berubah menjadi keakraban yang hangat. Tanpa sadar, kami sudah melangkah bersama menuju kantin.
Setelah hari pertama yang panjang, aku akhirnya tiba kembali di rumah. Di dalam kamar, aku duduk di depan meja belajar yang masih menyimpan sisa-sisa energi siang tadi. Di hadapanku tergeletak catatan yang kutulis sebelumnya—rapi, penuh coretan stabilo dan garis-garis yang tak pernah melenceng.
Perlahan, tanganku mulai menyusun alat tulis satu per satu: pensil 2B, penggaris, stabilo warna pastel, dan sticky note berbagai warna tapi ukuran sama. Semua harus sejajar. Semua harus simetris. Jika satu agak miring, aku ulang lagi dari awal. Sampai letaknya pas. Sampai rasanya… lega.
Tiba-tiba, napasku jadi lebih pendek. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk ukuran malam yang tenang. Aku bangkit, merapikan bantal yang sebenarnya sudah rapi, lalu melipat ulang selimutku.
“Harus sempurna,” bisikku. “Harus tertata. Harus rapi. Harus teratur.”
Tiba-tiba, pandanganku kembali tertuju ke meja belajar. Ada selembar kertas tugas yang belum sempat kuselesaikan tadi siang, sedikit miring di antara tumpukan lain yang sudah rapi. Rasanya mengganggu. Aku menarik napas, lalu bangkit lagi. Lampu meja kembali menyala, menyinari kertas itu dengan cahaya hangat. Meski mataku sudah berat, tanganku mulai menulis. Pelan, hati-hati. Harus selesai. Harus benar, meski mataku mulai lelah.
Setiap huruf kubentuk dengan ukuran yang sama, tekanan pulpen harus merata. Bila satu huruf tampak miring, kucoret dan kutulis ulang. Tanganku gemetar kecil, tapi aku memaksakan diri tetap menulis. Setiap kali kepalaku terasa berat, aku menghela napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk berhenti.
“Kalau sekarang menyerah, besok pasti lebih buruk,” gumamku.
Jam di dinding berdetak pelan. Pukul 23.47. Tapi tugas itu belum selesai dengan rapi. Mataku mulai perih, tapi aku justru berdiri, mengambil penggaris dan mulai menggarisi bagian tepi kertas agar sejajar sempurna. Aku merasa lebih tenang saat semuanya berada dalam garis lurus. Namun tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan.
Tok. Tok.
“Nara, belum tidur?” suara Mama terdengar dari balik pintu.
Refleks kututup bukuku. “Sebentar lagi, Ma.”
“Jangan dipaksa, ya… besok kan masih bisa dilanjutkan.”
“Iya, Ma,” jawabku pelan, meskipun aku tahu aku tidak akan bisa tidur sebelum semuanya selesai.
Langkah kaki Mama menjauh, dan sunyi kembali turun. Aku menatap bayanganku di cermin meja belajar. Mata panda mulai membayang di bawah mataku. Rambutku agak berantakan. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang menyala.
“Aku harus bisa,” ucapku pelan, hampir seperti mantra.
Lalu aku kembali fokus, menarik napas panjang, mengatur posisi dudukku agar lurus, dan mulai menulis ulang seluruh halaman pertama karena menurutku tadi huruf ‘a’-ku terlalu bulat.
Jam terus berdetak. Dan malam perlahan larut dalam keheningan yang penuh usaha. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Aku memutuskan untuk tidur.
Keesokan paginya, aku sudah bangun sebelum alarm berbunyi. Jam lima kurang sepuluh, langit masih kelabu. Tapi aku tidak bisa tidur lagi, ada sesuatu yang mengganjal. Aku membuka buku catatanku. Lagi. Halaman yang sudah kutulis ulang semalam, kubaca lagi satu per satu. Di halaman ketiga, aku berhenti. Ada satu huruf ‘e’ yang menurutku terlalu tinggi. Aku meremas kertas itu, lalu menarik lembar baru.
“Nggak bisa kayak gini. Nanti nggak enak dilihat,” bisikku sambil mulai menulis ulang dari awal.
Semua harus rapi. Semua harus sesuai urutan warna. Semua garis margin harus sejajar. Setelah selesai, kutatap catatan yang baru. Senyum kecil muncul di wajahku. Tapi hanya sebentar. Mataku lalu bergerak ke sisi kanan buku. Sticky note hijau pucat yang kutempel semalam miring tiga derajat. Aku mengangkatnya pelan, lalu menempelkannya ulang. Dua kali. Tiga kali. Sampai benar-benar lurus.
Suara Mama memanggil dari dapur. “Nara, ayo sarapan!”
“Iya, Ma!” jawabku sambil buru-buru merapikan meja. Tapi aku nggak bisa pergi begitu saja. Meja harus bersih. Pulpen harus kembali ke kotaknya dan tersusun sesuai warna dari biru ke merah, lalu hitam. Baru setelah itu aku keluar kamar. Tapi bahkan saat duduk di meja makan, pikiranku masih kembali ke buku catatanku.
Tadi aku udah betulin semua kan? Tadi... ‘e’-nya udah bagus semua? Kalau belum, nanti dicek lagi. Nanti dicek lagi. Nanti dicek lagi.
Di meja makan, aku menyendok nasi dengan tenang. Mama duduk di seberangku, sesekali melirik dengan pandangan kosong. Papa masih di kamar, mungkin bersiap untuk berangkat ke kantor. Di tengah sunyi itu, hanya bunyi sendok dan piring yang terdengar.
“Kuliah hari ini jam berapa?” tanya Mama pelan, nadanya lebih seperti rutinitas daripada keingintahuan.
“Jam sembilan. Tapi aku mau berangkat jam tujuh, sekalian baca-baca dulu di perpustakaan,” jawabku sambil tersenyum. Suaraku stabil. Mataku jernih. Aku terlihat seperti gadis yang siap menjalani hari.
Mama mengangguk kecil. “Mau di siapin bekal untuk brunch?.” Tanya Mama.
“Udah, Ma. Ga perlu. Ini aja udah cukup.”
Mama tiak menjawab, hanya mengangguk.
Setelah selesai makan, aku membersihkan meja, mencuci piringku sendiri, lalu kembali ke kamar. Aku berdiri di depan cermin, memeriksa jaket almamaterku. Ada lipatan kecil di kerah sebelah kiri. Kubetulkan. Lalu kutatap bayangan diriku.
“Harus kelihatan rapi. Harus teratur”
Langkahku terasa ringan saat keluar rumah. Ada kepuasan kecil setiap kali semuanya berada di tempat yang semestinya. Di dalam kereta menuju kampus, aku membuka buku catatanku—sekadar memastikan bahwa semua lembar masih tersusun rapi, tanpa lipatan, tanpa noda. Dari luar, aku mungkin tampak seperti mahasiswa teladan: serius, rajin, dan teratur. Tapi hanya aku yang tahu, betapa lelahnya menjaga semuanya tetap sempurna.
Setibanya di kampus, angin pagi menyambut dengan lembut. Aku baru saja melangkah ke taman depan kelas saat suara ceria memanggil dari arah gerbang.
“Naraaaa!” seru Dita sambil melambaikan tangan.
Aku langsung tersenyum lebar, membalas sapaan itu tanpa ragu. Ada sesuatu yang hangat dalam caranya memanggil namaku—seolah kami sudah berteman sejak lama.
“Yuk!” katanya antusias sambil menyamakan langkah.
“Kamu udah ngerjain tugas dasar desain arsitektur? Aku sempat revisi sedikit tadi pagi.” Kataku sambil tersenyum.
Dita tertawa. “Kamu niat banget, sumpah. Aku aja belum buka.”
Dan aku hanya membalas dengan tawa ringan, menahan diri untuk tidak berkata bahwa “sedikit revisi itu sebenarnya menulis ulang delapan halaman sejak subuh”.
Sepanjang kelas, aku mencatat cepat dan bersih. Saat dosen bertanya, aku bisa menjawab dengan mantap. Aku tampak cerdas, bahkan mungkin sempurna di mata orang lain.
Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, pikiranku terus mengulang:
Kalau tidak sempurna, semuanya akan sia-sia. Kalau tidak teratur, nanti ada yang salah. Kalau aku salah, aku menyakiti orang lain.
Tapi dari luar, aku tetap Nara yang ceria. Nara yang pintar. Nara yang kuat.
Saat istirahat siang, aku dan Dita duduk di bawah pohon flamboyan dekat gedung fakultas.
“Kamu tadi jawab pertanyaan Bu Fika cepet banget. Seriusan deh, aku belum nyambung, kamu udah angkat tangan duluan,” celetuk Dita sambil mengunyah bekalnya.
Aku tersenyum. “Aku udah baca materinya tadi subuh. Soalnya aku enggak bisa tenang kalau belum paham.”
Dita mengangguk-angguk. “Kayaknya kamu tipe yang harus ngerjain semua jauh sebelum deadline ya?”
“Banget,” aku mengangguk sambil tertawa kecil. “Rasanya kayak ada yang gatal di kepala kalau belum diselesaikan.”
“Wah, aku kebalikannya banget. Deadline tuh sahabatku,” ujar Dita, tertawa keras. “Tapi seneng sih duduk bareng kamu. Jadi keikut semangat!”
Aku hanya tersenyum, lalu dengan refleks merapikan kertas catatanku yang tertiup angin. Tepi halaman yang mencong sedikit, kuluruskan pelan. Dita tak memperhatikan.
Sore harinya, di rumah, aku membantu Mama di dapur. Sesekali Mama bicara, kali ini suaranya agak lebih hidup.
“Tadi kuliah belajar apa?”
“Dasar-dasar desain arsitektur. Bahas soal prinsip proporsi sama penataan ruang. Seru, Ma. Dosenku juga enak cara ngajarnya.”
Mama mengangguk sambil mengiris wortel. “Bagus, ya. Kamu kayaknya betah.”
“Iya, Ma. Aku suka. Kayaknya ini pilihan yang pas.”
Mama tersenyum tipis. “Papa kamu tadi tanya-tanya juga, loh. Katanya lihat kamu makin rajin.”
“Beneran?” mataku membesar, ada secercah harapan di sana.
Mama mengangguk. “Tapi ya kamu tahu Papa. Dia ngomongnya pakai gaya ‘gimana kuliahmu?’ terus langsung bahas cuaca,” ujarnya sambil terkekeh pelan.
Aku tertawa, tapi hatiku menghangat. “Nggak apa-apa. Yang penting nanya.”
Kami melanjutkan memasak. Saat aku merapikan bumbu di rak, aku menyusun botol-botol itu sesuai tinggi dan warna labelnya tanpa sadar. Mama memperhatikanku sesaat, lalu berbalik mengaduk wajan.
Malam itu, aku duduk di kamar sambil membaca ulang catatanku. Lampu meja menyala lembut, menyoroti barisan tulisan tangan yang bersih dan teratur. Di luar kamar, terdengar suara TV dari ruang tengah. Suara Papa dan Mama sedang berdiskusi soal acara berita. Tidak tegang. Tidak berantem. Hanya… biasa. Dan itu sudah cukup.
Aku menarik napas pelan. Menutup bukuku, menyusunnya sejajar dengan yang lain di rak. Tanganku berhenti sejenak saat melihat sticky note yang sedikit mencuat. Kutekan perlahan agar rata. Kemudian aku bangkit, mematikan lampu meja, dan berjalan ke tempat tidur. Selimutku kurapikan sekali lagi sebelum berbaring. Posisi bantal kuatur, sudut selimut kuluruskan. Semua harus seimbang.
Di langit-langit kamar, bayangan cahaya dari jendela membentuk pola-pola samar. Aku menatapnya tanpa bergerak, seolah membiarkan tubuhku diam, padahal pikiranku terus bekerja. Ada daftar kegiatan yang berputar di kepala—hal-hal yang harus kulakukan, kuhafal, kurapikan, kususun… semuanya berbaris rapi, tapi tak pernah benar-benar berhenti.
Besok, aku akan kembali tersenyum, mencatat rapi, dan menjawab pertanyaan dosen dengan mantap. Aku akan tetap jadi Nara yang kuat, yang rajin, yang terlihat baik-baik saja. Padahal jauh di dalam diriku, ada suara yang terus berbisik pelan: satu kali lagi. Coba ulangi. Belum pas. Belum cukup. Tapi malam sudah larut. Dan untuk kali ini, aku membiarkan mataku terpejam. Dengan napas yang melambat, dan jantung yang masih berdetak dalam irama tekun. Dunia pun sunyi. Sejenak.


 bunca_piyong
bunca_piyong







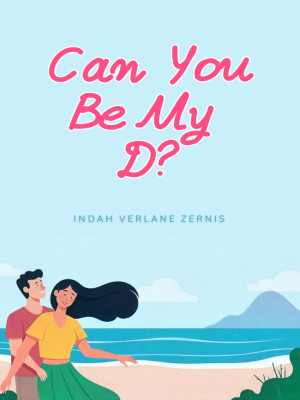




ga ada typo, bahasanya puitis tapi ringan, setiap bab yang di baca dengan mudah membawa masuk ke cerita. ceritannya juga unik, jarang banget orang mengedukasi tentang KESEHATAN MENTAL berbalut romance. dari bab awal sampe bab yang udah di unggah banyak kejutannya (tadinya nebak gini taunya gini). ini cerita bagus. penulisnya pintar. pintar bawa masuk pembaca ke suasananya. pintar ngemas cerita dengan sebaik mungkin. pintar memilih kata dan majas. kayaknya ini bukan penulis yang penuh pengalaman...
Comment on chapter PROLOG