Titik balik tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir diam-diam, dalam bentuk semangat yang bangkit dari reruntuhan, atau keteguhan untuk bangun setiap pagi dan mencoba lagi.
**
Lampu meja belajar menyinari buku-buku yang terbuka lebar. Malam menelan sisa-sisa suara rumah; hanya suara detik jam dinding yang terdengar, bergulir pelan seperti bisikan waktu. Aku duduk di meja belajar, menulis rumus yang tadi siang belum dipahami. Dan kini, satu per satu semua rumus itu mulai masuk akal.
Tak ada yang tahu kalau aku sudah mulai menempelkan target ujian di dinding. Tak ada yang tahu kalau aku mengganti playlist-ku mejadi lagu-lagu instrumental biar bisa fokus. Tak ada yang tahu, dan memang tak perlu tahu. Karena bagi ku, kalau tekat sudah bulat, prosesnya cukup aku yang tahu, tanpa diumbar dan tanpa berisik.
Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan.
“Nara?” terdengar suara Mama, nyaris ragu di balik pintu.
Aku buru-buru memindahkan bukuku, menutup lembar soal tryout, lalu menjawab, “Iya, Ma.”
Pintu terbuka sedikit. Mama menyembulkan kepala. “Belum tidur?”
“Belum Ma. Belajar sedikit lagi.”
Mama mengangguk kecil. Matanya masih terlihat lelah. Ia tidak masuk ke kamar, hanya berdiri di ambang pintu. “Jangan terlalu malam, ya.” Katanya mengingatkanku.
“Iya, Ma.” Jawabku sambil tersenyum.
Pintu kembali tertutup. Aku menoleh ke jendela. Gelap. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang menyala, api kecil yang aku jaga sendiri. Aku menarik napas panjang dan kembali membuka buku.
“Sekarang, waktunya menjawab soal matematika halaman 42.” Gumamku bersemangat.
Aku terus mengerjakan semua tugas dengan saksama. Setiap rumus kucatat dengan teliti, kuhitung ulang tanpa celah, dan materi-materi kubuat ringkasannya agar lebih mudah dipahami. Tanpa kusadari, ketika malam perlahan memberi ruang bagi pagi, aku masih di sana—terlelap di antara tumpukan soal tryout, di atas meja belajarku yang dingin dan sunyi.
Ketika aku terbangun. Langit belum sepenuhnya terang. Udara masih dingin, dan cahaya belum menyentuh kaca jendela kamarku. Aku menyeduh teh sendiri di dapur, lalu kembali duduk di meja belajar, mengulang pelajaran yang semalam belum selesai. Tak ada yang menyuruhku. Tak ada yang memaksa. Tapi aku merasa seperti sebuah kewajiban, harus dilakukan demi Mama, demi Papa, dan demi Bara. Karena... kalau bukan aku siapa lagi?
Di sekolah, aku lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan daripada di kantin. Aku memilih untuk langsung pulang setelah kelas selesai, bahkan menjauh dari obrolan-obrolan yang terasa tak penting bagiku—gosip, basa-basi, atau percakapan yang hanya membuat pikiranku lelah.
“Ra... Kamu udah lama nggak ikut nongkrong lagi sepulang sekolah?” tanya Laras, sedikit heran waktu aku buru-buru mengemasi bukuku.
“Enggak deh. Mau langsung pulang. Soalnya mau lanjut ngerjain tugas” jawabku ringan.
Laras berkedip. “Wah, gila. Raji banget sih kamu, Ra.”
Aku hanya tersenyum kecil, tanpa merasa perlu menjelaskan apa pun.
Di rumah, Papa mulai memperhatikan bahwa sekarang aku lebih sering berada di kamar untuk belajar, bukan mengurung diri dalam keheningan pasif seperti dulu. Bahkan saat Papa pulang malam dan melempar pandang ke ruang makan, aku sedang duduk di sana: membuka buku, mencatat, tanpa banyak bicara. Mama sesekali memperhatikanku juga. Kadang membawa sepiring buah, meletakkannya tanpa berkata apa-apa. Aku hanya menoleh dan tersenyum, lalu kembali mencatat.
Tapi di balik semua usahaku untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan keluargaku yang retak, masih ada malam-malam ketika air mata ketika jatuh diam-diam di pipiku—saat bayangan Bara datang membawa rindu yang tak berujung dan meninggalkan perih. Saat melihat Mama yang menangis di atas sajadahnya, atau Papa yang termenung di teras rumah.
Tapi kali ini aku tidak diam saja. Aku terus berusaha. Jadi, aku lebih sering membuka buku. Mengulang materi. Mencatat mimpi yang belum sempat kubagi pada siapa-siapa. Semua kulakukan pelan-pelan, dengan harapan kecil bahwa ini akan mengubah sesuatu. Karena, satu kalimat terus berputar di kepala: ‘Kalau bukan aku, siapa lagi?’. Dan dari sudut rumah yang dulu penuh luka, kini ada cahaya kecil yang menyala. Tidak besar. Tapi cukup hangat untuk mengawali sesuatu.
Malam demi malam, kamarku berubah jadi ruang tempur yang tenang. Meja belajarku dipenuhi sticky notes warna-warni, pulpen dengan tinta hampir habis, dan kertas latihan soal yang berantakan tapi penuh coretan.
Setiap kali jarum jam menunjuk angka dua belas malam, aku akan memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu kembali membuka mataku dengan sorot tak kalah tajam. Kadang-kadang tanganku gemetar karena lelah. Kadang tulisanku mulai miring dan tak rapi. Tapi aku tetap duduk di sana, menyelesaikan satu bab, lalu bab berikutnya.
Buku-buku pelajaran bukan lagi kewajiban. Mereka adalah jembatan. Ke sesuatu yang lebih baik. Tak ada musik. Tak ada ponsel. Duniaku hanya terdiri dari lembar soal, tinta pena, dan suara detik jam yang berjalan pelan. Satu-satunya suara yang kadang muncul hanyalah bisikan kecil dalam kepalaku—bukan keluhan, tapi pengingat: Untuk Mama. Untuk Papa. Untuk Bara. Untuk diriku sendiri juga.
Saat libur tiba dan suara tawa mulai mengisi ruang-ruang pesan singkat, aku justru tenggelam dalam tumpukan rumus dan catatan. Ajakan teman-teman untuk bersantai sering kali hanya kujawab dengan singkat, “Belum bisa.”
Lama-lama, ritme belajarku seakan mengubah suasana rumah. Mama kini tak sekadar meletakkan potongan buah di meja—kadang, ia mengusap kepalaku pelan saat lewat, seolah diam-diam menyemangati. Papa masih jarang bicara, tapi suatu malam ia berdiri cukup lama di ambang pintu kamarku. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya diam menatap, lalu pergi begitu saja. Tapi aku bisa merasakannya—ada sesuatu dalam tatapan itu. Bukan sekadar kelelahan. Bukan sekadar dingin. Mungkin, itu cara Papa menunjukkan perhatian… dengan caranya sendiri.
Malam itu, setelah menyelesaikan satu set latihan soal tryout, aku berdiri pelan. Aku meraih selembar kertas berisi daftar universitas impianku, hasil cetak dari warnet beberapa hari lalu, kemudian menempelkannya ke dinding tepat di atas meja belajarku. Bukan untuk pamer. Bukan untuk dipuji. Tapi sebagai penanda: ini jalanku. Dan aku akan sampai.
**
Pagi menyelinap pelan di balik tirai tipis jendela kamar. Aku baru saja selesai salat subuh. Rasa kantuk masih menggantung, tapi tubuhku terasa ringan. Ada sesuatu yang hidup kembali dalam diriku—meski kecil, tapi hangat.
Aku turun ke dapur, menemukan Mama yang sudah sibuk menyiapkan sarapan. Aroma telur dadar menyambutku, disusul suara sendok beradu pelan di atas piring.
“Nara, kamu bangunnya pagi banget sekarang, ya,” ucap Mama tanpa menoleh, tapi suaranya hangat.
Aku hanya tersenyum kecil sambil mengambil gelas dan menuang air. “Udah biasa, Ma. Enak belajar pagi-pagi.”
Mama menoleh sejenak. Tatapannya mengandung sesuatu yang tak terucap, campuran haru dan bingung. “Nggak capek?”
Aku menggeleng pelan. “Nggak juga.”
Kami duduk berseberangan di meja makan kecil. Mama menyuapkan nasi hangat ke mulutnya perlahan, lalu tiba-tiba bertanya, “Ujian masuk kampusnya kapan, Ra?”
Pertanyaan itu membuatku sedikit terdiam. Aku menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara yang lebih pelan, “Beberapa hari lagi, Ma.”
Mama meletakkan sendoknya. Matanya sedikit melebar. “Hah? Lah, kok Mama baru tahu? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin?”
Aku hanya tersenyum. “Nggak penting, Ma. Doain aja, ya.”
Ada jeda disana. Lalu tangan Mama menyentuh punggung tanganku. Lembut, sehangat dulu. “Mama doain tiap hari, Ra. Tanpa Nara minta Mama doain”
Hatiku mencelos sedikit. Tapi aku tetap tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Hanya mengangguk.
Hari-hari berlalu pelan, seperti menghitung detik dengan dada sesak. Sampai akhirnya, pagi itu datang juga—hari ujian masuk universitas. Sebelum berangkat, aku sempat menatap Mama lebih lama dari biasanya. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Tapi ada sesuatu yang baru tumbuh di antara kami, pengertian yang tenang, seperti fajar yang tidak terburu-buru datang tapi selalu pasti.
Langit tampak kelabu pagi itu. Udara di luar jendela kamarku dingin, tapi dadaku lebih dingin lagi. Aku berdiri di depan kaca, mengenakan seragam rapi, rambut tersisir sempurna. Pencitraan diriku terlihat baik-baik saja. Tapi dalam hati, kegelisahan merayap perlahan, tak bisa kututupi.
Tanganku menggenggam rapat kartu peserta ujian yang sudah kusiapkan semalam. Suasana tenang yang biasanya ada dalam diriku kini tergantikan dengan detak jantung yang keras dan cepat. Aku menarik napas panjang, kemudian mengeluarkannya pelan-pelan. “Bisa, Nara. Bisa. Kamu pasti bisa,” gumamku pada diri sendiri.
Ketika aku keluar dari kamar, Mama sudah menungguku di meja makan, menyodorkan sarapan hangat. Aku tersenyum, sedikit memaksakan diri, mengambil beberapa suap.
“Jangan lupa doa, Ra,” Mama mengingatkan dengan suara lembut, wajahnya sedikit cemas meski berusaha tetap terlihat tenang.
Aku hanya mengangguk. “Iya, Ma. Doain aku.”
Sesampainya di tempat ujian, suasana penuh sesak dengan siswa-siswi yang sama tegangnya. Ada yang berbicara dengan teman-teman, ada yang memegang buku dengan gemetar. Aku hanya berjalan dengan langkah mantap, meski jantungku berdebar-debar. Aku menghela napas sekali lagi, berusaha menenangkan diriku.
Setelah melewati pemeriksaan dan duduk dengan tenang di bangku ujianku. Aku menatap soal yang tersebar di depanku. Semua yang kupelajari selama ini terasa seperti bercak-bercak di kepala—kadang-kadang terang, kadang-kadang kabur. Namun, ketika ujian dimulai, tanganku bergerak otomatis, menyentuh kertas jawaban dan mulai menjawab soal satu per satu. Setiap soal yang sudah kukerjakan, membuat rasa percaya diriku meningkat menggantikan kegelisahan. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk mencoba membalik arah takdir yang selama ini diam-diam menggerogoti kebahagiaan kami.
Beberapa jam kemudian, ujian selesai. Aku melipat kertas ujian dan mengumpulkannya. Rasa cemas mulai mereda, digantikan rasa lega. Aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik. Semua waktu belajar dan rasa lelah itu tidak akan sia-sia.
“Percaya sama diri sendiri,” gumamku saat melangkah keluar.
Langit siang terasa lebih cerah dari biasanya, seolah ikut merayakan selesainya satu beban besar di pundakku. Langkahku ringan, meski kaki masih pegal karena duduk terlalu lama. Di lorong kampus, suara obrolan bercampur tawa terdengar dari kelompok-kelompok siswa yang juga baru keluar dari ruang ujian.
Aku menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, napas itu tidak disertai degup panik di dada.
“Gimana ujianmu?” tanya Laras yang tiba-tiba sudah sejajar denganku, menyodorkan minuman dingin dari vending machine.
“Lumayan,” jawabku sambil tersenyum tipis. “Nggak sempurna, tapi aku yakin cukup.”
“Kalo kamu mah aku yakin sih Ra,” kata Dita sambil tersenyum lebih lebar. “Kita tinggal nunggu hasilnya, terus move on ke fase berikutnya: nunggu pengumuman sambil pura-pura nggak stres.”
Aku tertawa kecil. Pura-pura memang sudah jadi keahlianku sejak lama—pura-pura baik-baik saja, pura-pura kuat, pura-pura tak apa-apa. Tapi hari ini, rasanya bukan pura-pura. Hari ini, aku benar-benar merasa lega.
Beberapa minggu pun berlalu. Pagi di rumah tetap berjalan seperti biasa—dengan rutinitas yang tenang, nyaris tanpa percakapan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Hari pengumuman penerimaan universitas telah tiba, dan ada ketegangan halus yang mengisi udara. Mama, yang biasanya sibuk mondar-mandir mengurus pekerjaan rumah, kini duduk diam di depan televisi, memegang remote dengan tangan yang tak tenang. Wajahnya menyimpan kegelisahan yang tak sepenuhnya bisa ia sembunyikan. Papa juga ada di meja makan, tampak membaca koran, tapi sesekali matanya melirik ke arahku—diam-diam mengawasi, seperti menanti sesuatu yang penting.
Aku menatap ponselku, jantungku berdetak lebih kencang, seperti menghantam rongga dada setiap detiknya. Layar ponselku memuat lambat, seolah tahu betul betapa menegangkannya detik-detik ini. Aku bisa merasakan Mama berdiri tak jauh di belakangku, menahan napas sama sepertiku.
Saat halaman itu akhirnya terbuka sepenuhnya, mataku langsung menyapu baris-baris teks yang terpampang. Mencari namaku. Mencari sesuatu yang bisa membuat semua malam panjang dan tangis diam-diam itu terasa tidak sia-sia. Dan di sana… di baris pertama, paling atas, aku menemukannya. Namaku. Tertera jelas. Lolos.
Tanganku menutupi mulut. Air mata menggenang begitu cepat, padahal aku tadi berjanji tidak akan menangis. Tapi rasanya terlalu besar untuk disimpan di dada.
Mama mendekat. “Gimana?” tanyanya pelan.
Aku menoleh perlahan, senyumku gemetar. “Aku keterima, Ma.”
Ruangan itu sempat sunyi sejenak. Mama menatapku lama—matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya memelukku erat, seolah ingin menumpahkan segala rasa yang tak terucap. Papa, yang biasanya lebih pendiam, ikut mendekat. Ia menyunggingkan senyum kecil, lalu menepuk punggungku pelan, hangat.
“Selamat, Ra. Kamu hebat,” kata Papa, suaranya berat, namun penuh makna.
Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang terus keluar. Aku merasa, meski tidak ada perayaan besar, ini adalah langkah pertama yang sangat berarti, untuk diriku, untuk keluarga, dan untuk masa depan yang lebih cerah.
Setelah momen haru itu, aku kembali duduk dengan tenang. Dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Walau ada banyak tantangan di depan, aku merasa siap untuk menghadapinya. Keputusan untuk menjadi mahasiswi di universitas terbaik itu bukan hanya tentang impian pribadi, tapi juga tentang Mama, tentang Papa, dan tentang Bara. Tentang upaya kecil untuk membuat mereka bangga—dan mungkin, mengembalikan secercah kebahagiaan di tengah hidup kami yang sempat runtuh.


 bunca_piyong
bunca_piyong














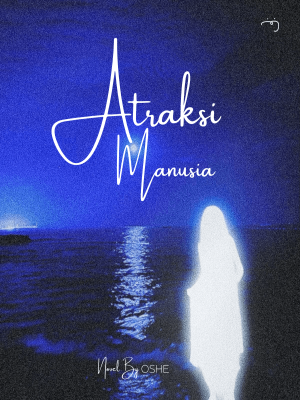



Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .