Di rumah ini, ada yang selalu lebih: lebih dipilih, lebih disayang, lebih diperhatikan. Dan aku hanya ada di sisi bayangnya, menunggu tempat yang tak pernah kutemukan.
**
Bara sedang menuang susu ke gelas bening, kausnya lusuh dan rambutnya masih acak-acakan. Jam baru menunjukkan pukul enam pagi, dapur masih setengah gelap. Lampu utama belum dinyalakan, hanya sisa cahaya lembut dari jendela yang temaram.
Aku berdiri ragu-ragu di ambang pintu. Langkahku membunyikan suara pelan di atas ubin yang dingin. Bara menoleh sekilas, lalu kembali menutup pintu kulkas dengan perlahan.
“Udah bangun?” tanyanya pelan, suaranya masih berat seperti orang yang baru saja terjaga dari tidur.
Aku mengangguk. Suaraku belum siap keluar.
Dia meletakkan kembali botol susu ke dalam kulkas, lalu jalan ke arah wastafel. Aku duduk di meja makan. Entah kenapa, pagi itu aku ingin bicara. Tapi entah juga harus mulai dari mana.
“Kalau mau, ada roti di piring yang sudah aku buatkan,” katanya, sambil mencuci gelas.
Aku tidak menjawab. Hanya melihat punggungnya. Dulu, waktu kecil, aku sering berada di punggung itu. Bara suka menggendongku kalau mati lampu. Tapi sekarang.. aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kami bersalaman.
Selesai mencuci, dia mengelap tangan ke celana. Lalu berjalan pelan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia sempat menoleh dan bilang, “Kalau mau bikin susu, air panasnya masih sisa di teko.” Kalimat itu sederhana. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Seperti... perhatian yang tidak berani tampil utuh.
Aku hanya mengangguk. Lalu menatap rotinya. Ada dua potong roti dengan selai nanas. Kesukaanku.
Bara memang bukan tipe orang yang suka bertanya, “Kamu kenapa? Atau mau apa?” Tapi dia pernah diam-diam menyisihkan satu potong nugget terakhir ke piringku. Tanpa bilang apa-apa.
Dia juga bukan orang yang akan mengantarkan ku ke dokter kalau aku demam. Tapi pernah suatu malam, aku terbangun karena batuk tak berhenti, dan kudapati segelas air hangat sudah ada di meja, lengkap dengan minyak kayu putih yang dibuka setengah. Mama tidak mungkin menaruhnya. Papa juga tidak. Dan cuma Bara yang tahu aku sering batuk di malam hari.
Bara juga bukan tipe Abang yang berbagi pelukan kepada Adeknya. Bahkan seingatku dia tidak pernah memelukku. Tidak pernah bilang sayang. Tidak pernah membelaku saat Papa membentak.
Tapi dia pernah mengganti channel TV diam-diam saat aku kesal tidak bisa menonton kartun, karena remote-nya disembunyikan Papa, katanya aku harus belajar, bukan nonton. Saat itu, Bara pura-pura lagi iseng nyari acara bola, lalu tiba-tiba kartun pagi itu muncul lagi di layar. Dia tidak bilang apa-apa, cuma duduk di ujung sofa sambil makan biskuit kayak biasa. Tapi aku tahu, itu ulahnya.
Dia juga pernah memotongkan buah untukku tanpa diminta. Pernah juga, sekali, mengelus kepalaku saat aku ulang tahun. Cepat sekali, kayak angin lewat. Tapi aku mengingatnya lebih dari kejutan apapun.
Aku jadi ingat sesuatu. Dulu, waktu aku kelas dua SD, aku pernah terjatuh dari sepeda. Lututku sobek, darahnya mengucur deras. Mama lagi di pasar dan Papa belum pulang. Yang pertama datang waktu mendengar aku menangis bukan tetangga. Tapi Bara. Dia tidak bilang apa-apa, tapi langsung mengangkat ku ke kamar mandi, menyirami luka pelan-pelan, lalu menyobek kausnya sendiri untuk dijadikan perban.
“Jangan bilang Mama, ya,” katanya waktu itu, setengah takut. “Nanti Mama panik.”
Aku hanya mengangguk sambil terisak.
Bara duduk di lantai kamar mandi, tangannya tetap menekan lututku yang berdarah. Dan saat itu, aku merasa... dilindungi, diperhatikan, dan disayang. Tapi setelah hari itu, kami tidak pernah membicarakannya lagi.
Semenjak aku SMA, kami benar-benar semakin jauh. Bukan karena ada pertengkaran besar. Tapi karena terlalu banyak diam yang dibiarkan tumbuh, sampai jadi jurang.
Bara jarang ada di rumah. Alasannya selalu tugas kampus, atau lembur di tempat magang. Kalaupun pulang, dia lebih sering mengurung diri di kamar. Pintunya selalu tertutup rapat, dan hanya ada cahaya dari sela bawah pintu yang menandakan dia ada di dalam. Sehingga keberadaannya nyaris tak terasa. Seperti bayangan: ada, tapi tak bisa disentuh.
Pernah suatu hari, aku pulang sekolah lebih cepat karena guru sedang rapat. Rumah sepi. Tapi lampu kamar Bara menyala. Aku hampir mengetuk pintunya, cuma karena.... entahlah, mungkin aku hanya ingin mendengar suaranya. Tapi tanganku berhenti di udara. Aku sadar, aku tidak punya alasan apa-apa untuk mengetuk. Tidak ada yang perlu kutanyakan, dan tidak ada juga yang harus kujawab.
Jadi aku pergi ke dapur, mengambil air, dan kembali ke kamar. Sambil menutup pintu, aku mendengar suara langkahnya. Tapi tidak ada yang saling menyapa. Seperti dua orang asing yang tidak sengaja tinggal di rumah yang sama. Dan itulah masalahnya—kami terlalu terbiasa saling membiarkan, sampai lupa caranya saling hadir.
Aku tahu bara bukan orang jahat.., tapi aku merasa selalu hidup dalam bayang-bayang dirinya. Bara tumbuh dengan pelukan dari Mama dan Papa, dengan seluruh perhatian dan cinta yang harusnya dibagi rata denganku. Tapi tidak, semuanya hanya tertuju pada Bara, mungkin karena Bara lahir duluan atau karena saat kecil Bara sering sakit-sakitan. Sehingga ia lupa, bahwa tidak semua orang tumbuh dengan pelukan yang sama.
Pernah sekali, waktu aku demam sampai muntah-muntah, aku mengira akan mendapatkan perhatian yang sama seperti Bara dapatkan. Aku menunggu. Di kamar, dengan badan gemetar dan kepala berat. Tapi yang datang hanya suara Mama dari dapur, “Minum obatnya jangan lupa, Ra.” Tidak ada yang duduk di sampingku. Tidak ada tangan yang menyeka keningku pakai handuk dingin. Tidak ada yang bertanya, “Mau dimasakin apa?”
Sejak hari itu, aku semakin merasa bahwa Bara itu seperti matahari di rumah. Semua gravitasi keluarga kami bergerak mengelilinginya. Dia juga seperti hadiah—yang dibanggakan, dijaga, dan diceritakan ke mana-mana. Sedangkan aku… Aku seperti bayangan di sudut ruangan, ada tapi tak pernah jadi pusat. Seperti ruang kosong yang tidak dicari, kecuali saat dibutuhkan.
Mungkin karena itulah hubungan kami semakin lama semakin rumit. Bukan karena dia jahat, bukan juga karena aku membencinya. Tapi karena ada sesuatu yang mengendap lama, semacam perasaan tidak dipilih, tidak cukup berharga untuk diprioritaskan.
Bahkan di balik perhatian Mama dan Papa kepadanya, aku kadang merasa iri… atau entahlah, mungkin cemburu. Bara seolah selalu tahu cara membuat mereka tersenyum. Sementara aku… hanya bisa diam, menonton dari jauh, seperti penonton yang tidak pernah diberi panggung.
Aku mencoba menjadi anak baik. Tidak banyak menuntut. Tidak membuat masalah. Tapi justru di situlah letak kesalahannya, karena aku terlalu senyap, sehingga mereka lupa aku juga butuh dilihat.
Pernah aku berpikir, mungkin kalau aku lebih hancur, lebih keras, dan lebih berantakan.., mereka mungkin akan mulai memperhatikan. Tapi aku tak pernah benar-benar bisa melakukannya. Yang aku tahu hanyalah bertahan dalam diam, menunggu… sambil pelan-pelan belajar untuk tidak merasa asing di rumah sendiri. Belajar menerima bahwa mungkin begini caraku ada—tidak mencolok, tidak dicari, tapi harus tetap bertahan.


 bunca_piyong
bunca_piyong









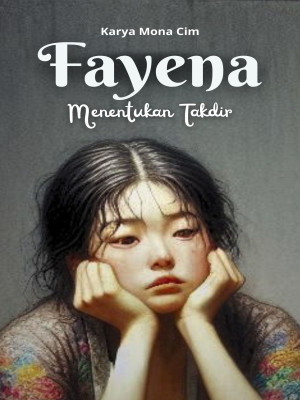






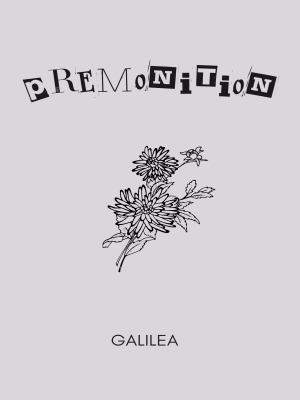

Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .