Malam itu, langit menggantungkan bulan purnama di atas halaman rumah. Tara duduk di bangku kayu, ditemani semilir angin yang membelai rambutnya perlahan. Di sudut halaman, lampu taman temaram menyinari langkah Mamah yang mendekat dengan kehangatan yang khas: kehangatan seorang ibu yang mengerti, meski tak selalu dimengerti.
"Ra," suara Mamah memecah keheningan, lembut tapi mantap, "kamu kan sekarang udah punya gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Apa gak mau gunain uang kamu untuk terapi yang disarankan dokter Arini waktu itu, supaya kecemasan kamu membaik?"
Tara tak langsung menjawab. Hatinya sempat tergetar oleh kalimat itu. Ada sebagian dari dirinya yang bersyukur atas pencapaiannya, tapi ada juga bagian lain yang langsung menghitung: kuliah, kebutuhan sehari-hari, tabungan kecil untuk masa depan. Ia menarik napas pelan, mencoba menyusun jawaban.
"Makin hari makin membaik kok, Mah," ucapnya dengan senyum tipis, "aku bisa atasin ini sendiri."
Mamah memiringkan kepala, masih menatap anak gadisnya yang dulu pernah menangis diam-diam di balik pintu kamar.
"Kamu yakin? Kata kamu, kamu masih sering diserang panik sewaktu-waktu," tanyanya, memastikan.
Tara mengangguk. "Iya Mah, tapi setidaknya aku sudah tahu cara ngatasinnya. Dan itu… tanpa bantuan siapapun."
Mamah menatap Tara beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu tersenyum, "Yasudah deh, Alhamdulillah. Mamah seneng dengernya, kalau kamu bisa sembuh karena diri kamu sendiri."
Tara membalas senyum itu. Senyum yang mengandung banyak rasa: syukur, lega, dan sedikit diam yang tak bisa dijelaskan.
Begitu Mamah beranjak masuk ke dalam rumah, Tara masih tetap duduk di sana. Ia menatap bulan, seakan cahaya pucat itu sedang bicara padanya. Malam begitu tenang, tapi dadanya menyimpan jejak-jejak badai lama yang mulai bisa ia jinakkan.
Anxiety, panik, psikosomatis, semuanya pernah menjadi monster besar dalam hidupnya. Tapi sekarang, mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah bagian dari dirinya. Dan yang paling penting, Tara mulai berani menatap mereka tanpa takut.
Ia meletakkan telapak tangan di dada, merasakan degup yang dulu sering membuatnya panik, tapi kini justru mengingatkannya bahwa ia masih hidup, masih bertahan, masih berjuang.
Ia menutup mata, membiarkan udara malam masuk perlahan ke dalam paru-parunya, dan menghembuskannya pelan.
Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri,
"Anxiety, ayo kita berteman mulai sekarang. Aku janji, gak akan anggap kamu musuh lagi."
Itu bukan kata-kata penyembuhan instan. Tapi itu adalah janji kecil dari seorang perempuan yang sudah cukup kuat untuk bertahan, dan lebih kuat lagi untuk menerima.
***
Malam merayap pelan, membawa keheningan yang pekat ke dalam kamar kecil itu. Hanya terdengar suara napas Sekar yang teratur, lembut seperti nyanyian malam yang menenangkan. Tara duduk bersandar di atas ranjang, cahaya biru yang berkedip samar dari layar laptop menyinari wajahnya yang tampak tenang namun penuh isi.
Di layar, hanya ada satu kalimat:
"Lukisan Tanpa Warna"
dan di sampingnya, sebuah sampul berwarna coklat tua, sederhana tapi menyimpan pesona yang dalam. Tara menatapnya beberapa detik, seperti seseorang menatap pintu yang belum ia buka, namun tahu di baliknya ada semesta yang belum pernah ia jelajahi.
Ia menghela napas, lalu jemarinya mulai menari di atas keyboard. Di pikirannya, imajinasi tumbuh seperti benih yang disiram bulan. Akarnya bercabang ke segala arah. Mencari cahaya, mencari suara, mencari makna.
"Akan kuceritakan sebuah keluarga," bisiknya lirih, "keluarga yang hangat, namun menyimpan rahasia yang bisa membakar ingatan siapa pun yang menyentuhnya."
Lalu ia menambahkan dalam hati,
"Dan akan ada seorang pelukis,yang mencintai warna lebih dari dirinya sendiri, namun pada akhirnya harus melukis dengan kenangan, bukan cat."
Tara tersenyum. Senyum seorang pencipta yang baru saja menemukan celah cahaya dalam kepalanya yang riuh. Ia tahu betul, cerita ini tak akan mudah. Tapi satu hal yang ia yakini:
cerita ini akan berbeda.
Bukan sekadar tentang cinta. Bukan sekadar tentang rahasia. Tapi tentang bagaimana satu garis bisa menyimpan sejarah, dan satu warna yang hilang bisa menyuarakan luka yang tak pernah dikatakan.
Jari-jarinya kembali menari, menuliskan kalimat pertama dan di sanalah malam memeluknya, membiarkan Tara larut dalam dunia yang hanya bisa lahir dari seorang penulis yang pernah hidup dalam sunyi, dan berdamai dengan gelisahnya.
***
Pagi itu, aroma nasi goreng dan teh hangat menyelimuti ruang makan kecil mereka. Suasana akrab mengisi sela-sela keheningan, sampai suara deham Kak Dira memecah segalanya. Seperti pertanda bahwa pagi itu akan berbeda.
Tara sempat mendongak, lalu kembali memandangi piringnya. Tapi telinganya tajam menangkap setiap nada dalam suara sang kakak.
"Aku mau kasih tahu kabar mengejutkan," kata Kak Dira sambil menahan senyum.
Mamah otomatis menghentikan gerakan sendok. "Kabar apa? Penasaran nih?"
Semua mata perlahan menoleh. Bahkan Sekar, yang biasanya paling cuek saat sarapan, kini memperhatikan penuh minat.
"Mah, Yah. Alhamdulillah aku naik jabatan di kantor. Karena kuliahku jurusan akuntansi, aku dipercaya menempati posisi head of finance."
Ayah spontan mengangkat alis, senyumnya merekah. "Wah, hebat banget anak Ayah!"
Pujian itu meluncur hangat, seolah tak perlu dipertanyakan lagi nilainya. Mamah ikut bersinar, bangga bukan main.
"Gimana ceritanya bisa naik jabatan gitu, Kak?"
"Iya, jadi para senior dipindahkan ke cabang. Kita-kita yang junior ini ditunjuk isi posisi kosong. Dan aku salah satunya."
"Wah, keren banget. Gajinya naik pasti itu," Ayah menggoda disusul gelak kecil dari Dira.
"Iya naik kok, alhamdulillah," jawabnya singkat tapi penuh rasa syukur.
Obrolan terus mengalir. Pujian demi pujian seperti aliran sungai yang tak habis-habisnya mengalir ke arah Dira. Tara hanya diam, tapi ia menyimak dengan saksama. Ada senyum di bibirnya, ikut bahagia untuk sang kakak. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang lain. Bukan iri, bukan cemburu. Hanya… keinginan kecil yang ia simpan dalam-dalam.
Ia berharap suatu hari nanti, ketika semua ini telah berjalan cukup jauh, akan ada pagi seperti ini untuknya. Bukan untuk gelar atau jabatan besar. Tapi untuk sesuatu yang ia bangun sendiri, dengan seluruh imajinasi dan air mata yang kadang hanya ditampung kertas kosong.
Tara ingin, suatu hari nanti, Ayah dan Mamah akan memandangi layar ponselnya, membaca namanya di sampul buku, lalu berkata dengan mata berbinar, "Hebat banget anak Mamah dan Ayah."
Dan saat itu tiba, Tara tahu, tak ada yang akan ia syukuri selain kalimat sederhana, barangkali:
"Terima kasih, sudah percaya padaku yang memilih jalan sunyi ini."


 intanaaw
intanaaw



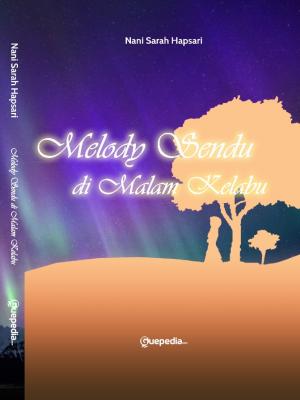









relate banget, gak berlebihan cerita ini (emot nangis)
Comment on chapter PROLOG