Minggu pagi menyapa dengan udara yang jernih dan matahari yang belum terlalu terik. Kota masih setengah terjaga dan jalanan belum ramai, kios-kios belum sepenuhnya buka. Tapi di salah satu sudut kota, langkah kaki Tara terdengar ringan, meski dalam dadanya ada gemuruh yang belum sepenuhnya tenang.
Hari ini adalah hari pertama Tara duduk di bangku kuliah, setelah cukup lama ia melaksanakan ospek, tibalah Tara di hari ini.
Ia mengenakan kemeja coklat sederhana dan celana panjang hitam, ransel kecil tergantung di punggungnya. Rambutnya diikat separuh ke belakang, wajahnya polos dengan riasan tipis-tipis. Ia betulan tampak seperti mahasiswa baru, meski dirinya adalah seorang pekerja untungnya kampus swasta tempatnya kuliah membuka kelas karyawan di akhir pekan, dan hebatnya lagi bisa memilih hari antara Sabtu atau Minggu, dan Tara memilih jadwal Minggu karena baginya itu satu-satunya hari yang bisa ia sisihkan di tengah kesibukannya.
Setibanya di kampus, aroma bangunan tua dan suara burung yang berkicau dari pepohonan halaman menyambutnya seperti sapaan yang tak asing. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara memanggil dari arah samping.
"Taraa!"
Tara menoleh cepat. Senyumnya langsung mengembang saat melihat dua wajah yang familiar, Nisa dan Dita, teman yang ia kenal saat ospek beberapa. Mereka bertiga memang cepat akrab, seperti sudah saling kenal bertahun-tahun.
"Ya ampun, aku deg-degan banget," ucap Dita sambil mengibas-ngibaskan kipas kecilnya. "Tapi pas lihat kalian... aku rada tenang dikit."
"Untungnya kita sekelas ya," tambah Nisa. "Kalau enggak, mungkin aku udah pulang."
Tara tertawa kecil, dadanya terasa lebih hangat. Ada sesuatu tentang kehadiran mereka yang membuatnya merasa tidak sendirian di dunia yang baru ini. Ia menggandeng lengan Nisa, dan mereka bertiga berjalan berdampingan menuju ruang kelas yang sudah ditentukan.
Kelas itu belum ramai, tapi cukup untuk membuat Tara kembali canggung. Ia memilih duduk di dekat jendela, dan Nisa serta Dita otomatis mengisi kursi di sebelahnya. Dosen pun datang tepat waktu dan membuka perkuliahan dengan perkenalan ringan. Tara menyimak, mencatat, kadang tertawa kecil karena bisikan lucu Dita.
Di sela-sela penjelasan dosen, Tara sempat memandangi luar jendela. Pepohonan bergoyang pelan, burung-burung sesekali melintas. Dan di dalam dadanya, tumbuh keyakinan baru—meski ia berada dalam jurusan yang tak ia inginkan, tapi setidaknya ia bisa merasakan hangat di sini. Dan, untuk apapun yang sudah terjadi, Tara pastikan, ia tak akan menyerah di tengah jalan.
***
Setelah kelas pertama usai, Tara, Nisa, dan Dita sepakat untuk mampir sebentar ke sebuah kafe kecil tak jauh dari kampus. Tempatnya sederhana tapi nyaman, dengan hiasan tanaman gantung dan kursi-kursi kayu yang hangat. Mereka memilih duduk di sudut, dekat jendela, dan langsung memesan minuman serta camilan ringan.
"Aku masih kepikiran cogan yang duduk di pojokan tadi deh," celetuk Nisa tiba-tiba sambil tertawa kecil. "Yang pakai kemeja biru itu. Senyum mulu, padahal enggak ada yang diajak ngobrol."
"Eh iya! Yang rambutnya agak ikal itu kan?" timpal Dita cepat. "Sumpah deh, kayak karakter utama di drama Korea."
Tara ikut tertawa, merasa hangat di tengah kehebohan mereka. "Kalian nggak fokus banget sih. Tapi emang sih... ya lumayan ganteng juga," timpalnya, membuat dua temannya berseru girang.
Obrolan mereka berlanjut ke hal-hal lain yang lebih receh, soal nasi uduk kampus yang katanya legendaris tapi belum sempat dicoba, sampai materi dosen tadi yang bikin kepala mutar seperti disetelin kipas angin.
"Baru awal aja udah pusing, gimana semester depan," keluh Tara sambil mengaduk minumannya.
"Makanya, kita harus sering belajar bareng," ujar Nisa dengan nada dramatis. "Atau enggak, kita jadiin alasan buat ngumpul terus."
Tawa mereka menggema lembut di sudut kafe itu.
Tara memandangi mereka berdua, wajahnya sedikit melembut. Dalam hati, ia menarik napas dalam-dalam. Beberapa bulan lalu, ia begitu merasa sendiri. Teman-teman lamanya sibuk dengan dunia masing-masing, dan ia sempat berpikir mungkin dirinya memang terlalu berbeda. Ia sempat belajar menikmati kesendirian, tapi tak bisa memungkiri; ada bagian dalam dirinya yang selalu berharap punya tempat untuk berbagi tawa ringan seperti ini.
Dan hari ini, Tara merasa doanya dijawab. Ia tidak sendiri lagi. Ia punya teman baru yang seru, yang tulus dan apa adanya.
Itu sangat cukup. Lebih dari cukup.
***
Di perjalanan pulang, angkot yang ditumpangi Tara berguncang pelan, membawanya menembus senja kota yang mulai padam. Ia duduk di pojok belakang, menatap kosong ke arah jendela, membiarkan pikirannya mengembara ke mana-mana. Pikirannya tiba-tiba terlempar pada Tomorrow, cerita yang pernah ia tulis beberapa waktu lalu dan sudah lama tamat.
Sudah berhari-hari sejak terakhir ia membuka aplikasinya. Tara buru-buru merogoh ponselnya, membuka aplikasi menulis yang selama ini jadi tempat ia menyimpan dunia-dunia kecil dalam imajinasinya. Notifikasi loading muncul sebentar sebelum akhirnya halaman cerita terbuka.
Jumlah view-nya hanya bertambah sedikit, hanya seribu dalam waktu cukup lama.
Tara terdiam.
Satu sisi dirinya merasa lelah. Ia melihat penulis lain di aplikasi yang sama bisa dengan cepat melambung—judul-judul cerita mereka viral, komentar ribuan, bahkan dibicarakan di media sosial. Sementara Tomorrow hanya melangkah pelan di tengah keramaian itu. Ia sempat bertanya dalam diam, "Apa ceritaku tidak cukup bagus?"
Pikirannya mulai dipenuhi keraguan dan rasa kecil hati. Ia tahu tak seharusnya membandingkan, tapi tetap saja, rasa itu menelusup perlahan, diam-diam.
Saat itu, angkot yang ditumpanginya berhenti dan seorang anak kecil masuk, membawa gitar mini dan sebuah gelas plastik bening. Tanpa banyak kata, anak itu mulai bernyanyi. Suaranya serak, napasnya pendek-pendek, tapi matanya bersinar, seolah setiap lirik yang ia nyanyikan adalah harapan yang dipaksakan untuk tetap menyala.
Tara terdiam, memperhatikan anak itu.
Ia merogoh uang dua ribu rupiah dari dompet kecilnya dan menyelipkannya ke dalam gelas plastik yang digenggam anak itu. Anak kecil itu tersenyum lebar dan mengucap terima kasih sebelum melanjutkan lagu berikutnya.
Tara mengalihkan pandangannya kembali ke luar jendela.
Perlahan, pikirannya tentang jumlah pembaca cerita tadi memudar. Ia merasa malu sendiri. Anak kecil itu tetap bernyanyi meski tak tahu akan dapat berapa rupiah hari itu. Ia tetap memberi suara untuk dunia, meski dunia belum tentu menyadarinya. Lalu, kenapa ia harus ragu hanya karena angka?
Tara menyandarkan kepalanya ke kaca jendela.
"Aku tidak akan berhenti menulis," bisiknya lirih. "Karena dengan menulis, aku bisa lebih mengenal diriku sendiri."
Angin sore masuk dari celah jendela yang terbuka. Tara membiarkannya menerpa wajahnya, sambil perlahan-lahan membayangkan cerita baru yang ingin ia tulis. Ia merenung, memutar-mutar bayangan dalam kepalanya. Kali ini, ia ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya cerita cinta atau drama kehidupan biasa. Ia ingin membuat cerita yang bisa menyentuh batin pembacanya, yang bisa mengguncang dunia dengan keheningan.
Lalu, ia bertanya pada dirinya sendiri dalam hati.
"Apa yang aku suka?"
Ia menjawab, "Aku suka menggambar. Aku suka menulis."
Dan sekali lagi ia bertanya, "Apa yang suka aku ciptakan dalam lukisan?"
Jawaban itu datang dengan jernih, sederhana.
"Sebuah sketsa hitam putih... tanpa warna."
Tara tersenyum. Tangannya refleks membuka aplikasi catatan di ponselnya, lalu menulis satu kalimat di sana:
Lukisan Tanpa Warna.
Judul itu terpatri kuat di benaknya. Ia tahu, cerita itu akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Cerita tentang luka, harapan, dan seni. Cerita tentang dirinya.
Dan perjalanan lain baru saja dimulai.


 intanaaw
intanaaw








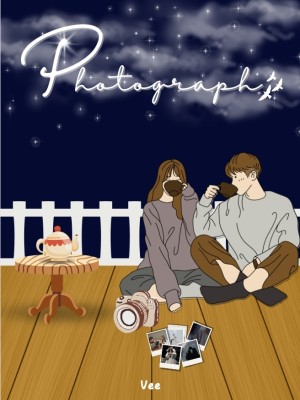







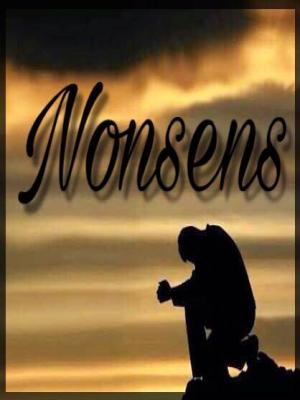
real anak tengah sering terabaikan tanpa ortunya sadarii
Comment on chapter Bagian 4: Sebuah Kabar Baik