Pagi belum sepenuhnya cerah ketika Dira merapikan rambutnya di depan cermin. Raut wajahnya terlihat lelah, tapi ia tetap memaksakan senyum tipis seperti biasa. Seragam kerjanya sudah rapi, tas kerja di bahunya, dan roti tawar dalam genggamannya nyaris tak disentuh. Ia harus bergegas sebab kereta tak pernah menunggu.
Di ruang tamu, Mamah sudah duduk menunggunya. Ada gelisah di mata perempuan itu, dan Dira bisa menangkapnya hanya dalam satu pandang.
"Dira, bentar," panggil Mamah sebelum anak sulungnya itu sempat menyentuh gagang pintu.
Dira menoleh. "Kenapa, Mah?"
Mamah menarik napas pelan, lalu berkata, "Mamah pengin bawa Tara ke psikolog. Sejak kejadian kemarin itu, Mamah ngerasa anak itu kayak meledak. Sekarang dia jadi banyak takutnya. Tidur aja gelisah terus. Bisa, enggak, Mamah pinjam dulu uang dari kamu?"
Dira diam. Matanya menatap lantai sejenak, seakan mencoba menyusun kalimat. Dalam benaknya, ia langsung menghitung pengeluaran bulan ini, biaya sehari-hari, cicilan kecil yang masih berjalan, dan rencana-rencana kecil yang sempat ia susun diam-diam.
"Iya, Mah... aku usahain ada, ya," jawabnya akhirnya, pelan. Dan senyum Mamah, walau tipis, seperti menambahkan beban baru ke pundaknya.
***
Di kantor, Dira duduk di hadapan layar komputer yang penuh angka dan tabel. Beberapa berkas menumpuk di sisi mejanya. Rekan-rekan kerjanya tertawa di meja sebelah, sibuk merencanakan liburan ke pulau akhir bulan ini. Suara obrolan itu masuk ke telinganya seperti alunan lagu yang asing.
"Dir, ikut dong! Ayo lah, kita butuh yang rame juga," ajak salah satu temannya dengan penuh semangat.
Dira tersenyum, menahan keinginan untuk berkata ‘iya’. Ia ingin sekali rasanya berlibur, menghela napas jauh dari rutinitas. Tapi kepalanya kembali memutar ulang suara Mamah pagi tadi. Tentang Tara. Tentang ketakutan adiknya. Tentang uang yang seharusnya bisa untuk dirinya sendiri, tapi kini harus dialihkan.
"Kayaknya... enggak dulu, deh," ucapnya, pelan. "Lagi banyak keperluan keluarga."
***
Langit kelihatan menguning ketika Dira berjalan cepat di area stasiun untuk mengejar jadwal berangkatnya kereta. Keadaan sore itu penuh sesak. Dira berdiri di dekat pintu, berpegangan erat pada tiang. Tubuhnya terdorong ke depan saat penumpang lain berdesakan. Seseorang hampir menimpa bahunya, dan Dira terhuyung.
Sekuat mungkin ia menahan tubuhnya agar tidak jatuh.
Di titik itu, semua rasa capek seperti memuncak. Ia ingin sekali duduk dan menangis. Tapi matanya tetap menatap jendela yang kabur karena embun dan debu. Ia menarik napas dalam-dalam, seperti menelan semuanya dalam diam.
Ia anak sulung. Yang harus kuat. Yang harus mengerti. Yang harus ada kalau keluarga butuh. Yang harus bisa, bahkan saat dirinya sendiri belum tentu baik-baik saja.
Begitu sampai di rumah, malam sudah turun. Dira membuka pintu pelan. Dari luar sebuah kamar, ia melihat Mamah sedang menyelimuti Tara yang masih tertidur. Dua potong kue tersisa di atas meja. Dan meski lelah, Dira tetap tersenyum tipis. Ada cinta di rumah ini, dan meski kadang melelahkan, itulah alasan mengapa ia terus bertahan.
"Mah," panggilnya pelan.
Suara Dira membuat keduanya kini berada di ruang tengah duduk di depan televisi yang menyala tanpa ada yang menonton. Dira mengeluarkan amplop putih dari tasnya, dan dengan gerak lembut memberikan itu untuk Mamah.
"Buat berobatnya Tara."
Mata mamah kelihatan berbinar tapi menggenang air dalam pelupuknya, ia seperti menahan tangis karena merasa tidak enak selalu merepotkan anak pertamanya itu. Mamah mengambil amplop dari tangan Dira pelan, ia menggenggam lengan si sulung yang dingin akibat menerobos malam hanya untuk sampai ke rumah.
"Terimakasih ya, semoga rezeki kamu lancar selalu."
Dira mengangguk, dengan suara pelan ia mengaminkan doa dan harapan Mamahnya.
***
11 Juli 2022
Hari itu, Tara memutuskan untuk izin tidak masuk kerja. Ia mengirim pesan singkat pada atasannya pagi tadi, menyebutkan bahwa ia sedang tidak sehat. Tapi sebenarnya, yang ia maksud bukanlah sakit demam atau flu, melainkan sesuatu yang tak kasat mata-yang selama ini tak bisa ia jelaskan dengan benar.
Dengan rujukan dari BPJS dan tambahan biaya seadanya, akhirnya Tara bisa datang ke klinik psikolog yang cukup tenang dan sederhana bersama mamahnya. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan saling menggenggam erat di pangkuan. Mamah duduk di sebelahnya, tak banyak bicara, hanya sesekali menatap anak gadisnya dengan sorot cemas.
Suara panggilan dari pengeras suara memecah keheningan siang itu.
"Tara Aksara... silakan masuk ke ruang dua, ya."
Mamah menepuk lembut tangan Tara. "Udah, enggak apa-apa. Ceritain aja semuanya, ya?"
Tara mengangguk kecil, lalu berdiri. Langkahnya pelan dan sedikit ragu saat menuju ke pintu bertuliskan: Ruang Konsultasi 2 - dr. Arini M.Psi.
Begitu pintu terbuka, seorang perempuan dengan senyum ramah menyambutnya. Wajahnya hangat, dan tatapan matanya menyiratkan bahwa ruang ini aman-bahwa di sini, Tara boleh menjadi rapuh.
"Silakan duduk," ujar Dokter Arini, menunjuk ke sofa kecil di hadapannya.
Tara duduk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang terasa tak beraturan.
"Namamu Tara, ya? Gimana kabarnya hari ini?"
"Agak pusing," jawab Tara jujur. "Tapi... lebih baik setelah tadi pagi tidur sebentar."
Dokter Arini mengangguk sambil mencatat.
"Ada hal yang ingin kamu ceritakan hari ini?" tanyanya lembut.
Tara diam sejenak, seperti menimbang. Tapi kemudian, ia menghela napas dan mulai berbicara-pelan, tapi mengalir seperti sungai yang sudah lama tersumbat.
"Aku enggak tahu mulai dari mana... Tapi aku capek, Dok. Aku sering ngerasa takut sendiri, takut ditinggal, takut enggak cukup baik. ini gila, tapi aku juga suka takut sama hal-hal yang belum terjadi. Kadang... aku sendiri juga enggak ngerti kenapa bisa sesesak ini."
Ia berhenti sebentar, menahan napas yang mulai tercekat. Tapi Dokter Arini tetap diam, memberi ruang.
"Sejak kejadian kemarin, aku kena panic attack. Dan sejak itu... semuanya terasa berubah. Dadaku sering sakit, kaya ditimpa batu. Napasku kayak selalu berat, susah masuk. Perutku mual terus, leherku kaku, kepalaku juga suka berat tiba-tiba. Tubuhku... ngerasa lemas terus. Tapi setiap periksa ke dokter umum, katanya aku sehat."
Suaranya mulai serak. Tapi ia tak menangis. Hanya mengembuskan semua itu seolah baru kali ini ia berani mengakuinya.
Dokter Arini meletakkan pulpennya dan menatap Tara dengan penuh empati.
"Apa yang kamu alami itu nyata, Tara," katanya pelan. "Rasa sakit di tubuh kamu, sesak di dada kamu, leher yang kaku, kepala yang berat-semua itu memang terasa menyakitkan. Tapi sumbernya bukan dari tubuhmu. Itu bukan penyakit fisik."
Tara mengerutkan dahi, menatapnya bingung. "Bukan penyakit... fisik?"
"Bukan," Dokter Arini mengangguk. "Itu yang disebut psikosomatis. Gejala fisik yang muncul akibat tekanan emosional dan stres yang berkepanjangan. Jadi, tubuhmu bereaksi atas beban yang terlalu lama kamu pikul sendiri."
Tara menunduk. Tiba-tiba saja, semua rasa itu seperti menemukan rumahnya. Ia tidak gila. Ia tidak lebay. Ia hanya... terluka dan terlalu lama diam.
"Artinya... aku masih bisa sembuh, Dok?"
"Bisa, tentu bisa. Tapi kamu perlu waktu. Dan kamu tidak perlu menjalaninya sendirian. Kita akan pelan-pelan cari cara untuk membuat kamu merasa lebih ringan. Mulai dari mengenali emosi kamu, mengatur napas, sampai nanti mungkin terapi rutin. Yang penting sekarang, kamu sudah datang ke sini. Itu langkah besar, Tara."
Untuk pertama kalinya hari itu, Tara mengangguk pelan. Di dalam ruang kecil bernama konsultasi itu, ia merasa tidak lagi sendirian.
***
Sesi konsultasi Tara pun selesai setelah hampir satu jam. Ia keluar dari ruang konsultasi dengan wajah sedikit lebih tenang. Mamah yang sejak tadi menunggu di luar langsung berdiri dan menyambut Tara dengan senyum tipis.
"Gimana?" tanya mamah pelan, mengusap punggung Tara.
"Lumayan lega, Mah..." bisik Tara. "Aku tunggu di luar ya," lanjutnya sambil duduk kembali di bangku tunggu.
Dokter Arini kemudian memanggil mamah untuk berbicara empat mata. Di dalam ruang konsultasi, suasananya tetap tenang. Dokter Arini mempersilakan mamah duduk, lalu membuka pembicaraan dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan profesional.
"Bu, saya sudah mendengarkan cukup banyak dari Tara hari ini. Dan dari gejala yang ia ceritakan, juga dari cara ia merespons, saya bisa menyimpulkan bahwa Tara mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder."
Mamah terdiam. Matanya memantulkan cemas yang berbeda-sebuah kecemasan seorang ibu yang baru menyadari luka anaknya tak hanya fisik.
"Gangguan kecemasan itu apa ya, Dok?"
"Anxiety disorder itu gangguan mental yang ditandai dengan rasa cemas atau khawatir berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya kecil atau tidak nyata ancamannya. Dan kecemasan itu bukan sekadar pikiran, tapi sudah berdampak ke fisik Tara-seperti yang tadi ia jelaskan: sesak napas, mual, tubuh lemas, nyeri dada, sampai kelelahan mental yang membuatnya merasa tak sanggup menjalani hari."
Mamah mengangguk pelan, menyimak.
"Biasanya gangguan ini berkembang karena banyak faktor, Bu. Bisa karena tekanan hidup, pola asuh, pengalaman traumatis, bahkan kecenderungan genetik. Tapi yang jelas, kondisi ini nyata. Dan butuh penanganan yang serius, bukan hanya dikuat-kuatin atau diabaikan."
Dokter Arini melanjutkan dengan penuh perhatian, "Saya menyarankan Tara untuk menjalani terapi secara rutin. Nanti akan ada sesi lanjutan, mungkin juga dilengkapi dengan terapi perilaku kognitif, dan kalau dibutuhkan, kombinasi dengan pengobatan. Tujuannya supaya Tara bisa mengenali dan mengelola kecemasannya secara bertahap."
Mamah terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Tapi... apa anxiety enggak bisa sembuh sendiri ya, Dok? Maksud saya, mungkin... kalau didiamkan, nanti juga reda sendiri?"
Dokter Arini menatap mamah dengan tatapan hangat namun tegas.
"Saya paham kekhawatiran Ibu. Banyak orang juga berpikir begitu. Tapi sayangnya, anxiety disorder itu tidak seperti demam yang bisa reda sendiri dalam beberapa hari. Ini seperti luka yang tak kelihatan-kalau dibiarkan, bisa semakin dalam. Bisa mengganggu hubungan sosial, pekerjaan, bahkan membuat penderita merasa tak berharga dan putus asa."
Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Memang, kadang ada fase di mana gejalanya hilang sementara. Tapi tanpa penanganan, kecemasan itu bisa datang kembali dengan intensitas lebih besar. Itu sebabnya penting untuk mengajarkan Tara cara mengelola pikirannya, emosinya, dan tubuhnya-bukan hanya berharap semua membaik dengan sendirinya."
Mamah menunduk.
"Terima kasih ya, Dok. Saya jadi ngerti sekarang. Saya bakal usahain bawa Tara rutin ke sini... semampu saya."
Dokter Arini tersenyum tulus. "Itu keputusan terbaik, Bu. Tara butuh dukungan, dan dia beruntung punya Ibu yang peduli seperti ini."
Mamah mengangguk lagi. Tapi, pikirannya terbang; keluarganya tak sekaya itu untuk membawa Tara rutin berobat ke psikolog bahkan untuk melakukan terapi yang di sarankan. Mamah melihat Tara dengan senyum lebarnya ketika keluar dari ruangan konsultasi, hatinya berharap semoga anak itu bisa sembuh sendiri dan dengan bantuan keluarganya tanpa harus sering-sering ke psikolog.


 intanaaw
intanaaw









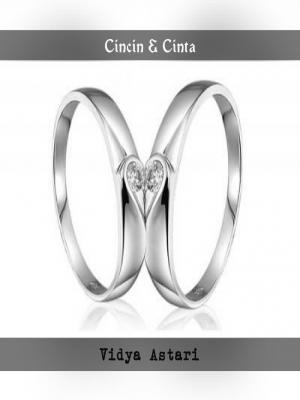



relate banget, gak berlebihan cerita ini (emot nangis)
Comment on chapter PROLOG