Di depan gerbang sekolah, Aditya dan Vania berdiri bersebelahan. Masing-masing terlena dengan pikiran-pikiran yang berkalut. Sementara matahari terbenam menyemburkan gurat oranye di langit biru. Pak Eko pun terlihat asik mengambil gambar langit menggunakan HP jadul miliknya dibandingkan memerhatikan Aditya dan Vania.
Tanpa Vania ketahui, Aditya sudah mencuri-curi pandangan kepada Vania semenjak mereka keluar dari ruangan Pak Tirto. Dia sudah membuat beberapa versi kalimat di kepalanya tetapi lidahnya menjadi kaku setiap dia ingin mengutarakan sesuatu. Aditya terus memikirkan bagaimana Vania juga mengalami hal yang tidak adil oleh para orang tua murid hanya karena mereka memiliki nilai yang lebih tinggi; bagaimana usaha keras mereka disepelekan oleh orang lain dengan kalimat 'kalian terlahir jenius' dan karakter mereka difitnah bila mereka tidak mau mengajari anak lain. Mempertahankan nilai itu tidak mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan; waktu, tenaga, juga kesehatan, serta pertemanan, bahkan keluarga. Jadi mengapa orang tua anak-anak itu dengan mudahnya menuntut Aditya dan Vania untuk 'berbagi pengetahuan' secara sukarela yang pastinya akan memakan waktu dan tenaga mereka? Waktu dan tenaga yang bisa mereka fokuskan untuk kesehatan atau keluarga mereka. Mengapa juga orang tua anak-anak itu menuntut seakan sudah selayaknya Aditya dan Vania mau memberikan contekan pada anak-anak itu?
Sejujurnya, Aditya tidak habis pikir mengapa selama ini dia mengiyakan tuntutan-tuntutan tidak adil tersebut, bahkan hingga pernah demam tipes karena hampir setiap hari pulang malam mengajari 'teman-temannya' itu. Sementara gadis yang hanya setinggi mulutnya ini berani menolak permintaan tidak masuk akal itu dari awal dan menjaga kemurnian integritasnya. Aditya ingin Vania tahu bahwa ia mengalami hal yang sama, bahwa Vania tidak sendirian mendapatkan tuntutan tidak adil dari orang-orang dewasa yang tidak punya waktu mengawasi anak-anak mereka sendiri. Dia juga ingin Vania tahu bahwa mulai sekarang dia akan memberanikan diri menolak tuntutan-tuntutan yang tidak menguntungkannya, terutama tuntutan membantu memberikan contekan.
Begitu menyadari mereka akan berpisah sebentar lagi menuju rumah masing-masing, ia akhirnya memaksakan diri untuk membuka mulut dan bersuara-
Sayangnya, Vania lebih berkata, "Ini semua gara-gara lo!" Gadis itu menatap tajam pada Aditya. Kedua tangan mungil dikepalkan begitu kuat di samping tubuh rampingnya. "Kenapa sih nilai lo harus sama dengan gue? Lo nyontek gue ya?"
Hilang sudah rasa empatinya dengan Vania, terbakar dengan ego Aditya yang tersulut. "Enak aja!" serunya dengan nada lebih tinggi dari yang ia kira. Vania pun tersentak dengan bentakan itu.
"Gue akui gue sering kasih contekan ke anak-anak tapi jawaban gue selalu milik gue sendiri, dari otak gue," Aditya menunjuk pelipisnya, di mana urat dahinya begitu menonjol karena emosi. Lo kali yang diam-diam ngikutin jawaban di contekan gue."
Mata Vania membelalak. Belum pernah ada seorang pun yang menuduhnya menyontek. Vania terkenal sebagai pribadi yang kaku dan bahkan sedikit anti-sosial -meski Vania tahu itu adalah sebuah misnomer, karena tidak pernah sudi memberikan contekan. Tuduhan Aditya ini seakan menuangkan oil ke percikan api dalam dirinya.
"Gila ya lo! Gimana caranya gue nyontek lo ketika lo di kelas yang berbeda. Gue IPA, lo IPS!" seru Vania. Tanpa ia sadari, dirinya sudah berjinjit hingga matanya selevel dengan Aditya.
"Nah, tuh lo tahu!" balas Aditya, "Gimana caranya gue nyontek lo juga?"
"Argh!" Vania menarik rambut di pelipisnya, menyebabkan ikatan rambutnya lepas. Helaian rambut yang seperti sutra jatuh pada pundaknya yang bergetar. "Gue harus mendapatkan beasiswa ini, Aditya."
"Dan menurut lo gue engga?" lanjut Aditya, "Udahlah, Cess. Ga usah berlomba siapa yang paling butuh beasiswa ini. Lo sendiri tahu jawabannya siapa."
"Apa maksud lo?"
Merasakan tatapan panas dari Vania membuat Aditya yang biasanya cukup kalem menjadi jengkel. Entah mengapa perempuan di sampingnya ini selalu dapat mengusik ketenangan mentalnya dan menggores egonya.
“Lo kan Princess yang bisa minta tolong kapanpun ke bokap lo yang motivational speaker kaya itu –yang sampai masuk majalah sebagai tokoh inspirasi Jakarta,” Aditya tidak berhenti meski menyadari kedua mata Vania berlinang, “jadi pasti lo mau beasiswa bukan karena butuh duit tapi karena butuh rekognisi. Lo selalu butuh validasi. Lo butuh orang muji lo kalau lo yang paling pintar, paling berprestasi."
Aditya mengira Vania akan membuat argumen bahwa beasiswa yang mereka incar ini tidak hanya untuk yang kurang mampu, tetapi sejatinya untuk yang berprestasi. Alasan yang lemah, pikir Aditya. Bagi pemuda satu ini, dirinya termasuk tidak mampu dan berprestasi, maka beasiswa itu lebih pantas diberikan padanya.
"Sedangkan gue," lanjut Aditya ketika Vania masih bergeming, "Gue udah ga punya bokap yang bisa bantu biaya kuliah. Jadi selama lo masih punya bokap kaya kenapa lo bersikeras mau dapat beasiswa?"
"Oh, pantas lo ga punya bokap," kata Vania dengan nada pelan tetapi tajam, "Dari cara lo ngomong aja udah ketahuan."
"Apa lo bilang?" Panas api kemarahan sudah meraih ubun-ubun Aditya. Jarang sekali orang bisa membuatnya gusar, tetapi Vania selalu menjadi juara dalam menyulut kejengkelan Aditya.
Perempuan itu menggelengkan kepalanya kecil, seakan menghalau air mata dari terjatuh, kemudian menghela napas kasar. "Gini deh, gue tahu lo benci gue," katanya.
Aditya hanya terdiam. Panas api yang tadi seakan mencapai ujung kepalanya menjadi reda seperti telah disiram air dingin.
"Gue tahu lo pikir gue ga pantas dapat beasiswa ini," Vania mengambil napas tercekat seperti sedang menahan tangisan di tenggorokkan, "tapi gue ga akan menyerah berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi take it or leave it. Antara kita kerja sama besok nangkap bukti Bari melakukan tawuran dan membuat Pak Tirto mengubah syarat beasiswa, atau gue akan berusaha sendiri sampai gue dapat beasiswa itu."
Aditya tahu perempuan itu berusaha keras membuat suaranya datar. Memang kalimat yang ia lontarkan meenggambarkan ketenangan yang logis. Namun Aditya juga menangkap getaran-getaran kecil di suara saingannya ini, membuat Aditya merasa sedikit bersalah. Apakah aku sudah mengatakan sesuatu yang keterlaluan? batinnya.
Namun, lagi-lagi ego membuatnya berkata dengan nada ketus, "Oke. Besok sehabis istirahat kita ikutin Bari dan dapatin bukti itu."
"Oke," balas Vania. Kali ini nadanya lebih tinggi, tidak lagi bergetar. Seakan nada Aditya sebelumnya telah menyulut ego Vania pula.
"Oke!" seru Aditya kembali, "kita akan bolos setengah hari besok. Lo siap ga? Lo kan ga pernah bolos sekolah, Cess."
"Oke! Siapa takut?" sahut Vania, "Lo juga ga pernah bolos sekolah. Ga usah sok keren!"
"Besok mungkin akan bahaya lho, bokap-nyokap bakal khawatir ga? Karena kalo ada apa-apa gue sih bakal nyelamatin diri gue sendiri, ga bisa jadi ksatria kuda putih Princess."
"Gue ga akan bilang. Emang lo bakal bilang? Dan gue ga butuh cowo buat nyelamatin gue!"
"Engga, gue juga ga akan bilang tuh!" seru Aditya. Entah sejak kapan, kedua batang hidung mereka hanya tinggal beberapa ruas jari saja. Bahkan Vania dapat merasakan embusan napas panas yang keluar dari mulut Aditya. Mereka saling menahan tatapan penuh tekad satu sama lain, sebuah peperangan kasat mata. Kemudian di saat yang bersamaan, mereka membuang muka dan mulai berjalan menuju dua arah yang berbeda. Masing-masing dengan berbagai perasaan kalut bergerumuh di dada. Satu hal yang pasti, api di dalam diri mereka masing-masing berkobar lebih terang dari sebelumnya.
"Aku akan dapat beasiswa itu," kata Vania penuh tekad pada dirinya sendiri.
Di saat yang sama, Aditya tenggelam dalam pemikirannya. Dia mengingat Vania berkata, 'gue tahu lo benci gue.'
Lo benci gue, katanya.
Aditya sadar bahwa Vania tidak pernah sekalipun bilang, 'gue benci lo,' dan itu membuat perbedaan yang cukup berarti bagi Aditya.
"Gue ga benci lo, Van," bisik Aditya pada dirinya sendiri.
***
Di kejauhan, tepatnya di lapangan parkir sekolah yang terletak di belakang posko satpam, Pak Eko menghampiri sebuah mobil Toyota berwarna abu-abu. Di kursi pengemudi, Pak Tirto duduk memperhatikan kaca spion yang memperlihatkan bayangan Aditya dan Vania.
"Pak, dikau apakan kedua anak baik-baik itu hingga berantem seperti ini?" tanya Pak Eko dengan khawatir.
Pak Tirto hanya tersenyum tipis kemudian berkata, "Aku sedang memberi mereka pelajaran, Ko."
"Pelajaran hidup."


 penulisabal
penulisabal





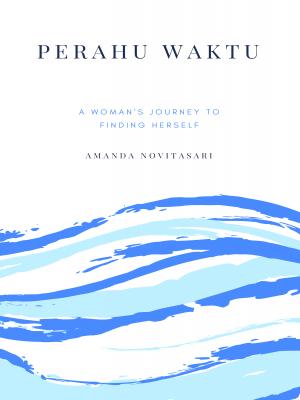

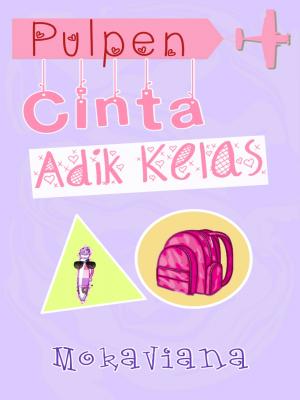


Persaingan ketat, Nih. semangat nulisnya Kakak
Comment on chapter Bab 1 : Peringkat Satu Itu Milikku