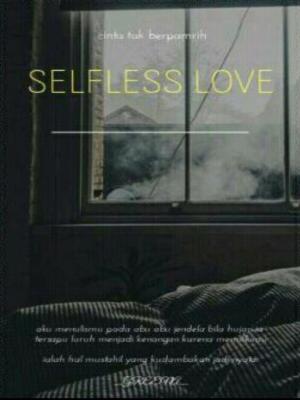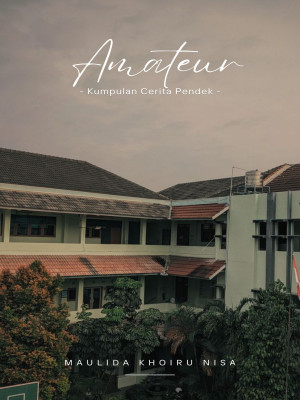We were strangers in the storm
Both lost, both cold, but kinda warm
I was over it, you were throwing shade
But the sky low-key said, “this ain’t over, babe”
“Lowkey Destiny” – The Lost Seventeen
***
Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Sebastian sebelum menerima tawaran LOCO Entertainment sebagai vokalis baru The Lost Seventeen: dia adalah salah satu Youth yang pernah bermimpi bisa satu panggung bersama mereka, dan dia tidak harus memulai semuanya seorang diri—berbeda jika menjadi solois. Debut dalam band yang sudah ‘eksis’ tentu bukan pilihan buruk dan terlihat lebih mudah. Lagi pula, bukannya ini namanya ‘sambil menyelam minum air’?
Atau dia salah?
Sepulang sekolah, sesuai kesepakatan dengan Tio, Dewa, dan Lea—manajer The Lost Seventeen, Sebastian datang ke ‘markas’ atau ruang latihan The Lost Seventeen yang letaknya di belakang gedung agensi. Awalnya dia pikir tempat ini semacam rumah kosong terbengkalai yang disulap menjadi ruang latihan yang aksesibel dan estetik. Nyatanya, tempat ini lebih cocok dijuluki ‘gudang bekas yang mungkin saja dipakai latihan bocah-bocah gabut’. Seketika imaji Sebastian pada band yang dia idolakan sedikit berantakan.
Dia lantas memasuki ruangan yang tak begitu besar dan cukup suram itu. Dindingnya dilapisi panel kedap suara yang beberapa sisinya tampak menguning. Di sudut kiri—dekat pintu masuk—terdapat sofa lusuh berlubang yang dipenuhi coretan spidol berisi tanda tangan dan keluhan-keluhan ‘gaje’ para member, lalu di sekitarnya ditempeli stiker-stiker band, seperti The Beatles, Nirvana, The Rolling Stones, Queen, AC/DC, dan masih banyak lagi. Raut muka Sebastian yang semula menekuk sontak semringah saat mengabsen printilan ruang latihan itu satu per satu.
“Halo? Ada orang, nggak?”
Sebastian masih mencoba memanggil penghuni lain ruangan ini, tetapi nihil. Sepertinya memang hanya dia yang mendengar suaranya sendiri. Apa mungkin sejak meninggalnya vokalis terdahulu, mereka belum pernah kemari lagi? Lelaki yang masih mengenakan seragam putih abu-abu itu tak dapat menahan rasa penasarannya.
Bagaimana dia tidak curiga? Kabel-kabel yang dibiarkan berserakan di lantai saja sangat tak terurus. Kemungkinan kabel itu digunakan untuk menghubungkan amplifier ke gitar, drum elektrik, dan mixer kecil yang kelihatannya nyaris overload. Tak heran saat pertama kali masuk, Sebastian merasa udara di dalam sini agak pengap, seperti ada campuran bau gosong dan keringat. Namun, anehnya, baginya justru begitu nostalgic dan menyenangkan.
Tak berselang lama, terdengar suara pintu berderit—klasik. Seseorang yang Sebastian tahu bernama Tio, leader dari The Lost Seventeen, baru saja tiba dan melempar ranselnya ke sembarang arah. Tanpa ragu juga dia melangkah mendekati Sebastian yang tak berkutik saat melihat bias-nya ada di depan mata, lagi.
“Lo udah lama di sini?”
Sebastian mengangguk kecil. “Lumayan. S-sori, gue langsung masuk gitu aja. Soalnya tadi nggak dikunci, terus—”
“Iya, nggak apa-apa, kok,” potong Tio sambil menyalakan lampu. “Duduk dulu.”
“Makasih, Bang.”
“Kan kemarin gue udah bilang, panggil ‘Tio’ aja. Lagian kita cuma selisih beberapa bulan.”
“O-oke, deh, Tio.”
Sebastian lekas duduk di kursi kecil yang Tio berikan. Dia refleks menatap lampu neon di langit-langit yang sesekali berkedip. Mungkin dia lelah, monolognya lirih. Kalau dipikir-pikir, kesan dia atas betapa ‘buruk’nya tempat ini—untuk ukuran ruang latihan band superterkenal—justru seakan menjadi saksi dari setiap progres yang telah dilewati personil The Lost Seventeen. Bahkan, selain di sofa, banyak coretan (seperti) lirik lagu yang dibiarkan mengotori lantai dan dinding begitu saja. Membekas dengan cara yang indah dan berharga, kan?
“By the way, lo udah siap?” tanya Tio datar tanpa melihat Sebastian. Sedari tadi dia masih sibuk mengecek peralatan dan kabel.
“Seratus persen siap.”
“Oke. Pertahankan kepercayaan diri lo itu di depan anak-anak lain nanti.”
Sebastian tidak sepenuhnya mengerti maksud dari kalimat itu, tetapi dia tetap mengangguk. Dia bukannya tidak tahu-menahu dengan rumor yang beredar, tetapi Tio yang dia ‘kenal’ memang ketus dan dingin seperti ini. Dia adalah sosok leader yang di mata Youth sekalipun terlihat tegas dan susah dijangkau. Jadi, alih-alih berprasangka buruk, Sebastian hanya tersenyum tipis dan menguatkan genggamannya, memberi kekuatan pada diri sendiri.
Pada pertemuan sebelumnya, dia tidak keberatan jika The Lost Seventeen ingin menguji coba dirinya terlebih dulu. Sebastian yakin dengan kemampuannya dan dia percaya bisa bertahan berdiri bersama idolanya itu. Terlebih, kalaupun skenario terburuk terjadi, pihak agensi bersedia memberi kompensasi dan jaminan kariernya. Jadi, tidak ada salahnya mencoba, kan?
Dan hari ini, Tio ingin Sebastian unjuk kebolehannya di depan personil lain. Tujuan utamanya ada dua: melihat apakah dia bisa membawakan lagu The Lost Seventeen layaknya mendiang Ryan—minimal mendekati sempurna atau sekitar 90 persen mirip—dan melihat apakah dia memiliki aura panggung yang cocok dengan image The Lost Seventeen—bakal lebih bagus lagi jika dia juga punya chemistry dengan Malik, gitaris yang kerap berdiri di samping vokalis. Kalau berhasil mendapat lampu hijau, Sebastian akan sah dinyatakan bergabung dalam band. Namun, kalau tidak, tidak ada masa depan apa pun di antara mereka.
Sebastian tentu tidak keberatan dengan hal itu. Hitung-hitung pemanasan. Lagi pula, menyanyi sudah menjadi bagian dalam hidupnya selama belasan tahun. Tidak ada keraguan dalam dirinya, terlebih ini membawakan lagu-lagu yang hampir dia dengarkan setiap hari.
Satu-satunya yang membuat Sebastian gugup adalah respons untuknya nanti.
Sambil menunggu personil lain datang, Tio tampak menyetel gitar dan bass—tuning—pada aplikasi tuner di ponselnya agar nadanya pas. Dia juga men-setting volume pada ampli dan melakukan sound check agar semua instrumen terdengar seimbang saat dimainkan bersama. Melihat itu, Sebastian refleks menggaruk tengkuk. Meski dalam skala latihan kecil hal-hal semacam ini biasa terlihat, dia berpikir sekelas LOCO Entertainment setidaknya memiliki teknisi atau operator yang membantu proses tersebut.
“Em, mau gue bantuin nggak, Yo?” tanyanya memecah hening. Rasanya agak canggung kalau tetap diam saja ketika orang lain kesusahan.
“Boleh. Lo bisa cek mic-nya.”
“Oke!”
Sebastian lekas mendekati satu-satunya mic stand di tempat ini. Lagi-lagi dia menemukan stiker yang ditempel di mana-mana, bedanya kali ini dia hanya melihat stiker “Fish out of Water”—album pertama The Lost Seventeen—dan stiker karakter chibi kelima personil, lengkap dengan instrumen yang mereka mainkan: Tio-drum, Bagas-bas, Malik-gitar, Awan-keyboard, dan Ryan-mikrofon. Love languange mereka pakai barang-barang kayak gini kali ya, pikir Sebastian.
“Cek, cek. Gimana, udah aman, Yo?”
Tio manggut-manggut. “Coba cek vokal lo sekalian.”
“Boleh, mau lagu apa?”
“Terserah, yang paling lo kuasai aja.”
Sebastian pun tersenyum. “Kalau gitu, ‘Lowkey Destiny’, gimana?”
“Lo yakin?”
Bukan Tio, melainkan Malik-lah yang bersuara. Lelaki berambut ikal yang selalu memakai topi entah di dalam maupun luar ruangan itu baru saja masuk. Dia langsung duduk di sofa lusuh tadi lalu menyilangkan kaki. Di tangannya ada kopi kemasan yang esnya sudah mencair, menyisakan sisa-sisa embun di luar cup. Tak berselang lama, dua member lainnya—Bagas dan Awan—menyusul tanpa basa-basi.
Dilihat dari seragam ketiganya—empat dengan Tio, mereka bersekolah di SMA yang sama, SMA Pahlawan. Setahu Sebastian, dia dan mereka juga seumuran—sama-sama kelas dua belas. Namun, dia tidak tahu pasti alasan Tio bisa sampai lebih dulu ke sini atau alasan mereka datang terlambat, yang jelas sekarang dia mesti menyiapkan diri untuk diaudisi, sekali lagi.
“Lo yakin, nggak?” tanya Malik lagi, mungkin karena Sebastian terlalu lama melamun.
“Ya-yakin, kok,” jawab Sebastian sedikit terbata. Dia lalu menelan ludah.
“Oke. Ayo mulai kalau gitu.”
“Hah? Sekarang?” Awan mengerutkan kening. “Baru juga duduk.”
Tio yang semula berada di dekat sound lekas berjalan menuju drumnya. “Siapa suruh telat.”
“Ya udah, cepetan!”
Sebastian lantas mengusap wajah dan tengkuknya setelah mendengar seruan Awan. Meski badannya paling pendek dan kecil, suaranya paling kencang dan tatapannya juga paling menakutkan.
“Ayo, nunggu apaan?” ucapnya lagi, kemudian memutar bola mata malas.
“I-iya.”
Sebastian buru-buru berdiri di depan mic stand dan segera merilekskan tubuhnya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menghelanya berulang kali secara teratur, dia menoleh ke arah Tio dan tersenyum manis—memberi aba-aba bahwa dia sudah siap.
***
Entah terlalu pintar atau terlalu bodoh, menurut Tio, pilihan lagu Sebastian cukup berisiko. Meski jika terpilih nanti mau tidak mau dia akan membawakan lagu “Lowkey Destiny”—cepat atau lambat, entah di event mana pun itu—menyanyikannya sekarang untuk memberi first impression yang ‘bagus’ tidaklah mudah.
Lagu yang Tio buat di awal debut The Lost Seventeen itu memadukan pop-punk dan rock alternatif. Tidak hanya memerlukan skill vokal yang mumpuni, banyak interpretasi emosional yang mendalam di dalamnya, mengingat lirik yang ditulis oleh Ryan dalam lagu ini banyak memuat isu kerentanan dan refleksi diri. Namun, apa boleh buat? Lelaki di depannya itu tampak begitu percaya diri dengan kemampuannya.
Sesuatu yang kini tidak dimiliki personil lain The Lost Seventeen.
Tio lekas mengetuk-ngetuk stik drumnya lalu memukul cymbal sebagai tanda dimulainya lagu. Setelah itu, Sebastian mulai menyanyikan lirik pertamanya.
“Do you remember we meet in the worst of days? We clashed like fire and gasoline. Too tired to care, too loud to scream.”
Meski berada di belakang dan tak sepenuhnya dapat melihat ekspresi Sebastian, Tio masih bisa menangkap permainan mimik mukanya dari samping, yang semula terpejam lalu tersenyum pahit, seperti seseorang yang sedang mengingat memori lama yang begitu indah, tetapi juga menyakitkan. Sesekali si vokalis baru itu menghadap ke arah Malik, bersitatap seolah berbagi rasa, yang Tio rasa sebenarnya bertujuan untuk menjaga timing-nya agar tetap harmonis.
“You talked like the world owed you peace. I laughed ‘cause I thought I was the least. But under the rain in our head, we just two kids lost in denial.”
Sebastian mampu mencapai bridge dengan aman, padahal lagu ini memiliki tempo yang cepat dan energi tinggi. Ryan saja seringkali lost control atau kurang bisa mempertahankan stamina performanya di sepanjang lagu, terutama setelah falsetto pada chorus pertama dan kedua.
“We broke, we bled, but now I see. ‘Cause I’m not fixed yet, but I’ll heal with you.”
Seketika Tio melirik Bagas yang kini menatapnya tak percaya. Scream ringan Sebastian nyaris terdengar serupa dengan milik Ryan. Meski warna suara Sebastian lebih ‘berat’, dia berhasil menguasai lagu ini layaknya lagunya sendiri, sehingga kualitas yang diberikan pun tak main-main. Bisa mencapai high note dengan baik alias tidak ada crack dan penghayatan sempurna. Apa yang harus Tio lakukan setelah ini?
“Bravo! Bravo!”
Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah sofa setelah lagu selesai, yang ternyata berasal dari Dewa. Entah sejak kapan talent manager LOCO Entertainment itu sampai tempat ini. Tio tidak menyadarinya karena terlalu fokus memperhatikan penguasaan lagu Sebastian.
“Emang kualitas runner up Indonesian Idol kita ini nggak perlu diraguin lagi. Ryan aja pas pertama kali bawain lagu ini kesulitan, lho. Iya, kan, Yo? Gue inget dulu dia sempat minta buat turunin kuncinya, tapi lo bawain ini kayak nggak ada beban-bebannya sama sekali, Bas. Keren!” pujinya panjang lebar yang membuat Tio mengepalkan tangan.
Sebastian pun membungkuk kecil dan mengucap, “Makasih, Bang.”
“Santai, santai,” Dewa menepuk-nepuk bahu calon vokalis baru itu, “jadi gimana? Sah, kan? Apa gue bilang? Kita nggak bakal salah pilih. Kalian bakal baik-baik aja.”
Belum sampai Tio menjawab, Malik sudah mendahuluinya dengan berkata, “Sori, Bang, gue minta waktu buat diskusi dulu berempat. Lo dan Sebastian bisa tunggu di studio agensi. Nanti kami nyusul.”
Sejenak Dewa tampak menimbang-nimbang. Dia sempat bertukar pandang dengan Tio, mungkin mencari pertimbangan tambahan sebelum mengambil keputusan. Sebagai leader, Tio ingin menghargai pendapat anggotanya dengan senantiasa menjadi pendengar, jadi dia mengangguk sebagai isyarat agar Dewa segera enyah bersama Sebastian.
Peka akan kode tersebut, Dewa pun mengangguk. “Oke, tapi jangan lama-lama, ya. Ayo, Bas!”
“Du-duluan, ya,” pamit Sebastian dengan lambaian kecil yang ragu-ragu. Tio lekas tersenyum sepersekian detik padanya lalu menuju sofa kebangsaan mereka.
Selama beberapa menit, tidak ada suara yang mengawali ‘musyawarah’ mereka. Tio hanya menatap Malik yang memandang kosong ke arah mic stand Ryan, Bagas yang menggigiti kuku jarinya, dan Awan yang mengentak-entak lantai secara konstan.
“Gue udah ngira kalian bakal speechless setelah lihat sendiri gimana kemampuan anak itu.” Akhirnya Tio-lah yang memulai percakapan serius ini.
“Emang lo enggak? Ini mah bukan sekadar nyari vokalis baru, tapi emang nyari Ryan 2.0, Yo.” Malik sontak mengacak rambutnya. “Mereka terlalu mirip. Lo lihat sendiri, kan, Wan? Tadi dia juga mainin mic kayak Ryan. Gelagatnya pas screaming juga persis. Nih, ya, kalau gue merem, gue bisa aja ngira Ryan hidup lagi tahu, nggak?”
Awan mendengkus. “Iya, gue juga kaget. Gue tau dia jago, tapi nggak nyangka se-jago ini. Lihat dia berasa lihat fotocopy-an Ryan. Perasaan pas di Indonesian Idol gayanya nggak gini-gini amat, dah. Kok bisa seberubah itu, ya? Merinding!”
“Ya itu berarti dia bisa beradaptasi dengan baik,” respons Tio sambil mengangkat bahu.
“Kalau gini ceritanya … kita jadi nggak ada celah buat bantah Bang Dewa nggak, sih?” tanya Bagas.
“Dari awal emang udah hopeless, tapi gue masih pengen berharap ada jalan, walaupun itu cuma satu persen. Ternyata satu persen aja nggak ada di pihak kita. Nasib, nasib,” jawab Tio pelan. “Mau nggak mau, kita emang harus jalani apa yang agensi pengen.”
“Sial banget!” Bagas refleks menendang kaki sofa hingga merintih kesakitan.
Malik sontak geleng-geleng lalu menatap stiker album band-nya yang bertebaran di meja. Dia juga mengembuskan napas panjang sebelum berkata, “Not gonna lie, banyak band di luar sana yang kehilangan ‘ruh’ mereka karena ganti vokalis. Mungkin Bang Dewa nggak mau hal itu terjadi ke kita, jadi dia kirim Sebastian buat masuk sini.”
“Cih, sejak kapan orang itu peduli? Nggak usah sok positive thinking gitu, Lik. Nggak cocok.” Awan berdecak lalu memutar bola matanya.
Tio lekas melerai, “Udah, udah. Mending kita buruan ke agensi. Takutnya kalau kelamaan Bang Dewa bisa curiga.”
“Oh, come on, kita nggak ngapa-ngapain, Yo.”
Meski apa yang Malik katakan tidak salah, dia tidak bisa juga mengiakan. Tio tetap memaksa anggotanya untuk segera beranjak atau hal yang tidak diinginkan—rumor baru, misalnya—akan terjadi. Saat ini, penting bagi mereka untuk mengikuti arus atau terlihat bersahabat dengan Sebastian.
Nyatanya, mau tidak siap sekalipun, dia dan teman-temannya harus tetap menyapa takdir di depan mereka.


 hwarien
hwarien