Ruang BK sore itu terasa seperti penjara dingin tanpa jeruji. Aroma tipis kertas dan plastik dari rak-rak file bercampur dengan aroma parfum Bu Meri yang lembut, menciptakan kontras yang ganjil. Waktu seolah berhenti berdetak di dalam ruangan itu.
Lara duduk di kursi plastik, tangannya gemetar di atas pangkuan, menggenggam kuat tas kecil yang tak memberinya rasa aman. Di depannya, Bu Meri duduk dengan ekspresi campuran antara lelah dan prihatin. Di sampingnya, Lusi—Ibu Lara—bersandar di kursi dengan dagu terangkat dan alis melengkung tajam seperti pedang yang siap menyerang.
Sebelumnya, Bu Meri sempat menelpon Leo, Ayah Lara. Tapi jawabannya cepat, tajam, dan tak membuka ruang untuk diskusi.
“Saya sibuk. Suruh saja istriku yang datang. Itu urusannya.”
Dan kini, sang Ibu—yang seharusnya jadi pelindung—datang dengan wajah tak kalah dingin.
“Terima kasih sudah datang, Bu Lusi,” ucap Bu Meri, pelan dan penuh hati-hati. “Saya tahu Ibu pasti sangat sibuk… tapi saya rasa ini penting. Lara… dia melakukan sesuatu yang tak biasa. Dan cukup serius.”
Lusi mendengus kecil. “Masalah seperti apa, Bu? Sampai-sampai saya harus mengorbankan waktu kerja saya yang berharga, untuk anak merepotkan ini?”
Lara menunduk. Ucapan itu seperti pisau, tepat di ulu hati.
Bu Meri terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara tenang. “Saya memergoki Lara menindas temannya… bahkan memalak.”
Lusi langsung menoleh pada anaknya dengan tatapan membunuh. “Itu benar, Lara?! Benar kamu melakukan itu?!”
“Enggak Bu, sumpah… Lara nggak kayak itu. Tadi itu Kesya—”
“Diam, Lara.” Bu Meri memotong, nadanya tetap tenang tapi tegas. “Dengar dulu, Ibu belum selesai bicara. Dari yang saya amati, Lara sepertinya kekurangan perhatian dari keluarganya. Mungkin ini juga alasan ia mulai—”
Lusi langsung menepis. “Jadi maksud Ibu, saya nggak perhatian sama anak saya sendiri?”
“Bukan begitu maksud saya, Bu…” Bu Meri menarik napas. “Tapi, dalam pengamatan saya, Lara sering tampak murung di sekolah. Ia pendiam, namun dulunya rajin membantu. Beberapa waktu terakhir… dia mulai berubah. Ia mulai menolak saat saya memintanya mengajari temannya belajar. Alasannya—dia sendiri belum paham.”
Lara mengangkat kepala dengan mata berkaca. “Bu, tapi pas itu Lara emang bener-bener belum paham—”
“Bu lihat sendiri, kan?” potong Bu Meri. “Sikap Lara barusan? Dia makin sering membantah. Padahal dulu, dia anak baik yang patuh,”
Lara kembali menuduk, menahan tangis yang nyaris tak terlihat, ia menunduk semakin dalam. Air mata menetes di pipinya yang pucat. Tapi tidak ada yang memandangnya—karena semua sudah terlanjur yakin siapa yang bersalah. Dan Lara, si anak baik yang dulu selalu tersenyum, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu.
*****
Sepulang sekolah, Lara berjalan di bawah langit mendung. Sera mencoba menyapanya, tapi Lara hanya melirik sekilas dan terus melangkah. Bukan karena marah—tapi karena terlalu letih untuk berkata apa-apa.
Ia berjalan perlahan pulang ke rumah. Hujan yang sempat reda mulai turun kembali, tipis tapi menusuk dingin. Setelah pertemuan tadi Ibunya langsung pergi menaiki mobil, tak menunggu Lara.
Tapi ada satu kalimat yang Ibunya katakan kepada Lara sebelum pergi. "Puas kamu? Membuang waktu saya yang berharga? Dasar anak nakal!"
Dan begitulah. Si anak baik yang kini berubah jadi pembuat onar. Setidaknya, begitulah dunia melihatnya sekarang.
Apakah salah jika orang tuanya kecewa?
Mungkin tidak.
Tapi bagi Lara, yang tak bisa ia terima adalah—tuduhan yang Bu Meri sebutkan padanya tidak semuanya benar. Bahkan sebagian terasa seperti karangan yang dilebih-lebihkan. Lara ingin bicara. Ingin mengatakan yang sebenarnya. Ingin menjelaskan bahwa ia tidak memalak, tidak menindas, tidak seperti yang semua orang pikirkan.
Tapi apa gunanya bicara, jika tak ada yang mau mendengar?
Apa artinya kejujuran, jika sudah ada label yang menempel di dahinya?
Begitu membuka pintu rumah, belum sempat melepas sepatu atau menaruh tas, suara itu menyambutnya—lebih cepat dari langkahnya masuk.
“Anak nggak berguna!” teriak ibunya dari ruang tengah. Suaranya nyaring, tajam, menusuk seperti pisau yang dilempar tanpa aba-aba. “Kamu bisa nggak sih hidup tanpa bikin masalah?! Guru-guru sampai heran kamu berubah segitunya!”
Lara berdiri mematung. Basah hujan di ujung lengan seragamnya menetes ke lantai, seperti mencerminkan air mata yang belum sempat jatuh. Tapi hatinya sudah remuk.
"Sebenarnya kenapa sih, Lara?! Kamu marah sama kami? Kesel karena kita sering nyuruh-nyuruh kamu?" Lusi terus memburu dengan suara keras yang tak memberi ruang untuk bernapas.
Lara mencoba menahan getaran di suaranya. “Tapi itu bukan salah aku, Bu…”
“Kenapa?! Kenapa kamu jadi sering membantah akhir-akhir ini? Ibu tuh capek, Lara! Capek harus ngertiin Luna yang lagi puber! Jangan sampai kamu ikut-ikutan!”
Ada jeda.
“Setidaknya Luna itu membanggakan! Dia juara satu di fashion show kemarin!” Nada Ibunya berubah jadi lebih dingin. “Lah kamu? Nyusahin aja yang ada.”
Lara menunduk. Jemarinya mencengkeram ujung tas yang masih digendong, seperti berpegangan pada sisa harga dirinya. “Maaf, Bu…” suaranya lirih, nyaris tak terdengar. “Maaf Lara nggak bisa seperti Luna. Maaf belum bisa bikin membanggakan…”
Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi nadanya jujur.
“Tapi Ibu tahu kenapa Lara belum bisa membanggakan?”
Lusi diam, menatap tanpa ekspresi.
“Karena Lara nggak tahu arah, Bu… Yang Lara tahu, cuma Lara suka puisi. Lara kadang bingung, sebenarnya harus ke mana? Harus jadi apa? Harus gimana? Lara juga perlu dituntun, Bu...”
Matanya mulai berkaca. “Lara juga belum dewasa…”
Plakk!
Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Wajahnya terpaksa berputar, seolah kenyataan memaksanya menoleh pada luka yang selama ini ia hindari.
Lara memegangi pipinya. Napasnya tercekat. Dunia seperti berhenti beberapa detik.
“Maaf…” bisiknya.
“Maaf, Bu…”
Tapi maaf sudah tak ada artinya lagi.
Lusi menarik kerah seragam Lara dan menyeretnya menuju kamar. Dengan kasar ia mendorong pintu dan membentaknya masuk. “Diam! Nggak usah membantah! Kamu harus sadar salah kamu di mana! Dan jangan nyalahin orang lain!”
Suara pintu dibanting menutup. Suara kunci diputar.
Dari balik pintu, suara ibunya masih terdengar—penuh kebencian yang menusuk.
“Saya juga lelah pura-pura jadi Ibu yang baik untuk kamu!”
Deg.
Kalimat itu lebih keras dari tamparan mana pun.
Dan Lara diam. Air mata yang ditahannya sejak tadi akhirnya jatuh, membasahi pipi yang masih perih. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kalimat itu. Kata-kata yang terdengar seperti kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan senyum palsu dan kata-kata sok bijak.
Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya sendiri.
Dan dalam heningnya kamar, Lara bertanya dalam hati—“Kalau ibu lelah pura-pura jadi Ibu yang baik, berarti dari awal aku ini benar hanya beban ya?”
*****
Malam itu, di balik tirai yang basah oleh air mata, Lara duduk bersila dengan buku tulis di pangkuan. Ia menulis.
Tangannya gemetar. Tapi puisi ini bukan lagi tentang alam, atau tentang mimpinya.
tapi tentang luka.
Aku duduk di antara batas percaya dan pasrah
Di antara kata ‘ibu’ yang jadi doa, tapi kini jadi luka
Apa salahku mencintai kata?
Apa salahku tak sehebat Luna?
Aku bukan cahaya, Bu…
Tapi tak berarti aku gelap
Aku cuma tak tahu jalan dan tak ada yang mau menuntun
Maaf kalau aku gagal jadi kebanggaan
Tapi tolong jangan pura-pura sayang
Karena pura-pura itu lebih tajam dari benci
Dan aku, Bu…
Aku cuma ingin didengar, walau sekali
Bukan disalahkan, dipukul, lalu dikurung seperti mimpi buruk yang ingin dilupakan
Lara menutup bukunya pelan. Kertas terakhirnya sedikit basah oleh tetesan air mata, tintanya buram di beberapa kata, seperti luka yang tak bisa dijelaskan. Ia mendekap buku itu ke dadanya seolah-olah benda itu satu-satunya yang tersisa dari dirinya yang masih percaya pada harapan.
Dan untuk sekian kalinya malam itu, ia memeluk dirinya sendiri. Bukan karena dingin, bukan karena takut—tapi karena tak ada lagi yang mau memeluknya. Tangannya menggenggam lengan sendiri dengan erat, seolah jika dilepas, dirinya akan runtuh dalam sekejap.
Di luar, hujan turun semakin deras. Gemuruh petir sesekali menggetarkan kaca jendela kamarnya yang buram. Tapi tak satu pun suara lebih menggelegar dari sunyi yang mengoyak di dalam dadanya.
Ia duduk mematung di pojok ranjang, tubuhnya meringkuk seperti ingin menghilang dari dunia. Dalam kepalanya, ribuan pertanyaan berputar, tapi tak satu pun menemukan jawaban. Ia merasa kecil. Tidak dilihat. Tidak diakui.
Seperti orang yang tenggelam di lautan, tapi semua orang mengira ia sedang berenang. Ia melambai-lambai di antara gelombang—bukan untuk bermain, tapi untuk meminta tolong. Namun mata-mata di sekitarnya tak menangkap sinyal itu. Mereka melihatnya sebagai anak keras kepala, pembangkang, pembuat masalah.
Padahal kenyataannya, Lara hanya ingin diselamatkan.
Ia hanya ingin didengar.
Ingin ditanya, “Kamu kenapa?” tanpa didahului kemarahan. Ingin dipeluk, bukan dipukul. Ingin ditemani dalam diam, bukan dihakimi dengan kalimat-kalimat tajam.
Tapi malam ini, tak ada satu pun yang datang. Tak ada tangan yang meraih. Tak ada suara yang memanggil namanya dengan lembut.
Jadi Lara memeluk dirinya sendiri, erat-erat. Menyimpan semua luka itu dalam diam. Dan berharap… mungkin suatu hari, dunia akan benar-benar melihatnya.
Bukan sebagai masalah.
Tapi sebagai anak yang terluka, yang selama ini cuma ingin pulang ke rumah yang hangat.


 yourassiee
yourassiee











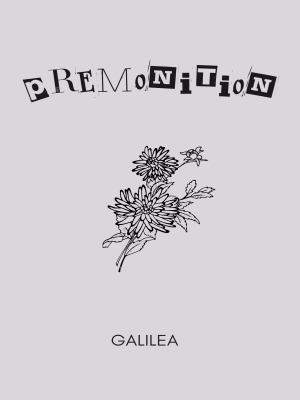



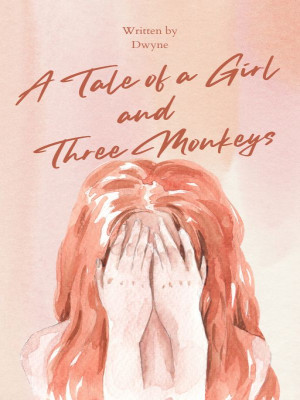


@pacarmingyuu, ahaha, maaf aku sensi, abisnya komennya menjerumus banget, aku kepikiran punya salah apa, dikomen juga aku jelasin, aku harap aku salah, kalau beneran aku salah, aku minta maaf ya😔😔🙏🩷
Comment on chapter 3 - Aku ingin berubahthank you udah berkenan komen juga, have a great day🩷🙏