Senja sudah hampir habis ketika Lara tiba di rumah. Langit memudar dari jingga ke keabu-abuan, dan dedaunan di halaman depan bergoyang pelan dipukul angin sore. Rumah itu berdiri tenang seperti biasa—rapi, terawat, dan diam. Hanya diam.
Langkah Lara perlahan saat menaiki undakan depan. Udara sore merayap masuk lewat sela lengan bajunya. Tote bag yang tergantung di bahu kirinya terasa berat—tentunya bukan karena isinya, tapi karena apa yang dibawanya ikut menyeret pikirannya jatuh.
Jemarinya kaku, seolah darah sudah malas mengalir ke sana. Nafasnya pendek dan tidak teratur, seperti tubuhnya menolak berada di tempat ini.
Pintu terbuka bahkan sebelum ia sempat mengetuk.
“Jam berapa ini?” suara Ayahnya menyambut tajam, bukan keras, tapi cukup untuk memukul hati. Wajah Ayahnya itu tak menyimpan kekhawatiran, jelas hanya kekesalan.
“Kalau cuma main, jangan bohong bilang kerja kelompok.”
Lara belum sempat bicara, Lusi sudah menyusul dari ruang tengah. Dengan wajah letih dan nada sinis, Ibunya menambahkan, “Dasar sok sibuk! Ibu juga yakin kamu ini bukan kerja kelompok! Malas-malasan aja! Ibu capek beresin rumah sendirian, kamu kemana aja? Kamu itu anak pertama, harus bisa diandelin!”
Lara menggigit bibir. Tangan kirinya gemetar sedikit, tapi ia rapatkan ke belakang tubuhnya agar tak terlihat.
“Tadi aku bantu kegiatan. Selesainya agak lambat... aku nggak main kok, Bu,” suara Lara nyaris tak terdengar. Bukan karena takut, tapi karena lelah menjelaskan.
“Ya, selalu begitu! Ada aja alasan. Kamu pikir hidup kamu penting?” Ayahnya berbalik, suara ponsel di tangannya terdengar klik saat dia menutupnya. “Kami di rumah ini juga capek. Jangan egois, Lara.”
Lusi menatap tajam. “Bilang aja kamu gak peduli sama Adikmu kan? Kegiatan luar lebih penting, ya?” ucapnya sinis.
Tak ada yang menunggu penjelasan. Tak ada yang benar-benar ingin tahu.
Tak ada yang menunggu penjelasan.
Tak ada yang benar-benar peduli untuk tahu.
Lara hanya mengangguk kecil, lalu berjalan naik. Setiap anak tangga seperti menghantam pelipisnya dari dalam, satu per satu. Sakit kepala yang mengendap sejak siang kini membengkak, menekan seperti sesuatu yang ingin pecah di balik tengkorak. Pandangannya kabur, berbayang. Tapi ia tetap melangkah, tetap diam.
Sudah biasa.
Lelah selalu jadi alasan yang paling mudah—dan paling aman.
Ia duduk di ujung ranjang dan memejamkan mata. Wajah-wajah tadi siang—anak-anak yang tertawa dan bersyukur, Udara panas yang menyengat kulit saat membagi nasi bungkus—semuanya muncul lagi di kepalanya, tapi kini terhalang oleh denyutan pelan yang menyiksa di belakang mata kirinya.
Tangannya meraba meja belajar. Ada secarik kertas dari Satya.
Kakak janji ngajarin jam 2, tapi gak datang. Aku belajar sendiri. Gak usah diajarin lagi.
Tulisan Satya sedikit berantakan. Lara tahu itu bukan marah sungguhan. Satya sedang ngambek. Hanya kecewa. Dan itu justru yang paling menyesakkan—karena Satya adalah satu-satunya yang kadang, walau jarang, benar-benar melihatnya. Menyadari kehadirannya.
Tapi hari ini, tidak ada satu pun yang melihat.
Lara menghela napas, memandang langit yang berubah gelap di luar jendela. Lalu berjalan pelan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Pandangan matanya bertemu dengan bayangannya sendiri di cermin. Pucat. Bibir sedikit kering. Ada lingkaran samar di bawah matanya.
Tapi tidak apa-apa, katanya dalam hati. Ini pasti hanya kecapekan.
Ia tidak akan bilang siapa pun. Tidak akan membuat repot siapa pun.
Seperti biasa.
*****
Lara kembali ke meja belajarnya. Buku matematika kelas lima SD milik Satya terbuka di depannya, tapi ia hanya membalik-balik halaman tanpa benar-benar membaca. Bukan karena malas—justru karena terlalu ingin memahaminya. Tapi kata-kata di buku itu seolah bergetar pelan, mengikuti denyut kepalanya yang semakin berat.
Ia menghela napas, berusaha menahan diri untuk tidak memejamkan mata terlalu lama. Dari luar kamar, terdengar suara Leo menyuruh Satya mandi, sementara Lusi sibuk mengomel soal cucian yang belum disetrika. Suara-suara rumah yang seharusnya terasa akrab malah membuat Lara merasa seperti orang asing.
Lara berjalan menuju rak kecil di pojok kamar, mengambil dompet kecil berisi stiker lucu, lalu dengan hati-hati menyelipkan satu stiker bergambar planet Saturnus berwarna biru di sampul buku Satya. "Biar semangat," bisiknya, meski tak ada yang mendengar.
Kembali ke meja belajar, ia membuka ponselnya. Tak ada notifikasi baru. Grup relawan yang tadi siang ramai kini sudah senyap. Beberapa pesan dari teman sekolah yang menanyakan PR, tapi tak ada yang benar-benar peduli.
Tiba-tiba, notifikasi baru muncul. Sebuah pesan dari Sera masuk. Lara membuka pesan itu.
Lara, makasih buat hari ini, aku seneng banget. Semoga kamu baik-baik aja ya di rumah^^
Lara terdiam sejenak, matanya sedikit berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti menyentuh bagian yang lama ia sembunyikan. "Setidaknya ada satu, yang peduli sama aku,"
Begitu membaca pesan itu, Lara segera bangkit, ia tak bisa membiarkan dirinya terlalu larut. Perlahan, ia mematikan ponselnya, meletakkannya di meja.
Cahaya dari jendela semakin meredup. Angin malam mulai masuk lewat celah kisi-kisi. Kepalanya makin terasa berat, tapi ia enggan tidur. Seakan-akan, jika tidur sekarang, semuanya akan makin terasa sepi.
Tepat pukul sembilan malam, Lusi mengetuk pintu kamar. Tanpa menunggu jawaban, pintu sedikit terbuka.
“Jangan lupa besok ajarin Satya belajar sepulang sekolah. Awas aja kalau Satya sesedih tadi. Lara, jadilah Kakak yang berguna, ya?” suara Lusi tajam, seolah menuntut lebih dari sekadar perkataan.
Lara mengangguk lemah, menunduk, berusaha menghindari tatapan Lusi. "Iya, maaf," jawabnya pelan, hampir tidak terdengar.
Lusi hanya mendesah, lalu menutup pintu dengan langkah cepat. Tak ada "Makasih", apalagi "Kamu capek?" Lara merasa ada ruang hampa yang mengisi dadanya. Mungkin sedikit perhatian, bahkan hanya kata-kata biasa, bisa membuat malam ini terasa lebih hangat.
Setelah semua lampu rumah mati, Lara berbaring di tempat tidurnya, menyelipkan tubuhnya ke balik selimut tipis. Tapi matanya tak kunjung terpejam. Ada bunyi seperti detak yang keras di dalam kepala. Tidak sakit yang mencolok, tapi cukup untuk membuatnya sadar kalau tubuhnya sedang berusaha memberi tahu sesuatu.
Kepalanya berdenyut perlahan, matanya sedikit kabur, dan kadang suara dari luar terasa tenggelam, seperti berada di dalam air. Tapi ia tak mau berpikir yang aneh-aneh.
“Mungkin karena matahari siang tadi terlalu terik,” gumamnya. “Besok pasti baikan.”
Ia memeluk bantal kecilnya, yang sudah ia gunakan sejak kecil. Ada bordiran namanya di sudut bawah. Ibunya yang menjahitkan waktu ulang tahun ke-3. Saat itu, Lusi sempat membuatkan kue, meskipun rasanya asin. Saat itu, rumah terasa lebih hangat. Saat itu, semuanya belum berubah seasing ini.
Lara terpejam dengan bisikan pelan dalam hati—jadi anak baik, jangan bikin masalah, jangan bikin orang lain repot.
Besok pagi, ia akan bangun lebih cepat. Mungkin menyiapkan sarapan untuk Satya. Mungkin juga akan menyapu halaman supaya Ibunya tak marah. Kalau sempat, ia akan diam-diam membeli vitamin. Kalau tidak sempat, ia akan pura-pura baik-baik saja.
Karena begitulah Lara hidup, menjadi baik agar tidak ditinggalkan.
****
Pagi hari datang lebih cepat dari yang Lara bayangkan. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah jendela, membangunkannya sebelum alarm berbunyi. Lara mengerjapkan matanya, masih lelah, tapi tetap memaksa tubuhnya bangun.
Ponselnya ada di meja belajar, layar gelap. Tanpa pikir panjang, ia menggapainya dan mematikan alarm. Jemarinya menyentuh layar, membuka pesan dari Sera yang masih tersimpan di sana. Meski baru sebentar, kata-kata itu masih hangat di pikirannya. Ia tersenyum pelan, merasakan sedikit kedamaian sebelum hari baru dimulai.
Lara bangkit dari tempat tidur, menarik selimut tipis itu dan melipatnya dengan cepat. Ia mengusap wajahnya, merasa sedikit pusing, namun berusaha menepisnya. Ia tahu, tak ada waktu untuk merasa lelah. Di luar, suara ayam berkokok mulai terdengar. Lusi sudah mulai sibuk di dapur, seperti biasa.
Ia berjalan pelan menuju kamar Satya, melihat adiknya yang masih terbaring di meja belajar dengan wajah cemberut. Satya belum tidur semalaman, buku matematika terbuka di depannya. Lara merasa sedikit kasihan melihatnya, tapi ia juga tahu, Satya tak akan pernah mengakui kalau dia butuh bantuan.
Lara duduk di sampingnya, menatap buku itu sebentar. “Satya, kamu tidur?” tanyanya pelan.
Satya hanya menggeleng, masih terlihat kesal. Lara mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. “Maaf ya, kemarin Kakak lupa, ini Kakak bawain stiker planet, kesukaan Satya. Maafin Kakak ya?"
Satya mendongak, menatap kakaknya sejenak. Walaupun terlihat enggan, akhirnya ia mengangguk pelan. “Nyebelin. Pokoknya hari ini Kakak gak boleh lupa lagi,"
Lara tersenyum sedikit lebih lebar. "Iya dek,"
Pagi itu terasa lebih tenang. Meski masih ada rasa lelah di tubuhnya, Lara berusaha menjalani hari dengan sebaik mungkin. Setelah memastikan Satya masih bisa sedikit fokus pada pelajarannya, ia keluar dari kamar dan menuju dapur.
Di sana, Lusi sudah mulai menyiapkan sarapan. Lara membantu sejenak, menyiapkan roti dan teh hangat. Sebelum terlalu larut, ia berjanji pada dirinya sendiri, hari ini ia akan lebih baik. Ia akan jadi anak yang bisa diandalkan, meskipun kadang merasa sendiri.


 yourassiee
yourassiee








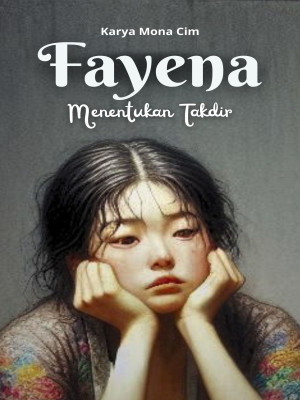









@pacarmingyuu, ahaha, maaf aku sensi, abisnya komennya menjerumus banget, aku kepikiran punya salah apa, dikomen juga aku jelasin, aku harap aku salah, kalau beneran aku salah, aku minta maaf ya😔😔🙏🩷
Comment on chapter 3 - Aku ingin berubahthank you udah berkenan komen juga, have a great day🩷🙏