Lara belum ingin sampai. Langkahnya pelan, bukan karena lelah, tapi karena hatinya belum siap. Setiap meter yang mendekatkannya ke sekolah terasa seperti dorongan halus ke jurang yang sama—jurang tempat ia harus tersenyum meski tak benar-benar merasa ada.
Hari itu ia berangkat lebih pagi dari biasanya. Bukan berarti ia rajin. Tapi ia hanya butuh waktu sendiri, butuh jeda di antara rumah dan kelas, antara tuntutan dan peran.
Ia menemukan sebuah halte kosong di tengah perjalanan. Bukan tempat biasa untuk singgah, tapi entah kenapa kakinya berhenti. Ia duduk, tidak untuk menunggu bus—hanya untuk diam. Untuk merasa bahwa dirinya masih bisa memilih sesuatu hari ini, walau hanya tempat duduk.
Ia membungkuk, menatap jemarinya yang saling menggenggam. Sekilas terasa seperti memegang sesuatu. Mungkin dirinya sendiri, agar tidak tercecer.
“Hai!”
Sebuah tangan melambai tepat di depan wajahnya. Lara tersentak kecil, tapi tak menunjukkan keterkejutan.
Seorang perempuan berdiri di hadapannya. Tubuhnya sedikit berisi, rambutnya panjang tergerai, dan senyum hangat menghiasi wajahnya yang asing.
“Kamu mau ke SMA Pelita Nusa, ya?”
Lara menoleh pelan, matanya masih redup. Ia mengangguk tanpa kata. Perempuan itu langsung duduk di sampingnya, tanpa takut. Lara menoleh cepat, bingung.
“Kamu siapa?”
“Oh! Aku lupa ngenalin diri, ya.”
Perempuan itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga sebelum mengulurkan tangan.
“Namaku Seraphine Callidora. Tapi kamu bisa panggil aku Sera.”
Lara ragu sejenak, lalu menjabat tangan itu dengan lemah.
“Aku Lara,” katanya pelan.
Sejenak hening. Angin kembali bertiup. Canggung menggantung di antara mereka.
“By the way… kamu cantik banget ya, Lar,” ucap Sera tiba-tiba memecah keheningan. Nadanya ringan, tapi tulus.
Lara sedikit terkejut, bibirnya menegang.
“Ah, enggak… yang cantik itu kamu, Sera.”
Sera tersenyum tipis, lalu menunduk. Wajahnya berubah sendu, matanya berkilat.
Lara mengerutkan kening, lalu cepat-cepat mengambil tisu dari tas.
“Kamu… nangis?”
Sera buru-buru menyeka matanya.
“Enggak, aku cuma… kaget. Terharu. Baru kali ini ada yang muji aku. Biasanya orang cuma lihat… bentuk badan aku. Kayak nggak punya hal lain buat dilihat…”
Suaranya mengecil.
“Aku tahu kok, aku gendut…”
Lara menatapnya. Ada sesuatu di dada yang menghangat dan mengencang.
“Enggak kok, Sera. Sumpah, kamu cantik. Lucu lagi,"
Sera tersenyum lebar. Matanya berbinar, seolah-olah kata-kata Lara barusan berhasil menyalakan cahaya kecil di ruang hatinya yang sempat gelap.
“Serius?” tanyanya dengan suara bergetar pelan, seakan takut harapan itu hanya mimpi.
Lara menatapnya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Hangat.
“Serius,” jawabnya sambil mengangguk, senyumnya tulus.
Dan saat itulah, bus yang mereka tunggu akhirnya tiba—berderu pelan dan membuka pintunya. Tapi suasana di antara mereka terasa lebih tenang dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang baru saja terlahir—rapuh, tapi nyata.
Mereka naik bersama. Dua gadis asing yang dipertemukan di bangku halte, tapi kini duduk berdampingan dengan tawa kecil yang mulai tumbuh di antara mereka.
*****
Lara melangkah pelan masuk ke kelas. Sendiri. Tadi, ia dan Sera terpisah saat hendak keluar dari ruang guru. Hatinya terasa kosong, seperti tak punya arah. Suara-suara teman sekelas bagai gema yang tak ia pahami. Ia duduk di bangkunya, menunduk. Jemarinya saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan detak jantung yang tak kunjung melambat.
Ia tidak tahu harus ke mana, tidak tahu harus bagaimana.
Tak lama, suara pintu terbuka. Seorang guru masuk, diikuti seorang siswi baru. Mata Lara membulat. Ia hampir tak percaya.
Itu Sera.
"Saya perkenalkan, ini Sera. Mulai hari ini dia akan bergabung dengan kalian. Tolong dibantu, ya," ucap Bu Reni.
Sera maju perlahan ke depan kelas. Ia mencoba tersenyum, walau jelas terlihat canggung. "Hai, aku Sera. Semoga kita bisa berteman baik," katanya pelan.
Suasana sempat hening, tapi tak lama suara-suara kecil mulai terdengar.
“Eh, badannya gede banget, ya…”
“Sejak kapan kelas kita kemasukan hulk?”
“Baru masuk aja udah kayak nutup separuh papan tulis.”
Bisikan-bisikan itu makin lama makin menyakitkan. Beberapa siswa saling pandang dan tertawa kecil sambil menutup mulut. Sera hanya berdiri diam, masih berusaha tersenyum, walau sorot matanya mulai meredup.
Tatapan Bu Reni langsung menyapu ke arah barisan tengah, tepat ke arah asal suara. Matanya tajam, bukan marah meledak-ledak, tapi cukup membuat siapa pun yang ditatap merasa ingin menciut di kursi.
“Kalau kalian sudah selesai berkomentar hal yang tidak penting,” kata Bu Reni dingin, “boleh saya lanjutkan?”
Tawa-tawa itu langsung lenyap. Beberapa siswa menunduk, berpura-pura sibuk dengan pena mereka.
“Sera, kamu bisa duduk di bangku kosong di sebelah Lara,” kata Bu Reni.
Sera mengangguk pelan dan berjalan ke arah bangku itu. Langkahnya tenang, tapi ada sedikit getar di bahunya. Ia duduk dengan hati-hati, menaruh tasnya di sisi bangku tanpa banyak bicara.
Lara meliriknya sebentar, lalu berbisik, “Nggak apa-apa, ya. Aku senang kamu di sini.”
Sera tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Matanya tampak berkaca-kaca, dan tangan yang menggenggam ujung roknya bergetar pelan.
*****
Waktu istirahat tiba. Begitu bel berbunyi, Lara langsung berdiri dan menoleh ke arah Sera. “Mau ikut aku ke taman belakang?” tawarnya pelan.
Sera sempat ragu, tapi kemudian mengangguk. Mereka keluar kelas tanpa banyak bicara, menyusuri lorong sekolah yang ramai, lalu melewati taman tengah, dan akhirnya sampai di sudut sekolah yang lebih sepi—taman belakang.
Tempat itu sederhana, hanya rerumputan, beberapa pohon besar, dan bangku kayu panjang yang sudah agak lapuk. Tapi bagi Lara, tempat ini adalah satu-satunya ruang bernapas.
“Biasanya aku makan di sini,” ujar Lara sambil membuka bekalnya. “Gak banyak yang tahu tempat ini kok, jadi tenang aja.”
Sera duduk di sampingnya, menarik napas pelan. “Adem ya, Lar.”
Mereka makan dalam diam. Sesekali angin meniup pelan, menggerakkan rambut mereka. Sera tampak lebih rileks. Wajahnya masih menyimpan luka, tapi ada secercah kelegaan. Ia akhirnya menemukan tempat untuk menjadi dirinya sendiri—walau hanya sebentar.
Namun keheningan itu tak bertahan lama.
Langkah kaki mendekat. Suara tawa tinggi, sengaja dikeraskan. Lara langsung menegakkan badan. Ia mengenali suara itu—Zea.
Dan benar saja. Zea muncul bersama dua temannya. Mereka berdiri tak jauh dari bangku Lara dan Sera, tangan dilipat, pandangan penuh sindiran.
“Ciee, sekarang udah gak sendirian lagi ya? Hebat deh. Dapet temen juga akhirnya,” ucap Zea, senyumnya manis tapi tajam.
Lara menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Tangan yang tadi menggenggam sendok, kini gemetar.
Sera diam. Matanya menatap tanah.
Kesya ikut bersuara, nadanya dibuat santai, tapi jelas menyudutkan. “Tapi kok… temennya itu ya? Gendut banget. Kan kasian bangkunya.”
Tawa kecil terdengar, namun Zea tak ikut tertawa. Ia justru menatap Lara lama, ekspresinya tak lagi sinis, tapi penuh pertanyaan. “Lo tuh kenapa sih, Lar?” tanyanya lirih, tapi tetap terdengar menusuk. “Beberapa hari ini aneh banget.”
Lara mengangkat kepala pelan. Ada keterkejutan di matanya—Zea terdengar... kecewa?
Zea melangkah lebih dekat. “Dulu lo itu penurut banget. Gue ngerasa cocok sama lo. Tapi sekarang lo kok, berubah. Udah mulai merasa dibutuhkan ya?"
Lara tak menjawab.
Citra menyikut Zea pelan. “Eh, udahlah. Ngapain juga dibawa baper.”
Zea mendengus pendek, lalu menatap Lara lagi. “Gue cuma mau lihat tugas fisika lo, lo malah nolak. Dikit doang padahal. Dulu juga nggak pernah nolak.”
Lara menahan napas. Ia melirik Sera—gadis itu masih diam, tapi matanya kini sedikit mengerut, seperti sedang menahan emosi.
Lara menarik napas panjang, lalu menguatkan suara. “Aku… nggak mau,” katanya pelan.
“Apa?” Zea menyipitkan mata.
“Aku bilang… aku nggak mau ngerjain tugas kamu lagi,” ulang Lara. Suaranya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. “Aku tahu kita emang temen. Tapi jadi teman bukan berarti aku harus selalu nurut. Aku capek, Zea.”
Zea terdiam sejenak, seperti tak menyangka. Lalu ia mengangkat alis, menyeringai kecil, seolah menutup luka yang tak ingin terlihat.
“Oke. Terserah lo,” katanya dingin. Tapi nada suaranya… terdengar lebih seperti kekecewaan ketimbang amarah.
Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suara panik memotong.
“Eh, Zea,” bisik Citra tergesa. “Ada Bu Meri.”
Zea menoleh cepat, dan benar—dari kejauhan, sosok guru BK mereka, Bu Meri, tampak berjalan mendekat. Zea menghela napas panjang, menahan kata-kata yang belum sempat ia lontarkan. Ia membalikkan badan.
“Yuk, girls,” gumamnya datar. Kali ini tak ada tawa, tak ada ejekan. Hanya kepergian yang terasa menggantung.
Lara tetap duduk di tempatnya. Ketika suara langkah mereka menghilang, tubuhnya lunglai. Ia menatap tanah, dan air mata jatuh pelan ke punggung tangannya yang mengepal. Ia tak tahu perasaannya: takut, lega, atau justru sedih.
Sera diam di sampingnya. Ia menunduk, lalu pelan-pelan menggenggam tangan Lara. Hangat. Tidak banyak kata, tapi cukup untung membuat Lara sedikit tenang.
Lara mengangkat wajahnya, dan mereka saling menatap. Hening. Tapi dalam hening itu, tumbuh sesuatu—bukan hanya keberanian, tapi juga kesadaran bahwa setiap perubahan butuh keberanian untuk kehilangan.


 yourassiee
yourassiee















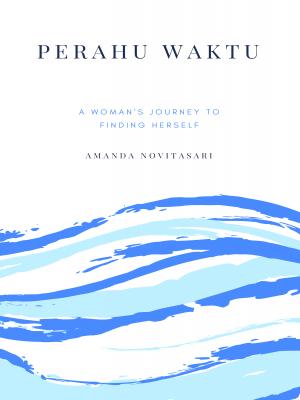

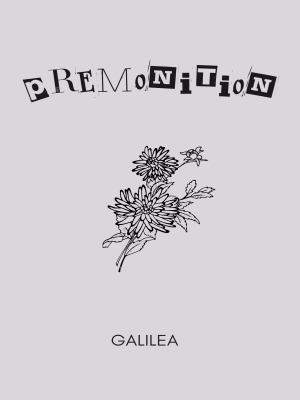

i wish aku punya temen kaya sera:((
Comment on chapter 9 - Luka yang tak diakui