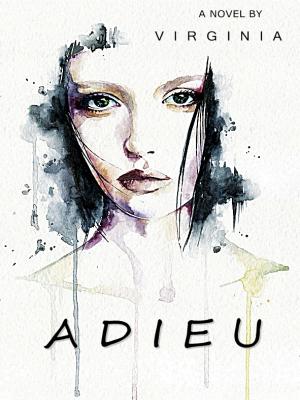Jarum jam berdetak. Berbunyi tiga kali. Tiga pagi ini hawa dingin menjalari kamar. Dinding seolah berembun. Langit-langit berderak. Kayu. Kayu tua dan lama di atas kamar kecil itu sudah minta ganti sejak lama. Tak ada orang peduli. Tak ada yang mengganti.
Pukul tiga sebelas menit. Sunyi sekitarnya. Gelap bayang di hadapannya. Siluet meja, kursi, lemari, bertumpuk di matanya. Padahal semua benda itu berdiri satu per satu di tempat masing-masing.
Dia memandang jemu. Pada sekitarnya. Pada meja kayu lingkaran itu. Dia teringat saat itu. Ketika seorang wanita melempar salah satu vas ke arahnya. Memang pecah, tapi dia tak peduli. Wanita itu tak muncul lagi setelahnya. Sepi pun melanda. Dia merasa telah mengusirnya.
Kakinya menuntunnya ke pintu, membukanya. Hembus dingin hanya memperkantuk matanya. Tapi dia bertahan.
Seseorang berdiri di sana. Kepalanya tertutup tudung mantel hitam. Tangannya memeluk diri, seolah ini musim dingin seperti di barat sana.
Dia sempat berharap wanita itu adalah dia. Dari belakang tampaknya mirip. Wanita itu berbalik menampakkan mukanya. Bukan. Tentu ada kekecewaan, tapi dia bersedia menyambut ketika wanita itu berjalan ke arahnya.
”Kau Alvin?”
”Ya. Ada apa?”
”Ikuti aku!” Jalan cepat, wanita itu menuju mobil merah di sana. ”Ayo!” Wanita itu membalik muka ketika mengetahui Alvin hanya diam.
Dengan celana pendek dan kaus santai seperti itu, tentu setiap orang merasa tak pantas untuk bepergian. Tapi dia penasaran dan tidak enak untuk mengabaikannya. Sudah diputuskan.
”Siapa yang menyetir?” tanya Alvin yang duduk di kursi belakang, di samping wanita itu.
”Kau.”
”Aku? Aku bahkan tak tahu ke mana kau akan membawaku. Aku bahkan tak mengenalmu.”
”Aku membawamu? Tidak. Kau membawa mobil ini.”
Alvin terdiam bingung. Tapi melihat tatapan memaksa wanita itu, dia keluar, membanting pintu. Dia kini berada di kursi depan, menyalakan mobil. ”Baik. Ke mana?”
Wanita itu tak menjawab. Dia hanya berkonsentrasi pada ponsel dalam genggamannya.
Sesuatu bergetar di paha Alvin. ”Ini milikmu? Ada pesan.”
Wanita itu masih tak menjawab.
Menyebalkan, pikir Alvin. Tanpa izin yang tak berguna lagi, dia membuka pesan itu. Lorong, kata itu saja yang tertulis di pesan. Apa dia tidak bisa bicara? kata Alvin dalam hati. Ngotot kesal dia menggerakkan tuas dan menginjak gas.
Keluar dari lantai rumput, ban mobil kini menginjak aspal. Tak seperti pagi biasanya. Penjual sayur di tepi jalan selalu dapat mengisi kekosongannya. Kali ini, semua terlewat begitu saja. Beberapa kali Alvin melirik ke kaca. Wanita itu masih fokus pada ponsel.
Di depannya dua cabang jalan. Jalan di sisi kiri seolah tak dipedulikan. Orang cenderung memilih melewati jalan kanan yang lurus. Hanya angin yang menemaninya menukik ke dalam terowongan itu. Sunyi. Hanya cahaya lampu yang setengah-setengah menerangi.
Dia berhenti. Bunyi kesunyian mengisi telinga. Bahkan angin takut untuk berbisik. ”Baiklah, kita sudah sampai. Sekarang apa? Jangan bilang kau hanya mau sopir gratis.”
”Kenapa kau membawaku ke sini?”
”Kau yang memintaku.”
”Aku tak pernah memintamu.”
”Tapi, pesan itu…” Alvin terdiam kesal. ”Baik, katakan saja apa yang harus kulakukan!”
Wanita itu keluar, menutup pintu.
”Hei, jangan pergi begitu saja! Apa kau ingin aku menjaga mobilmu selagi kau pergi?!”
”Mobilku? Siapa bilang ini mobilku.” Wanita itu berpaling. Ponselnya dia simpan di tas merah di cangkingannya, mulai melangkah.
”Jadi, kau mencurinya?!” teriak Alvin hingga suaranya menembus kaca mobil yang masih tertutup rapat. Dia berpikir telah membantu kabur seorang pencuri.
Wanita itu tak peduli. Dia menuju sebuah ruang kosong.
Kesal, Alvin keluar mengejarnya. Ketika dia buka pintu itu, tak ada orang di dalam sana. Yang ada hanya goresan-goresan cat yang tak tertata. Kursi dan meja tak ada yang utuh. Lampu neon hanya berkedip-kedip dengan periode tak tentu. Tak ada pintu lain untuk keluar. Wanita itu pergi seperti hantu. Atau, dia memang hantu?
Sementara waktu Alvin berada di dalam ruangan itu, menelusurinya. Benar-benar tak ada siapa pun. Dia mulai gelisah. Dia pun kembali ke mobil merah itu, lekas menginjak gas.
Kemunculannya dari lorong seperti kapal Flying Dutchman yang naik ke permukaan. Bumi tak bergerak. Kesunyian masih menemani. Dia baru sadar. Ponsel yang dia tinggalkan di sana tak ada di tempatnya lagi. Sepucuk surat menggantikannya. Dia membukanya. Hanya satu kata, Lurus. Dia menginjak rem sekuatnya, berhenti. Dia mulai berpikir. Seseorang telah memasukkannya ke dalam permainan. Siapa dalangnya, dia penasaran.
Alvin benar-benar memaknai kata lurus itu secara detail. Tiga buah pertigaan, lima buah perempatan, dan dua jalan melingkar dia lewati. Itu termasuk jalan kecil yang belum terlapis aspal. Memang sial, atau ada makna lain? Mobilnya mogok di jalan, kehabisan bensin. Pepohonan mengepungnya. Tak ada apa-apa. Tadi dia sempat melihat sebuah toko yang menjual bensin eceran cukup jauh di belakang. Dia berjalan ke sana.
Ketika dia kembali, ada yang berubah. Mobil itu ada tiga dalam satu baris, sama. Pintu di ketiganya tak terkunci. Setelah diperhatikan, entah kenapa ia tertarik pada mobil yang tengah. Dia mengisikan bensin, lantas mengendarainya dan meninggalkan dua mobil lain.
”Jangan menengok!” Sebuah suara muncul dari belakang.
Jantungnya berdegup kencang. Alvin merasakan todongan pistol tepat di belakang kepalanya. Dia baru menyadari tidak ada cermin yang menggantung seperti mobil sebelumnya.
”Terus jalan!” Pria bersuara berat itu memaksa.
Tak ada pilihan lain, Alvin terus menjalankan mobilnya. ”Sia...”
”Diam! Terus jalan!”
Benar-benar terdesak. Dia tak dapat melakukan apa pun. Tidak selama mulut pistol itu menempel tepat di belakang kepalanya.
Selama perjalanan, si penodong terus memaksanya berjalan kemana pun yang dia inginkan. Dia tinggal berkata kanan atau kiri, atau ”Berhenti!”
Alvin menginjak rem sekuatnya. Sesuatu dilempar dari belakang, jatuh pada kursi di sampingnya –sebuah pistol.
”Lima menit lagi bus akan berhenti di halte itu. Ada seseorang yang akan turun. Kau harus membunuhnya dengan pistol itu.”
Alvin terkejut. Jantungnya berdegup lebih kencang. ”Kalau aku menolak?”
”Maka kau yang akan mati.”
”Aku bisa membunuhmu.”
”Kau takkan berani. Lagipula aku bisa membunuhmu lebih dulu.”
Alvin semakin terpojok. Belum pernah dia membunuh orang seumur hidupnya. Tak ada keputusan yang dapat dia ambil. Haruskah dia mengotori tangannya dengan darah untuk mencegah darah? Dia bahkan belum sanggup untuk menggenggam pistol itu. Hanya ada dua pilihan. Membunuh, atau dibunuh. Sepertinya dia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang sulit. ”Jika aku yang membunuhnya, kau tetap akan ditangkap. Seseorang akan mengenali mobil ini dan melaporkannya.”
Sesuatu kembali dilempar menjatuhi pistol tadi.
Alvin mengambilnya. Itu STNK. STNK mobil ini. Tertera namanya di sana. Pria itu lebih cerdas dari yang Alvin kira. Dia menyiapkan segalanya dengan matang. Jika polisi melacak mobil itu, tentu Alvin yang akan ditangkap. Pilihannya semakin sulit. Mati, atau hidup dalam bayang-bayang kesalahan.
”Apa lagi yang kau bantah? Ayo, mainkan permainannya!”
Alvin benar-benar tak bisa membantahnya lagi. Semakin berjalannya waktu, semakin dia gelisah. Dia harus menentukan pilihannya dalam dua menit ini. Dua menit yang dapat menjadi akhir hidupnya. Dia teringat dengan wanita tadi. Mobil itu bukan mobilnya, itulah yang dikatakan wanita tadi. Mobil itu miliknya, sesuai STNK itu. Artinya, wanita itu ada hubungannya dengan si pembunuh ini. Tapi bagaimana?
Bus putih pucat berhenti di sana.
Getar kaku tangan Alvin meraih pistol itu. Keputusannya masih belum bulat. Masalah ini melibatkan nyawa. Tapi, dia tidak ingin kehilangan nyawa. Belum. Ada keinginan yang timbul beberapa hari terakhir ini dan keinginan itu belum dapat dia penuhi. Dia ingin bertemu wanita yang melemparnya dengan vas beberapa hari yang lalu.
Bus putih itu memutar rodanya kembali. Dari baliknya, muncul sesosok manusia yang sedang berdiri –seorang wanita. Mengejutkannya, wanita itu adalah DIA! Wanita yang selalu bersamanya. Wanita yang bersamanya mengucap janji satu tahun lalu. Wanita paling sabar yang pernah dia temui. Tapi, orang sabar yang marah akan lebih mengerikan dari seorang pemarah yang marah, seperti beberapa hari yang lalu. Saat wanita itu melemparnya dengan vas.
”Bunuh aku.” Alvin menjatuhkan kembali pistol itu, pasrah. Kesunyian kembali menyelimutinya. Bahkan suara gesekan kecil dapat dia rasakan. Gesekan dari bergeraknnya pelatuk pistol. Sebuah sengatan sempat dia rasakan.
”Tamat.”
Alvin membuka matanya. Dimulai dari segaris tipis. Dia terbangun dari tidur panjangnya. ”Apa? Siapa itu?”
”Sudah tamat. Aku membaca novel sampai tamat untuk menunggumu bangun.”
Sesosok wanita duduk di sampingnya. Sekali lagi dia bertemu dengan seseorang yang tak dikenalinya. Lebih aneh lagi, dia masih hidup! Ia masih di mobil yang sama. ”Seharusnya aku sudah mati.”
”Kenapa sih, ada saja orang yang tidak menikmati hidupnya?”
”Apa? Tidak. Aku bukan tipe bunuh diri. Maksudku, seseorang telah membunuhku.”
”Mimpi buruk. Itu sering terjadi.”
”Jam berapa sekarang?”
”Lihat ini!” Wanita itu menyodorkan lengannya yang berhias jam tangan mewah. 11:03. Sudah lama sejak terakhir dia sadar.
”Kau orang misterius ketiga yang kutemui hari ini.”
”Hm?”
”Wanita yang kutemui tadi ada hubungannya dengan pembunuh...” Sesuatu menyangkut di pikiran Alvin. ”Oh, tidak!” Kedua tangannya meremas kepalanya sendiri. ”Katakan! Apa ada pembunuhan yang terjadi hari ini?”
”Entahlah. Aku tidak tertarik dengan berita seperti itu.”
”Katakan, di mana posisi kita!”
”Kenapa kau jadi memaksaku? Ayo, sebaiknya kita ke tujuan kita!”
Alvin menginjak gas dan membanting stir, berputar seratus delapan puluh derajat.
”Eh... eh... eh...” Wanita itu berusaha mempertahankan posisinya meski sabuk pengaman telah siap melindungi.
Gang elit menjadi tujuannya. Di sana, rumah-rumah dengan bentuk sama tertata rapi. Satu rumah dengan rumah lain berbatas pagar alami. Harmonis. Di antara banyak rumah itu, satu rumah menjadi tujuan khususnya. Dia berhenti tepat di depannya.
Dia membuka pintu rumah. Ada seorang wanita, tapi bukan yang dia inginkan. Dia adalah wanita pertama yang dia temui hari ini. ”Kenapa kau di sini? Kau pasti bekerja sama dengan si...”
Seseorang muncul dari balik tirai hijau. Itu adalah dia. Wanita yang ingin ditemuinya. Tak ada kata-kata yang dapat diluncurkan. Alvin membeku. Seolah dia sedang terbawa arus sebuah teater indah. Dia berjalan pelan sambil mencoba memahami apa yang terjadi. ”Arini...” Dia memandang seperti melihat hantu.
Wanita itu, Arini, hanya tersenyum tipis.
Alvin mempercepat langkah, memeluk erat kekasihnya itu. Arini balas memberi pelukan. Keduanya secara tak langsung sepakat untuk bersama lagi. Sepercik api yang tersisa kini benar-benar padam.
”Arini!” Suara seorang pria memecah perasaan Alvin. Pria itu muncul dari balik tirai hijau, sama seperti Arini.
Meski sebenarnya tidak, Alvin merasa mengenalinya. Bukan dari mukanya, melainkan suaranya. Suara itu pernah membuat hidupnya hampir berakhir. Alvin menatapnya seperti bagaimana dia menatap Arini. ”Kau... suara itu...”
”Dia kakakku.” kata Arini.
”Apa maksudnya?”
Arini tersenyum licik yang indah. “Kau masih orang baik seperti yang kutemui dulu.”
Alvin tersenyum. Permainan ini tak sesulit seperti dalam pikirannya dan dalangnya tak sejahat yang ia bayangkan.


 Arsyadmdz
Arsyadmdz