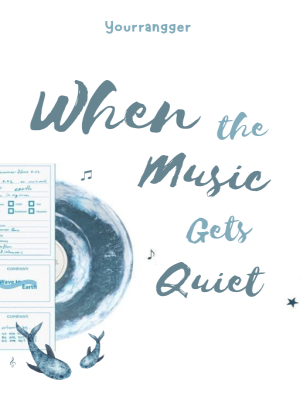“POLISI!”
Semua anak berseragam putih abu-abu yang tadinya adu jotos di persimpangan jalan, mendadak buyar sendiri-sendiri, seiring terdengarnya sirine kendaraan kepolisian yang meraung-raung memberi sinyal tanda bahaya.
Hera, gadis berambut hitam yang berdiri di barisan terdepan SMA Pancasila, tidak menghiraukan itu. Di tangannya masih tersimpan batu berukuran besar yang dibungkus plastik hitam. Lalu, dilemparkannya benda tersebut, entah mengenai siapa. Dalam tawuran seperti ini tidak kenal kawan atau lawan, tidak ada yang bisa menjamin kamu tak akan terkena pukulan oleh teman satu sekolahmu sendiri. Terlalu banyak orang di sini dan semuanya sibuk menyerang, entah siapa yang kena pukul tak ada yang peduli. Hal terpentingnya adalah, kelompokmu menjadi pemenangnya, perkara kamu terluka itu jelas bukan urusan bersama.
Hera tidak menyediakan asuransi kesehatan untuk teman-teman yang mukanya sudah mengalahkan korban kekerasan di televisi.
“Her! Cabut!” Leo yang sudah nangkring di atas sepeda motor besarnya memanggil gadis itu. Dia menoleh sesaat lalu berlari secepat mungkin. Namun sayang, sepertinya Leo memilih lokasi yang salah untuk parkir. Polisi muncul dari arah berlawanan, membuat massa kebingungan.
“LO BALIK DULUAN SAMA YANG LAIN!” teriak Hera, berlari ke arah lain di persimpangan.
Jalanan macet total siang itu, di tengah sinar matahari yang terik membakar kerongkongan, ratusan kendaraan terjebak macet. Tidak ada yang berani menghentikan perkelahian dua kubu: SMA Pancasila dengan SMA Perkasa. Sudah menjadi rahasia umum jika kedua sekolah yang sebetulnya bergengsi itu memiliki dendam pribadi.
Hera menyelinap, mengenakan jaket hitamnya rapat dan menutup kepala sambil berusaha bersikap tenang. Dengan langkah besar, dia melewati barisan kendaraan dan para penumpang yang saking penasarannya sampai turun ke jalanan, tapi tidak berani mendekat.
“Mereka menyedihkan sekali,” gumam Hera
Sebagian orang selalu saja bersikap memalukan. Mereka jauh lebih suka melihat perkelahian, memotret, memajangnya di media sosial tanpa berniat membantu menyelesaikan. Terkadang, Hera suka mengamati keadaan di sekitarnya, berpikir, dan menganalisis. Meskipun dia berandalan, tidak lulus UN berulang kali, perokok sekaligus pemabuk berat, tapi sebetulnya dia jauh lebih baik dari orang-orang yang memandangnya sebelah mata.
Setidaknya dia tidak harus berpura-pura baik, mengomentari tanpa memberi contoh atau kebanyakan menuntut seperti mereka. Dia hanya gadis biasa, menikmati masa muda sekaligus terjebak di masa lalunya.
Semua yang Hera alami, telah membentuk karakternya menjadi sosok yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah seperti dahulu. Dia tidak sudi menangisi orang yang salah atau malah menjadi orang yang terlalu lemah.
Dirogohnya sebatang rokok dari saku celana dan menyalakannya. Asap putih mengepul ke udara. Mungkin mengganggu, tetapi mas-mas di sebelahnya malah menatap gadis itu heran. Bukan karena anak sekolah merokok sebab itu sudah biasa, tetapi mungkin wajah cantiknya. Sejujurnya dia lebih cocok disebut model majalah dengan paras cantik dan tubuh seksinya, tapi Hera tak akan melakukannya. Usianya hampir dua puluh tahun ini, masih kelas dua belas SMA, dan berkecukupan. Tinggal menggesek kartu, puluhan bahkan ratusan lembar uang seratus ribuan mengalir begitu saja. Hanya saja, bukankah ada pepatah yang mengatakan jika uang bukan segalanya?
Jika ada yang mengatakan itu omong kosong, berarti kamu adalah orang yang tak bahagia karena kekurangan dana. Namun, Hera berbeda; mamanya kaya raya, tidak pelit apalagi melarangnya meminta. Hanya saja, Hera tak pernah merasakan apa itu keluarga. Semuanya sudah hancur sejak perceraian Salma dan Hardi ketika usianya menginjak tujuh belas tahun.
Menyiksa! Benar-benar melukai perasaannya.
“Polisi?”
Hera agak kaget ketika melihat beberapa orang petugas mencari dirinya. Hera jelas tidak mau masuk kantor polisi. Bukan karena takut, tetapi dia sudah bosan saking seringnya tertangkap ketika tawuran. Mending kalau setiap kali ditangkap langsung dipenjara dalam waktu lama. Nah ini, pakai acara dibela pengacara mamanya. Bahkan Salma sendiri seperti tidak memedulikannya.
Dia mempercepat langkah, membuang puntung rokok ke selokan lalu mencari tempat persembunyian. Namun sayangnya, mereka melangkah terlalu cepat.
“Anda tahu anak perempuan berseragam SMA yang lewat sini?” Salah satu dari Polisi bertanya kepada orang di pinggir jalan.
“Tadi jalan ke arah utara, Pak.”
Sialan! umpat Hera yang sedang berada tak jauh dari mereka. Dia berlari, membuat mereka harus kucing-kucingan seperti dalam adegan film action produksi Hollywood. Namun, latarnya bukanlah jalanan indah di Eropa, hanya jalanan macet dan becek sisa hujan di kota Jakarta yang sumpek dan menyesakkan. Dan yang namanya melawan polisi, mereka sudah terlatih untuk menghadapi masalah seperti ini. Ujung-ujungnya dia ditangkap juga.
***
Di dalam kantor polisi Hera duduk menunggu Bram yang datang dua puluh menit kemudian. Lelaki berambut tipis itu menenteng tas hitam di tangan kiri, menyalami polisi lalu duduk di samping kanannya.
Seperti biasa, setelah pembicaraan alot akhirnya Hera hanya ditahan dua malam. Tidak lama, sebab masih banyak pertimbangan. Bram memang pengacara yang sangat andal dan bisa diandalkan. Sebelum pulang, dia mengantar Hera masuk.
“Kenapa kamu selalu saja seperti ini, Hera?” tanya Bramsudah kelelahan menghadapinya.
“Siapa yang ngasih tahu lo kalau gue ada di sini tadi? Dan dibayar berapa lo sama Mama untuk membela gue?” Tatapan mata Hera tajam dan menusuk.
Lelaki itu terperanjat, jelas-jelas kaget mendengar gadis muda seperti Hera bicara kasar. Namun, Bram tersenyum, dia paham apa yang Hera rasakan. Marah dan merasa tak dibutuhkan oleh Salma, ibu kandungnya.
“Aku membelamu bukan hanya karena uang, tetapi juga karena aku peduli kepadamu, Hera. Aku empati melihat keadaanmu yang merusak diri sendiri macam ini setiap hari. Kenapa kau tidak berhenti saja membuat ulah, hidup tenang dan memikirkan ujian sehingga bisa lulus tahun depan?”
“Lo meledek gue?”
Bram tersenyum lagi. “Tentu saja tidak, Hera.”
“Dengar ya, Bram! Lo boleh nggak membela gue kalau sudah bosan karena gue nggak butuh rasa kasihan dari siapa pun termasuk juga lo.” Hera bersungguh-sungguh.
“Jangan bertindak seperti ini,” kata Bram. “Baiklah, aku akan pulang. Lusa aku akan menjemputmu keluar dari tempat ini. Jika kamu butuh apa-apa jangan sungkan untuk menghubungiku, aku pasti datang secepat mungkin.”
Setelah Bram pulang Hera digiring masuk ke sel tahanan perempuan untuk menginap dua malam ke depan. Terhitung sore ini tentu saja.
Baginya ruang tahanan bukan lagi momok menakutkan karena dia sudah hafal hampir semua penghuninya. Mereka berteman baik, akrab, dan tidak semenyeramkan yang dia pikirkan di awal ketika sudah berada di dalam. Hanya saja tindak kriminal seperti apa pun tetap tak bisa dibenarkan meskipun berkelit dibalik sejuta alasan.
“Baru dua bulan lalu keluar sekarang sudah masuk lagi!”
Bu Ita, teman satu selnya geleng-geleng. Beliau masuk tahanan karena ketahuan mencopet untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Suaminya tidak bertanggung jawab dan lari dengan wanita lain. Dia jelas tidak mau melakukannya, hanya saja terpaksa.
“Berapa malam?” Yang di sebelahnya bernama Viona, dia mantan penyanyi jalanan yang entah kenapa juga digelandang ke ruangan ini.
“Dua.”
Hujan turun lumayan deras, Hera bisa merasakan udara yang dingin menusuk tulang. Lantai penjara terasa menyiksa dan ini bagian yang paling tidak dia suka. Namun, kalau dipikir-pikir, bukankah selama ini dia memang terpenjara? Terpenjara dalam diri dan keputusasaannya sendiri. Jauh lebih menyedihkan. Mamanya di Jepang sejak bulan lalu, entah kapan akan pulang. Tidak ada yang tahu. Salma berhak melakukan apa pun yang dia suka. Mungkin dia sudah lupa jika masih memiliki Hera. Itulah alasan kenapa Hardi menduakannya lalu memilih jalan perceraian untuk mengakhiri rumah tangga mereka.
Hera benci mamanya. Kenapa Salma tidak bisa bersikap seperti seharusnya seorang ibu? Paling tidak agar Hera merasa memiliki keluarga walaupun dia jelas-jelas sendirian.
Dua malam di dalam sel terasa melelahkan dan akhirnya hari pembebasan pun datang. Bram menjemput dan mengantarnya pulang pagi itu. Di depan gerbang rumah, Mbok Mah menunggunya dengan cemas.
“Neng Hera kenapa nggak pulang berhari-hari? Mbok khawatir banget,” katanya.
“Memangnya Bram nggak bilang?” Hera melirik mobil Bram yang memelesat meninggalkan kediamannya.
Mbok Mah menggeleng.
“Terus Mama telepon nggak, Mbok?”
“Ibu sih nggak telepon, cuma dua hari lalu orang kantor nyuruh Mbok menyiapkan kamar beliau. Katanya, Ibu pulang seminggu lagi.”
“Oh.” Wajah Hera kecewa sekali.
Hera tahu, berharap mengenai sesuatu yang jelas tidak boleh dilakukan sangat menyakitkan. Akan tetapi sebagai seorang anak, apakah salah bila dia mengharapkan sedikit saja perhatian dari orang tua kandungnya sendiri?
Setelah mandi, sarapan dan berganti pakaian Hera menuju meja makan. Mbok Mah sudah memasak telur dadar dan nasi goreng pedas kesukaannya. Dengan rambut basah dibungkus handuk warna biru, dia duduk di kursi kayu menghadap piring. Hidungnya mencium aroma makanan.
“Kayaknya enak banget nih, Mbok.”
“Terima kasih.” Mbok Mah menaruh segelas air di depannya. “Mau berapa banyak?”
“Banyak, Mbok. Aku lapar banget. Di kantor polisi masakannya nggak enak.”
Mbok Mah kaget mendengar apa yang baru saja Hera katakan, lalu menatapnya tak percaya. “Neng Hera ditangkap polisi lagi?”
Wajahnya berubah muram dan kecut. “Iya.”
“Ada masalah apa lagi, Neng?” Mbok Mah prihatin dan memilih duduk di sebelahnya.
“Biasa, Mbok. Memang apa lagi?”
“Berantem?”
Mbok Mah sendiri bingung kenapa anak majikannya yang sudah dia rawat sejak masih bayi itu berubah drastis semenjak naik kelas tiga SMA. Hera dulu pintar dan penurut, tetapi entah kenapa bisa tidak lulus UN berkali-kali. Aneh memang, tetapi semua bisa berubah, bukan?
“Ya, sudah. Neng makan nasi gorengnya, biar Mbok buatkan pisang goreng dulu di belakang.”
“Nggak usah, Mbok!” katanya menghentikan langkah Mbok Mah sebelum sampai di dapur. “Setelah sarapan aku mau langsung keluar. Ada urusan.”
Sarapan buatan Mbok Mah memang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan masakannya. Bahkan mamanya saja yang katanya memiliki bisnis restoran paling besar di Bali, tak ada apa-apanya. Salma hanya bisa berbisnis, tidak untuk keluarga.
Hera meminum segelas air menutup sarapannya, lalu mendorong kursi ke belakang. Dia akan menyisir rambut basahnya yang sudah agak mengering, berganti pakaian dan pergi secepatnya. Dia tidak betah berlama-lama di rumah.
Sejak Hera masih kecil, mamanya tidak pernah ada di sisinya, lalu apa salahnya jika dia juga memilih jalan yang sama? Mereka memang dua orang yang jauh berbeda dan tak seharusnya hidup bersama.
Motor CB hitam Hera meninggalkan gerbang dengan suara meraung-raung merusak telinga, hingga membuat beberapa sekuriti di depan gerbang perumahan hanya bisa geleng-geleng. Mereka sebetulnya pernah menegur Hera, hanya saja tak dihiraukan olehnya. Lagi pula mereka juga terlalu takut kepadanya. Hera pernah membuat salah satu dari mereka babak belur dengan sekali pukul. Heran juga, sebetulnya punya ilmu apa dia.
Dengan kecepatan tinggi, Hera melajukan motor kesayangannya di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Sejujurnya dia tidak pernah suka berkendara seperti ini. Hanya saja, makin cepat dia mati akan jauh lebih baik. Setidaknya jika dia tewas karena kecelakaan maka tak perlu lagi repot-repot bunuh diri.
Hera berhenti di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan. Tangan kanannya merogoh saku celana lalu menemukan sebatang nikotin. Dia menyalakan ujungnya, menghirup lewat mulut lalu membuang sisanya lewat hidungnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari merokok tanpa ada yang melarangnya. Masa bodoh dengan kesehatan. Hera bahkan sudah tidak peduli apabila dia akan mati besok pagi.
“Hera, akhirnya datang juga lo.”
Hera memandang Reza yang tersenyum kepadanya, lalu memutuskan duduk di depannya cuek. “Nggak usah buang-buang waktu lagi. Mau lo apa?”
“Santai, Her! Jangan tegang begitu! Lo pesan minum dulu deh, nanti gue yang bayarin,” jawab Reza.
“Memang lo kira gue butuh duit lo?”
“Jangan nyolot begitu dong, Her. Gue nggak punya maksud apa-apa kok. Beneran.”
Hera menghela napas kasar. “Intinya kenapa lo minta ketemu di sini? Langsung saja ngomong sekarang atau gue akan pulang.”
“Iya... iya ....”
Reza sendiri adalah anak SMA Perkasa. Ketua mereka tepatnya, yang berarti musuh terbesar Hera. Rival. Setahu Hera, sejak masih kelas sepuluh sampai hari ini, Reza memang berambisi menjadi ketua kelompoknya. Akhirnya, mereka bisa berhadapan sebagai lawan yang seimbang.
“Kemarin teman gue ada yang luka parah.” Reza menatapnya serius.
“Lalu?”
“Siapa teman lo yang bawa pisau? Dia terluka karena itu. Kalian sudah menyalahi perjanjian awal kita untuk tidak memakai benda tajam.”
Hera tersenyum mengejek. “Nggak salah?” Pandangannya sangat merendahkan. “Setahu gue pihak kalian sendiri yang selalu melanggar perjanjian kita. Bahkan tawuran kemarin juga gara-gara kalian mengeroyok Deo sampai masuk rumah sakit, kan? Za, masalah lo itu sama Deo. Masalah pribadi kalian yang rebutan Nia. Jadi selesaikan berdua, jangan main keroyokan. Lalu siapa yang salah di sini sebetulnya?”
Reza memanas, dengan tangan mengepal dia memandang wajah kaku Hera Almira. Kalau tidak mengingat ini tempat umum dan Hera masih berwujud perempuan, maka sudah dia pukul sejak tadi. Namun, dia menahannya. Bagaimana pendapat masyarakat tentangnya jika mereka tahu ada seorang laki-laki berbadan kekar memukul perempuan?
“Lo jangan asal ngomong kalau nggak tahu apa-apa. Harusnya lo bilang ke Deo, nggak usah nyari masalah ke gue kalau nggak mau berakibat fatal.”
“Lo berani memerintah gue?” Pandangan Hera menusuknya tajam. “Dengar ya, Za! Gue nggak peduli! Dari awal kan gue sudah bilang kalau gue nggak peduli sama urusan kalian, tapi gue nggak suka sama sikap pengecut lo.”
Wajah Reza memanas dengan tangan membentuk kepalan siap menyerang.
Hera yang melihatnya hanya tersenyum sinis dan tenang. “Kenapa, Za? Emosi? Mau marah? Atau malah mau memukul gue? Silakan!”
Perlahan Reza mengendurkan telapak tangannya, lalu menarik napas berulang agar lebih tenang. “Awas saja lo, Her!” katanya sebelum akhirnya pergi meninggalkan Hera di meja restoran cepat saji tersebut.
Hera terkekeh. Benar-benar konyol. Siapa yang mengundang tapi malah siapa yang pergi dengan emosi?
***
“Her, gawat!” Hera yang sedang menonton televisi kaget ketika mendapat telepon dari Damar. “Gawat banget! Lo harus ke sini sekarang! Cepat, Her!”
“Lo kenapa, Mar?” tanyanya bingung. “Kalau ngomong yang jelas!” lanjutnya berdiri dari kursi, sambil memasukkan potongan buah mangga ke dalam mulut dan menelannya.
“Itu, Her... pokoknya gawat deh.”
“Ck.” Hera menghela napas kasar, tidak habis pikir kenapa temannya itu bicara tidak jelas dan menjadi panik. Tapi secara teknis Damar memang selalu panik dalam menghadapi masalah. Namun, yang perlu diacungi jempol adalah dia begitu setia kawan. Jangan-jangan dia berulah lagi. “Leo mana? Gue mau ngomong sama dia.”
Tidak lama kemudian terdengar suara Leo di seberang.
“Halo, Her. Lo di mana?” tanya Leo dengan suara yang jauh lebih enak didengar ketimbang Damar.
“Gue di rumah,” jawabnya. “Ada apa? Kenapa Damar panik banget kayak begitu?”
Leo seperti sibuk berbicara dengan orang lain. Entah bagaimana, suasana di seberang telepon benar-benar tidak baik. Hera bisa mendengarnya dengan jelas dari sini.
“Yo!”
“Iya, Her. Suasana di sini kacau. Ada anak kelas sepuluh yang diculik sama anak Perkasa.”
“Apa?” Hera langsung naik pitam. “Kok bisa?”
“Mereka datang setelah bel pulang sekolah. Reza menculik anak yang lagi menunggu jemputan di halte.”
“Kurang ajar, Reza!” umpatnya. “Ya sudah, sekarang lo kumpulkan anak-anak dan kita berangkat bareng dari markas. Gue ke sana sekarang.”
“Baik, Her.”
“Yo, yang diculik hanya satu anak, kan?”
“Iya.”
Tidak ada yang tahu apa sebenarnya mau Reza. Dia benar-benar pengecut karena berani-beraninya menjadikan perempuan sebagai sandera. Dengar! Hera tidak akan pernah membiarkannya lolos kali ini. Dia sangat emosi.
Diambilnya kunci sepeda motor yang digantung di dinding, mengenakan jaket kulit warna hitam kesayangannya, sepatu boots senada, serta mengikat asal rambut panjangnya yang berantakan. Motornya melaju dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya menuju markas mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Lama-lama dia seperti dipermainkan. Seperti belum mengenalnya saja kamu, Reza.
Seharusnya berpikirlah dahulu sebelum bertindak dan mengambil keputusan.


 nandreans
nandreans