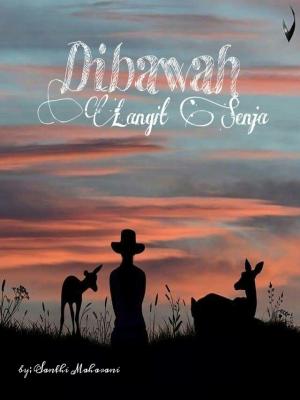Iago bersandar pada sisi samping mobilnya. Ara menghentikan langkah, mengamati cowok itu dari jarak sepuluh langkah, sembari pelan-pelan mencoba mengubah pandangannya pada Iago. Rasanya tetap saja sulit, sebab kesan negatif di awal pertemuan mereka sudah terlanjur terpatri di benaknya. Jadi sekalipun Ara berkata akan memikirkannya, bukan berarti dia setuju. Semua ini tak semudah membalikkan telapak tangan.
Setelah menghela napas dalam-dalam, Ara bergegas menghampiri Iago. Dia kira cowok itu akan menyambutnya dengan antusias, tapi ternyata tidak. Cowok itu cuek-cuek saja. Sepasang AirPods menyumpal kedua telinganya, sementara kepalanya agak menunduk, entah apa yang dilihat atau dipikirkannya.
Merasa gemas, Ara mencabut salah satu AirPods dari telinga Iago, membuat cowok itu tersentak kaget. “Gue kira lo nggak bakal dateng,” sambut Iago datar.
Mata Ara menyipit.
“Hobi lo kan kabur dari gue,” lanjut Iago.
“Ck—”
“Pasang di telinga lo kalau lo mau tahu lagu apa yang gue dengerin tadi pagi,” potong Iago, dia melepas AirPods yang satunya lagi dan memberikannya pada Ara. Iago lalu mengeluarkan ponsel dari saku celananya untuk memutar ulang lagu yang dimaksud dari awal.
Mulanya Ara enggan, meski pada akhirnya dia memasang benda berwarna putih itu di kedua telinganya. Suara petikan gitar yang berpadu dengan dentingan kibor di awal lagu langsung menarik perhatiannya. Disusul dengan suara serak dari seorang pria yang menyanyikan bait pertama. Setelah bait pertama usai, barulah terdengar gebukan drum.
Tanpa sadar kedua mata Ara terpejam, larut dalam lagu yang didengarkannya.
And one day we will find a way toward this distant golden age
The cries of war will sound the day
We stand before the dawn of a new world
Usai mendengarkannya, Ara membuka mata dan mendapati Iago sedang berjongkok di sebelahnya. “Baru tahu gue kalau ada lagu metal yang enak didengerin kayak gini. Gue pikir lagu-lagu metal bakalan bikin kuping gue budek,” komentarnya. “Terus, gue juga baru tahu ternyata lo penggemar genre musik yang penyanyinya om-om gitu.”
Iago menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. “You get one more point.”
“Lo ngomong apa sih?” Ara bersedekap dengan tampang sebal. “Gue bilangnya apa, lo nanggepinnya gimana....”
“Barusan lo tahu kalau gue penggemar musik metal,” balas Iago. Cowok itu berdiri di hadapan Ara. “Masih banyak hal tentang gue yang lo nggak tahu.”
“Emang iya.” Ara mengangguk setuju. “Dari yang pernah gue baca di majalah yang ada di lobi kantor Papa, yang waktu itu memuat profil keluarga lo, lo itu perfect banget. Satu-satunya anak laki-laki keluarga Kresna, tajir, ganteng, pinter.... Well, kali aja Nia Ramadhani seumuran lo, dia pasti bakal milih lo daripada suaminya sekarang.”
Iago nyengir.
“Sayang banget kenyataannya nggak gitu,” imbuh Ara.
Embusan napas pendek lolos dari bibir Iago. Ekspresinya terlihat seperti ingin menanyakan sesuatu, walau realitanya tak satu pun kata yang terlontar.
“Lo kasar, nuduh sembarangan, suka maksa—”
“Sori,” serobot Iago menghentikan kalimat Ara. “Malam itu gue yang salah. Gue.... Eh, lo beneran nggak denger apa-apa, kan?”
Dengan santainya Ara menjawab, “Dengerlah! Orang gue punya kuping dan nggak budek!”
Iago terbelalak.
“Tapi cuma sepotong-sepotong,” sambung Ara. “Seperti musik, bisnis, sekolah, dan nggak tahu apa lagi. Gue udah coba merangkai semua kata yang gue denger, tapi nggak berhasil jadi kalimat yang cocok.”
“Oh....” Iago mengembus napas lega.
Sayangnya itu tidak bertahan lama karena Ara bertanya, “Lo waktu itu ngomong apa sih?”
Cowok itu terdiam cukup lama, membuat Ara mengerti bila obrolan Iago di telepon saat itu bukanlah sesuatu yang ingin dibaginya dengan orang lain. Bahkan malam itu Iago sampai mengancamnya.
“Nih,” Ara mengembalikan AirPods milik Iago, “anterin gue pulang gih!”
Tanpa kata Iago membukakan pintu mobil untuk Ara. Setelah mereka berdua berada di dalam, Iago baru membuka omongan, “Bokap gue nggak suka gue main musik, padahal waktu itu gue main juga karena Teguh nggak bisa dateng. Nggak lucu kan, kalau band sekolah kita yang penampilannya ditunggu-tunggu malah nggak jadi tampil.”
Ara menyimak dengan antusias.
“Terus gue ngancam kalau bakal sebarin kelakuan bokap gue yang doyan bawa cewek ke rumah itu ke media massa.” Iago nyengir. Tak ada tanda-tanda penyesalan atau rasa malu, malahan raut wajah cowok itu terlihat lega. “Otomatis image jelek itu bakalan berimbas ke semua bisnisnya. Dan akhirnya kami bertengkar. Bokap marah, gue marah,” lanjutnya.
“Tapi kalau lo bongkar kelakuan bokap lo, image lo juga bakalan ikut rusak.”
“Lo pikir gue peduli? Image nggak bisa bikin lo kenyang, Ra, apalagi bahagia!”
Ara meneguk ludah, agak-agak tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ini adalah kali kedua Ara mendengarkan cerita tentang Iago. Parahnya, semua cerita yang terucap dari mulut cowok itu sangat kontras dengan yang selama ini dipublikasikan.
“Makanya gue minta tolong sama lo,” kata Iago lagi. “Lo boleh kok minta nyawa gue sebagai bayarannya. Gue rela. Asalkan lo nolongin gue dulu.”
“Lo nggak bercandain gue, kan?”
Iago menyeringai. “Gue pengin. Tapi sayangnya hidup gue bukan panggung OVJ yang ngelawak melulu.”
Ara sempat tertawa kecil mendengarnya. Namun detik berikutnya berubah menjadi hening. Semakin banyak Ara mengetahui tentang Iago, rasa simpatinya semakin membengkak. Ini salah, tak seharusnya Ara peduli pada cowok itu. Lalu kenapa dia seolah tidak mampu mengabaikan Iago? Padahal di sisi lain Ara masih harus mencari cowok berkekurangan cinta untuk menyelamatkan hidupnya sendiri.
“Dari kecil gue tahu kalau gue ini spesial. Nggak ada bedanya gue sama putra mahkota. Papi, Mami, dan kakak-kakak gue memperlakukan gue dengan spesial.” Iago berbicara lagi. “Tapi lama-kelamaan, gue mulai ngerasa kalau ada sesuatu yang berbeda. Ketika gue ngelihat temen-temen gue yang bebas, temen-temen gue yang punya mimpinya sendiri, gue jadi tahu apa itu yang disebut terkekang. Yah, gue nggak bisa bebas menentukan tujuan hidup gue sendiri. Dan di saat Papi tahu, ada sesuatu yang gue suka, tapi nggak sesuai dengan rencananya, Papi bakal nentang gue.”
Ara masih tak merespons, otaknya masih sibuk memproses apa yang didengar oleh telinganya. Sekali pun, tak pernah terbayangkan oleh Ara jika dia akan bersedia mendengarkan cerita-cerita Iago. Dan nyatanya, di sinilah Ara sekarang, diam dengan saksama mendengarkan apa pun itu tentang Iago.
“Waktu masih kecil, gue cuma bisa memendam semuanya. Tapi sekarang, gue udah nggak mampu ngelakuin itu lagi. Ruang kesabaran gue udah penuh, gue harus putar otak biar bisa lepas dari kendali bokap gue,” lanjut Iago lagi.
Ara menoleh, mencoba bersuara, “Go—” Kalimatnya macet saat bersitatap dengan Iago. Raut wajah Iago biasa-biasa saja, tapi entah kenapa Ara bisa merasakan kalau cowok itu sebenarnya tengah kesakitan sendiri.
“Selain kakak-kakak gue, lo adalah orang luar yang pertama tahu soal kebusukan bokap gue. Jadi harusnya lo ngerasa spesial,” ucap Iago pelan. “Lo boleh jual informasi yang lo denger kok kalau lo butuh duit asalkan lo mau nolongin gue.”
“Apa?!” Ara tercengang, tak menyangka Iago menilainya seperti itu.
Kalimat Iago itu tentu melukai harga diri Ara, padahal baru saja dia merasa simpati pada cowok itu. Serendah itukah dirinya di mata Iago?
“Informasi itu nggak penting buat gue,” sinis Ara.
“Oh ya?”
Ara mengangguk ketus. “Karena lo juga bukan orang yang penting buat gue.”
Iago berpaling. Dadanya bergemuruh. Gelisah. “Gue anter lo pulang.”
*


 sandrabianca
sandrabianca