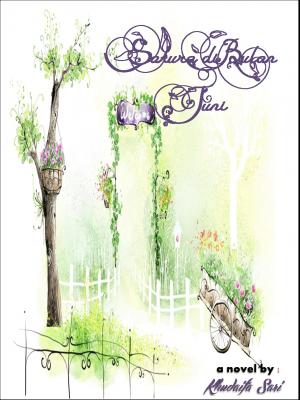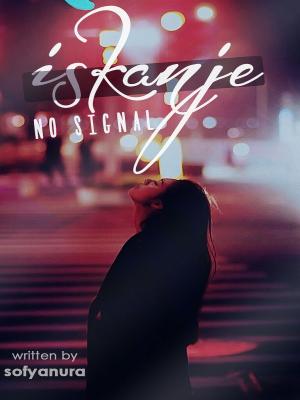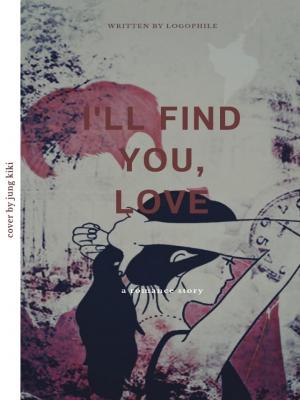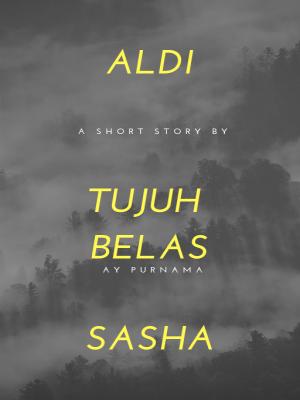Pagi ini tak seperti pagi-pagi sebelumnya. Di luar suram, awan abu-abu gelap yang menggantung di langit menandakan bila tak lama lagi akan turun hujan. Belakangan ini cuaca di seluruh penjuru daerah di Indonesia memang tidak bisa diprediksi. Bulan-bulan yang seharusnya menjadi musim hujan, malah berubah menjadi seperti musim kemarau, begitu juga sebaliknya.
Alam menjadi seperti ini karena adanya hukum sebab akibat, itu bisa diterima. Namun, bagaimana dengan takdir yang dengan seenaknya menuntut keseimbangan atas semua cinta yang diterima Ara? Dari lahir hingga detik ini, Ara tidak pernah meminta untuk menjadi orang yang dikelilingi oleh cinta. Semua itu berada di luar kendalinya. Lantas jika dirinya tidak pernah meminta, kenapa semesta harus menuntut sesuatu darinya?
“Lama-lama gue bisa gila beneran,” rutuk Ara.
Belakangan ini suasana hatinya selalu dirundung awan mendung. Kelabu. Rentetan kejadian yang dialaminya betul-betul membuatnya resah—dan takut. Pernah Ara berpikir jika semua ini hanyalah mimpi, sayangnya meski dia telah tidur dan terbangun berkali-kali, kenyataannya tetap sama. Ramalan itu terus saja menghantui.
Tatapan Ara beralih pada plester di lututnya. Plester itu hampir lepas karena terkena air sewaktu mandi tadi. Dengan kasar, Ara merenggut plester itu hingga lepas dan melemparkannya sembarangan. Setelahnya, Ara menyambar tas sekolah dan keluar dari kamar tanpa menutup pintu.
Di ruang makan, kedua orangtua dan kedua kakaknya sudah berkumpul untuk sarapan. Papa pernah bilang jika ruang makan adalah tempat paling penting dalam sebuah rumah. Karena ketika kita makan dan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga, kita bisa saling bertukar cerita. Maka dari itu keluarganya memiliki sebuah aturan bila sarapan harus dilakukan di rumah.
Kebersamaan adalah bahan bakar untuk memulai hari-harimu yang melelahkan.
“Kok tumben baru turun?” tanya Mama. Wanita yang sudah rapi dalam balutan baju kerjanya itu mengamati wajah anak perempuannya. “Kamu sakit? Kelihatan nggak semangat banget.”
“Cuma kurang tidur, Ma,” jawab Ara sambil menyendokkan nasi goreng ke piringnya.
Kak Marcel berhenti makan dan menanyai Ara, “Lo semalam kenapa pulang naik ojol? Bukannya si Alan yang harusnya nganter?”
Ara memutar mata. Dia paling malas kalau kakaknya sudah mulai mengitimidasinya. “Habis nonton basket sama Alan, Ara mampir ke rumahnya Vika dulu, Kak.”
“Alan?” Papa menyipit pada Ara. “Pacar kamu?”
“Bukan, Paaa....”
“Pacar juga nggak apa-apa. Kamu boleh kok pacaran asal arahnya positif,” timpal Mama.
“Ma, Pa, Kak,” Ara menatap anggota keluarganya satu per satu, “Ara nggak pacaran sama siapa-siapa. Alan itu cuma teman Ara.”
“Kok gue nggak percaya.” Kali ini Kak Marvel yang bersuara.
“Ya itu terserah Kakak,” balas Ara tak acuh kemudian menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulutnya.
Selanjutnya topik beralih pada Kak Marvel yang indeks prestasinya menurun dibandingkan dengan semester lalu. Mama mulai mengomel, sementara Papa mencoba menasihati.
“Papa nggak pernah maksa, kamu sendiri yang memilih jurusan itu. Jadi kamu harus bisa bertanggung jawab sama pilihan kamu sendiri,” kata Papa. “Lagi pula Papa nggak pernah menuntut nilai sempurna. Tapi kalau nilai kamu bagus, itu juga bakalan berguna bagi masa depan kamu sendiri.”
“Ya, Pa,” sahut Kak Marvel.
“Ya udah, makannya buruan dihabisin biar nggak telat,” ujar Mama.
Selera makan Ara menguap. Hatinya mendadak sedih. Andai kata dirinya tidak bisa menemukan cowok itu, lalu dia mati ... apakah suasana sarapan akan tetap seperti ini?
Ara mencengkeram sendoknya. Nggak, gue nggak mau mati! Pokoknya gue harus bisa menemukan cowok itu.
“Hari ini Ara ke sekolahnya nebeng Mama ya,” pinta Ara pada Mama usai menuntaskan sarapan.
“Lho? Nggak bareng sama Vika?”
“Vika hari ini dijemput sama Dion. Monic bareng sama Brian.”
“Nanti kalau kamu udah punya SIM, Papa bakalan kreditin kamu mobil sendiri,” timpal Papa dari kejauhan.
Mendengarnya, Ara sontak melompat kegirangan dan menghambur untuk memeluk Papa. Awan kelabu yang sedari tadi menaunginya langsung berganti dengan langit biru cerah. “Beneran, Pa?”
“Iya. Makanya belajar yang rajin sana.”
“Yeyyy!!! Makasih, Pa.” Ara memeluk erat Papa. “Kalau gitu Ara mau bareng sama Papa aja.”
Mama mencebik. “Kamu ini gimana sih? Sekolah kamu kan nggak searah sama kantornya Papa.”
“Oh iya.” Ara cengengesan. “Kalau gitu ayo kita berangkat, Ma.”
Berhubung kelasnya terletak di gedung B, Ara meminta Mama untuk menurunkannya di gerbang belakang agar dia tidak harus berjalan jauh untuk mencapai kelas. Suasana sekolah terbilang sudah ramai karena hari ini Ara tiba lebih siang daripada biasanya.
Melewati area parkir, Ara mendapati mobil convertible putih yang terlihat paling mencolok di antara mobil-mobil lainnya. Keputusannya sudah bulat, dia akan mengabaikan Iago dan fokus terhadap pencariannya sendiri.
Rencananya, hari ini Ara akan mulai mendekati Jefrey, cowok dari klub drama. Sembari berjalan, dia memutar otak, apa yang sekiranya dapat dilakukan untuk mendekati cowok pemalu itu?
“Pagi, Ara....” Seseorang menyapanya.
Hendra.
“Pagi, Hendra,” balas Ara seraya melambai kecil.
“Tumben sendirian.”
“Iya, tadi berangkat bareng sama Mama.”
“Oh ya, nanti pas istirahat pertama kita rapat. Lo nggak lupa, kan?”
Ara menggeleng. “Nggak dong. Ntar gue ingetin Vika sama Monic. Eh, Dion juga ding!”
“Oke sip! Gue duluan ya, soalnya harus ngurus izin buat anak-anak futsal yang hari ini ikutan lomba.” Cowok itu berujar sembari berjalan mundur menjauhi Ara, seakan tidak rela berpisah dengan cewek yang selama setahun terakhir disukainya.
“Iyaaa. Jalan yang bener. Nggak lucu kalau pagi-pagi kepala lo udah kejedot tembok,” balas Ara setengah berteriak.
Hendra adalah cowok yang paling tidak ingin Ara sakiti. Ara nyaman-nyaman saja dengan hubungan mereka yang seperti ini. Jangan sampai hubungannya dengan Hendra rusak hanya karena ada perasaan lain yang melewati garis pertemanan. Itulah mengapa Ara keberatan ketika Vika dan Monic memasukkan nama Hendra ke dalam daftar cowok yang harus didekati. Lebih dari itu Ara yakin, perasaannya pada Hendra tidak akan berkembang lebih dari yang dimilikinya saat ini.
“Gue mau ngomong sama lo pas pulang sekolah nanti,” ucap sebuah suara di belakang Ara.
Ara spontan memutar badan, membuat sosok di belakangnya secara otomatis menabraknya. “Lo lagi, lo lagi! Lo itu demit apa orang sih?”
“Hah?”
“Muncul seenak udel. Gue kan kaget!” sembur Ara. “Untung jantung gue sehat.” Ara mengelus dada.
“Gue mau ngomong sama lo pas pulang sekolah nanti.” Iago mengulangi kalimatnya.
“Gue nggak mau!”
“Lo harus mau!”
“Pulang sekolah gue ada urusan.”
“Gue tunggu lo.”
“Urusan gue bakalan lama.”
“Gue tunggu lo sampai urusan lo kelar.”
“Arghhh!” Ara kesal setengah mati. Ingin rasanya dia menendang cowok—yang lagi-lagi mengenakan hoodie putih—itu jauh-jauh. “Eh, lo dengerin gue baik-baik ya.... Gue. Nggak. Mau.” Lalu Ara berbalik dan berlarian kecil meninggalkan Iago.
Iago yang tak mau kalah nekat meneriaki Ara, “Gue tetep nungguin lo!”
“Terserah!” balas Ara yang suaranya tenggelam bersamaan dengan bunyi bel masuk.
Mendadak, perasaan itu muncul lagi. Tak hanya soal ramalan, Iago pun turut membawa awan kelabu baginya.
*


 sandrabianca
sandrabianca