Kak Roni sedang menerima telepon sambil sibuk membolak balik buku catatan daftar pelanggan -yang biasa dia sebut buku agenda. Aku sedang bercengkrama ringan dengan Zacky, fotografer yang sudah bekerja empat tahun untuk Kak Roni. Usia kami nyaris sama. Nama Zacky itu telah melekat padanya sejak hari pertama bekerja. Kak Roni yang memberikan nama itu secara spontan sebab terkejut saat dia memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya Zakar, Zakardi.
Wajah Kak Roni menahan malu saat menceritakan kronologis nama Zacky dulu. Saat itu aku tertawa hingga perutku sakit dan langsung berhenti ketika Zacky masuk. Zacky, seorang yang langsung bekerja setelah lulus SMK multimedia, telah banyak menyerap ilmu dari Kak Roni dan masih ingin terus belajar. Dia bahkan menanyakan padaku bagaimana membuat hasil foto dengan efek dramatis seperti satu foto pernikahan yang diperlihatkannya dari sebuah website.
“Ini ada triknya, Zack. Lensa filternya diolesi lotion pinggirannya, tapi jangan kebanyakan, ntar malah burem banget,” kataku menjelaskan pada Zacky. Dia berdiri, berjalan menuju lemari kecil dan kembali dengan satu lensa filter. “Daerah sini aja yang diolesi, Gam?” katanya, telunjuknya menyusuri dan berputar-putar pada pinggiran lensa.
“Yah, nyisain diameter satu senti di tengah juga gak masalah. Atur aja ntar, di tes.”
Zacky ini lincah dengan badannya yang cenderung kecil, benar-benar seperti kancil. Tidak lama dia mengambil kunci motor yang tergantung dan segera bergegas entah kemana. Mataku mengikuti arah langkahnya.
“Lu ngomong apa ke dia, Gam?” tanya Kak Roni yang telah selesai dengan telepon.
“Dia nanya bikin efek blur dramatis untuk weddingan. Gua saranin pake lotion,” jawabku.
“Yah, paling tu anak langsung nyari lotion.”
Benar saja, tidak lama satu pesan masuk dari Zacky, mengirimkan dua foto merk lotion. Aku tersenyum, “Bener, Kak. Nih!” kataku sambil menunjukkan layar handphone. Kak Roni melihat sekilas, dan juga tersenyum singkat,“Ya, gua syukur banget punya anggota begitu. Mau belajar,” jawabnya sambil mencatat di buku. Saat masih belum selesai dengan masalah merk lotion, sebuah pesan masuk dari tim yang akan berangkat ke Pulau Siberut, Pak Bahar mengirimkan tempat dan waktu untuk kami berkumpul membahas perencanaan produksi sekitar tiga jam lagi. Aku yang hari ini berencana menemui Aruna untuk menyelesaikan masalah kami, lantas bergegas.
“Kak, gua balik, ya!”
Kak Roni menoleh segera saat aku sudah meraih ransel, “Gam! Lu punya kabel power? Pinjem. Kabel gua gak aman kayaknya.”
“Oke! Ntar malem gua bawain.”
Langit sore tampak muram, gelap melebihi batas yang seharusnya. Setengah perjalanan, bajuku sudah lembab karena gerimis dan sudah kuyup saat sampai di kost. Pintu kamar Aruna tertutup rapat dan sepasang sepatu oxford hitam mengilap terletak persis di samping keset kaki. Tiba-tiba, karena melihat itu, gejolak panas menyebar cepat di dalam dada. Aku tahu, Aruna dan Andre berada di dalam sana. Lalu aku masuk ke kamar dan segera minum untuk mendinginkan sesuatu yang panas itu. Aku termenung menatap butiran hujan yang menempel di kaca jendela saling mendahului untuk jatuh. Satu sisi aku cepat sadar diri, namun di sisi lainnya aku sedang membujuk jiwa yang meronta untuk dikasihani.
-oOo-
Nyaris saja aku terlambat datang ke pertemuan tim. Ares sudah duduk bersama enam orang lainnya. Aku merasa lega karena diskusi belum dimulai sebab masih harus menunggu produser. Rencana bertemu dengan Aruna meleset sepenuhnya, gagal total. Ini salahku karena tidak mengabarkan bahwa akan datang hari ini. Saat hujan sudah reda tadi, aku dengan harap-harap cemas keluar kamar. Melihat sepatu hitam mengilap itu masih tergeletak di depan pintu, aku tahu bahwa hari ini tidak ada waktu yang bisa disisakan Aruna untukku. Aku menatap pintu Aruna yang seminggu lalu masih bisa dengan leluasa aku buka. Gagang pintu itu seolah memanggil untuk segera kuraih. Tapi aku sadar, itu hanya sebuah kebiasaan. Saat aku mengunci pintu kamar, samar terdengar mereka ribut di dalam. Saat suara itu semakin mendekat, aku buru-buru turun tangga, menghindari sakit yang aku tahu akan sangat menyiksa. Tepat saat aku berbelok ke lantai dua, suara pintu Aruna terdengar dibuka diiringi suara pertengkaran mereka.
Berusaha menepikan masalah dengan Aruna, aku mencoba memberikan atensi penuh pada perbincangan panjang mengenai pekerjaan di Taman Nasional Siberut. Pria sekitar usia empat puluh awal, dengan wajah seperti orang yang selalu bersedih hati –kelopak matanya turun dan tatapannya sayu, memperkenalkan diri sebagai produser. Dia menceritakan, (sepertinya menekankan pada aku dan Ares saja karena hanya menatap pada kami berdua selama bercerita) bahwa proyek di Taman Nasional Siberut ini adalah destinasi terakhir dikarenakan kendala perizinan. Sepertinya hanya aku dan Ares yang benar-benar orang baru karena hanya kami berdua yang diperkenalkan Pak Bahar kepada tim. Perbincangan berjalan rapi dan tidak keluar arah. Daripada teknis, diskusi ini lebih mengarah pada hambatan dan rintangan yang terjadi pada proyek sebelumnya agar dapat diantisipasi untuk pekerjaan kali ini. Di tengah-tengah obrolan, produser menanyakan kesanggupanku dan Ares untuk dapat bekerja rangkap sebagai kameramen dan editor video (juga bertanggung jawab atas desain visual, grafis, dan estetika keseluruhan film) sebagai salah satu cara penghematan dana. Sebab dana untuk berjaga-jaga perlu disiapkan lebih. Tanpa terlihat berpikir, Ares mengangguk cepat dan yakin, dan sepertinya itu juga mewakili jawabanku sebab produser beralih pada topik lain dan orang lain sebelum menunggu aku menjawab. Saat produser sedang berbicara dengan penulis naskah, seorang laki-laki berkacamata trendy, yang duduk berhadapan denganku, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkan kepadaku dan Ares. Dia adalah satu-satunya tenaga medis dalam tim ini.
“Diisi, ya. Ini gak kalah penting,” katanya dengan nada bicara khas perawat, ramah yang profesional. Dia menunjukkan barisan gigi kecil putihnya saat tersenyum. Aku dan Ares membalas senyuman itu dengan canggung. Dua lembar kertas itu berisi kuesioner singkat yang mendukung pekerjaannya nanti bersama kami. Seketika ingatanku terlempar pada momen mengisi kuesioner untuk penelitian Aruna. Semuanya, dari awal kami bertemu di tangga saat dia membelikan makanan bersama Gina, situasi yang canggung karena Aruna salah paham dan hari itu berakhir dengan bagaimana lucunya kami berpacaran. Penuh intrik, gumamku lirih berbisik. Aku tersenyum walau hatiku sebenarnya perih.
-oOo-
Kak Roni setengah memohon kepadaku untuk mengambil alih pekerjaannya menjadi fotografer pernikahan untuk Sabtu dan Minggu karena dia dan Fahmi harus pulang ke Wonogiri. “Ada masalah keluarga mendadak, Gam,” katanya dengan wajah lelah, sepertinya dia sudah menahan kantuk semalaman. Kak Roni tidak menyambung kalimatnya, aku juga tidak bertanya ada masalah apa. “Detail kerjaannya ada di buku itu,” ujarnya lagi sambil menunjuk buku agenda yang membuatku menoleh ke meja reservasi dimana buku biru beludru seukuran 8R terletak di atasnya. Aku mengira-ngira pekerjaan yang harus selesai sebelum berangkat ke Pulau Siberut: website untuk perusahaan nirlaba dan desain kemasan satu toko oleh-oleh. Sepertinya akhir minggu ini akan sibuk. Tapi aku akan mengaturnya untuk membantu Kak Roni. Lagi pula aku harus membalas kebaikan yang sudah kuterima hingga hari ini. Dia merangkulku erat setelah aku menyetujui, lalu menyerahkan kunci mobil, “Pake aja buat dua hari besok. Gua sama Fahmi ke Wonogiri bareng saudara yang lain,” katanya lagi. Lalu dia pergi dan sepertinya sedang menelepon Fahmi saat keluar dari studio.
“Jadi kita berdua aja ntar, Gam?” tanya Zacky dengan wajah termangu melihat Kak Roni berlalu begitu saja tanpa berpamitan dengannya.
“Ntar gua ajak Ares juga.”
Zacky mengangguk lalu dia mengatakan akan bermalam di studio sebab mobil Kak Roni terparkir di luar.
Ares menyanggupi untuk ikut menjadi fotografer pernikahan besok dan lusa. “Sejak lu nginep di sini kayaknya rezeki gua lancar. Pindah ke sini aja, deh!”
Awalnya aku mengira Ares bercanda, tapi saat menoleh kepadanya, raut serius pada wajahnya itu tampak nyata. Aku nyengir.
“Beneran! Ambil tuh kamar, biar gua di depan,” katanya lagi. Percakapan itu terhenti saat Trisna mengetuk pintu.
“Jadi, kalau Trisna datang begini? Gua yang keluar?” ucapku pada Ares yang tampak berpikir.
“Yah, itu bisa dibicarakan.”
Kami tertawa.
Trisna membawa seblak yang membuatku akhirnya duduk –tidak jadi keluar. Aku dan Ares sedang menahan pedasnya seblak saat dahi Trisna mengerut, dia sedang fokus menatap layar komputer pada meja kerja Ares mengerjakan title design dan opening credits untuk salah satu film dokumenter.
“Makan dulu, Ay!” ajak Ares. Spontan aku menoleh ke Ares dan Trisna bergantian dengan tatapan geli.
“Ntar, Ay! Nanggung,” jawab Trisna tanpa menoleh kepada Ares yang duduk melantai di belakangnya
Aku tertawa, “Ay! Suapin!” godaku pada Ares dengan nada kemanja-manjaan. Ares membalas candaanku, menyuapi seblak dengan tingkah tidak kalah imut. Tidak lama kami berdua dilempar Trisna dengan buku, lalu buku itu masuk persis ke mangkuk Ares.
Ares yang melihat kertas buku catatannya beralih warna menjadi jingga, berseru, “Tanggung jawab!”
Trisna yang tahu pacarnya bercanda menjawab sekenanya, “Tanggung jawab pakai cara lain, boleh?” sambil mengedipkan mata jahil dan senyum nakal.
“Ah! Gila lu pada! Gak sanggup gua!” kataku sambil berdiri membawa mangkok seblak keluar. Mereka terkikik saat aku melewati pintu dan aku masih tergelitik saat menyendok seblak setelah duduk di teras. Namun hanya sekejap, aku lantas teringat Aruna. Kami juga selalu tertawa bersama meski hal lucu itu secuil saja. Sendok kututup karena sudah kehilangan selera makan lalu merogoh handphone, mengecek pesan yang masih setia dia kirimkan, membuka sosial medianya, seperti biasa, tidak ada perubahan. Dia bukan pengguna sosial media yang aktif, hanya satu foto yang diunggah selama enam bulan terakhir, fotonya saat bekerja. Fragmen-fragmen kenangan kembali terkuak saat membuka galeri foto. Lalu cerita di balik satu foto muncul seperti sebuah narasi panjang dalam kepala. Banyak fotonya yang aku ambil diam-diam. Dia sangat kikuk jika harus berpose, dia pun mengakuinya. Rasanya baru kemarin aku terpingkal saat melihatnya latihan pose di depan cermin untuk foto model rumah sakit. Dia memintaku menilai tapi aku tidak tahan untuk tidak tertawa yang membuatnya merajuk nyaris setengah hari jika saja aku tidak membujuknya dengan jalan-jalan sore sambil jajan –yang sehat tentunya. Aku kembali mengejek pilihannya, burger bayam, yang dia sendiri dengan susah payah mengunyah karena rasanya tidak enak. Namun karena gengsi, dan seolah membuktikan padaku bahwa cemilan sehat tetap lebih baik walau rasanya mirip makanan basi, dia habiskan burger bayam yang ternyata membuatnya mual semalaman suntuk. Saat itu dan saat ini ketika mengingatnya, aku tertawa dan masih saja. Foto dia sedang memilih roti di supermarket, foto dia sedang memasak, foto dia sedang melambai padaku saat menjemputnya. Wajahnya ceria sekali, seperti anak TK yang berlari masuk ke toko mainan saat menghampiriku. Aku lagi-lagi tersenyum, seakan mencari-cari kebahagian untuk sekedar menenteramkan hati. Walau sesaat.
Alam seolah paham, pesan dari Aruna masuk saat aku baru saja akan menyimpan handphone. Dia menanyakan apakah aku sudah makan. Untuk pertama kali setelah nyaris dua minggu, aku meneleponnya. Tidak sampai deringan pertama, telepon itu diangkat Aruna.
“Halo? Gam?” Sapanya. Suara lembut itu membuatku semakin rindu … dan pilu. Dan yah, entahlah aku bergetar mendengar suaranya. Entah getaran suka atau duka aku juga tidak tahu.
“Ya? Kamu udah selesai dinas?” tanyaku setelah beberapa saat. Aku yakin suaraku terdengar serak.
“Udah. Aku dinas pagi hari ini. Kamu dimana?”
“Aku di kontrakan Ares. Udah dua minggu ini di sini.”
“Oh …,” suara Aruna terdengar lemah, “syukurlah. Dia udah gak pindah-pindah, ya?”
“Iya.”
“Sekarang dia ngontrak?”
“Ya.”
Lalu kami diam cukup lama. Aku sibuk menelan ludah.
“Gam?” panggil Aruna.
“Ya?”
“Pulanglah ….”
Walaupun dia mengatakan dengan pelan, namun bagiku suaranya terdengar nyata seperti dia berbisik tepat di sampingku. Aku terdiam. Lalu dia mengulang permintaannya dengan lirih, “Pulanglah, Sayang. Aku rindu.”
Tenagaku seakan disedot habis hingga merasa tidak berdaya mendengar kata rindu darinya. Punggungku yang tadinya tegak kini bersandar pada bingkai kayu jendela yang setengah terbuka.
“Ya.” Kataku setelah menguatkan hati.
“Ya?”
“Besok. Besok sore aku pulang.”
“Aku tunggu.”
“Sekarang tidurlah, Runa. Udah malam.”
Aruna tertawa pelan, tawa yang tidak sebenarnya. Bahkan sangat jelas dia sedang menyembunyikan gundah.
“Tidur buatku sekarang cuma sekedar rebahan,” dia berdeham, “aku udah tiga kali ngambil shift seharian penuh cuma menghindari pulang, karena aneh rasanya gak ada yang nungguin aku, Gam.” Aruna diam sebentar, sepertinya sedang berhati-hati memilih kata berikutnya, “Lagi pula itu cara biar aku gak terlalu kepikiran …,” dia mendesir, “kepikiran masalah kita.”
“Jangan.” Aku menyambar cepat sebab aku paham apa yang dia rasakan. Itulah bentuk penolakan dari emosi yang menyakitkan dan sayangnya itu yang kami lakukan. Ingin sibuk. Ingin mengalihkan pikiran hingga merusak diri sendiri.
“Kamu gimana? Istirahat cukup? Begadang?”
Aku diam, tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku memilih bungkam untuk tidak menggali-gali emosi demi meraih iba.
“Jangan terlalu paksain kerja, kamu baru aja sembuh,” Kataku mengalihkan pertanyaannya.
“Mungkin aku berharap sakit lagi biar kamu datang jemput aku lagi.”
“Itu bodoh namanya. Kamu mengorbankan diri sendiri.”
“Demi kamu.”
“Enggak.”
“Demi kita.”
“Enggak juga. Bukan demi siapa-siapa. Belum tentu aku bisa datang. Kalau udah gitu, gimana? Makin sedih, kan?” Tiba-tiba skenario buruk muncul di kepalaku, bukan aku tapi Andre yang datang tergesa-gesa jika dia sakit. “Kamu percuma aja ingatin aku buat sehat, makan teratur, istirahat, tapi kamu aja gak kasih contoh yang baik!” ujarku lagi dengan tegas. Aku tahu kata-kataku terdengar kasar dan menyebalkan. Aku terbawa emosi karena aku sendiri memikirkan apa yang terbaik untuknya tapi dia justru menjerumuskan diri sendiri kepada penyakit yang dicari-cari. Atau mungkin juga karena wajah Andre tiba-tiba menusuk kepala. Entahlah. Aku hanya tidak ingin Aruna jatuh sakit.
Dia diam. Tidak lama Aruna terdengar mendesis yang membuatku tahu dia sedang menangis. Dan aku mulai menyesali kata-kataku sendiri.
Napasku terhela lemah, “Istirahatlah. Mau pulas mau enggak, kamu tetap harus coba tidur,” kataku lagi ingin segera mengakhiri percakapan sentimentil ini, “ya?”
“Ya. Ya …,” suaranya tersangkut. Lalu dia matikan telepon itu seakan tidak mau mendengar kata-kata yang lebih menyebalkan dari mulutku. Tidak lama dia mengirimkan foto jendela kamarku yang di ambil dari sudut kasur. Dia berada di kamarku, di kasurku.
Kalimat di bawah foto itu membuatku merasa sudah seperti orang paling jahat di dunia. Entah hingga berapa kali, tapi saat berbaring, aku kembali membuka pesan yang membuatku merasa bersalah itu. ‘Mestinya aku gak ngomong apa-apa selain rindu’
Sabtu pagi, aku, Ares dan Zacky sudah berada di hotel tempat acara pernikahan. Acara yang berjalan lancar juga membuat pekerjaan kami berjalan semestinya, profesional. Meskipun aku merasa sedikit sempoyongan karena sudah kurang tidur beberapa hari belakangan.
“Heran gua sama diri sendiri,” kata Ares sambil mengunyah potongan melon.
“Gua juga,” kataku. Aku dan Ares sedang duduk, istirahat sebentar. Sedangkan Zacky sibuk memotret pengantin saat tetamu sedang sepi. Sebelah tanganku memegang piring kertas yang berisi potongan buah, sebelah lagi menyuap dengan gerakan anemik. Pada ujung bangku yang kami duduki, terdapat segelas soju. Aku dan Ares tidak berani menyantap makanan lain dalam pesta pernikahan pasangan cina ini. Dalam kepala masing-masing, pikiran kami sama: mengkhawatirkan perkara halal dan haramnya makanan namun disisi lain tanpa pikir panjang mengonsumsi alkohol.
“Kita bajingan.” Kataku.
“Yang takut neraka.” Sambar Ares.
Lalu kami menatap kosong makanan-makanan yang diantarkan pramusaji secara bergantian ke meja-meja tamu. Meja bulat itu penuh dengan hidangan berwarna cerah juga beraroma menggiurkan.
“Kita gak bodoh, kan?” tanya Ares lagi.
“Bodoh.”
Jakun Ares bergerak naik turun karena menelan ludah.
Acara pernikahan ini seharusnya berakhir tepat pukul dua. Jika ditambah dengan waktu mengemasi peralatan fotografi, maka paling lama aku akan sampai di kost pukul lima. Sayangnya, acara tidak berjalan sesuai rencana, acara ini berlanjut hingga pukul empat sore. Pihak keluarga membayar lebih pada hotel dan membicarakannya juga pada kami. Kak Roni dan Fahmi yang tidak mengangkat telepon membuat kami harus menyetujui permintaan keluarga pengantin.
“Yah, demi nama baik studio Kak Roni juga.” Kataku pada Ares, menyemangatinya yang sudah berencana akan segera tidur setelah pulang dari pekerjaan ini.
Sisa sore, hanya keluarga inti yang tertinggal. Mereka menyetel lagu berbahasa mandarin dan berjoget bersama. Tugas kami adalah mendokumentasikan momen-momen diluar agenda ini.
Terpaksa, aku sepertinya tidak bisa datang menemui Aruna lagi kali ini. Saat aku sudah selesai, dia justru sudah harus berangkat kerja. Aku mengirimkan pesan pada Aruna mengatakan aku belum bisa pulang.
Malamnya Ares langsung tidur pulas dan dengkurannya terdengar lebih antusias. Aku yang tidak bisa tidur lantas membersihkan mobil ditemani kopi, juga memastikan peralatan dalam kondisi siap untuk digunakan besok pada acara pernikahan berikutnya.
Kami sudah berangkat lagi ke rumah pengantin lain. Di sana, saat bergantian istirahat, Ares tampak makan dengan puas tanpa lagi dilema halal dan haram. “Bon appétit!” bisiknya sambil cengengesan saat aku hampiri. Lalu Zacky yang sepertinya benar-benar menyukai teknik filter dramatis itu, untuk hari ini lebih banyak bereksperimen dengan lensa filter dan lotion dalam mengambil foto pasangan pengantin. Saat diperlihatkan hasilnya, sepertinya pasangan baru itu menyukainya. Wajah Zacky yang tirus itu kembang oleh senyuman saat dipuji. Aku turut senang.
Tidak seperti kemarin, acara pernikahan kali ini selesai sesuai jadwal. Walau di sepanjang acara terdapat banyak kendala, keluarga pengantin cukup mengintervensi pekerjaan kami, sehingga butuh kesabaran yang ekstra untuk tetap profesional.
“Yang begini ini, nih yang bikin capek jadi double!” bisik Ares kesal.
“Tapi untung makanannya enak, kan?” Aku menyindirnya yang sudah menghabiskan nasi satu piring dengan aneka lauk pauk.
“Ah! Lu!” rutuknya sambil berlalu.
Kami sudah selesai mengemasi peralatan tepat pukul empat. Lalu berpisah di tengah jalan, Zacky minta diantar pulang saja sedangkan Ares minta diantar ke tempat Trisna bekerja.
“Besok jangan telat bangun. Jam satu udah di bandara!” Aku mengingatkan Ares dan dia mengacungkan jempol, “Siap!” Lalu melangkah riang saat melihat Trisna menunggunya dengan tegak pinggang di seberang.
Sebuah pesan masuk dari CMO perusahaan nirlaba saat aku berhenti di persimpangan lampu merah, mengatakan terima kasih atas website yang sudah aku kerjakan dan juga mengirimkan bukti pembayaran komisi. Lampu hijau menyala, aku membawa mobil Kak Roni ke kost untuk menemui Aruna, berbicara padanya sebab ini satu-satunya kesempatan yang kami punya sebelum besok berangkat ke Pulau Siberut. Jam sudah menunjukkan pukul lima saat aku memarkirkan mobil di kost. Aku turun, mengemas semua peralatan fotografi yang sebagian besar milik Kak Roni dan membawanya dalam satu kali angkut saja karena awan gelap sudah mengukung membuat langit mendung. Angin dingin masuk menembus pori-pori hingga sampai ke tulang, membuatku merinding kedinginan. Aku mempercepat langkah untuk segera masuk.
“Nge-job begini seru kali, bang?” sapa Dion, tetanggaku di lantai satu. Walaupun tidak jadi melanjutkan pendidikan ke kampusku, dia tetap mengambil jurusan multimedia pada kampus lain. Kami berpisah di lantai dua saat terdengar suara gemuruh dari luar yang membuat dinding bergetar.
Baru saja sampai pada lantai tiga, aku melihat Aruna dan Andre berdiri di depan kamar dengan pintu terbuka. Mereka berseru dalam silang kata, sepertinya percakapan pribadi. Meskipun terkadang Andre bernada tinggi, dia segera sadar lalu kembali berbisik. Aku tidak punya pilihan lain selain terus melangkah hingga kamar. Aruna terperangah melihat aku datang. Mata kami bertemu dan entah kenapa aku tertunduk sambil berpura sibuk memperbaiki tali ransel yang menggantung di bahu. Andre melihatku sekilas saat melewatinya, lalu tampak tidak acuh dan masih mengatakan sesuatu dengan setengah berbisik setengah berseru pada Aruna. Dari suaranya aku tidak bisa mengatakan dia sedang marah, justru dia terdengar seperti seseorang yang sedang gundah dan memohon pada Aruna. Aku menyadari sepertinya tidak pernah bertemu laki-laki secerewet ini –bahkan dia lebih cerewet dari Galih. Aruna diam dan sabar seperti menghadapi bocah yang merengek. Hanya Andre yang berbicara dengan tempo dan kata yang tidak beraturan. Aku perkirakan mungkin lidahnya lebih tebal dari ukuran orang pada umumnya, sebab kata-katanya tidak terurai dengan baik. Tebal, seperti orang berkumur. Aku tidak bisa, itu lah satu-satunya kalimat yang kudengar jelas dan berkali-kali terucap dari mulut Andre saat aku berdiri cukup lama memutar anak kunci –di saat tidak tepat begini, anak kunci ini macet.
Sepasang mata cokelat yang selalu aku rindukan itu tampak sendu dengan lapisan air mata. Aku yang tidak tahan melihatnya segera menutup pintu, sedikit membanting sebenarnya, seakan melempar kekesalan.
Di dalam, aku tidak tenang dan hanya bisa mondar-mandir sambil menggigit bagian dalam pipi. Suara keributan mereka, walau tidak jelas kata per kata, mampu menembus dinding yang tipis ini. Tidakkah mereka sadar? Tidakkah seharusnya Aruna tahu bahwa aku bisa mendengar? Tidak bisakah mereka seperti selama ini saja –berbisik-bisik sehingga aku tidak menyadari ada yang ganjil? Tidak menyadari sudah dibohongi, dipermainkan, dimasukkan ke dalam rencana tanpa tahu apa-apa?
AH! SIAL! Aku mengusap wajah hingga telapak tangan terasa panas. Lalu berusaha menjauhi suara-suara itu dengan pergi ke kamar mandi. Diriku yang rentan ini nyaris membuatku gagal mengendalikan emosi. Hampir saja aku keluar lagi dan membawa Aruna masuk, atau bahkan meninju Andre, atau mungkin keduanya: membawa Aruna masuk setelah meninju wajah Andre. Tidak. Aku tidak melakukan apa pun selain melamun di depan cermin.
Telingaku panas mendengar keributan mereka, perasaanku gusar melihat Aruna berlinang air mata. Tapi masalahnya aku tidak begitu tahu dalam posisi sekarang ini, bagaimana cara meresponsnya, dan itu benar-benar membuatku jengkel juga tolol secara bersamaan.
Lima menit kemudian, aku sudah mandi dan menyulut rokok sambil membiarkan angin dingin yang membawa butiran tipis hujan menerpa wajah. Langit semakin pekat, hujan juga semakin lebat membuat suara ribut –yang terkadang dipaksakan berbisik– mereka berhasil teredam. Kesenangan yang baru saja aku dapatkan seketika hilang karena kilat mulai menyambar, membuatku bergidik ngeri dan segera menutup jendela. Tidak lama handphone-ku berdering, Fahmi menelepon menanyakan pekerjaannya yang kami gantikan. Aku mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar. Telepon itu singkat dan berakhir cepat sebab aku takut suara petir yang kian memekik lantang.
Mulai menyibukkan diri, aku mengemasi isi ransel, memindahkan kamera milik Kak Roni masuk kembali ke tasnya yang aku tinggalkan di kamar, memilah barang-barang yang akan aku bawa terbang besok hari, mengemas koper dan memasukkan obat-obatan.
Tidak berapa lama, pintu kamarku terdengar dibuka lalu derap langkah cepat mendekat. Aku baru menyadari pintu itu belum sempat terkunci. Tanpa menoleh, aku tahu dengan pasti siapa yang baru saja masuk dan hanya bisa terpaku saat tangan kecil melingkari pinggangku. Dia mengeratkan jari-jemarinya membuat pelukannya semakin kuat. Kepalanya bersandar pada punggungku sedang tubuhnya bergetar seolah sedang menahan emosi yang merubungi hati. Sedang aku kini hanya menunduk dengan perasaan berkecamuk, “Sampai mana kamu sanggup menyakitiku, Runa?” tanyaku padanya. Tangis Aruna pecah dalam isakan yang menyakiti tidak hanya dirinya tapi juga diriku. Aku yang tidak mendengar satu kata pun dari bibirnya, menganggap tangisannya adalah jawaban dari pertanyaanku. Dia melepas segala rentetan kesedihan, sedang aku berusaha menahan sekuatnya di dalam dada. Punggungku terasa hangat oleh air mata yang merembes dari kaos. Aku berusaha tetap diam, menatap tetesan hujan yang menimpa jendela. Mengapa momen seperti ini harus disertai hujan? Luar biasa memang bagaimana hujan mampu membuai melankolia menjadi sebuah nestapa. Mungkin karena simfoni alami yang merdu perlahan berubah menjadi deru, mungkin juga karena aroma tanah basah, atau justru karena sentuhan lembutnya yang menipu lalu tahu-tahu kamu sudah berada di tengah badai yang keras.
Aruna masih tersedu-sedan. Tangisannya seolah sedang berpacu dengan deru hujan. Meskipun kilat datang mengejutkan dan diiringi suara yang menggelegar, baik aku dan Aruna sepertinya hanya ingin larut dalam situasi ini lebih lama, walau dengan kecanggungan yang tidak mampu aku ungkapkan dengan kata-kata. Kami berdua sama-sama tidak ingin beranjak dari depan jendela. Aneh memang, tapi beginilah, dua anak manusia yang sedang mencoba menunda luka.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden




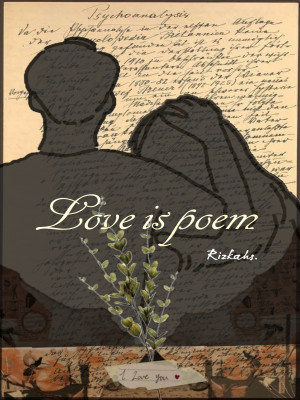








Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)