Suara di kiri kanan pelan tapi saling berhamburan sehingga tidak terdengar jelas apa yang orang-orang katakan. Tawar menawar, menanyakan warna, berkomentar sendiri mengenai pakaian yang dipegang. Aruna melakukan yang ke tiga, berkomentar sendiri dengan suara pelan, macam-macam perkataannya. Terkadang berdecak karena bagus atau berdecak kesal karena warna bajunya tidak sesuai selera. Aku berdiri tepat di belakangnya, melihat dia yang sepertinya masih memiliki banyak tenaga untuk mengitari pusat perbelanjaan ini setiap lantai hingga lima kali demi mencari baju untuk dikenakan saat acara wisudanya. Acara wisuda kami sama-sama dilaksanakan pada bulan ini, Oktober, Aruna pada tanggal delapan belas sedangkan aku dua hari setelahnya. Maka disinilah kami, Thamrin City, Minggu sore.
“Ini gimana? Bagus, gak?” Aruna memutar badannya sambil memperlihatkan sebuah gaun biru muda. Aku mengangguk sebagai jawaban lalu mengacungkan jempol. Aruna kembali menggantungkan gaun itu ke tempat semula, lalu memperlihatkan lagi kepadaku sebuah gaun berwarna ungu, lebih mirip warna terong, “Kalau ini dibanding yang tadi? Bagusan mana?” tanyanya lagi. Belum sempat aku menjawab, dia memberiku baju ungu itu, “pegang dulu.” Aruna mengambil gaun biru muda tadi segera, “nih! Coba liat deh. Bagusan mana?”
Jujur, aku bingung. Keduanya terlihat sama, hanya beda warna.
“Kamu suka yang mana?” tanyaku. Bergantian mataku bergerak dari gaun biru yang di tanganku ke gaun biru yang dipegang Aruna.
“Hmmm,” Aruna berfikir, meletakan satu telunjuk pada dagunya. Dia membandingkan keduanya, “dua-dua nya aku suka, sih. Tapi ak –”
Aku segera menyambar gaun di tangannya, membawanya ke kasir dan membayar keduanya. Biru dan ungu. Aruna yang setelah sadar, segera mengikutiku ke meja kasir.
“Ngapain beli dua-dua nya?!” bisiknya tepat di telingaku sambil berjingkat.
“Kalau suka beli aja,” aku menjawab santai.
“Gak gitu, juga, ih!”
Lagi-lagi pinggangku di cubit, untung saja luka itu sudah tidak sakit. Aku tersenyum simpul sambil menerima tas belanja.
“Terima kasih, langganan, ya, Mas~” ujar kasir tersebut sambil mengusap cepat tanganku yang masih menerima tas belanja, perempuan ini memang centil. Bukan hanya kepadaku, sedari tadi, selama berdiri di toko ini, aku melihat dia yang berbicara manja kepada pelayan toko pria. Aku tersenyum kikuk. Aruna cekikikan. Kami bergegas menjauh, mencari tempat duduk sekedar minum dan istirahat.
“Tuh! Digodain mbak nya. Seneng, kan?” goda Aruna sambil menggamit lenganku.
Aku tertawa, “Seneng lah, balik yuk minta nomor hapenya.”
“Oke. Biar aku yang minta,” Aruna segera berbalik. Aku menariknya kembali dan dengan cepat mendekapnya. Bisa-bisa kalau tidak begitu, Aruna akan benar-benar meminta nomor handphone kasir tadi. Serius. Aruna bisa begitu. Dia selalu berpikiran kalau perempuan yang menggoda duluan, itu tidak akan berhasil menarik minatku. Beda cerita kalau aku yang tertarik duluan, dia akan uring-uringan. Seperti dengan Trisna dulu, Aruna beranggapan bahwa aku menyukai Trisna sebab aku bercerita bekerja dengannya menyenangkan, lalu dia cemburu. Lalu saat di bar, bersama Ares, dia khawatir aku akan menemukan perempuan lain saat dia di Tangerang, bukan akan lebih khawatir jika aku mabuk. Masalahnya, apa memang masih bisa aku tertarik pada perempuan lain? Aku rasa tidak. Makin kesini aku semakin menyadari bahwa aku menyukai Aruna karena dia pintar. Dia seksi karena apa yang ada di kepalanya, bukan karena apa yang ada di balik bajunya. Isi baju itu-itu saja, sedangkan isi kepala ada-ada saja.
Kami terus berjalan, Aruna kehausan tapi tidak mau berhenti pada beberapa gerai minuman yang sudah terlewati.
“Mau yang ada makanannya.”
Katanya saat aku mengajaknya berhenti pada satu kedai yang memang hanya menjual minuman. Aku menuruti saja sambil tanganku tetap digamitnya.
“Kamu datang ke wisuda aku?” tiba-tiba Aruna menanyakan hal yang tidak perlu dia konfirmasi lagi.
“Kok ditanya? Ya, datang, lah,” jawabku sedikit heran.
“Kan kerja?”
“Untungnya aku gak punya atasan.”
“Deadline, gimana? Ares juga belum full datang, kan?”
“Aku lanjut kerjain di kost. Kamu juga tahu.”
“Kerja aja, gak apa-apa. Kamu keseringan begadang bawa kerjaan pulang.”
Aku menghela nafas. Dilema apakah sebenarnya aku diundang atau tidak ke acara wisuda Aruna.
“Ini sebenarnya yang kenapa-napa kalau aku datang itu, kamu atau aku?”
Aruna diam, dia menatapku lama. Aku pura-pura tidak menyadari bahwa dia melihatku. Pandanganku lurus sambil berjalan.
Kami tidak berbicara hingga duduk pada satu kedai makan. Aruna malah memesan bakso duluan walau tadi katanya kehausan. Aku membukakan botol air mineral, menggesernya dekat ke Aruna untuk mengingatkan dia agar segera minum.
“Gam?” Aruna melirik dengan tatapan mau pesan apa saat dia memegang buku menu dan seorang pelayan sedang menunggu juga menatapku.
“Samain aja.”
Aruna mengangguk, pelayan itu mencatat lalu meminta buku menu dan segera pergi.
Air mineral yang sudah terbuka itu mulai diteguk perlahan, kemudian Aruna menggenggam tanganku di atas meja, “Gam …,”
Lagi-lagi aku diam, bergeming, pura-pura sibuk memperhatikan orang yang lewat.
“Gam?” dari menggenggam tangan, kini Aruna mengusap punggung, berusaha mengambil perhatianku dari memperhatikan orang-orang.
Aku malas-malasan melihatnya, sudah pasti Aruna masih ingin melanjutkan pembicaraan tentang hadir atau tidaknya aku di acara wisuda.
“Ya, sayang? Kenapa?” ujarku sambil tersenyum enggan. Dia tahu aku keberatan, lalu sedikit merengek mengatakan, “Kamu kerja aja, ya?”
“Aku gak boleh datang ke acara wisuda pacar sendiri? Orang-orang sampai bawain bunga, aku masa datang aja gak boleh?”
“Bu Sarah, Bu Hafsari datang,” ujarnya cepat.
Aku menghela nafas sambil membuang muka.
“Iya, aku tahu mereka datang. Pasti datang. Apalagi Bu Sarah. Tapi kan aku gak yang gujuk-gujuk meluk kamu, rangkul kamu. Kamu bisa bilang aku teman. Tetangga bahkan. Aku gak masalah,” aku kembali menutup perkataanku dengan menghembuskan nafas. Ini bukan lagi perasaan tidak enak, Aruna sudah mencapai titik takut. Ketakutan sendiri.
“Kamu tuh gak tahu, Gam,” ujarnya lirih.
“Ya makanya kasih tahu. Apa, kenapa. Semuanya kasih tahu ke aku. Masih ada yang belum kamu ceritain?” tanyaku sambil melihat matanya, jaga-jaga jika sudah mulai dilapisi air mata. Untungnya tidak.
Aruna diam dan menggeleng kuat. Entah maksudnya tidak ada lagi rahasia atau tidak mau menceritakan apa-apa.
Ingin mendesaknya bercerita, tapi tidak ingin-ingin amat, malas. Bahkan ingin kesal saja aku sudah terlanjur malas. Akhir-akhir ini situasi ‘ingin dan malas’ cukup sering aku rasakan. Bukan hanya urusan Aruna, urusan lainnya juga. Malah lebih ekstrim, seperti waktu itu aku mengantuk, ingin tidur tapi malas. Bisa ternyata malas tidur walau sudah mengantuk. Bahkan sering aku alihkan rasa kantuk itu pada bekerja walau tidak sedang dikejar tenggat. Haus, tapi karena malas mengambil minum, aku berharap haus itu hilang begitu saja. Terkadang malah memacu diri sendiri apakah aku sanggup malas untuk menahan keinginan? Ternyata setelah beberapa kali percobaan, si malas menang telak. Aku tahu ini aneh, tapi begitulah. Ingin, tapi tidak ingin-ingin amat. Mengambang. Malas.
“Bakso jamur dua, es teh dua.”
Pelayan yang entah kapan datangnya tiba-tiba saja muncul di hadapan kami sambil mengulurkan pesanan.
“Selamat makan…,” ujarnya lagi sambil berlalu. Wajahnya datar. sama datarnya dengan wajahku kini.
“Nih, makan dulu,” aku menaruh sendok dan garpu pada mangkuk Aruna, sedang Aruna membuka bungkusan kertas pada sedotan dan menempatkannya pada gelas kami masing-masing. Aruna tampak senang melihat dua mangkok bakso dengan kepulan asap dan aroma lezat menguar di depan mata.
Aruna seperti biasa, lahap. Aku hanya menyeruput kuah bakso sekitar tiga atau empat sendok dan memakan satu bakso. Bukan karena tidak enak, lagi-lagi dengan alasan yang sama: malas, malas mengunyah. Sepanjang perjalanan pulang, kami hanya sedikit berbicara, satu-satunya hal yang membuat kami cekikikan adalah mendengar sejoli yang berbicara seperti balita. Motor kami terparkir bersebelahan.
“Kamu cuka bando balu aku?” tanya si perempuan.
“Iya. Ayang lutu pakai itu,” jawab si laki-laki. Tak lupa gestur lucu yang mereka buat saat berbicara.
Sebenarnya gemas, tapi ke arah yang berbeda. Bukan gemas menyenangkan seperti melihat balita (atau Aruna, menurutku).
Pak Yahya menyapa, aku meminta Aruna naik sedangkan aku duduk bersama Pak Yahya. Sudah lama kami tidak duduk santai sore, sejak membuka studio. Aku dan Ares akhirnya merubah jadwal studio, khusus hari Minggu, studio hanya buka hingga jam dua siang. Sudah tiga minggu berjalan seperti itu, sejak kembali dari Hotel di Tangerang. Aruna bekerja pada pelayanan kesehatan home care Senin hingga Sabtu. Katanya, dia bekerja sebagai caregiver, merawat seorang wanita usia akhir empat puluhan yang terkena stroke ringan. Saat siang ibu itu hanya berdua dengan seorang tetangga yang sudah paruh baya untuk membantunya mengurusi rumah. Sore pukul lima, baru lah suaminya pulang dan di jam itu juga Aruna batas Aruna bekerja. Sudah tiga minggu berturut, Aruna ikut ke studio, membantu pekerjaan sebab Ares terkadang tidak datang karena masih merampungkan karya. Aruna yang sangat asing dengan dunia kerjaku tapi mencoba mau belajar, mencoba mau mengerti sekedar untuk membantu. Dia cepat memahami hal-hal dasar. Dia dengan cekatan tanpa ragu tahu mana yang harus dia bantu. Cerdas dan membuatnya semakin memikat. Aruna telah menjadi kawan untukku. Kawan berbagi cerita, kawan berbagi keresahan, kawan yang mampu memahami tanpa aku harus banyak bicara. Kawan hidup, jika aku bisa berlebihan mengatakannya.
“Mas Gamma sama Mbak Aruna dari mana?” tanya Pak Yahya sambil memberiku segelas kopi yang dia seduh sendiri. Kini di pos kecil Pak Yahya terdapat dispenser.
“Dari belanja untuk wisuda Aruna, Pak,” aku menyeruput kopi yang tidak terlalu panas itu, “Makasih, Pak. Enak.”
“Ya iyalah enak, sachetan, kok!” celetuk Pak Yahya.
“Iya, biar bapak senang aja.”
“Waduh! Mas Gamma bisa aja!” Pak Yahya terkekeh, “udah wisuda aja, ya? Cepat amat waktu lewat. Mas Gamma gimana? Wisudanya kapan?”
“Dua hari setelah wisuda Aruna, Pak.”
“Wah. Selamat, ya, Mas. Saya ikut senang. Inget banget waktu Mas Gamma pertama datang.”
“Gimana emang, Pak?”
“Imut-imut.”
“Sekarang?”
“Gagah!” Pak Yahya mengangguk yakin.
“Ah! Bisa aja Pak Yahya.” aku tersenyum ganjil.
“Iya, biar Mas seneng aja.”
Pak Yahya membalas ucapanku sebelumnya. Kami tertawa.
“Mbak Aruna sama Mas Gamma pacaran?” tanya Pak Yahya sambil menyalakan rokok.
Aku mengangguk setengah-setengah, tidak mengiyakan namun juga tidak mengisyaratkan berkata tidak. Jika mengikuti kehendakku, tentu aku akan berkata lantang dengan anggukan kuat mengatakan iya. Tapi ingatan tentang sikap Aruna tadi membuatku ragu apakah dia akan menyukai jika Pak Yahya tahu.
“Kenapa, Pak?”
“Yah, kalau yang saya lihat-lihat, sih, Mas Gamma naksir Mbak Aruna,”
“Kalau itu, sih, iya,” aku tak tahan untuk tidak tersenyum, “kalau Aruna nya, gimana, Pak?”
“Hmmmm, sek, tak ingat-ingat dulu,” ujar Pak Yahya membuat wajah serius, pandangannya ke atas seolah berpikir keras. Menghembuskan kepulan asap rokoknya.
“Ah, Bapak!” aku terkekeh. Pak Yahya tertawa.
“Habisnya, Mbak Aruna itu sering nunduk, jadi gak ketahuan deh dia suka Mas atau engga. Banyak diam juga orangnya. Paling senyum doang kalau lewat.”
Aku manggut-manggut. Menyetujui.
“Pernah nanya langsung, Mas? Tanya aja!” lanjut Pak Yahya.
Deg!
Pertanyaan Pak Yahya menyadarkan bahwa selama ini aku memang tidak pernah menanyakan langsung. Tapi apa itu penting? Toh, kami sudah pacaran. Toh, secara keseluruhan kami baik-baik saja. Segala sikapnya, perhatiannya, usahanya benar-benar sempurna untuk dikatakan sedang mencintai seseorang. Dia percaya padaku seperti dia percaya melewatkan malam bersama tanpa khawatir sedikitpun. Dia peduli terhadap pendapatku mengenai apapun yang dia ragu. Dia resah jika aku berdekatan dengan perempuan lain. Dia tanpa henti-hentinya mengingatkan untuk selalu sehat. Dia yang hujan-hujanan hanya untuk membeli hadiah kelulusan. Memaksakan datang walau sedang sakit. Hanya satu hal yang berkebalikan dengan itu semua, rasa takut-takut mengenai hubungan ini terhadap keluarga-nya. Rasanya, kecuali yang satu itu, tidak mungkin dia lakukan jika tidak memiliki perasaan cinta.
Aku mengangguk sendiri, menyetujui apa yang aku pikirkan.
“Perempuan itu punya banyak wajah, Mas. Dia dibekali kemampuan memainkan raut lebih baik dari laki-laki. Kadang kita laki-laki mikirnya dia kecintaan, gak taunya kesenangan doang. Diantar kemana-mana, seneng. Dijajanin, seneng. Disayang-sayang, seneng. Mereka seneng aja, jadinya ya gak nolak, tapi pas diajak nikah malah kabur. Alasannya belum siap, gak cinta, parahnya dikira adik-kakak. Halah!”
Jelas Pak Yahya kemudian. Aku terkejut sampai-sampai berhenti menyesap kopi. Menatapnya heran.
“Bukan, Mas. Bukan cerita saya. Ibunya Zahara gak nolak dulu. Langsung iya katanya pas saya ajak nikah,” Pak Yahya tersenyum bangga kemudian, “itu curhatan Bang Tigor, tau kan? Lantai satu, sales motor. Tiga tahun bareng, diajak nikah malah kata perempuannya gak cinta. Adik-kakak katanya. Adik-kakak apaan kalau malam-malam Bang Tigor rela datang cuma karena yang perempuannya takut kecoa, rela ngusirin.”
Aku tidak suka membicarakan orang. Namun karena Pak Yahya terdengar menyampaikan pesan, walaupun dengan cara menceritakan kisah orang, aku manggut-manggut mendengarkan, “Kasihan amat.”
Kemudian kami membahas hal-hal remeh lain, tidak begitu penting. Seperti merk kopi sachet yang lebih enak, bude jamu yang kini sudah jarang lewat, atau mentertawakan cerita lucu Pak Yahya tentang anaknya. Namun sejujurnya ujaran Pak Yahya tentang perempuan, berkelebat hebat di kepala. Berputar-putar. Sesekali membuatku ingin segera berlari menemui Aruna dan bertanya perihal perasaannya. Aku urung, mencoba mempertimbangkan lagi dengan segala sikap-sikap berbalut kasih yang selama ini telah dia tunjukkan.
Gak mungkin pura-pura.
Jam menunjukkan hampir pukul delapan malam saat telepon berakhir dengan ibu dan Marwa. Kami membicarakan perihal wisuda. Ibu dan Marwa akan datang dan Marwa meminta untuk kali ini sebaiknya mereka menginap di hotel saja, lebih nyaman. Aku menyetujuinya. Tadinya, aku berencana melanjutkan film yang tertunda, namun malas. Lantas aku ke mengetuk kamar Aruna.
Dia dari dalam sana berseru agar aku masuk. Pintunya tidak dikunci. Dia dengan baju tidur iconic -nya, lagi-lagi sedang menatap dua gaun yang baru saja dibeli, menggantungnya bersisian.
Aruna tersenyum.
“Pintu harus dikunci, jangan teledor,” ujarku sambil duduk dikasur.
“Iya, lupa aja tadi.”
“Masih itu juga?” tanyaku menunjuk gaun yang tergantung.
“Iya, nih! Bingung.”
“Pakai aja dua-duanya. Dilapisin,” jawabku iseng sambil membuka ponsel, memesan hotel.
“Solutif sekali Anda, Tuan,” ujarnya berkacak pinggang kesal.
Aku tertawa. Aruna cemberut masam.
“Lagian kamu mau keliatan cantik di depan siapa? Aku juga gak datang, kan?”
Aku menatapnya berdiri di hadapan dua gaun itu. Kakiku lurus bersilang, menggoyangkannya santai. Ya, aku tengah santai, pembicaraan ini santai, malam ini santai. Tidak bermaksud merongrongnya dan sama sekali tidak ingin memberatkan Aruna. Hanya saja aku butuh memdengar jawaban yang setidaknya membuatku berfikir bahwa memang sebaiknya aku tidak datang.
“Kamu beneran gak datang?”
“Maunya kamu gitu, kan?”
“Kamu datang atau engga?”
“Aku datang. Mau gimanapun kamu merengek, aku bakalan datang,” tegasku.
“Gam~” Aruna berkeluh. Kini tampak resah. Dia menampilkan raut yang selalu berhasil membuatku mengalah. Memang, aku nyaris menyerah dan hampir saja turun dari kasur untuk memeluknya. Aku urung, kali ini aku bertahan sedikit lebih kuat.
“Aku malu-maluin kamu?”
“Bukan gitu.”
“Aku jelek banget sampe untuk dibilang tetangga aja gak bisa?”
“Jelek apaan? Orang tadi di godain mbak-mbak. Kamu jangan gitu, dong~”
“Kamu yang jangan gitu. Coba deh, alasan yang masuk akal itu apa?”
Aku menunggu jawaban dari Aruna yang bungkam. Sambil berpangku tangan dia menggaruk-garuk lengannya yang aku tahu tidak gatal. Nyala matanya sendu. Aku mulai dilingkupi rasa bersalah. Tapi bersalah untuk apa? Bersalah untuk tetap datang? Lucu sekali. Tiba-tiba perkataan Pak Yahya kembali menyusup ke kepala. Ada rasa ganjil di hati untuk menanyakan apakah dia mencintaiku atau tidak, terdengar aneh dan menggelikan. Setelah menimbang, akhirnya aku ubah pertanyaan personal itu menjadi pertanyaan subjektif, “Kamu pernah jatuh cinta, gak?”
“Maksudnya?” Aruna tercekat mendengar pertanyaan itu. Mata sendu itu seketika berubah menjadi kalut. Alisnya tadi dengan sudut naik, kini menukik tajam dan bertaut.
“Kamu tahu persis apa maksudnya.”
Aruna masih bungkam, dia tampak tidak begitu senang.
Melihatnya begitu, aku tersenyum simpul. Kecewa karena dia tidak bisa langsung menjawab, malah terlihat berpikir. Jeda cukup lama untuk sekedar menjawab pernah, sekarang, sama kamu atau mungkin jawaban lebih menyakitkan: tidak. Walaupun untuk jawaban kedua aku tidak akan siap. Tapi lebih baik daripada harus ada jeda yang membuat seakan-akan jawaban setelahnya adalah pura-pura.
“Pernah, sama kamu, sekarang. Aku bakal jawab itu dengan cepat kalau kamu yang nanya,” ujarku memecah hening.
“Aku cuma kaget. Gak ngira kamu nanya itu,” Aruna mendekat perlahan. Langkahnya ragu-ragu. Menurutku langkahnya itu menggambarkan perasaannya juga. Ragu.
“Kali ini aku tanya.”
“Pernah, sama kamu, sekarang,” jawab Aruna cepat.
“Itu jawaban aku.”
“Sama. Itu juga jawaban aku.”
“Jadi gak otentik.”
“Itu jawaban umum untuk pertanyaan tadi kalau jawabannya pernah.” jawab Aruna cepat.
Aku tidak bisa berujar mendengar jawabannya yang pintar. Walau sebenarnya ingin menambahkan bahwa kata-kata itu terdengar tidak tulus, tapi aku telan karena terkesan kekanak-kanakan.
“Kalau udah selesai milih baju, kita makan.”
Akhirnya hanya kalimat itu yang keluar. Aku dengan malas-malasan mulai berbaring. Meraih bantal strawberry dan menutup wajahku menggunakan bantal itu, meredam cahaya lampu.
Tidak lama kasur sedikit bergoyang, Aruna naik dan aku menerka-nerka dia berbaring disisiku. Benar.
Dia melingkarkan tangannya melewati perutku, memeluk. Aku mengangkat bantal dari wajah dan langsung tampak Aruna menatap lekat sambil mengangkat dua sudut bibirnya menjadi senyuman indah. Aku tidak bisa tidak membalas senyumannya.
Dia mencium pipiku, aku balas mencium keningnya.
Dia bilang, “Kamu boleh datang,” dengan berbisik.
“Aku gak butuh izin kamu untuk itu. Aku datang. Aku pikirin caranya ntar,” ujarku juga berbisik.
Aruna mengangguk tak yakin, “Maafin aku,” ujarnya kemudian.
“Gak gitu orang minta maaf.”
“Jadi?”
“Masa minta maaf mukanya kecut,” telunjukku menyentuh ujung hidungnya. Aruna menahan senyum. Setelah itu dia dengan usil menaruh jari telunjuknya pada leherku. Aku kegelian, dia tertawa lalu mulai menggelitik habis-habisan. Menyerbu leher, pinggang dan telapak kaki. Derai tawanya memecah ketegangan yang baru saja terjadi diantara kami. Dengan cepat dan lincah jari jemari halusnya berpindah untuk terus menggelitikku. Dan berhenti saat aku berhasil menguncinya kuat-kuat.
“Nyerah! Udah! Udah gak main lagi!” ujarnya tersengal sebab lelah tertawa.
Akhirnya aplikasi pesan antar makanan pada handphone Aruna berguna juga. Kami memesan sate yang pernah aku kirimkan fotonya. Benar, sate itu sesuai selera Aruna. Kami makan sambil meributkan salah satu film yang kami tonton beberapa bulan lalu, bahwa Groot dalam film Guardians of The Galaxy sangat lucu saat bayi dan saat dewasa terlihat menyeramkan.
*****
Ares datang ke studio Selasa siang tepat saat Bu Lin baru saja keluar. Bu Lin datang kembali ingin membuat materi baru dan menagih janjiku untuk memberinya buku menu digital. Mereka bersalaman sebentar sebelum Ares masuk dan Bu Lin naik ke mobil.
“Oi!” sapa Ares saat masuk.
“Yop!” jawabku sambil mengemas kertas-kertas berantakan pada laci meja reservasi.
“Gua dari kampus. Gua maju awal November,” ujar Ares seraya mengambil minuman.
“Tanggal?”
“Dua.”
Aku diam sejenak, tanggal itu aku berencana pulang ke Bogor. Setahun Bapak meninggal, ibu meminta pulang agar kami bersama-sama membersihkan makam bapak. Yah, walaupun menurutku membersihkan makam bisa kapan saja, tanpa harus menunggu waktu tertentu. Lagipula ibu dan Marwa hampir setiap bulan mengunjungi makam. Mungkin menurut ibu akan lebih dramatis jika datang khusus hitungan tahun. Aku menuruti saja.
“Mungkin gua gak balik ke studio. Gua abis dari liat lu, mau ke Bogor. Pulang bentar.”
“Ada apa di rumah?” tanya Ares.
“Setahun Bapak meninggal. Gak ada apa-apa. Cuma pengen ke makam.”
“Ooh ….”Ares mengangguk pelan, “Ikut!” ujarnya kemudian.
“Liat ntar, kalau kerjaan banyak, lu balik. Kerja,” ujarku kini sambil memisah-misahkan kertas.
“Hah …, iya, deh.”
Kami mulai bekerja, Ares seperti biasa, kebut-kebutan. Dia lagi-lagi bekerja pada dua alat, tablet dan komputer. Aku pada kamera, di studio, shooting. Menjelang sore, kami duduk berdua, memikirkan copywriting untuk satu agen perjalanan. Banyak diam dan melamun, namun di kepala kami berhamburan kata-kata yang akan ditulis untuk materi promosi, namun tidak ada yang benar-benar tepat. Ares terkadang bergerak mengejutkan, dia memegang pena dan kertas sambil pandangannya jauh ke atas, lalu saat ide muncul, dia menghentakkan kaki dengan kuat sambil berteriak yes, lalu menulis. Namun tak lama kemudian apa yang ditulisnya itu kembali dia coret. Kemampuan kami dalam menulis copy memang kurang. Selama ini, hampir seluruh ide copywriting dibantu oleh Trisna. Tak jarang, Trisna juga mendapat keuntungan dari bisnis ini.
“Telepon Trisna aja, deh! Pusing gua. Gak ada ide!” pintaku.
“Lu aja. Dia ngindarin gua.”
“Oke, lah!”
Aku menelpon Trisna. Ares yang tadinya duduk pada sofa berhadapan, kini melompat tepat disampingku, mendekatkan telinganya untuk mencuri dengar.
Aku menatapnya heran sambil menjauh dari wajah Ares dengan raut seolah berkata apa, sih?
Lalu bibir Ares bergerak mengucapkan ‘kangen’. Aku menggelengkan kepala sambil menekan tombol pengeras suara, “Tuh! Lu puas-puasin denger!” ujarku berbisik. Ares tersenyum lebar, sangat lebar seolah garis senyumnya mampu melewati batas wajah.
Aku berbicara pada Trisna, menyampaikan hal yang kami pusingkan. Trisna mendengarkan dan meminta brief client tersebut dikirim melalui email dan mengatakan sebelum jam delapan malam ini dia akan mengirimkan copywriting.
Aku lega.
Ares kegirangan.
“Thanks, Tris,” ujarku.
“Sama-sama, Gam."
Ares yang mesem-mesem membuatku mual.
“TRIS! ARES KANGEN!” seruku sebelum menutup telepon.
Ares terperanjat, wajahnya seolah terpekik. Dia sampai memanjat sofa untuk mencengkram leherku kuat dengan lengannya sambil berteriak “SIALAN LU, MONYET!”
Aku melawan hingga membuat sofa terbalik dan kami jatuh cukup kuat ke lantai. Ares masih mencengkram dan aku masih berusaha membalasnya saat seseorang masuk sambil berteriak, “Astaghfirullah!”
Kami berdua mendongak ke arah pintu, pada posisi yang terlihat terbalik itu berdiri seorang wanita membawa baki berisi dua gelas es kelapa muda. Mbak penjual minuman di seberang.
Ares langsung berdiri, merapikan pakaiannya dan mengambil gelas itu dari baki.
“Thanks, darling…,” ujar Ares sambil mengedipkan sebelah mata jahil.
“Ka-kalian ngapain siang-siang? Kalian lurus, kan?” Mbak penjual minuman tampak sangat terkejut, matanya membesar, mulutnya ternganga dengan wajah merah padam.
“Kadang bengkok, sih…,” jawabku santai sambil memposisikan sofa seperti semula. Dalam hati aku tertawa.
Mbak penjual minuman semakin ternganga. Dia shock berat sehingga tetap dalam posisi memegang baki tegap sempurna walau Ares sudah mengambil dua gelas di atasnya.
“Tapi saya masih doyan perempuan, kok, Mbak!” Ares kembali mengedipkan mata.
“Gusti Allah!” pekiknya kemudian.
Sambil berdengus perempuan itu keluar. Mulutnya jelas sekali komat-kamit mengatakan amit-amit. Sesekali dia menoleh ke belakang kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil bergidik ngeri. Membuat aku dan Ares tertawa terpingkal.
Sambil santai minum es kelapa, Ares mulai bercerita bahwa Trisna sengaja menjauh justru untuk melindunginya. Pacar Trisna yang memang babak belur wajahnya akan melaporkan Ares ke polisi. Lalu Trisna memohon-mohon agar tidak melakukan hal sejauh itu. Kesempatan itu digunakan oleh pacarnya untuk mengancam Trisna, jika saja Trisna masih berhubungan dengan Ares, maka Ares akan berakhir dipanggil pihak berwajib.
“Trisna nelpon gua omongin itu pas baru sampai rumah buat nitipin kacamata mami ke Mbok Rah,” ujar Ares sambil berdecak kesal.
“Kasihan.”
“Siapa?”
“Trisna.”
“Kok Trisna? Gua, dong!”
“Semua perbuatan buruk pasti ada konsekuensi. Lu mukul orang,” jawabku tenang sambil perlahan mengunyah kelapa muda.
“Pacarnya jelas-jelas main perempuan!” ujar Ares kesal.
“Itu urusan mereka.”
“Urusan gua.”
“Lu siapa?”
Ares diam tampak berfikir, lalu tak lama dia memukul sofa dengan raut masam, “Bener. Dia gak bisa jawab pas dulu gua tanya. Mungkin karena itu dia lebih milih jauhin gua,” guman Ares.
“Jadi lu lebih seneng kalo Trisna milih lu di penjara?”
“Penjaranya belakangan, paling juga mediasi kalau kasus begini. Seenggaknya gua tahu kalau Trisna milih gak jauhin gua.”
“Setiap orang emang punya hak buat bego, Res. Tapi lu jangan ambil hak bego orang lain. Bego lu jadi kuadrat!” ujarku kesal sambil meletakkan dengan kuat gelas kosong ke meja meninggalkan bunyi ketukan.
Ares diam, tampak tidak paham. Kelapa dikunyah pelan saat matanya mengerling ke kanan atas tanda berpikir.
“Oke, anggaplah berakhir mediasi. Lu pikir Trisna langsung jadi ama lu? Terus orang tuanya mikir apa? Anaknya ninggalin dokter demi kriminal? Yang ada lu bakal lebih jauh lagi, Goblok!”
Ares sontak berhenti mengunyah kelapa dan kini menatapku tajam. Mungkin dia kesal mendengar apa yang aku sampaikan. Tapi aku ingin dia sadar bahwa tindakan yang dilakukan secara impulsif itu cenderung menyesatkan. Kadang beberapa orang butuh hantaman kuat di kepalanya agar dia tahu kesalahannya. Aku bahkan siap jika Ares menyerang lagi karena marah. Asal dia berfikir setelahnya dan kemudian menyadari bahwa dia kurang mampu dalam mengendalikan diri, tidak masalah.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia diam cukup lama hingga berseru, “Ah! Sial!” sambil menghentakkan gelas yang tidak tandas ke meja. Dia tidak marah, tapi mungkin kesal. Dia tidak menyerang, tapi tadi keinginan itu mungkin ada, sebelum akhirnya dia memikirkan ulang.
“Lagian, sebelum lu lakuin apa-apa, pastiin dulu perasaan Trisna. Biar gak sia-sia.”
Ares mengambil nafas dalam dan mengusap-usap wajahnya.
“Udah, ah,” ujarku sambil berdiri
“Kemana woi?”
“Udud.”
Sore itu, kami merokok sambil kembali menatap pemandangan yang itu-itu saja, lalu lintas sore yang memuakkan. Macet, asap, dan klakson yang memekak. Aku melirik Ares, dia duduk di atas motor, merokok lebih banyak dari biasa dan melakukan hal yang jarang-jarang dia kerjakan: merenung.
*****
Layar ponsel menyala, sebuah pesan masuk. Ini masih jam delapan pagi, aku sedang menyeduh kopi membuka pesan itu, dari Aruna. Dia mengirimkan foto selfie mengenakan baju wisuda lengkap dengan toga. Akhirnya gaun biru muda yang dia kenakan. Aruna berdiri di depan jendela, menampilkan latar belakang suasana kamarnya. Bu Sarah duduk pada tepi kasur sedang mengobrol dengan Bu Hafsari yang duduk di sofa.
Telunjuk dan jempol bergerak saling menjauh untuk membesarkan foto tersebut, melihat dengan jelas wajah Aruna yang manis sekali dengan riasan tipis.
‘Selamat wisuda. Kamu cakep banget!’ balasku.
Tidak lama setelah mengirimkan pesn itu, terdengar riuh ramai dari luar. Suara ketukan-ketukan sepatu pada lantai terdengar tergesa-gesa.
Mereka udah jalan.
Aku duduk pada meja kerja sambil membawa kopi yang tidak terlalu panas sebab aku tidak sabar menunggu air mendidih sempurna. Mengambil pena dan menuliskan tanggal wisuda Aruna pada buku bersampul coklat. Lalu menyalakan komputer, melanjutkan beberapa pekerjaan yang seharusnya aku kerjakan nanti sesampai di studio.
Satu setengah jam kemudian, aku mengirim pesan kepada Ares.
‘buku menu Bu Lin done, desain flyer udah gua masukin copy dari Trisna.’
‘Sip! Ntar gua cek ulang. Salam sama Aruna.’ balas Ares cepat tak sampai semenit setelahnya.
Aku bersiap, segera meraih ransel dan topi lalu melesat ke tempat acara wisuda berlangsung. Perjalanan ditempuh selama hampir satu jam. Hotel yang tidak terlalu besar ini penuh sesak. Untuk memarkirkan motor saja memakan waktu lima belas menit. Aku mempercepat langkah menuju lantai dua berharap sampai sebelum para wisudawan keluar dari ruangan. Mengalungkan kamera dan mengenakan topi sambil berjalan menaiki tangga. Aku tidak bisa menghubungi Aruna, lebih tepatnya tidak memungkinkan. Dia tidak akan membalas atau bahkan tidak mengangkat telepon jika diapit oleh Bu Sarah dan Bu Hafsari.
Tepat saat aku menginjakkan kaki pada lantai dua, pintu ruangan itu terbuka. Perlahan tapi pasti, para wisudawan dan undangan keluar. Ramai namun teratur. Dengan wajah-wajah bahagia mereka saling berbincang dengan orang-orang di kiri-kanan. Lantai dua mulai penuh oleh teman-teman dan keluarga yang hadir untuk memberikan selamat. Banyak di antara mereka yang menerima buket bunga hingga boneka beruang mengenakan toga. Namun aku tidak melihat Aruna. Aku melepas topi untuk pandangan lebih luas.
“Woi!”
Seseorang menepuk pundakku dari belakang. Saat aku menoleh, perasaan menggelikan merayap cepat. Si Culun! Anehnya lagi, aku tersenyum. Sialan!
“Nyari Aruna?” tanyanya.
“Ya.”
“Masih di dalam kayaknya, sama ibunya. Gak tau yang mana, ada dua.” jelas si culun kemudian.
“Oh. Oke.” aku menatapnya dari atas hingga bawah. Untung saja dia mengenakan baju wisuda untuk menutupi selera berpakaiannya yang retro. “Selamat wisuda,” ujarku sambil mengulurkan tangan.
Dia menyambut uluran dan dengan berani menggenggam kuat, seolah itu akan menyakitiku. Aku tersenyum karena ini terasa menyenangkan, andai dia tahu bagaimana aku dan Aruna hampir setahun ini.
“Thanks,” ucapnya.
Lalu dia menggerakkan kepalanya mengisyaratkan kehadiran Aruna. Aku menoleh. Aruna keluar ruangan dengan anggun. Cantik sekali. Sesaat dia keluar ruangan, di mataku orang-orang yang berada di sini tiba-tiba menjadi ilalang kuning, termasuk si culun di depanku. Suara riuh berubah menjadi suara angin lembut. Ilalang-ilalang ini bergerak pelan, berayun seolah mengikuti langkah kaki Aruna yang mendekat. Aruna yang bergerak lamban, rambutnya bergoyang kiri dan kanan dengan lembut menciptakan efek dramatis. Aku tersenyum lebar menyambutnya, senyum selebar yang Ares buat saat sumringah.
“Reza! Kita belum saling ucapin selamat,” ujar Aruna saat tiba di hadapanku.
Halah! Seketika ilalang-ilalang indah tadi berubah ke wujud asli diiringi suara ingar bingar. Aku tahu Reza si Culun hanya sebuah alasan, Aruna sebenarnya ingin menghampiriku. Aku tersenyum sendiri atas apa yang aku bayangkan barusan. Segera mengenakan topi dan mengulurkan tangan ke Aruna.
“Selamat, Mbak,” ujarku cepat sebab Bu Sarah dan Bu Hafsari ikut menghampiri.
Aruna menyambut dengan tenang dan mengangguk pelan. Sebuah sikap yang aku tahu betul dia menguasainya dengan baik. Sedangkan si culun, terperangah kebingungan melihat kami berdua, lalu pamit pergi dengan alasan menemui teman lain.
Aruna terpaku melihat tali strap kamera yang melingkar pada leherku, hadiah ulang tahun dari nya, dengan bordiran ‘GA&AG’ sama seperti huruf yang ada di jam weker.
“Kamu ini, dimana, ya, saya pernah lihat?” Bu Sarah yang sedari tadi melihatku akhirnya bersuara dengan menanyakan hal yang sepertinya sejak dulu dia ingin utarakan. Sejak dia menatapku tajam berpapasan di lorong kost.
“Saya kameramen di acara festival makanan brand kecap itu, Bu.”
“Oohh, iya iya.” respons Bu Sarah terlihat tidak yakin, dia mengangguk perlahan dan tampak berfikir. Menunjukan kurang puas dengan jawaban yang baru saja dia dengar.
Aku melirik Aruna. Walaupun tampak sedikit khawatir, dia tetap tersenyum tenang, elegan, dan CANTIK! ASTAGA! Aku benar-benar ingin memeluknya.
“Saya juga tetangga Mbak Aruna. 301.”
“Oh, iya! Pantes, saya kayak hapal banget sama wajah kamu,” Bu Sarah tersenyum dan sudah tidak tampak ragu lagi, “Kamu datang untuk siapa? Adik?”
Untuk pacar saya yang berdiri persis di samping Ibu.
Aku menggeleng, “Saya kerja,” ujarku sambil mengangkat kamera.
Bu Sarah mengangguk memahami, “Kalau gitu boleh tolong fotoin kami? Soalnya saya gak sempat ke studio foto, harus cepat balik ke Tangerang. Kerja.”
Jackpot!
Aku mati-matian bersikap sewajarnya saat gejolak ingin memeluk Aruna sudah menembus kepala. Mengatakan dengan bangga pada seisi ruangan bahwa perawat cantik dan cerdas ini sudah punya pacar. Tapi apa daya, bahkan untuk datang saja aku harus berpura-pura. Dia tengah sibuk menerima ucapan selamat dan hadiah dari junior serta teman-temannya. Aku menggelengkan kepala pelan.
Gam gam …, begini amat lu demi pacar!
Ujarku membatin, menertawakan diri sendiri.
Aruna, Bu Sarah dan Bu Hafsari berfoto di ruang wisuda dengan backdrop bertuliskan keterangan wisuda dari kampus Aruna. Daripada foto Aruna berpose, aku lebih banyak mengambil fotonya diam-diam, candid yang justru terlihat lebih manis.
“Permisi, Mas. Fotografer, kan? Tolong fotoin, dong…” pinta seorang wisudawati. Aku tercekat, lalu menoleh kepada Aruna. Dia tahu aku meminta persetujuannya lalu dengan permainan raut wajah Aruna mengatakan silahkan saja. Aku sedikit cemberut dan membuat Aruna menutup mulutnya menahan tawa. Dia pergi keluar ruangan bersama Bu Hafsari, sedangkan Bu Sarah menghampiriku, “Makasih, ya. Kalau udah jadi, titip ke Aruna aja. Kabari saya berapanya.” ujarnya sambil menyerahkan kartu nama miliknya.
“Oke, Bu.”
Bu Sarah menepuk pundakku sedikit kuat, sebelum dia menyusul Aruna dan Bu Hafsari yang sedang berjalan keluar ruangan. Aku tidak tahu maksudnya apa, tepukan itu lebih kuat jika dikatakan sebagai basa-basi dan lebih lembut untuk dikatakan sebagai peringatan.
Tapi peringatan untuk apa?
Ah, mungkin hanya perasaanku saja.
Aku menatap punggung Aruna menjauh. Sebelum melewati pintu, dia menoleh ke belakang dengan menunjukkan simbol cinta menggunakan telunjuk dan jempolnya, simbol cinta pada drama-drama korea yang sesekali diikuti Aruna.
Melihat itu aku tertawa singkat.
“Mas? Jadi kan mau fotoin?” suara itu mengingatkan lagi.
“Ah, ya.”
Lalu aku dengan malas-malasan melayani orang-orang yang benar-benar mengira aku fotografer lepas pada acara ini.
Hah~ Malas!
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden




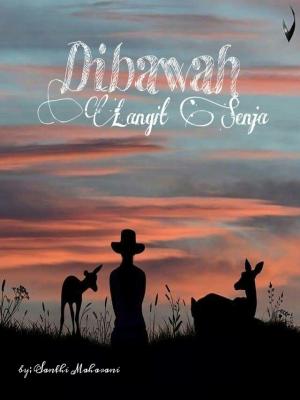








Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)