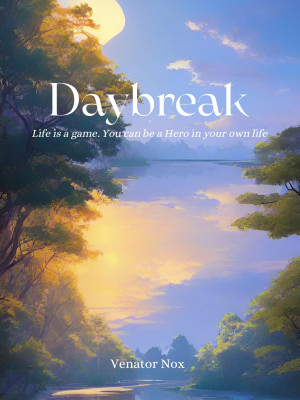Lu pernah kebayang enggak
sih, crush lu datang ke rumah
dan minta izin ke Mama lu
buat pacarin anaknya. —Andira
⋇⋆✦⋆⋇
Semenjak tahu kalau ayam adalah prioritas Mama dimulai jam empat sore sampai senja, aku menyumpahi diri agar tidak keluyuran di selepas waktu ashar. Mau semenarik semenarik apa pun buah mangga di pelataran rumah Jo buat dimalingi, atau begitu gatalnya kakiku mau ke rumah Anan --intinya BIAR SAJA SUDAH!
Dua tempat itu menjengkelkan. Pertama karena rumah Anan yang menjadi penyiar langsung kelakuanku di atas genteng, hingga membuat Renata tak berhenti membuka mulut saat menengadah ke langit-langit. Sumpah, kalau Pak RT yang lihat sih masih aman buatku. Tapi entah kenapa ketika harus di depan Renata, aku merasa seperti curut bau yang mau menandingi seekor kupu-kupu demi perhatian Anan.
Sebenarnya aku tidak cari perhatian, alias hanya klise. Tapi itu bisa dijadikan bahan kalau suatu saat (semoga saja tidak nih, jangan didoakan Aamin!) aku mau menjadi finalis gadis terbaik di dalam hidup Anan. Pemikiran tak berfaedah tersebut jadi seperti tugas kelas saja, berserabut dan memeningkan.
Kedua, tempat lain yang sangat menjengkelkan bagiku, yaitu rumah Jondara. Karena posisinya yang plek ketiplek agak serong kalau mau melihat ke rumah Anan, maka akan melintang begitu jelaslah tubuhku di atas gentengnya. Mudah saja kali, aku yakin Jo seperti melihat kuyang terbang saat tahu keberadaanku di sana.
Mau seberapa kuat aku melupakan kejadian tadi, jadi semakin kuat bayangan wajah Renata yang mirip emoji kuning dengan lelehan hijau di mulut pada papan ketik ponsel kita. Kepalaku jadi berat membebankannya, tapi juga tak mampu dibuang meski truk pengangkut sampah sedang terlihat bekerja di jalan depan rumahku sana.
Dari jendela kamar lantai dua, aku melihat Jo keluar dengan dua buah kantung hitam yang besar; menyumbangkan sampah. Ingin aku teriak dan bilang, "Pak! Angkut aja sekalian sama manusia-manusianya!" sakit terlampau jengkel diriku pada lelaki itu.
Akhir kisah, kututup jendal kamar dan gorden-gordenya. Bertepatan bagaimana kutemui Kak Novan nangkring depan pintu kamar dengan bahalai Gajah Duduk terselempang di badan. "Apa?" Kutanya begitu sambil mengambil peralatan ibadah juga.
"Jamaahan, yuk."
"Lah tumben." Aku membelalak dengarnya, persis ketika melihat tai ayam ada di telapak sepatuku.
"Ayok!" Tanpa neko aku ditarik oleh sang empunya keluar kamar, sampai menuju ruang tamu, di mana ada Mama dan juga ... Anan?
Langkahku tak bertenggang lagi saat di anak tangga terakhir, tak perduli dengan tatapan Kak Novan yang memaknaiku sedang melihat hantu, atau bagaimana senyum Mama begitu mekar saat ini. Karena yang kutahu, seorang Anandra Yang Tampan Anak Dari Tante Ratna ada di rumah kami. Pakai sarung; pakai peci; pakai baju koko juga.
WOI, KUA BISA KUY!
"Andira." Suara Mama mengacaukan ekspetasi itu, aku bahkan tersadar untuk mengambil napas banyak-banyak dari aksi tertahan yang tanpa kutahu terjadinya langsung begitu saja. "Ayo, Nak. Jamaah." Mama juga terlihat lebih semangat kali ini.
Aku secara lumrah saja ya. Keluarga kami mungkin jadi terlihat pasang muka karena tamu yang datang ini bersedia jadi imam. Kupikir semua begitu untuk satu keluarga yang keagamaannya tidak kental-kental sekali. Tapi kami tidak munafik, ibadah yo tetap ibadah. Hanya kali ini saja bisa dilakukan sama-sama dengan tempo waktu yang kebetulan mirip berada di masa luangnya dan ketika ada imam baru pula.
"Allahu Akbar." Mendengarnya itu, hatiku bergetar tanpa henti sampai ibadah kami selesai.
⋇⋆✦⋆⋇
"Tante Ratna nitipkan Anandra di sini, soalnya khawatir kalo sendiri di rumah. Nanti tidurnya sama Kak Novan." Sambil menunggui potongan ayam yang berenang di dalam wajan, Mama memberikan deskripsi singkat bahkan sebelum aku bertanya.
"Nginep?" Jadi kulanjutkan saja berbasa-basi sambil mencomot beberapa piring dari raknya.
"Iya," sahut Mama.
Aku agak tertunduk lalu menatap piring putih yang ada di bawahku, tiba-tiba wajah Anan terlukis di sana sambil menaik-turunkan dahinya, aku jadi senyam-senyum sendiri sampai kepergok oleh Kak Novan yang lagi buka pintu kulkas di sebelahku. "Naaaa, mulai mulaaiii." Dia menunjukku dengan gerakan siput, dan ketika mau kutangkis, gerakannya berubah jadi kilat.
"Ma, mulai gila dia, Ma!" Kak Novan berlalu dengan jalan yang melonjak. "Senyum-senyum tadi, Ma!" Kemudian nongol lagi dari jarak jauh.
"Kak Novaaannn!" Aku hampir lupa kalau Anan di sini, jika saja tidak, sudah kukejar tubuhnya sampai tertangkap dan kubogem banyak-banyak. "Apa sih ah, bikin kesal aja." Bibirku manyun sambil melipat tangan depan dada.
"Ssssttt, kakakmu lagi caper aja karena seneng ada temen tidur," ingat Mama.
"Dih sok iya aja dia." Aku bergegas mengangkat piring dan berjalan ke meja makan, di situ isinya ternyata sudah ditongkrongi oleh dua orang, Kak Novan dan Anan. Aku sih realistis saja, masih jengkel dengan satu lelaki dewasa yang tertawa-tawa menyambut kedatanganku, dan semakin jengkel saat lihat Anan diam-diam menyimpan raut olokkannya.
Ekspresi mereka bahkan masih terasa sama meski meja makan sudah dipenuhi bahan konsumsi kami malam ini. Aku yang duduk di sebelah Mama diam-diam mengulurkan jari tengah pada Kak Novan. Plak! Naasnya ketahuan Mama sampai gelak orang di seberangku pecah dua-duanya.
"Abang paha ...."
"Punya adek!" Kusambar begitu saat Mama mau menyodorkan sepotong paha ayam yang ditusuk pakai garpu.
"Ma ...."
"Punya Adek!" Lagi. Ayam tersebut berakhir melayang di antara dua kubu yang memperebutkannya, sedangkan Anan menghentikan gerakkan sembari melihat isi piringnya yang berisi potongan paha ayam juga. Omong-omong, Mama yang menyodorkan itu pada Anan. Tanpa ingat kalau dua anaknya pasti akan bersengketa hanya karena sepotong paha yang tersisa.
"I-ini buat Andira." Mama menghela napas ketika potongan paha yang semula dipiring Anan berubah posisi kepadaku, sementara sisanya yang masih melayang di udara akhirnya mendarat di piring Kak Novan.
"Maaf ya. Nak ...."
"Eh! Enggak apa-apa, Tante. Aku 'kan tamu, enggak enak kalau bikin orang jadi berantem."
Aku dan Kak Novan jadi tatap-tatapan ketika berbarengan menggigit potongan paha ayam yang sudah jadi milik kami masing-masing. "Sudah tua enggak mau mengalah," sindirku.
"Muda-muda enggak menghormati yang tua," sambut Kak Novan.
Mama geleng-geleng kepala dan pastinya berusaha menahan diri agar tak melayangkan sendok nasi ke puncak kepala kami. Kupikir Anan juga membantu dalam mengendalikan kesabaran beliau, dia hanya tersenyum-senyum sambil memandangku yang duduknya memang seberangan.
"Gimana rasanya balik lagi ke sini, An?" Kak Novan tanya di sela aktivitas kami.
"Seneng, Bang." Begitu saja jawabnya Anan.
"Gantengan ya lu sekarang, dulu ingat kagak kalo muka lu kayak alien di Toy Story?" Sambil tertawa kecil, Kak Novan masih terlihat sebagai orang yang dihormati oleh Anan. Padahal kalau aku yang duduk di sebelahnya, sudah kugetok gigi lelaki itu sampai dia tak mungkin bisa menyengir tanpa dosa begitu. "Eh, lu punya tanda lahir di dekat telinga, ya?" Apalagi waktu Kak Novan menunjuknya dengan jari telunjuk yang ditempeli beberapa nasi, aku sampai mendesis supaya jari itu jangan kena kulit tubuh Anan.
"Emang kenapa, Bang?" Anan tanya balik sebagai bukti tak keberatan dengan obrolan tersebut.
"Nih ya, menurut legenda ...."
"Mulai mulai." Aku menyela dan membuat Kak Novan melotot.
"Diem! Makan aja ngapa situ. Repot amat," sahutnya dengan tatapan yang terganggu dengan kehadiranku. "Menurut legenda." Kan, akhirnya dia lanjut bicara. "Tanda lahir sebenernya bekas peninggalan oleh kehidupan yang udah lampau. Itu bukan sekedar luka, tapi kayak gimana cara lu mati dalam kehidupan sebelumnya."
Aku dan Mama mungkin menganggap lumrah pembicaraan itu. Jika ada yang percaya dan merasa kagum akan kisahnya, bisa saja itu adalah anak-anak TK sampai dengan yang tengah berada di kelas tiga SD. Bukan berarti kami yang berusia belasan tahun akan mudah didongengi. Kecuali aku curiganya ketika lihat ekspresi Anan, dia menunjukkan binar yang setara dengan usia anak-anak yang kusebut sebelumnya.
"Beneran, Bang?"
DIA PERCAYA DONG!
"Cuma spekulasi, jangan percaya. Korban Tiktok dia itu," tegur Mama.
"Lah, dulu Mama yang bilang gitu lho." Kak Novan tak terima. "Abang punya tanda lahir di dada, konon, Abang dulu adalah raja yang dibunuh pakai panah demi membela rakyat."
Aku tergelak. "Adek punya di dekat mata nih, apa itu tandanya dulu Adek punya rinnegan?" tanyanya.
"Itu tai lancung."
"TAI LALAT!" Buru-buru kusemprot ejekkan dengan fakta, hampir harga diriku dipandang rendahan depan Anan. Sedangkan sang empunya tertawa lagi dengan perdebatan kecil kami.
"Maaf ya, Nak Anan. Besok-besok kalo jera main ke sini bilang aja." Mama lagi-lagi masih memperhatikan perasaan Anan, padahal kulihat dia sangat menikmati kealamiahan keluarga kecil kami.
"Oh iya, katanya Tante Ratna enggak ada dari kemarin. Tapi kenapa lu baru ke sini hari ini? Padahal enggak apa-apa kalo mau gangguin Andira, mageran juga anaknya kalo di rumah. Pas ada lu nih, jadi agak rajin."
Akulah sang botol kecap yang habis isinya. Alias, sudah tak ada kata-kata yang mampu kusembur pada omongan Kak Novan barusan. Aku pasrah saja sudah, seperti caption Tiktok : Capek-capek bangun image sebagai gadis elit, tapi lu punya abang yang miskin akhlak ngumbarin aib lu.
"Enggak enak aja, Bang. Gue kurang suka ganggu orang lain," jawab Anan.
"Kenapa jadi enggak suka?" Kak Novan tanya balik.
"Karena gue enggak suka diganggu," jawab Anan lagi, "Tapi kalo Andira yang ganggu, enggak apa-apa. Gue suka deh ...."
"Hussss!" Buru-buru kupotong bicara. "Omongan lu ...."
"Lu naksir Adek gue?" Baiklah, obrolan ini sama seperti barang obral. Yang berkelas akan terkesampingkan, seperti keberadaanku. Sedangkan barang murah laksana mulut Kak Novan, dia maju paling terdepan menggaet hati seseorang, termasuk menarik perhatian kami semua yang ada di sini.
"Izin, Tante." Anan membuatku tak mampu mengunyah makanan lagi, mungkin dia tidak tahu hal itu, karena fokusnya hanya pada Mama sekarang. "Izin suka sama Andira," lanjutnya.
Tbc;


 sunht06
sunht06