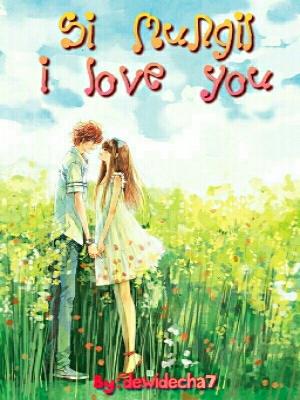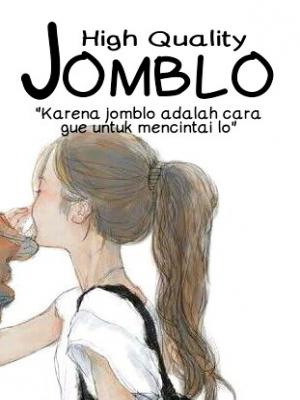Kangen elit, ungkapinnya sulit.
—Andira
⋇⋆✦⋆⋇
"Dek, ada Anandra." Kak Novan menyembul di balik pintu lalu pergi begitu saja. Masalahnya, aku takut dia cuma iseng, seperti kemarin bilang kalau Jo sudah pulang hingga membuatku berusaha keras berjalan ke rumah seberang. Tapi apa yang kudapat? Kosong. Rumah itu tidak berpenghuni sama sekali.
Hal itu menyebabkan aku tidak mau percaya omongannya hingga tetap di kamar saja, namun suara ponsel yang berdering memunculkan nama Anandra sebagai si pemanggil. Jangan bilang dia sungguhan di rumahku?
"Keluar woey, gue di pelataran!"
Ya Tuhan, ada Anan di depan. Aku hampir memukuli wajahku sendiri karena kesal membuatnya menunggu lumayan lama. Buru-buru kucoba bergerak menghampirinya, omong-omong kakiku tidak begitu nyeri lagi, sudah rutin diurut dan diberi minyak. Tapi tetap saja aku tidak berani mengajaknya berlari cepat seperti biasa, jadi Anan masih harus menunggu sampai aku berhasil menghampirinya ke depan.
"Anaaannn!" sapaku heboh, tiba-tiba muncul keinginan untuk menonjok wajahnya yang ganteng itu.
Namun ia tidak menggubris, terlihat kesal karena aku datang lama. "Ih maaf, kukira Kak Novan bercanda. Soalnya kemarin dia bilang Jo udah pulang dan bikin gue harus susah-susah nyebrang ke rumahnya," ujarku dengan langsung duduk di sebelahnya.
Terdengar Anan menghela napas, lalu menatapku dengan artian lagi marah. "Pas denger nama Jo, lu cepat bergerak ya, Dir." Dia mulai lagi, dan sifat ini sedikit menggangguku beberapa hari terakhir.
"Bisa enggak jangan ngomong kayak gitu? Lu dengan Jo sama-sama sahabat gue," ujarku.
"Tapi gue bukan sahabatnya Jondara, dan Jondara bukan sahabatnya gue."
"Anan, kalo lu emang sahabat gue. Maka musuh gue adalah musuh lu, dan sahabat gue adalah sahabat lu juga. Ngerti gak sih?"
"Jadi, pacar gue adalah pacar lu juga?"
"YA ENGGAK GITU JUGA!"
"Halah!" Anan sedikit menjauh, dan itu membuatku geram hingga mendekati dirinya lagi. Sifat ini masih sama seperti dulu, saat aku datang terlambat ke rumahnya, maka Anan akan menghindar hingga aku harus memeluknya dulu agar tidak mengamuk. "Jangan deket-deket!" Bahkan aku sudah hapal kalimat ini, tapi tidak mungkin 'kan aku mendusel dan peluk-peluk dia yang sekarang?
"Marah-marah terus ya, Anan," kataku sok ingin menggelitikinya, jari-jari tangan bergerak lentik untuk melakukan hal itu hingga ia jijik melihatnya. Lantas guna menghindar, Anan berdiri dan mengambil langkah untuk menjauh.
Namun aku tidak mau menyerah ya, kukejar dirinya hingga halaman rumahku berisi keributan baru antara kami berdua. Lama-lama ia tertawa, mengejekku karena tidak dapat meraihnya. "Sini gak lu!" Dan berujung aku yang kesal karena menerima wajah ganteng yang berusaha dijelek-jelekkannya itu, tapi namanya juga orang ganteng, mau dia olesi oli di wajah iya tetap saja ganteng.
"Kaki lu?" Anan kaget karena sadar kondisiku belum bisa dikatakan sembuh, ucapannya membuatku terdiam dengan kedua mata yang membulat sempurna.
Aku lupa, sungguh! Kakiku tiba-tiba terasa sangat sakit hingga perlahan aku terjatuh ke permukaan tanah. "Anan sakit!" rengekku yang membuatnya segera datang mendekat. Jujur, tadi saat lari-lari tidak terasa sakit, mungkin karena arah fokus hanya tertuju untuk menangkap Anan. Tapi sekarang, Ya Tuhan, kakiku terasa patah.
Anan menggendongku untuk menepi ke pelataran rumah, lalu ia masuk ke dalam untuk meminta apa saja yang bisa mengobati kakiku. Terlihat minyak urut yang biasa digunakan Mama untuk memijatku, Anan terlihat duduk di depan dan meraih bagian kaki yang ingin ia urus, diletakkannya di atas pangkuan dan mulai mengoleskannya.
"Maaf, Andira. Jangan nangis," katanya.
Terlihat Anan bingung mau berbuat apa, jadi dia hanya menekan kecil jari jempolnya secara naik turun di setiap elusan. Wajahnya begitu serius, seakan apa yang terjadi adalah karena salahnya. Padahal akunya saja yang babal jadi manusia. "Enggak apa-apa, Anan." Untuk sesaat, aku bisa melihat sosok Anan kecil di sini, suasana yang halus dan manis antara kami berdua.
"Udah enggak sakit, tadi syaraf gue kaget aja karena lu tegur." Kutarik bagian kaki yang berada di pangkuan Anan, lalu memintanya untuk kembali duduk di sebelahku. "Lu tau, gue ngerasa sedih di saat lu membandingkan diri sama Jo. Seakan kami enggak bisa nerima lu untuk bergabung, atau mungkin tentang gimana lu yang berharap mau sama gue aja tanpa adanya sosok Jondara. Tapi Anan, apa lu ingat gimana besarnya usaha kita dulu buat ngajak Jo main sama kita? Tentang sosok anak kecil yang dijaga sama Bundanya buat jangan keluar sama sekali," ujarku padanya.
"Dulu, di bawah pohon mangga tempat kita main dan ngelempar batu buat ngambil buahnya, gue nangis di sana. Berharap lu datang dan bilang jangan nangis, Andira. Tapi semakin hari, itu semua terasa kayak angan-angan doang, mungkin karena gue nangisnya ngegembel banget, tiba-tiba Jo keluar. Itu hari di mana dia pertama kali menginjak tanah bahkan tanpa alas kaki, dan itu juga jadi hari pertama di mana dia dimarahin sama Bundanya."
Anan terdiam, tampaknya ia hanya ingin menjadi pendengar setelah selama beberapa hari ini aku tidak pernah merespon keluh kesahnya.
"Bukannya takut sama Bunda Yohana, gue malah semakin menjadi-jadi main ke situ. Apalagi setelah nemuin Jo pernah keluar buat datangin gue, namanya anak-anak, gue semakin memancingnya main sama-sama. Sampai hal itu berhasil pas beliau lagi ke pasar. Gue sengaja bawa gayung sama sabun rinso, buat main gelembung, dan airnya kami dapat dari selokan depan rumahnya." Kulanjutkan cerita di mana Anan memang harus tahu cerita ini, agar dia juga tidak selalu salah paham akan diriku yang katanya mau melupakan dia karena sudah berteman sama Jo.
"Dia ketawa, bahkan kelihatan bahagia banget. Meski itu cuma permainan yang kami lakuin secara diam-diam, dan lu harus tau hal ini, waktu itu Jo nanya mana Anandra? Gue sempat diam, lama, bahkan bingung mau bilang apa. Karena waktu itu hanya satu yang gue tau tentang lu, Anan pergi, dan kalimat itu yang keluar dari bibir mungil gue." Aku menghela napas dan mengalihkan pandangan ke arah rumah Jo, bagian kecil dari bumi yang punya banyak cerita tentang kami semua muncul di sana.
"Setelah itu Jo nangis karena ngerasa kehilangan sosok yang belum sempat dia jadikan teman," lanjutku.
⋇⋆✦⋆⋇
Sebuah mobil sewaan terlihat berbelok ke arah rumah seberang, hal itu membuat tubuhku yang sedang duduk santai di pelataran rumah bangkit. Tepat satu minggu aku tidak bertemu dia, tidak menganggunya, tidak mendengar ocehannya. Aku juga padahal mau datang berkunjung ke rumah sakit, tapi kata Mama, bukannya Jo cepat sembuh malah semakin sakit. Makanya, saat melihat bagaimana Tante Yohana mengiringi Jo berjalan keluar dari mobil, aku berusaha menyebrang ke sana dengan langkah kaki yang masih belum stabil-stabil sekali.
"Jondara!" teriakku, dan hal itu membuat Bunda Yohana geleng-geleng kepala karena kehadiran anak gadis nakal yang tidak pernah jera main ke rumahnya. Meski beliau galak, aku tidak pernah takut menghadapinya, contoh saja sekarang di mana aku ikut masuk ke kamar Jo. "Masih hidup aja lu?" Dan pertanyaan itu membuat Bundanya mencubit lenganku dengan kuat.
"Tak pites kepala kamu ya, Andira!" kata beliau dengan pergi keluar meninggalkan kami berdua.
Percayalah, rasanya perih sekali, aku masih mengelus bagian itu hingga Jo tampak terhibur melihatnya. "Dasar tolol," ujarnya.
"Jo." Kupegang tangan yang kekar itu erat-erat sambil melihat bagian jidat yang masih ditutupi perban. "Maafin gue, kalo aja gue gak mulai pasti lu baik-baik aja. Gue pikir lu bakal mati, Jo. Malam-malam gue nangis karena takut arwah lu gentayangin kamar gue, berarti kemarin kita kurang laju," ujarku.
Jo menghela napas lalu menarik tangannya. "Lu memang barbar, kenapa harus ikut jatoh? Jadinya enggak ada yang jagain gue selain Bunda," ujarnya.
Mau bagaimana lagi? Waktu itu fokus mataku hanya pada adegan motor menabrak tubuh mobil, setelahnya keseimbanganku hancur hingga 'tak mampu mengendalikannya. "Luka lu." Aku ingin menyentuh bagian jidat Jo yang saat itu pernah mengeluarkan banyak darah, tapi ia menghindar dan mendorong bahuku.
"Rawan, anjer! Lu deket banget sama gue, sana jauh-jauh! Gue udah gak papa kali."
Aku tersenyum dan memukul bahunya hingga mengaduh. "Tapi gue serius, selama satu minggu ini gue khawatir sama lu," ujarku.
"Dan gue mau muntah bayanginnya," sahut Jo mendorong bahuku dengan kuat, bayangkan, padahal dia masih belum stabil sekali, tapi kekuatannya masih mampu membuatku hampir terjatuh dari sisi ranjangnya. "Gue udah sehat, besok bisa sekolah," katanya.
"Jangan macam-macam!" Bunda Yohana masuk dengan membawakan air minum jeruk, meski kami suka bikin gaduh, nyatanya beliau tidak sejahat itu sampai tidak memperhatikan kami. "Istirahat dulu, motor kamu juga enggak bisa dipake lagi," ujarnya.
Seketika aku merasa bersalah, membayangkan berapa besar kerugian yang dialami Jo dan membandingkannya dengan uang ganti kecelakaan dan sumbangannya, Ya Tuhan, berarti uang yang dia terima hanya dihabiskan untuk pengobatan. Hal itu mampu membuatku terdiam dan sedikit menunduk, aku juga tidak langsung menyerbu minuman yang disediakan padahal biasanya langsung ludes sekali hadap.
"Bukan salah lu." Jo seakan paham kenapa aku tampak beda. "Namanya juga kecelakaan, salah gue karena gak bisa ngatur semuanya." Bahkan ia mengatakan itu agar sang ibu tidak salah paham mengenai hal ini.
"Maaf, Jondara. Maaf, Tante." Tapi tetap saja aku tidak bisa menghindari rasa bersalah ini, dan jika Bunda Yohana marah pun tidak masalah bagiku. Namun, sebuah elusan di puncak kepalaku merubah segala rasa bersalah itu menjadi haru.
"Kondisi kamu gimana? Ini ya yang luka? Masih sakit?" Beliau berjongkok dan melihat-lihat keadaan kaki yang masih terbalut perban, padahal hanya memar dan terkilir di situ, bukan luka. Aku saja yang sok berlebihan buat pamer ke sekolah kalau kakiku terluka, jadilah kupaksa Kak Novan buat membalutnya secara asal-asalan.
"Tante, maafin Andira ya. Jangan larang Jo main sama Dira ya, Tan. Soalnya rumah ini bakal sepi kalo enggak kami bikin keributan, nanti Tante juga gak punya orang buat dimarahin."
Beliau tertawa, bahkan mengelus kedua lenganku seakan merasa gemas. "Kamu temannya Jondara, gimana bisa Tante yang ngatur. Kalian bakal pisah kalo salah satu dari kalian ada yang meninggal, selain dari itu, Tante yakin enggak ada yang bisa pisahin kalian," ujarnya.
Padahal keramahan ini bisa kujadikan kesempatan untuk mencari gara-gara, seperti mendorong beliau dari atas atap, atau memukul kepala anaknya menggunakan panci penggorengan. Sayangnya saja, kami mendadak bersikap manis seakan sedang menciptakan sejarah baru di hubungan perbacotan ini.
"Bunda ke dapur dulu, mau makan apa kamu, Nak?"
"Telur dinosaurus." Itu suara Jo ya, bukan aku.
"Edan!"
Kami tertawa saat melihat sifat aslinya kembali, beliau sempat menyentil telinga kami satu persatu baru pergi keluar. Kini tercipta lagi suasana di mana hanya ada aku dan Jo saja, kami saling beradu tatap entah untuk melakukan penyaluran gaib apa. Sebab setelahnya, ruangan ini lagi-lagi pecah dengan tawa yang tidak tahu apa sebabnya, tapi menurutku, rasanya sudah lama tidak tertawa sama Jo hingga setidaknya itulah yang kuperlukan sekarang.
"Bisa-bisanya satu mingguan ini gue kangen sama lu, Dir."
Dan apa yang dikatakan Jo barusan, membuat kamar yang kami tempati menjadi sepi.
Tbc;


 sunht06
sunht06