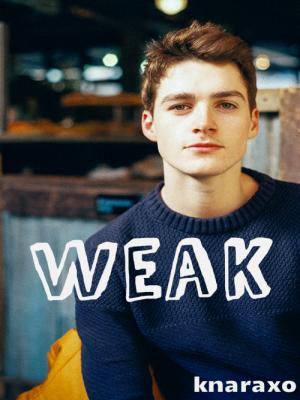Kumala menghambur memeluk Ara ketika kami baru menjejakkan kaki di halaman depan rumah. Padahal di sini, aku adalah kakaknya. Mengapa malah gadis itu yang disambut bagaikan ratu?
“Aku kira kalian berdua nggak pulang seminggu ke depan,” ujarnya.
“Tadinya sih, Kakak mau menetap di sana sehari lagi. Tapi Kakak juga kangen Kumala. Gimana, dong?”
Kutatap mereka yang saling merangkul di depanku. Mencibir, kuputar bola mata kesal. “La, kamu kok nggak pernah ya begitu ke Masmu sendiri?”
Dua perempuan di depanku itu menoleh. Di tempatnya, Ara tampak menahan senyuman. “Males ah. Bosan lihat Mas Radi.” Spontan, Ara meledakkan tawanya diikuti Kumala. Sialan. Senang sekali mereka rupanya mencampakkan aku.
Masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, Ibu menyambut putri kesayangannya itu dengan pertanyaan beruntun. Padahal aku adalah anaknya! Ibu dan Kumala sama saja.
“Kamu sudah makan, Nduk? Aduh Ibu kira kalian betah di sana dan ndak pulang. Kumala terus nanyain soalnya.”
“Sudah, Bu. Tadi sebelum berangkat sudah makan.”
“Yowis. Kamu ndang mandi. Kalau nanti malam pengin teh atau sesuatu, bikin saja. Atau minta buatkan sama Radi.”
“Kok aku sih?” Suaraku di belakang menyambar bagaikan petir di malam hari.
Ibu menghampiriku dan meninju bahuku pelan. “Uwis toh. Jangan jahat-jahat sama dia. Kalian berdua ndang mandi ya. Biar capeknya hilang.”
Usai mengiyakan kalimat Ibu, kami melenyapkan diri memasuki kamar. Kuhidupkan lampu dan meletakkan ransel di atas kursi. Tak lama, kurasakan keberadaan sebuah lengan yang merayap melingkar di pinggangku. Mengembuskan napas, kusambar handuk di tiang gantungan dan berbalik untuk menyodorkannya kepada gadis itu. Spontan ia mengerucutkan bibir dan mendesis.
“Jahat banget.”
“Mandi, Ra.”
Sebelum enyah menuju kamar mandi, ia daratkan tendangan mengenai kakiku dan membuatku mengaduh kesakitan. Gila. Tenaganya semakin meningkat. Kejam sekali ia. Aku tak yakin akan berani macam-macam bila ia kuperistri. Bisa-bisa mukaku setiap hari akan babak belur.
Ah, ngawur. Kugeleng-gelengkan kepala karena telah memikirkan hal yang bahkan masih belum pasti itu.
Menjamah ponsel, aku memosisikan diri di pinggiran kasur dan membaca pesan-pesan Dirja.
Dirja: Ada orderan lukisan nih. Udah pulang belum?
Reply: Yang mana? Iya. Udah pulang.
Tak lama, ia mengirim satu gambar lukisanku dengan sosok wanita gipsi terpampang di sana. Mataku melirik jajaran lukisan yang kuletakkan di depan tembok. Kupilah-pilah sekadar mengecek apakah benda itu ada di sana.
Denting ponselku terdengar.
Dirja: Aku ke sana bentar lagi. Mau keluar juga nggak sekalian?
Reply: Nggak deh. Besok aja. Ara pasti capek.
Dirja: Waduh. Tumben banget seorang Dewangga Fajar Pradipta mengkhawatirkan seorang perempuan. Bagus deh, Di. Aku sempet takut kalau kamu itu gay.
Reply: ASU.
Terakhir, ia mengirim stiker tertawa. Menyadari keberadaan Ara yang baru memasuki kamar, kuletakkan ponsel di atas kasur dan menghampirinya. Rambutnya yang masih basah itu meneteskan air dan membasahi kausnya. Mendekatkan wajah, kuendus aroma tubuhnya. “Hm. Gini dong, wangi.”
Ia menyodorkan handuk tepat terkena mukaku dan tersenyum miring hiperbolis. “Mandi, Radi.” Kukeluarkan kekehanku mendengar balasannya. Ia balas dendam padaku rupanya. Maka, kuputuskan untuk pergi membersihkan diri setelah mencubit pipinya dan membuatnya mendesis murka.
Aku pernah mendengar kalimat konyol yang mengatakan bahwa kamar mandi adalah tempat terbaik untuk berpikir. Dan ternyata memang benar. Bukan kelas, tapi kamar mandi, yang membuat kita merenungkan sesuatu. Ruangan ini serupa ruangan penuh ilham dan ide-ide baru.
Di kepalaku, terputar kembali kalimat-kalimat Ara yang memintaku agar mengatasi rasa ketakutanku sendiri dengan ikut bersamanya ke Jakarta. Bila aku menanyakan hal ini kepada Ibu, sudah pasti ia akan memberiku kebebasan memilih sesuai kehendakku sendiri. Namun, benar memang, aku akan sangat egois bila aku tetap berhenti di tengah jalan meskipun aku tahu sekarang akulah tulang punggung keluarga. Satu-satunya lelaki di rumah ini.
Kugesek-gesekkan handuk pada rambutku yang basah. Di atas kasur, Ara tengah memainkan ponselku dan menepuk-nepuk tempat kosong di sampingnya. Memberiku kode untuk mendekat. Menghampirinya, kuusap lembut sebelah pipinya. Sedangkan ia mendongak menatapku dengan matanya yang bagaikan lintang kejora. “Bentar ya. Aku mau ke Ibu dulu.”
“Oke.”
Usai mendapatkan persetujuannya, aku melangkah keluar kamar dan beralih mengetuk pintu kamar Ibu. Dari dalam, suaranya terdengar menyuruhku masuk saja. Ia tengah menjahit kain di pinggiran kasur dengan kacamata yang bertengger di pangkal hidungnya. “Tumben. Ada apa toh?”
Kuhampiri ia, lantas duduk menekuk lutut dan menyandarkan kepala di atas pahanya. Kurasakan tangannya mengelus rambutku perlahan. “Bu, Radi mau ngomong.”
“Ada apa? Hal serius?”
Tanpa mengangkat muka, aku berkata, “Ara mengajak Radi ke Jakarta.”
“Ya bagus, dong. Mungkin saja kamu bisa mencari penghasilan tambahan di sana. Kenapa? Masih takut?”
“Menurut Ibu sendiri gimana toh, Bu?”
Tangannya beralih mengelus punggungku. “Kamu tahu betul jawaban Ibu, le.”
Pada saat itu, barulah kuangkat kepala memandangnya yang tersenyum menenangkan. “Kalaupun iya, Radi minta restu yo, Bu?”
Kekehan singkatnya terdengar. Ia menepuk-nepuk pipiku. “Doa Ibu dan restu Gusti Pengeran ndak bakal lepas, le. Masa anak lanang Ibu mentalnya mental cengeng? Sudah berani menggandeng perempuan pula. Tanggung jawabmu bertambah satu.”
Kurasakan wajahku memanas, merambat hingga telinga. “Radi bakal bicarakan sama teman-teman Radi dulu mantapnya bagaimana ya, Bu.”
“Bagus. Yowis. Sana, Ibu lagi menjahit iki lho.”
Sebelum benar-benar mengangkat badan, kuangkat kepala kembali memandang Ibu. “Bu, kelupaan.”
“Apa lagi?”
“Radi boleh tidur sama Ara?”
Spontan, ibu mendelik seraya tertawa dan menghujaniku dengan pukulan tangannya. “Dasar bocah gendeng.” Tawanya menular, membuatku terbahak-bahak seraya menahan pukulan mematikan darinya.
“Jadi boleh ndak, Bu? Katanya Radi ndak boleh jahat-jahat sama dia?”
“Wis wis, kono. Sakarepmu.”
Terbahak, kukecup kedua pipi Ibu sebelum benar-benar enyah dari sana. Hendak aku menghambur masuk ke dalam kamar, suara Dirja dari pintu depan terdengar lantang memanggil namaku. Cepat-cepat kulongokkan kepala dan memberinya kode untuk tidak berisik. Kuhampiri ia dengan jari telunjuk di bibir menyuruhnya diam.
“Kenapa sih?”
“Kamu pulang aja deh. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi nanti, nunggu Ara tidur dulu.”
Ia menatapku dengan pandangan curiga. “Kalian nggak lagi mau ngapa-ngapain, kan?”
“Jangan ngawur. Ya enggaklah. Ada Ibu juga.”
“Jadi kalau nggak ada Tante Kinar, itu anak orang bisa kamu apa-apain? Pinter amat akalmu.”
Berdecak, kudorong bahunya agar segera enyah. “Udah. Sana. Nanti aku kabarin.”
“Iya, Sayang, iya.” Ia memutar bola matanya ke atas sebelum memosisikan diri di atas motor dan pergi dari halaman depan rumahku. Usai itu, kututup pintu dan beranjak menuju kamar. Kutatap Ara yang duduk menyelonjorkan kaki di atas kasur seperti istri yang tengah menunggu suaminya agar segera bermain.
Menyadari keberadaanku, ia mengerutkan kening. “Lama banget. Ngomongin hal penting sama Ibu?”
“Enggak. Kenapa sih? Masa ditinggal begitu aja udah kangen?”
Ia mendecakkan lidah sekali. Duduk di sampingnya, kulingkarkan lenganku merengkuh bahunya. Detik berikutnya kurasakan cubitan dari jemarinya yang dihiasi kuku-kuku cantik itu, membuatku meringis pedih. “Lihat nih. Si Sara itu kenapa kirim pesan ke kamu pakai nanyain lagi apa lagi apa segala. Ngaku deh. Kalian ini pasti ada apa-apa, kan?”
“Mana lihat?” Hendak tanganku menjamah ponsel, ia menjauhkan benda itu namun tetap memperlihatkan isi pesan Sara padaku. “Biasanya juga gitu. Apanya yang salah?”
“Apanya yang salah? Oh jadi gitu ya. Dari isi chatnya aja udah ketahuan banget dia suka sama kamu, lho.”
Kucebikkan bibir menanggapinya. Jadi begitu ya? Aku baru tahu hanya dengan satu kalimat tanya bisa disimpulkan sebagai rasa suka. Kuangkat bahu merasa hal itu tidak penting sama sekali. “Udahlah. Siniin, nanti kamu marah terus.”
“Nggak!” Ia menjauhkan lagi ponsel itu dari jangkauanku. Masih di dalam chat room Sara, ia membuka kamera dan memotret kaki kami berdua. Lantas memberikannya caption: Lagi sama cewekku nih.
“Wih, gila. Kamu ganas ya ternyata.”
Mengunci layar ponsel dan meletakkannya di atas meja, ia menolehkan kepala padaku dan membelalakkan mata. “Kenapa? Takut dia cemburu?”
“Kayaknya yang cemburu di sini justru kamu deh.”
Memajukan wajahnya mendekat, ia berbisik seolah-olah mengancam seorang tawanan. “Kamu mau mampus ya?”
Kukecup pucuk hidungnya sekilas. “Aku pernah bilang, kan, kamu itu super jelek kalau lagi marah?” Sebelum ia membuka suara, kuperosotkan tubuhku dan merebahkan badan. Kubuka lenganku sebagai kode agar ia mendekat. “Ayo tidur, Ra. Kamu nggak capek apa tadi perjalanan di kereta dan sekarang malah marah-marah?”
Kutunggu ia tanpa menghilangkan senyuman. Beberapa detik ia menatapku dengan tatapan garang. Namun pada akhirnya ia memilih menyerah dan merangsek dalam dekapanku. Selagi ia mencoba memejamkan mata, kukecup berkali-kali kening dan kelopak matanya, sedangkan tanganku menepuk-nepuk punggungnya bagaikan ayah pada anaknya. Dengan begitu, kuharap ia dapat tertidur dengan cepat.
*
Udara dingin malam semakin menusuk dan menembus tulang-tulangku seperti biasa. Namun warung kopi di depang gang rumah masih tetap ramai dipenuhi gelak tawa bapak-bapak di depan televisi. Sedangkan aku, Dirja, dan Ian yang hanya ikut-ikutan memilih menepi di atas kursi bambu lain.
“Ya baguslah, Di. Kamu ada niatan berkembang,” ujar Dirja dengan rokok di apitan jarinya. “Ajak aku juga ya sekalian. Aku khawatir sama dirimu kalau ke sana sendirian. Ya kalau keluarga Zeline mau menampung, kalau enggak? Bisa-bisa jadi gelandangan dirimu.”
“Ibu juga ngebolehin.”
“Ya iya, makanya. Kalaupun nanti usahamu di sana sukses, dan berhasil memasukkan karyamu ke galeri, kamu bisa cari perempuan lain. Jaga-jaga kalau Zeline udah nggak mau sama kamu.” Lantas, Dirja terbahak-bahak, diikuti Ian di sampingku.
“Kalau ngomong jangan ngawur, ah.”
Dirja melumat batang rokoknya di atas asbak kaca. Lantas memandangku, mirip figur ayah yang hendak memberi nasihat kepada anaknya. “Di, aku bicara sesuai apa yang udah-udah. Realita. Biar bagaimanapun cintamu ke perempuan segede badan Gatotkaca dan setinggi Gunung Arjuno, kalau memang ditakdirkan pisah ya pisah aja. Hidup sama kenyataan-kenyataannya memang kejam, Di.” Ia merangkul bahu Ian dan mendekap lehernya. “Kamu fokus sekolah aja. Jangan mentang-mentang denger beginian bisa coba-coba pacaran. Cari uang dulu. Jangan kayak Radi, goblok dia.” Dan mereka kembali terbahak-bahak.
“Asu.”
Menghentikan tawanya, Dirja menjamah cangkir kopi dan menyeruput isinya. “Eh, tapi serius deh, Di. Kenapa jadi pindah haluan dan baper sama itu perempuan sih? Hati-hati lho kamu, dia bukan perempuan biasa. Takutnya kalau nanti lingkungan Zeline kurang terbuka menerimamu, kamu sendiri yang ngenes.”
Kulempar pandangan pada hamparan sawah dan suara jangkrik yang mendominasi. “Nggak tahu, Ja. Mau diabaikan pun, sikapnya udah nggak baik banget buat kesehatan jantung kalau aku terus-terusan nggobloki diri buat nggak jatuh cinta sama dia.”
“Uluh-uluh. Penyair kesayangan kita mulai jatuh cinta!” Ia terbahak lagi. Perlahan, tawanya berkurang dan berhenti. Ia merangsek mendekatiku. “Tapi, Di. Jalani aja. Toh, kita nggak tahu masa depan bakal bagaimana. Kamu tahu apa yang menarik?” Kutatap ia dengan kernyitan di dahi dan gelengan kepala. “Dari sekian banyaknya lelaki kaya di club malam itu, dia memilihmu. Jaka desa yang hidup melalui seni dan sastra dan nggak punya apa-apa. Kamu tahu apa artinya? Sejak awal dia memang selalu memilihmu, Di. Sejak awal.”
Lewat tengah malam, kuputuskan untuk kembali pulang ketika kudengar suara guntur mulai bersusulan. Dengan langkah yang kujaga agar tak terdengar sama sekali, kuintip Ara yang masih tertidur pulas. Dalam hati aku mendesah lega. Lampu kamar masih menyala. Berdiri di samping kasur, kutatap ia yang tertidur begitu damai. Menunduk, kukaitkan rambutnya yang jatuh menutupi wajahnya ke belakang telinga. Lantas kudaratkan kecupan seringan bulu pada keningnya agar ia tak terjaga.
Namun aku tak memilih merebahkan tubuh di sampingnya, malah beranjak berdiri dan mengambil buku sketsa dan pensil. Kubagi pandangan antara dirinya yang tertidur dengan kertas putih di hadapanku. Hanya sketsa, sehingga aku tak membutuhkan waktu lama. Menutup buku sketsa dan kugeser ke samping, kupandangi gadis di depanku yang setia memejamkan mata. Suara hujan di luar menjadi musik menenangkan. Aroma tanah basah menambah pula kedamaian.
“Ra, aku tresna.”
***
Ruhku seolah-olah ditarik agar terbangun karena memang sudah waktunya untuk terbangun. Terkadang bangun tidur tidak perlu dideskripsikan dengan kalimat panjang lebar. Mungkin ruhku yang sempat berkeliaran entah di mana saja itu selalu kembali masuk ke dalam ragaku ketika pagi sudah tiba seperti ini.
Sebelum pikiranku menanyakan keberadaan Radi, mataku terlebih dahulu menangkap eksistensinya yang tidur sambil duduk di pinggiran kasur dengan berbantal lengan. Karena mataku masih belum sepenuhnya terbuka lebar, kusipitkan mata dan mengerutkan dahi. Sebelum tanganku terulur menjamah kepalanya dan menyuruhnya bangun, sudut mataku menangkap keberadaan sketch book yang setengah tertindih lengannya.
Kutarik perlahan benda itu agar ia tak terbangun. Ada beberapa sketsa di dalamnya. Kebanyakan sketsa wajah manusia, sebagian yang lain hanya goresan pensil dan drawing pen. Ia benar-benar memiliki tangan seniman. Bukan main. Tanganku terus membolak-balik kertas-kertas berisi sketsa hingga aku berada di halaman terakhir. Sketsa terakhir yang mungkin baru saja ia selesaikan. Ah, tidak, bukan lagi mungkin. Ia memang menyelesaikannya baru-baru ini. Karena ia membuat sketsa wajahku sendiri yang tengah tertidur.
“Hm, begini caramu mengamatiku saat tidur, Tuan Pradipta?” Bisikku, lebih kepada buku sketsanya sendiri. Sebelum aku menutup buku itu, kutemukan beberapa bait tulisan di belakangnya. Kedua alisku terangkat naik. “Puisi?”
Kekosongan juga merupakan bagian eksistensi
Dan di bawah bayangan kegelapan,
meringkuk tubuh mungil yang menggigil nyaris mati
Di antara batas tipis surga dan neraka,
malaikat dan iblis merayakan kelahiran kita
Dan lalu kita bertemu, Sayangku
Dan lalu kita mengadu
Kita pulalah yang saling mencumbu
Dalam kelahiran, kita bersatu
Dan dalam kebinasaan, kita akan bertemu.
~D.F Pradipta
Kuulas senyum simpul sebelum menutup buku sketsa di tanganku. Baru kusadari aroma tanah basah tercium sampai di sini. Rupanya semalam hujan. Kulabuhkan kembali perhatianku pada pemuda yang masih tertidur sambil duduk itu. Membungkuk, kudaratkan kecupan panjang di puncak kepalanya. Tanganku bergerak mengusap sebelah pipinya. Tak lama, kurasakan ia menggeliat dan membuka mata.
“Lho, udah pagi?” Suaranya terdengar serak. “Duh, aku ketiduran.” Ia beranjak berdiri dan naik ke atas kasur, memosisikan diri di sampingku. Tanganku kembali merayap naik dan mengelus sebelah pipinya. “Ada apaan sih?”
“Kamu ngapain tidur di bawah begitu?”
“Nggak apa-apa sih.”
“Ya udah.” Kucebikkan bibir sekilas sebelum beranjak dari atas kasur. Menyambar handuk dari tiang gantungan, aku melesat ke kamar mandi. Tak kutemukan Tante Kinar di dapur seperti biasa.
Selesai membersihkan diri dan memasuki kamar, kuikat rambutku membentuk kucir kuda di depan kaca. Radi memilih melanjutkan tidurnya dengan posisi tengkurap. Sudut mataku menangkap keberadaan kemoceng yang tergantung di paku. Kuputar kepala memandang Radi di atas kasur sebelum menyambar kemoceng itu. Hendak kupukul punggungnya, mendadak tanganku berhenti. Alih-alih memukul Radi, aku justru mengembuskan napas mengurungkan niat untuk memukulnya.
“Anak ini benar-benar.” Kubiarkan anak itu melanjutkan tidur pulasnya. Beranjak keluar kamar, aku berdiri di halaman belakang dan merenungkan segala hal dengan suara burung sebagai background music. Ah, benar, seindah apa pun Surabaya dengan gedung-gedungnya, alam yang asri dan bersih seperti ini tiada tandingannya. Untuk beberapa menit, aku berdiri diam tanpa memikirkan apa pun. Hanya berusaha mendalami bahasa alam.
Tak lama, kutolehkan kepala ke belakang. Tidak kutemukan tanda-tanda bahwa anak itu terbangun. Maka, kuputuskan untuk berjalan melewati rerumputan dan gerombolan dandelion menuju jalan setapak yang mengikuti pola kolam ikan. Aku tahu orang Jawa menyebutnya sebagai tambak. Sampai di depan gazebo kayu, kulirik anjing di bawah pohon besar yang menatapku dengan mata mungilnya.
Kukatakan kepadamu, aku ingin sekali menyentuhnya. Dia begitu lucu!
Tetapi, aku bahkan tidak pernah berinteraksi dengan anjing mana pun. Meski begitu, aku mulai melangkahkan kaki mendekatinya dengan sangat berhati-hati. “Hei, manis. Jangan jahat-jahat ya. Aku cuma mau kenalan, kok. Oke?” Anjing itu melengoskan muka seolah-olah tak memedulikan eksistensiku di sini. Ketika tanganku berhasil menyentuh ujung kepalanya walaupun hanya seujung telunjuk, hatiku benar-benar bersorak girang.
Aku berhasil menyentuhnya!
Astaga, begini saja sudah membuatku senang. Aku ingin memotretnya untuk Kenzo. Tapi, aku lupa membawa ponsel. Beranjak berdiri, aku menghambur masuk ke kamar untuk mengambil benda itu. Tak kutemukan keberadaan Radi di sana. Berdiri di ambang pintu, kutolehkan kepala ke kanan kiri. Dari arah depan, samar-samar kudengar percakapan dua orang dalam Bahasa Jawa. Maka, aku memilih mendekat untuk mencuri dengar. Aku tahu ini perbuatan yang tidak baik. Tapi aku benar-benar penasaran. Dari sudut mataku, kulihat Radi dengan seorang pria yang duduk-duduk di ambang pintu depan. Dari yang kudengar, pembicaraan mereka santai namun serius.
“Gak ilok, Di. Kowe-kowe iki durung rabi. Kalau pak RT dewe sing negur, iso-iso wedokanmu diusir teko kampung iki.[1]”
“Cuma sementara, Pak.”
“Iyo, aku paham. Mangkane, le. Wediku wong-wong podho nggosip. Sak cepete, suruh dia balik. Iku yo gawe apikmu dewe.[2]”
“Nggeh, Pak.”
Selanjutnya, mereka mengobrol. Tapi artinya tidak begitu penting. Sebelum Radi berbalik dan masuk ke dalam, kuputuskan untuk segera pergi ke belakang. Sampai di gazebo, dadaku naik turun. Meski aku tidak terlalu mengerti Bahasa Jawa, bukan berarti aku tidak memahami inti percakapan mereka. Ya, aku tahu memang ini konsekuensi bila Radi membawa gadis asing di desa. Apalagi aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga ini. Kupandangi sejenak layar ponselku, urung memotret anjing lucu tersebut. Tak lama, kudengar suara kaki yang menapak tanah.
“Udah kuduga kamu di sini.” Radi memosisikan diri di sampingku. “Tumben banget?”
Kulengoskan muka menatap ilalang seolah-olah mereka jauh lebih menarik untuk dipandang. Aku tidak akan diam dan berpura-pura tidak tahu. Aku bukan lagi ABG labil. Maka, kubuka suara setelah menelan ludah beberapa kali. “Kamu ditegur tetangga ya?”
Spontan ia menolehkan kepala padaku, menatapku dengan sorot terkejut. “Kamu dengar?” Tanpa mengangguk ataupun menggeleng, kutatap ia yang mengembuskan napas. “Nggak usah dipikir. Aku nggak mau bikin kamu khawatir.”
“Sebenarnya, aku belum mau pulang. Tapi setelah lihat kamu ditegur begitu, kayaknya besok aku pergi aja deh.”
“Ke mana?”
Mengangkat alis dan bahu, kucebikkan bibir sekilas sebelum berkata, “Entah. Hotel, mungkin? Aku akan bayar pegawainya untuk tutup mulut.”
“Enggak! Kamu bisa di sini untuk sementara.”
“Sampai kapan? Sampai kamu didemo warga desa? Ya kali, aku nggak seegois itu.” Aku beranjak berdiri. Menoleh sekilas pada anjing yang balik menatapku. Menunduk dan mengambil kerikil untuk melemparnya ke rawa-rawa yang dipenuhi rumput-rumput panjang dan ilalang. Apa pun kulakukan asalkan tidak menatap matanya. “I’ll go, Di. Kita masih bisa ketemu di luar. Ya?”
Hening. Ia tak menjawab apa pun meski sepatah kata pun. Aku anggap itu sebagai persetujuan darinya. Tak lama, tubuhku dipeluk dari arah belakang. Kulempar pandangan pada tangannya yang melingkari perutku. Kudengar embusan napasnya yang berat, dan ia berkata, “Aku ikut. Aku ikut kamu ke Jakarta.”
Untuk sesaat, kurasakan napasku tercekat. Mencengkeram lengannya, kepalaku terputar hanya untuk mendapati senyumannya yang menenangkan. Sedangkan aku hanya menatapnya dengan pandangan tak percaya.
*
Usai mengemas lukisan pesanan seseorang dan mengirimkannya melalui ekspedisi, kami kembali ke rumah. Karena Pras sedang sibuk dengan tugas kuliah dan segala tetek bengeknya, kami mengurungkan niat untuk berkunjung ke kafenya.
“Jadi, kapan kita mulai berangkat?” Suara Dirja menyahut di antara keheningan.
Kubulatkan mata dan tersenyum selebar-lebarnya, “Besok!”
“Buset, serius?”
“Nggak segampang itu, Ra.” Suara Radi yang menginterupsi membuatku memerosotkan tubuh dan mengerucutkan bibir. “Kita harus bawa semua lukisanku juga, belum lagi barang-barangku.”
“Pakai pick up? Bisa nggak sih? Dan kita terbang. Beres!”
“Uangku sama Dirja nggak cukup.”
“Halah, pakai uangku.”
“Nggak bisa gitu, Ra. Masa—”
“Yaudah! Buat sementara aja. Nanti kalau ada uang kalian ganti. Kayak sama siapa aja itung-itung!” Usai menyerukan kalimat itu, aku terdiam. Baru kusadari bahwa aku terlalu menggebu-gebu. Kutatap Radi dan Dirja yang mengangakan mulutnya menatapku. Detik berikutnya Dirja terbahak-bahak.
“Anjir, kalian udah kayak suami istri betulan.”
Kuperosotkan tubuh lagi dan melipat tangan di depan dada. “Udah, kalian nurut aja napa. Ribet amat mau ke Jakarta doang.”
“Yo wis. Kita siap-siap buat hari ini dan besok. Besok lusanya baru kita berangkat,” ujar Radi di sampingku.
“Kanvas-kanvasmu gimana?” Tanya Dirja dengan alis terangkat naik.
Kutegakkan punggungku dan menyibakkan rambut. “Kirim pakai jasa ekspedisi ajalah. Kita terbang juga nggak lama. Justru pengiriman barangnya yang bakal lama.” Sejenak, aku terdiam. Kugigit bibir bawah, lantas bergumam, “Tapi kita masih belum tahu kalian mau menetap di mana.”
“Kita masih bisa ngekos.”
“Hotel Papaku?” Serentak, mereka sama-sama melempar pandangan padaku dan terdiam. “Kalian di sana aja. Aku bakal suruh pegawai tutup mulut. Nggak ada protes ya!” Di samping, Radi hanya mengangkat bahu dan melempar pandangan pada Dirja sebagai pesan rahasia antara lelaki.
***
Sementara tubuhku sibuk bolak-balik dari lemari dengan kasur, kubagi pandangan antara barang-barangku dan Ara. Ia duduk menyilangkan kaki dan tetap memakukan pandangan kepadaku.
“Udah aku bilang. Aku beliin koper aja.”
“Enggak, Ra. Haduh.”
Kudengar decakan lidahnya yang kesal. Ia menyambar ponselku yang tergeletak di atas kasur. “Aku pesan sekarang ya.”
“Hm.”
Usai memasukkan sedikit baju dan perlengkapan lain yang sekiranya akan aku butuhkan ke dalam tas, aku mulai sibuk berkutat menyiapkan lukisan-lukisan dan mengikatnya menjadi satu. Lantas kumasukkan ke dalam kain besar yang sudah bersih. Bukan saja kanvas berukuran besar, ada pula yang kecil. Sketch book dan cat-cat yang bagiku sakral telah kusiapkan sedari tadi. Besok kami akan mengirim semua lukisan ini ke jasa ekspedisi, sekaligus mengunjungi Nenek dan Kakek—lagi—untuk berpamitan langsung.
Di sampingku, Ara berdiri seraya berkacak pinggang. “Hm. Good. Udah, kan?”
“Udah sih.”
Gadis itu merangkul lenganku dan berseru girang, lantas mendaratkan kecupan lama di pipiku. “Makasih, deh. Aku kira kamu beneran bakal nolak. Kamu nggak tahu betapa senangnya aku, Di.”
“Aku mau ke Ibu dulu deh.”
“Aku ikut.”
Kutatap ia, lantas menghela napas panjang. Meskipun begitu, aku tetap menggandengnya dan pergi menemui Ibu. Ia dan Kumala tengah menonton acara TV dengan semangkuk mie instan. Melepas gandengan tanganku pada Ara, aku menghambur duduk dengan lutut sebagai penyangga di depannya. “Dua hari lagi Radi berangkat ya, Bu.”
“Berangkat ke mana, Mas?” Kumala menyambar seperti petir yang menggelegar. Ara memutari kursi dan duduk di samping adikku, memeluknya.
“Jakarta,” bukan aku, tetapi Ara. Ia berbisik panjang-panjang di dekat telinga adikku dengan senyuman lebar.
“Jakarta?! Kok, tiba-tiba?”
Kurasakan tepukan pelan tangan Ibu di pipiku. “Bagus. Kamu sudah menjadi pria berani, seperti ayahmu.”
“Besok Radi mau ke Surabaya lagi. Pamitan langsung ke Mak sama Bapak.” Ibu menyengir dan mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai jawaban untukku.
Malam ini, kami menghabiskan waktu bersama di depan TV dan menceritakan segala hal. Dari sudut mataku, aku menangkap pemandangan indah perihal ketiga wanita yang sangat aku sayangi. Sesekali lirikan Ara ia lesatkan kepadaku. Kehadirannya serupa pelengkap dalam keluarga kecil ini. Dan aku sangat berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada dirinya.
*
Hari ini kami tidak menggunakan kereta. Hanya motorku. Dan Ara, tanpa kuduga-duga, sempat memberengut padaku dan sama sekali tidak mengajakku berbicara sepanjang perjalanan. Biasanya ia yang paling berisik. Hanya karena bila kami tak menaiki kereta, ia tak akan menaiki becak, kukatakan kepadamu. Becak!
Bahkan ketika aku memarkir motor di depan rumah Nenek, ia tetap tak mau menyapaku dan langsung menghambur masuk ke dalam setelah mengucapkan salam. Kakek melongokkan kepala dari ruang tengah menyadari kehadiran kami. Ara mengecup punggung tangan Kakek dan bertanya keberadaan Nenek. Mengetahui bahwa Nenek tengah tertidur di kamarnya, gadis itu melesat untuk segera menemuinya.
Menghampiri Kakek, kucium punggung tangannya. “Kalian kembali lagi. Ada apa, le, Karnaku?”
“Radi mau pamit, Pak. Besok ke Jakarta, sama Elin dan Dirja.”
“Wah, iya? Bagus, bagus. Kamu sudah berani melangkah rupanya. Benar, kan? Gadis itu memang ditakdirkan untukmu.”
Aku tertawa menanggapi kalimat itu, disusul keberadaan Nenek dengan tangan ara yang melingkari lengannya. Saat mata kami bertemu, gadis itu melengoskan muka. Rupanya ia masih belum mau berdamai denganku.
“Kalian kembali rupanya. Elin sudah bilang. Kamu benar-benar sudah berani.” Nenek menghampiriku, lantas mendaratkan kecupan pada dahiku. “Anakku. Tidak akan ada yang mencegahmu pada takdirmu. Berangkatlah, dan sempatkan kembali sebelum perang.” Kucium kedua pipi Nenek sebelum ia menyuruhku istirahat sejenak.
Sampai di kamar pun, gadis itu tak menyapaku. Kudecakkan lidah sekali melihat tingkahnya. Menghampirinya yang mengikat rambutnya, kupeluk ia dari belakang dan mengecup sekilas tengkuknya. “Kamu kalau lagi mau manja-manjaan sama aku bilang aja deh. Jangan pakai acara ngambek-ngambek begini.”
“Dih, apaan coba.” Ia berusaha melepas lenganku yang memeluknya, namun gagal. Pada akhirnya ia memilih mengembuskan napas, menyerah. Memutar tubuhnya, kutangkap sorotan dari kedua bola matanya yang indah. Detik berikutnya, tanpa aba-aba, sebuah tamparan mendarat pada pipiku. Panas menyemut di sana. Tetapi, ia bergerak maju dan mendaratkan kecupan singkat di tempat ia tampar tadi. “Aku mau ke kamar mandi dulu.” Lantas, ia pergi meninggalkanku yang melongo sendirian. Perempuan memang benar-benar susah ditebak.
Kuusap-usap bekas tamparannya yang menyisakan panas seraya berjalan ke ambang pintu, berniat keluar dan menuju ruang tengah. Namun, langkahku terhenti bahkan sebelum mencapai ruang tengah lantaran mendengar obrolan samar-samar Kakek dan Nenekku. Meski teredam suara TV, aku dapat mendengarnya dari sini.
“Paradoksal. Apakah bentuk sebenarnya dari sebuah paradoks, Sayangku? Sama seperti kita yang merajai dimensi depan dan memilih berpetualang justru di belakang. Pertanyaannya: Siapa nenek moyangnya? Tetapi pada akhirnya sebuah kilat perihal benar muncul di atas matanya yang terbuka. Bukan lagi tentang misteri kita dan mereka, ataupun surga dan neraka, melainkan perihal paradoks dunia cinta dengan segala persoalannya.”
“Kita berdiri di atas kaki sendiri. Kita bahkan memilih masa di mana akarnya berada. Tetapi, yang sebenarnya adalah, dunia ini tidak memiliki ujung ataupun kutub. Melainkan berkesinambungan dan berputar, tanpa memiliki ujung selain ujung kuku tangan dan kakinya sendiri.”
[1] Gak baik, Di. Kamu-kamu ini belum menikah. Kalau pak RT sendiri yang menegur, bisa-bisa perempuanmu yang diusir dari kampung ini.
[2] Iya, aku paham. Makanya, Nak. Takutku orang-orang pada menggosip. Secepatnya, suruh dia balik. Itu juga buat kebaikanmu sendiri.


 valentina
valentina