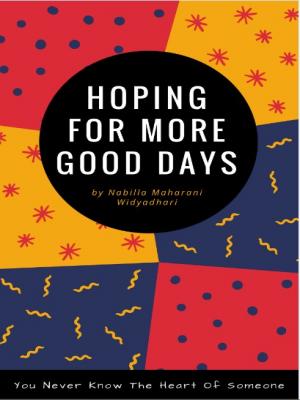Mentari masih bersembunyi di balik awan, malu-malu memancarkan sinarnya. Damian mengulas senyum tipis, bersiap untuk memulai hari dengan niat baik. Tangannya dengan cepat mengambil kunci mobil dan parsel buah di meja.
"Kamu dan Tante Nuri boleh buat keputusan sepihak, Ra. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkanku untuk bertemu calon anak kita," ujar Damian penuh keyakinan.
Hari masih bening ketika Ayla hitamnya menembus jalan Melati. Masih jelas di ingatannya bayangan dirinya dan Laras malam itu. Apa yang menguasai hati Damian hingga berani mengambil hal paling berharga milik Laras memang salah. Tapi Damian sungguh mencintai Laras hingga membuatnya punya kerinduan bertemu wanita itu lagi. Damian melirik apel, anggur dan pir yang tersusun rapi di keranjang. Lelaki itu yakin Laras pasti menyukainya.
Damian memelankan laju mobil saat rumah minimalis bercat putih itu sudah dekat. Ia menghembuskan napas sebelum kakinya melangkah melewati pekarangan rumah Laras yang rimbun di sisi kiri dan kanannya. Dengan erat, ia membawa bingkisan buah di kedua tangannya. Damian mengetuk pintu seraya menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang.
Di dalam, Dhisti yang tengah memotong daun bawang menghentikan pekerjaannya dan menoleh pada Laras. Saudara tirinya itu menunjuk ke arah ruang tamu. "Bukain sana. Aku nggak mau ketemu siapapun. Kalau itu Damian, usir aja."
Dhisti mendesah pelan sebelum meletakkan pisau di sebelah panci dan bergegas menyambut tamunya.
Manik cokelat yang berpadu dengan alis tebal itu kembali memenuhi penglihatan Dhisti. Segala pikiran yang berkecamuk tentang Laras dan Damian yang memadu kasih bermain di kepala Dhisti. Wanita bermata almond itu menelan ludahnya dan mencengkeram handle pintu, menjaga keseimbangan tubuhnya.
"Kenapa harus kamu sih, Dhis? Laras mana?" tanya Damian dengan kesal.
Dhisti mendongak, menatap Damian yang berdiri menjulang di depannya. Wanita itu menghembuskan napas, menghalau segala pikiran tentang apa yang Damian lakukan.
"Hm, Mbak Laras nggak mau ketemu Bapak. Tadi pagi mual-mual," jawab Dhisti cepat.
Damian membulatkan mata mendengarnya. Ia tidak pernah tahu proses kehamilan dan sungguh berharap bisa menemani Laras.
"Tapi dia nggak papa kan, Dhis? Saya perlu ketemu dia sekarang. Kamu bisa panggil dia?"ujar Damian sambil memanjangkan lehernya.
Dhisti terperanjat. Ia tidak mungkin membiarkan Damian masuk. Nuri sudah mengingatkannya untuk melarang Damian dan Nadia menginjakkan kaki di rumah ini.
"Maaf, Pak. Saya cuma menjalankan perintah. Lebih baik Bapak pulang. Tunggu sampai keadaannya membaik."
Damian berdecak. "Saya perlu tahu keadaan Laras dan calon anak kami, Dhis."
Dhisti mengulum bibir. Ia tidak bisa memberi kemudahan bagi Damian walau lelaki itu atasannya. Wanita itu menatap manik cokelat Damian yang memancarkan keseriusan. Dhisti tahu Damian pasti memegang janjinya tapi kalau ia harus berhadapan dengan kemarahan Nuri, hidupnya berakhir sudah.
"Gini aja ya, Pak. Saya kirim foto Mbak Laras dan perkembangan bayinya setiap dua hari sekali," ujar Dhisti, yang sejenak menyalahkan idenya.
Damian tahu Dhisti ada di posisi sulit. Ia harus mengikuti cara bermainnya dulu sebelum menemui Laras.
"Oke. Oh ya, kamu harus tetap kerja, Dhis. Sementara waktu, saya kasih kamu cuti. Besok kamu harus masuk. Ingat ya, kamu masih jadi bagian A Latte sampai batas waktu yang tidak ditentukan."
Dhisti mengiakan walau hatinya tidak karuan. Ia masih memerlukan pekerjaan tapi kalau ia harus bertatap muka dengan Damian, Dhisti harus belajar untuk menata hatinya.
Tak lama, Damian menyerahkan parsel buah ke tangan Dhisti.
"Kasih ke Laras. Tolong kabarin gimana perkembangannya. Saya udah cari klinik terbaik juga buat Laras. Suruh dia hubungi nomor di kartu nama itu."
Dhisti menatap parsel buah dan wajah Damian bergantian. Begitu terencananya setiap perbuatan Damian untuk menyambut anaknya. Dhisti hanya mengangguk pelan, mengabaikan hatinya yang menjerit kesakitan. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di hadapan Damian.
"Saya pamit, Dhis. Tolong jaga Laras dan calon anak kami. Saya kemari lagi lusa."
Dhisti mengiakan seiring hatinya yang patah berkeping-keping. Ia tidak tahu lagi harus menambal dengan apa segala luka di hatinya. Yang jelas, hari depannya akan dipenuhi berbagai kejadian tak terduga.
**
Bangunan bergaya retro itu masih sama, berdiri elegan di antara gedung lain dan perumahan minimalis. Dhisti mengulas senyum tipis sebelum melangkah masuk dengan hati mengembang penuh suka.
Fino mengangkat satu tangannya dan menyapa Dhisti. "Akhirnya lo datang juga."
Dhisti tersenyum ramah dan mengedipkan mata. "Iya, dong. Kangen sama kamu soalnya."
Fino tertawa mendengar candaan rekan kerjanya itu. "Tapi semua aman, kok. Gue bisa handle kerjaan lo walau nggak sempurna. Bisa lah, ya. Lo bilang Pak Bos biar naikin gaji gue," balas Fino, tertawa.
Dhisti mengencangkan tali apronnya, menatap lelaki dengan rambut gondrong yang diikat asal itu.
"Duh, kayak gue punya hubungan spesial aja sama Pak Bos. Thanks ya, udah bantuin gue. Nanti gue traktir cappucino, deh."
Fino hanya tertawa dan masuk ke pantry, meninggalkan Dhisti yang kini menyalakan komputer.
"Eh, tapi kalau gue perhatiin, lo cocok sama Pak Bos, Dhis. Pak Bos sering marahin lo buat hal remeh. Dan lo nggak ragu balas dia. Lucu aja."
Dhisti terperanjat mendengar perkataan Fino yang mendadak. Lelaki itu melihat Dhisti dari balik pintu sambil tersenyum geli.
"Ih, random banget lo, Fin," jawab Dhisti segera menyibukkan diri.
Pak Bos itu cuma suka Laras, Fin.
Manik hitam Dhisti kini tertuju pada table di layar komputer. Ia harus memeriksa beberapa hal yang berkaitan dengan pelayan. Dhisti segera tenggelam dalam aktivitasnya hingga mengabaikan Rania yang begitu heboh memanggilnya. Rania menggerakkan tubuhnya sambil bernyanyi lagu gembira. Dhisti tertawa sejenak melihat kelakuan Rania yang absurd.
"Ya ampun, Ran. Lo kayak nggak ketemu gue setahun aja," ujar Dhisti tersenyum lebar.
Rania memajukan bibir. "Dhis, asal lo tahu ya. Dua hari lo nggak masuk itu kita bagai ayam kehilangan induk. Mana nggak ngabarin apapun. Fino bisa nanganin sih, tapi beda."
Dhisti mengulas senyum menatap sahabatnya. Betapa ia menyadari dirinya sangat berharga dan dicintai terlepas dari apa yang ia tengah alami.
"By the way, Pak Bos kenapa, sih?"
Dhisti menaikkan alis memandang Rania. "Maksudnya?"
Rania mengedarkan pandangan ke segala penjuru sebelum menggamit lengan Dhisti. Rania menuntun sahabatnya ke taman belakang. Tembok kadang bisa mendengar dan menyebarluaskan segala hal. Jadi, lebih baik mencari tempat aman.
Semilir angin dari morning glory menyambut keduanya.
"Iya, Dhis. Pak Bos beberapa hari ini nggak masuk. Di grup juga nggak ada pengumuman apapun. Kita jadi ketar-ketir dia lupa menggaji kita nanti," lanjut Rania.
Dhisti mengangguk menyadari kecemasan Rania. "Tenang aja. Dia pasti ingat, kok. Sebenarnya dia lagi ada masalah yang hm, berat."
Rania mengernyitkan kening membiarkan Dhisti menceritakan apa yang menimpa Bosnya. Rania tak hentinya membuka mulut dan mengernyitkan kening.
"Hah? Lo serius? Terus, lo masih suka sama Pak Bos, Dhis? Dia udah jelas sayang sama saudara lo," ujar Rania dengan hati-hati.
Dhisti menaikkan bahunya menatap daun morning glory. Angin menerbangkan beberapa helai daunnya, mempermainkannya.
"Nggak tahu. Tapi gue nggak bisa benci dia. Biar aja rasa cinta ini bertumbuh atau malah hilang, Ran. Mana bisa gue paksa untuk selalu suka kalau hal sebaliknya yang gue rasa."
Rania terdiam sesaat menyadari ada kekuatan yang tersembunyi dalam perkataan sahabatnya itu.
"Dhis, yang tabah, ya. Ini pasti berat buat lo apalagi lo sering ketemu mereka."
Dhisti mengangguk. "Ran, jaga rahasia ini di antara kita. Gue nggak mau semua orang tahu yang sebenarnya."
Rania mengacungkan ibu jarinya. "Apa lo punya rencana lain, Dhis? Misalnya pindah kosan?"
Dhisti menoleh pada sahabatnya. "Belum. Bude Nuri pasti cari gue, Ran. Apalagi Mbak Laras yang lagi hamil dan perlu bantuan gue buat beli keperluannya atau cuma buat minuman. Gue nggak tahu ke mana takdir membawa hidup gue tapi pasti semua itu menuntun gue pada hal baik."
Rania mengulas senyum mendengar perkataan sahabatnya sebelum merangkul pundak Dhisti. "Lo memang the best, Dhis. Tetap begini, ya."
Dhisti membalas rangkulan itu dengan hangat. Wanita bermata almond itu tahu kalau dia tidak salah memilih teman untuk membagikan kisahnya.
**


 yulilavender
yulilavender