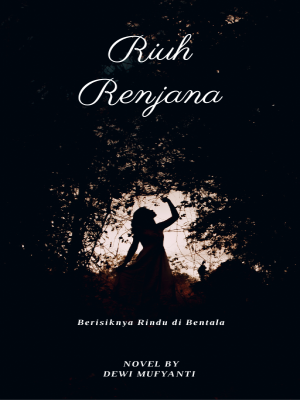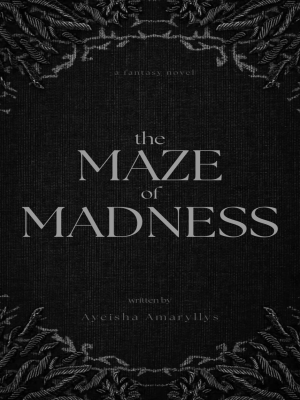"Aku mencintaimu," bisik Arya sebelum menempelkan hidung mancungnya dengan hidungku.
Namun, sebelum bibir kemerahannya ikut menempel di atas bibirku, aku lekas mendorong dengan kuat kepalanya ke batang pohon yang ada di belakangnya.
"Jangan harap aku kembali padamu, Arya! Aku bukan lagi wanita bodoh yang mudah diperdaya!"
Sebenarnya aku sedikit goyah untuk kembali pada si pemilik tubuh kekar itu. Aku paham arti tatapannya yang menyiratkan penyesalan sekaligus harapan untuk bersamaku kembali. Ia memiliki daya tarik tersendiri yang membuat hatiku dengan mudahnya terhasut tampang itu jika aku tak sedang dalam perjalanan untuk “pulang”. Meski begitu, aku pun terbayang saat ia berbaik-baik pada Tavisha sementara aku dibiarkannya mengerjakan semua pekerjaan rumah bagai budak. Aku tak bisa memberi kesempatan kedua bagi pengkhianat macam dirinya yang begitu mudah berpaling kepada wanita jalanan.
Aku melesat menyusul Pranaja dengan jarik terangkat hingga atas lutut, mengejar waktu yang hampir habis dengan semburat jingga yang mulai pudar tergantikan oleh langit malam. Sigasir mulai bernyanyi, tak acuh jika tanah tempatnya bersembunyi berdebum akibat langkahku.
Pranaja tak tampak batang hidungnya di lokasi tadi, membuat kepanikanku kian menjadi. Bagaimana kalau aku kesasar? Bagaimana kalau Pranaja yang kesasar? Bagaimana kalau kami tidak jadi pulang dan Arya menghabisiku karena tadi kubenturkan kepalanya?
Dadaku bergemuruh, kepalaku berdenyut seraya mengeluarkan bulir-bulir peluh sebesar biji jagung. Aku melangkah ke sana-kemari kelimpungan dengan jalan setapak yang bercabang-cabang.
Bruk. Seseorang menabrakku dari belakang, aku langsung berjengit dan ia mengeluarkan suara gaduhnya.
"Renjana! Kau Renjana atau makhluk halus penyamar?" tanyanya dan kugaplok bahunya. "Dasar makhluk kasar!" Dia menggerutu.
"Sudahi basa-basimu! Kita harus cepat sampai di pohon pule," kataku mengakhiri celoteh tak penting Pranaja.
"Pohonnya kan sudah di depan kita."
Aku menepuk jidat kemudian meringis malu.
Pranaja meletakkan tampah berisi ubo rampe di depan pohon pule kemudian mengucapkan sebaris kalimat yang sebelumnya diajarkan oleh Ki Darwanto. Kami bersila sembari mengosongkan pikiran di bawah langit malam yang sepenuhnya menggantikan lembayung senja. Semilir angin menerpa pipiku, menerbangkan anak rambutku yang tak tergelung. Bambu berderak, mati-matian aku menahan supaya mataku tetap terpejam dan pikiranku tak buyar.
Kurasa sudah satu jam kami bersemadi dan tak terjadi apa-apa. Namun, ketika membuka mata, aku mendapati raga Viva telah ambruk di hadapanku sementara kurasakan tubuhku seringan kertas. Jiwaku telah lepas dari raga Nayaviva. Aku memanggil Pranaja dan dia membuka mata, terbelalak melihatku yang semakin melayang.
"Kamu meraga sukma?!" tanyanya.
"Aku tak tahu."
"Terus bagaimana Nayaviva?"
"Coba periksa. Masih hidup gak? Siapa tahu jiwa aslinya balik." Pranaja pun memeriksa denyut nadi Viva di pergelangan tangan serta leher. Pranaja menggeleng, membuatku masygul dan merasa kehilangan diriku yang lain.
Aku tak sempat berduka lebih lama karena kemunculan Arya membuatku dongkol sekaligus gamang. Wajahnya merah padam, tatapannya nyalang tertuju kepada Pranaja. Langkah kakinya lebar dan tangannya mengepal.
"Apa yang kaulakukan kepada Viva?!" Arya menunjuk Pranaja murka. Sedangkan pemuda bermata sipit itu tergagap sembari menatap Arya dan jasad Viva bergantian.
Suara tapak kuda tertangkap pendengaranku sebelum muncul kereta kuda dengan dua ukiran naga di sisi kanan-kirinya yang berhenti di hadapanku. Dua kuda gemuk dengan surai dan bulu berwarna cokelat serta kusir yang tak lain adalah Roro Sukmo membuatku terbengong.
Aku lekas menaikinya dengan kaki yang tak menapak. Pranaja mestinya mengikutiku, tetapi dia malah berdiri kaku dalam posisi siap seperti akan melakukan upacara bendera.
"Pranaja, ayo!" seruku. Namun, Pranaja bungkam dengan manik yang bergerak gelisah.
Aku tahu, ini ulah Arya yang tengah memanfaatkan ilmunya. Dan aku tidak tahu cara menghentikannya.
Aku turun dari kereta kuda dengan air mata yang siap meluncur. Aku merasa gemetar meski tubuhku ringan dan melayang-layang. Saat itu juga, aku mendengar senandung merdu Roro Sukmo yang juga turun dari kereta kuda untuk menghampiri Pranaja. Suaranya sungguh menghanyutkan, entah tembang apa yang sedang dilantunkannya. Tanpa sadar, mulutku bergerak, mengikuti irama yang menjadi seuntai nada tak kalah merdu darinya.
Arya menengok ke sana-kemari mencari asal suara. Kurasa ia tak bisa melihatku dan Roro Sukmo yang kini berada tepat di depannya. Senandungku dengan Roro Sukmo semakin menjadi, sementara ia mulai berkeringat. Pranaja pun telah lepas dari genggaman mantra Arya dan sempoyongan memasuki kereta kuda.
Tepat ketika senandung usai, Arya ambruk tak sadarkan diri dan aku cemas dibuatnya. "Dia masih hidup, kan?"
"Tentu saja. Ilmuku belum mampu menghabisinya," jawab Roro Sukmo.
"Syukurlah," balasku.
"Kau senang dia tidak kuhabisi?"
"Renjana masih punya rasa kepadanya. Sudahlah, cepat naik!" celetuk Pranaja bersungut-sungut lalu muntah di dalam kereta kuda.
Ew, menjijikkan.


 orenertaja
orenertaja