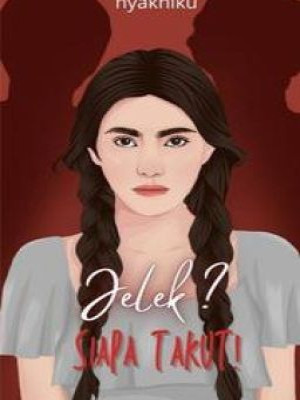"Mungkin kamu dituntun untuk memperbaiki diri di sini, bukannya mengulang kesalahan." Pranaja melanjutkan. Aku mendengus atas penghakiman lelaki ceriwis ini.
Malam diboyong oleh Bathara Candra di antara kelap-kelip kartika. Aku berdiam di rumah Pranaja sebelum pulang ke rumah Emak besok. Kepalaku pening, perutku perih karena tak makan seharian. Tubuhku menggigil kedinginan sementara gemeletuk di gigiku makin menjadi.
"Kamu sudah gak perawan lagi, kan?" bisik Pranaja dengan nada jahil.
Aku meliriknya sinis sebelum menggeplaknya.
"Kamu juga sudah jadi janda," ejeknya lagi.
Aku menjiwit lengannya menggunakan tenaga terdalam. Wajahku panas, mataku berair. Aku bahlul dalam menyembunyikan perasaan. Pranaja yang mengungkit-ungkit masalah rumah tanggaku hanya menambah penyesalan yang bercokol, menuding diri yang begitu bodoh membiarkan hati dijarah oleh pengkhianat.
"Renjana, maaf. Aku cuma bergurau." Pranaja memegang lengan telanjangku kemudian kutepis kasar.
"Guyonanmu agak keterlaluan. Memang benar aku janda, tapi apakah aku yang menginginkannya? Tidak," kataku.
Jujur, aku masih menaruh hati pada Arya. Coba bayangkan, kau menikah selama dua tahun lebih bersama orang yang benar-benar kaucintai dan dengan mudahnya dia membuang segala kenangan bersamamu. Kalau aku dapat mengendalikan perasaan, aku pun takkan membiarkan hati memilih orang yang salah.
Tavisha. Perempuan berdarah India itu merampas sumber kebahagiaanku. Arya, Biyung, Yu Nirmala, Lakshita, dan orang terdekatku yang lain. Ternyata sudah berlaku sejak zaman ini bahwa perempuan cantik lebih diratukan daripada perempuan benar. Orang-orang berbelas kasihan pada Tavisha karena dikira ia yang korban. Padahal aku juga korban pengkhianatan mereka yang lebih menyenangi perempuan cantik yang sok polos itu.
Omong-omong, aku jadi rindu pada Yu Nirmala dan adiknya. Yu Nirmala sudah menikah belum ya?
"Aku kangen sama Arya dan masyarakat di sana."
"Laki-laki itu bejat, Na. Dia sekarang sudah bahagia menanti anaknya." Pranaja mengompori hatiku. Aku tidak suka dia mencemooh suami-mantan suami maksudku.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah mengizinkan Arya berguru. Dengan begitu, mungkin dia tidak akan pernah bertemu Tavisha.
"Kamu tambah kurus, Na."
Batinku meronta hendak merutuki lelaki ceking nan aneh itu. Bisa-bisanya ia mengkritik fisikku tanpa berkaca terlebih dahulu?
"Kau kurus. Bukti Arya tidak membahagiakanmu. Jangan berharap padanya lagi, Na. Yuk makan dulu," ajak Pranaja.
Aku menyahut, "Memang punya makanan?"
"Ya."
Aku malas beranjak, dia pun membawakanku sepiring nasi dengan lauk nila bakar.
"Aku memasaknya tadi pagi sebelum kau datang. Belum basi kok," katanya setelah melihatku bergeming.
Aku membalikkan badan, memunggunginya karena mempertahankan ego. Namun, perutku yang keroncongan membuat pipiku panas ditambah tawa Pranaja yang menggelegar.
Akhirnya aku sadar bahwa sebetulnya Pranaja ialah sosok yang peduli, hanya saja memperlihatkannya secara tersirat.
Keesokannya, Pranaja mengantarku ke rumah Emak setelah kami sarapan singkong rebus.
Aku tidak memakai alas kaki, tidak ada waktu untuk membuatnya. Aku pun tidak berganti pakaian karena semua pakaianku masih berada di rumah Arya.
Pranaja di sampingku mengenakan pakaian yang ia pakai dari masa depan-celana jeans hitam dan kemeja hijau lumut, serta kakinya dialasi oleh sendal jepit.
Sampailah kami di Wanua Kapundungan. Suasana desa itu tampak sunyi, tak sekali pun kujumpai kebersamaan masyarakat seperti yang dilakukan setiap pagi oleh warga Wanua Bagorejo.
Orang-orang pun tidak menyapaku, atau mereka sudah lupa siapa aku?
Kami mengunci mulut hingga tiba di pelataran rumah Dadari dan Ki Darwanto. Rumah itu sudah berbeda dari yang terakhir kulihat. Kini bukan lagi berbahan dasar kayu, melainkan bata merah yang menandakan keluarga kecil itu bukanlah orang miskin. Hewan ternak pun tidak kulihat di halaman. Jagonya yang dulu dibanggakan, sekarang lenyap entah ke mana.
"Viva!" panggil Dadari di ambang pintu.
"Sahabatku!" balasku sembari berlari masuk gapura angkul-angkul rumahnya tanpa sungkan.
Kami berpelukan. "Apa kabar, Dadari? Aku merindukanmu."
"Sehat. Bagaimana kau? Kenapa bertambah kurus?"
"Sungguh menderita. Setiap hari aku kerja berat demi memperoleh beras, sedangkan yang makan paling banyak, si jalang itu tidak membantu sama sekali," aduku.
Kami melepas rengkuhan, Dadari menatapku prihatin kemudian menatap Pranaja. Ada senyum tertahan ketika sahabatku itu menatap Pranaja. Entah aku yang terlalu berburuk sangka atau memang jiwa perempuan nakal masih terselip pada sosoknya.
Kami dipersilakan masuk ke ruang tamu dan Dadari ke dapur membuatkan minum. Ia keluar bersama Ki Darwanto yang membawa sebatang cerutu.
"Tidak perlu repot-repot, Dadari. Kami hanya mampir sebentar. Aku harus menemui Emak," ucapku, teringat tujuanku datang ke desa ini.
"Beliau sepertinya sedang pergi ke pasar." Dadari menatapku enggan seperti hendak mengatakan yang lain tapi ditahan.
Kurasa hampir sejam kami berempat membisu. Minuman gula jawa telah kuhabiskan dan kretek Ki Darwanto pun telah berakhir di asbak ukir.
"Lastri murka padamu," ungkap Ki Darwanto santai, sedangkan Dadari melipat bibirnya ke dalam.
"Lah kenapa?" balasku heran.
"Kau sudah menjadi buah bibir, bahwa kau perempuan nakal yang mau saja tinggal bersama pemuda itu." Ki Darwanto melirik Pranaja dengan ogah-ogahan.
Sebenarnya aku sudah menduga, bahwa aku bakal menjadi bahan gosip orang dan mereka akan mengecapku seenak jidat. Walaupun begitu, aku akan tetap menemui emakku. Aku ingin mencium tangannya sebelum aku pergi.


 orenertaja
orenertaja