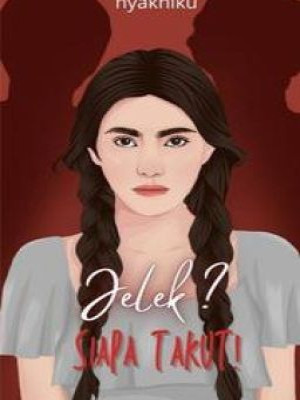(Mendung di Hati)
"Berhenti! Kalian jangan main hakim sendiri! Semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin," seruku, mengalihkan atensi warga yang kemudian mendelik kepadaku.
"Siapa kau?! Aku akan menghukum pemuda ini karena dengan beraninya mencuri kudaku!" balas pria jangkung dengan pakaian kebesaran khas patih. Tokoh yang memegang jabatan itu adalah Gajah Mada. Aku tak menyangka bisa melihat sendiri bagaimana sosok patih hebat yang amat dielu-elukan itu. Parasnya amat berbeda dari gambaran yang ada di patung maupun buku sejarah. Tubuhnya tidak tambun, tetapi tinggi kekar. Perutnya rata, pipinya tirus, memiliki cambang yang cukup lebat. Namun, tatapan merendahkan darinya membuatku makan hati.
"Saya rakyat jelata yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Memangnya ada bukti dia mencuri kuda milik Anda?" Aku berkacak pinggang. Patih itu terlihat menahan gejolak amarah mendapati sikapku.
"Berani-beraninya kau! Sudah jelas dia menunggangi kudaku lalu membawanya pergi. Untung aku berhasil menemukannya." Patih itu mengatakannya dengan berapi-api.
"Aku tidak mencuri. Aku hanya penasaran bagaimana rasanya naik kuda. Pas aku naik, eh kuda itu malah jingkrak-jingkrak tak keruan. Lagi pula kuda itu tak diikat, jadi kupikir itu kuda liar," jelas Pranaja.
"Aku tak mengerti ucapanmu. Kau tetap harus bertanggung jawab! Kau membuat kuda kesayanganku terluka." Sang Patih bergolak.
"Bapak tidak lihat badanku yang berlumur darah ini? Salahkan kudamu yang loncat gak jelas itu sampai jatuh ke jurang," balas Pranaja tanpa rasa takut.
"Viva, sudahlah! Kau tak perlu ikut campur masalah mereka," tegur Arya sembari menyeret lenganku.
"Tidak, Arya! Pranaja tidak boleh dihukum.” Aku menepis tangannya.
"Aku akan memberi keringanan apabila pemuda ini meminta maaf padaku," ujar Patih Gajah Mada dengan tegas.
Aku memberi kode pada Pranaja supaya ia meminta maaf, tapi si kepala batu itu malah memutar bola mata meremehkan. Dasar kekanakan, cari mati.
Aku mendesaknya sampai ia berlutut di depan Patih Gajah Mada yang tampak sangat dongkol. "Lekas minta maaf!" perintahku yang juga berlutut di dekatnya. "Kalau tidak, kamu bisa kena hukum mati."
"Mahapatih yang hamba hormati, hamba memohon ampun, sebab hamba telah membuat kuda Mahapatih terluka," ucap Pranaja dengan mengatupkan kedua tangannya di depan hidung atas himbauanku.
"Baiklah, Anak Muda. Lain kali berhati-hatilah." Pria kekar itu berlalu sembari menuntun kudanya yang lecet pada sekujur tubuhnya.
Warga yang tadinya berbondong-bondong menyaksikan maupun menghakimi Pranaja mulai angkat kaki satu persatu.
Aku bernapas plong kemudian berkata, "Menyusahkan."
"Kalaupun detik itu juga kena hukuman mati, aku berkenan. Siapa tahu dengan mati di sini, aku bisa balik ke masa depan," jelas Pranaja. Aku segera menoleh ke arah suami dan ibu mertuaku yang menatap kami dengan tatapan horor.
"Viva, kau kenal dia?" tanya Biyung.
"Dia ... kawanku."
Arya bersedekap sambil memandangku lekat. Aku tahu dia mencurigaiku.
"Kalau begitu, mari istirahat di rumah kami biar luka-lukamu kuobati" cetus Biyung dengan semringah.
Kulirik Pranaja yang tersenyum lebar hendak membuka mulut mengiakan, tetapi urung ketika beradu tatap dengan Arya yang menatapnya sinis.
"Ah, lain kali saja. Saya bisa membuat ramuan sendiri kok." Pranaja berlalu dengan langkah dingklang.
“Dia kawanku dari Mleccha baru-baru ini. Makanya ia belum bisa bahasa Jawa.”
Biyung tak terlalu memikirkannya, sementara Arya kerap menatapku dalam-dalam, layaknya mencari rahasia sekecil apa pun yang ada pada diriku.
Malamnya aku duduk di pelataran bersama Arya, memandang rembulan yang amat benderang di antara ratri yang pekat. Tak puas aku mengamatinya, ingin kuabadikan memori ini supaya terkenang.
“Di masa depan sudah ada kamera yang bisa mengabadikan setiap peristiwa secara cepat. Bahkan manusia tak perlu dibuatkan arca untuk mengenangnya, melainkan cukup menekan tombol sekali jadi. Aku kepingin dikenang, tetapi aku bukan manusia yang berpengaruh.”
🌼
Berserinya cakrawala berbanding terbalik dengan kegundahanku. Aku tengah bersandar di dada bidang Arya sembari menahan tangis. Sebab, Arya akan pergi berguru kepada seseorang di Gunung Ijen. Ia akan mempelajari ilmu melukis serta mendalami ilmu kanuragan-nya.
"Sudah-sudah, Arya tidak akan lama," ucap Biyung di sampingku sembari menepuk pelan punggungku.
"Iya, Nimas. Tunggulah aku. Jaga diri baik-baik dan jangan pernah berbuat nakal!" ucap Arya, menghapus anak sungai yang membasahi pipiku.
“Tak perlulah belajar melukis segala. Kau sudah menguasai banyak pekerjaan yang membuatmu tak bisa fokus pada satu bidang.”
“Aku bakal mencoba hal baru karena bosan menuangkan karya pada ukiran yang lama rampungnya. Jika ideku langsung dituangkan dalam lukisan, itu bakal cepat selesai dan takkan keburu hilang. Kalau aku berhasil menjadi anglukis, aku akan mengabadikanmu lewat lukisan agar semua orang bisa mengenangmu suatu saat.”
Dengan berat hati, aku melepas rengkuhanku pada tubuh kekarnya. Ia mencium keningku dengan penuh kasih sementara aku memejamkan mata meresapi.
"Jaga diri baik-baik, Kangmas! Aku menantimu," pesanku. Pandanganku buram terhalang air mata yang lagi-lagi hendak mengalir.
Aku dan Biyung memandang kepergiannya dengan sekantong bekal yang dipikulnya. Ia menoleh dan melambai sebelum sosoknya hilang tertutup pepohonan rindang. Aku memeluk Biyung sembari meneteskan air mata lagi.
Bagaimana pun, Arya adalah orang yang amat kucintai. Seseorang yang sering bergurau denganku di sawah, menghiburku yang tengah dilanda kebingungan akan peradaban. Arya yang selalu mengusiliku. Arya yang selalu memberiku kehangatan, tak akan kujumpai selama tujuh purnama mendatang.
🌼
Biyung bertolak ke pasar untuk membeli kain yang katanya sedang turun harga. Sedangkan aku hendak mencuci pakaian di sungai, sekalian bertandang ke tempat tinggal Pranaja yang cukup layak berkat sentuhan tangan Arya.
"Viva, mampir dulu sini!" seru Pranaja saat aku berjalan di depan rumahnya.
Aku yang memang niat bertamu pun mengiakan seruannya.
"Kenapa matanya sembab begitu? Habis nangis?" tanyanya.
Aku yang semula tersenyum ramah berubah menjadi lesu dan menyahut, "Ditinggal suami berguru."
"Kasihan. Belum isi?"
Mataku membola dengan pertanyaan ambigu itu.
"Isi apa maksudnya?" tanyaku ketus.
"Ya perut kamu," balasnya dengan enteng.
"Belum lah! Umurku saja masih ijo begini, belum siap jadi emak-emak!" ucapku bersungut-sungut. Malu sekali membahasnya.
"Hahaha. Mau mencuci? Aku bantu ya." Aku mengangguk, tak baik menolak bantuan.
Selepas mencuci, kami beriringan melewati jalan setapak yang tandus untuk kembali ke pondoknya. Di sepanjang jalan, beberapa mawar merah unjuk diri dengan keharuman.
Seandainya aku memiliki ponsel, sudah pasti Pranaja akan kusuruhi memotretku di tempat indah ini.
"Bagus sekali, ya. Di kota tidak ada suasana tenang seperti ini," celetuk Pranaja yang membawakan bakul beserta pakaian milikku.
"Iya. Minusnya, kemistikan masih kental di sini. Lihat saja di bawah pohon-pohon. Pasti ada dupa, bunga, kemenyan, atau sejenisnya," sahutku sembari melihat sesajen atau apa pun itu sebutannya di bawah pohon beringin. Pranaja mengiakan, mengikuti arah pandangku.
"Kita jalan berdua begini gak apa-apa? Nanti kalau suamimu tahu?" celetuk Pranaja setelah terjadi kesenyapan sekian detik.
"Gak apa-apa. Pondokmu jauh dari pemukiman dan takkan ada warga yang gosip atau mengadu ke Arya soal kita."
"Kata-katamu kayak kita lagi menyeleweng saja." Kemudian kami tergelak.


 orenertaja
orenertaja