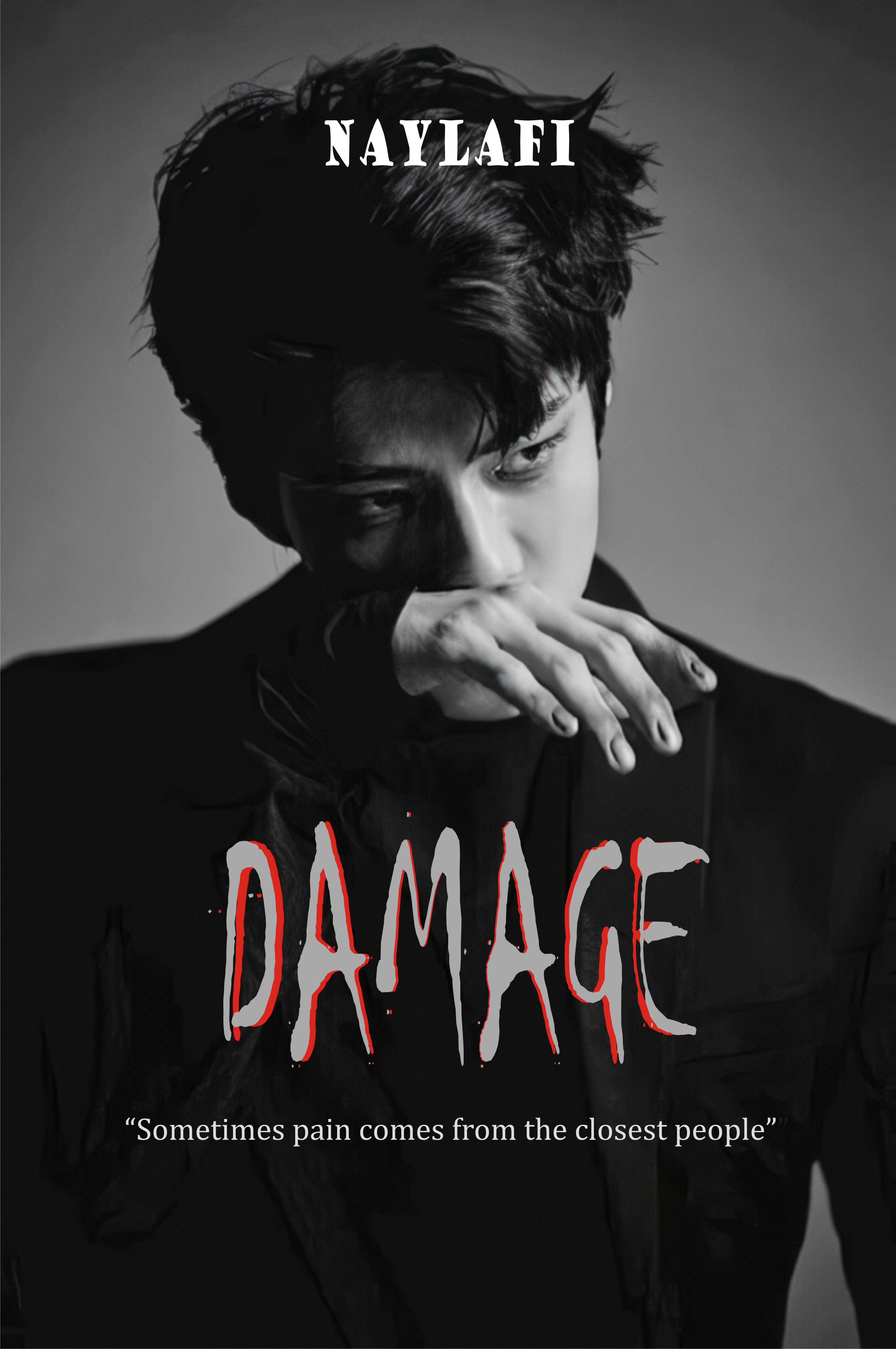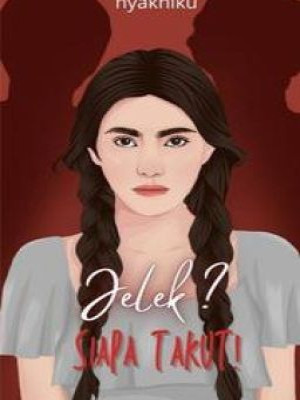Kami hanya berputar-putar mencari lahan kosong tetapi hasilnya nihil. Semua wilayah dijadikan ladang milik orang dan aku semakin dikejar waktu untuk kembali ke rumah karena matahari kian beranjak mencapai pucuk kepala.
“Kau dapat memotong bambu di sana kemudian kaujadikan anyaman bambu.” Aku meminjamkannya keris yang terselip di balik jarik yang melilit pinggangku.
“Jangan tinggalkan aku! Kau harus membantuku.” Ia menatapku nanar, mengambil keris yang kusodor dengan kuyu.
“Keluargaku bisa mengamuk jika aku tak kunjung pulang. Besok aku akan kembali ke sini.” Aku tak tega menatap wajah menyedihkan itu. Gegaslah aku berbalik, siap-siap mendapat wejangan karena telat pulang.
Matahari benar-benar mencapai atas kepala, membakar kulitku yang semakin gelap di bawah bulu halus yang menurut Arya menjadi penambah kemanisan seorang Nayaviva. Gapura batu bata sudah tampak dan aku gamang untuk ke sana, takut ditanya macam-macam. Namun, Arya sudah melihatku lebih dulu dari balik papan kayu yang tengah ia ukir.
“Kenapa berdiri di situ? Cepat kemari!” serunya, membuatku nyengir.
Aku menjemur cucianku pada tali yang memanjang dari pohon nangka sampai pohon jambu kemudian mencuci kaki dan tangan di sumur. Niatku ingin cepat-cepat masuk ke dalam menghindari Arya dan segala pertanyaan yang akan dilontarkan. Namun ia keburu memanggilku, membuatku melangkah gontai menghampirinya.
“Besok aku akan panen di sawah. Kau jangan pulang telat lagi karena harus mengirimiku makan siang,” ujarnya.
“Baiklah.”
“Mengapa kau pulang sampai tengah hari begini?”
Napasku tercekat sebelum menjawab, “Tadi cucianku ada yang hanyut. Aku harus mencarinya dahulu.”
“Apakah pria yang bersamamu itu tidak menolong?” Ia sibuk mengukir, tampak tak acuh padaku sementara lidahnya menghunjam jantungku.
“Jangan mengada-ada.” Aku berkilah, tetapi suaraku menelan ludah terlalu jelas.
“Di mana kerismu?”
Aku pura-pura mencari di balik jarik, kemudian mengatakan bahwa benda itu hilang.
“Viva, jangan sekali-kali membohongiku.” Ia menatapku tajam. Bayangan harimau putih terbayang lagi. Aku menciut menghadapi sikap Arya yang tak tengil seperti biasanya.
Aku terus menunduk sementara ia sibuk dengan pekerjaannya. Kami diselimuti kecanggungan yang baru pertama kali terjadi. Arya tak pernah menakutkan seperti ini. Aku lebih suka ia memarahiku terang-terangan daripada membunuhku dalam diam seperti ini. Terlampau takut dengan aura gelapnya, aku melangkah mundur sebelum berlalu ke dalam rumah.
Hari itu Arya tak kunjung buka suara kepadaku. Biyung tidak menyinggung apa permasalahan kami dan tampak tak acuh. Arya menolak makan bersama kami dan lebih memilih makan di teras. Dalam hati aku mengomeli sikapnya yang mirip anak kecil, mudah merajuk dan diam seribu bahasa seolah-olah aku bakal peka akan kesalahanku kemudian berlutut minta ampun padanya.
Jika ia bungkam seperti itu, aku juga bisa mengunci mulut rapat-rapat. Aku bakal memberinya umpan balik sesuai yang diberikannya padaku.
Esoknya, aku bergegas ke kali untuk mencuci kain yang sudah menumpuk lagi. Kudapati potongan-potongan bambu tergeletak yang belum dibelah apalagi dijadikan anyaman. Yang membuatku terperangah bukan itu, melainkan sosok Pranaja yang meringkuk di bawah pohon waru. Aku mendiamkannya dan lekas menyelesaikan cucianku.
“He kau! Aku lupa siapa namamu. Kuharap kau puas melihatku mengenaskan seperti ini,” celetuknya belum beranjak dari bawah pohon waru.
“Kan sudah kubilang, buatlah anyaman bambu lalu dijadikan gubuk,” sahutku.
“Kau pikir keris sekecil ini bisa menggorok bambu dengan cepat? Kalau bego jangan terlalu!” Ia balas mengotot.
“Dasar tidak tahu terima kasih! Menyesal aku menolongmu!” Aku melangkah cepat meninggalkannya. Terserah keris itu tak dikembalikan. Aku sudah muak dengan lelaki songong itu. “Kok bisa lanangan angkuh itu populer di kalangan mahasiswi. Edan. Gara-gara dia, Arya merajuk padaku.” Aku terus menggerutu dengan mulut manyun.
“Eh tunggu! Tak ada niat untuk membantuku?” Ia menyusul langkahku. Kulirik pakaiannya yang kusut dan wajah yang kucel. Bau keringatnya menguar membuatku tambah gondok akan sosoknya.
“Gunakan otakmu sendiri. Aku cuma perempuan bego yang tak kauperlukan.” Aku mempercepat langkah, risi dengan lelaki sombong yang telah merendahkanku itu.
“Maafkan aku, eh siapa namamu?” Ia menghentikanku dengan cekalan tangannya.
Aku menepis, tapi ia terlampau kuat. “Viva.”
“Viva, maafkan aku. Aku tiap kelaparan memang suka kelepasan. Tolong bantu aku, ya?” Ia berlutut sembari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukannya iba, aku malah tambah jengkel mendapati raut menyebalkan itu. Aku menolaknya dengan mengibas-ngibaskan cekalan tangannya di pergelangan tanganku yang terdapat gelang berukir naga. Setelah mengembuskan napas frustrasi, aku mengiakannya dengan syarat ia harus menuruti segala ucapanku.
“Nanti siang aku bakal mampir ke sini. Akan kubawakan kau golok dan alat lain untuk membuat gubuk. Sekarang aku harus cepat pulang. Lepaskan aku!”
“Ah, lama sekali! Aku keburu mati kelaparan!” protesnya.
“Kau sudah janji untuk jadi pengikutku. Jangan melayangkan protes apa pun! Selagi menungguku, kau bisa cari buah-buahan di sekitar.”
Akhirnya ia melepaskan cekalannya dengan tatapan tak rela sementara aku menjauh.
Arya sudah berangkat ke sawah ketika aku sampai rumah. Matahari baru menyingsing dan kabut tipis pudar sepenuhnya. Sembari menunggu waktu siang, aku bertamu ke beberapa tetangga untuk berkenalan lebih jauh supaya mereka tak lagi nyinyir terhadapku. Tiga rumah tetangga kusambangi, amat puas dengan suguhan mereka yang berupa pinang, daun sirih, dan jeruk nipis untuk kukunyah bersama mereka. Karena tak baik menolak, aku terpaksa melakukannya, toh gigiku juga bakal lebih bersih dan sehat.
Matahari hampir di atas kepala ketika aku berangkat ke sungai tempat Pranaja meratapi nasib. Kubawa golok, gorok, dan arit di dalam bakul yang juga berisi makanan.
“Kau mau ke mana lagi?” tanya Pranaja saat melihatku beranjak. Tangannya mencomot nasi dan ikan asin dengan buru-buru.
“Ke sawah, mengantarkan ini pada suamiku.” Aku menunjukkan bungkusan makanan lain dan segelas bambu air putih.
“Kau sudah bersuami?!” Ia melotot dan menghentikan kunyahannya. Sementara aku merengut kesal menghadapinya yang banyak tanya itu.
Aku bergegas melangkah ke petak-petak sawah yang letaknya tak terlalu jauh dari kali. Sesampainya di pematang sawah, aku melambai dari kejauhan pada lelaki yang sedang leyeh-leyeh di bawah pohon pisang.
"Apa yang kau lakukan di perjalanan?" tanyanya tanpa ekspresi.
"Ya berjalan lah," jawabku ketus.
"Kau bertemu laki-laki, bukan?"
"Kok tahu?"
"Aroma mu berbeda." Salah satu sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum miring. Aku bertanya-tanya dalam hati bagaimana bisa ia mengetahui segala yang kulakukan?
Keheningan lagi-lagi menyelimuti kami. Dua elang terbang jauh di atas kepala kami. Sang surya telah mencapai puncak singgasana, menyebarkan hawa panas dengan teriknya.
Arya memandang lurus ke depan. Sejak Arya tahu kalau aku berasal dari masa depan, ia tak lagi akrab padaku. Entah apa alasannya, padahal aku sudah nyaman dan bisa beradaptasi dengan tempat ini.
"Kurasa ada orang lain yang tertarik padamu," ucap Arya dingin.
"Aku tidak peduli! Kau pasti tahu kalau aku hanya mencintaimu seorang," sahutku tak terima.
"Kalau begitu, beri aku seorang putra agar hubungan kita lebih terlihat."
"Astaga, Kangmas! Kau sekarang seperti paedofil!" Dengan panik aku berlari menjauh darinya.
Kami berkejar-kejaran layaknya adegan di film Bollywood. Aku yang memakai jarik tentu saja kalah cepat dengan Arya yang punya langkah lebar. Ia berhasil menyergapku dengan melingkarkan lengan kekarnya pada perut rataku sebelum meletakkan dagunya di bahuku.
"Wajahmu memerah. Kurasa panas matahari terlalu menyengat hari ini," bisiknya di balik tengkukku sembari menggerakkan tangannya ke atas perutku, makin ke atas kemudian mengepal pelan buah dadaku, membuatku spontan mendesah.
"Viva! Kau meninggalkan lauk untuk sua... Aaaaa mataku ternoda!"
Astaga! Itu Pranaja. Aku segera memisahkan diri dari dekapan Arya kemudian menghampiri Pranaja.
"Dasar! Merusak suasana saja," kataku sambil menunduk menahan malu dan merebut bungkusan daun jati berisi lauk untuk Arya.
"Salah siapa lupa tempat." Pranaja mendekat pada sosok yang selalu membayangiku dengan harimau putih, mengulurkan tangan sambil berkata, "Hai, saya Pranaja Reswara."
Arya menatap tajam Pranaja tanpa membalas uluran tangan pemuda di depannya. Terpaksa, aku pun menyikut pinggang suamiku itu.
"Arya Buntara, suami Nayaviva."
"Posesif amat, Pak!"
"Aku tidak tahu bahasamu, tapi aku paham apa yang kau maksud. Apa perlu kukeluarkan keris dari warangkanya?" Aku melirik Pranaja yang jakunnya naik-turun itu. Arya memang senantiasa membawa sebilah keris yang dikaitkan pada ikat pinggangnya.
"Sudahlah! Kalian ini kenapa? Lebih baik petikkan aku kelapa muda!" Arya segera melengos pergi menuju pohon kelapa yang sedang berbuah hijau muda.
"Suami kamu mengerikan," kata Pranaja setengah berbisik.
"Begitulah, tapi sebetulnya tengil kok," sahutku setelah terkikik geli.
Sekembalinya Arya, ia menginterogasi hubunganku dengan Pranaja yang tampak mencurigakan di matanya itu. Aku menjelaskan awal pertemuan kami dan asal-usul Pranaja yang sama dari masa depan. Tak ketinggalan, kujelaskan penyebab Pranaja bertampang awut-awutan seperti itu, bahwa ia sedang butuh tempat tinggal.
Arya merengut padaku setelah mendengar bahwa aku diam-diam membawa beberapa senjata dari rumah untuk membantu Pranaja. Namun, aku berhasil membujuknya untuk membantu membangunkan tempat tinggal untuk Pranaja.
“Aku mau membantu bukan karena kau! Aku hanya tak membiarkan istriku berduaan denganmu.” Arya menghunus Pranaja dengan matanya yang tajam.
“Dan kau, Viva. Lain kali jujurlah padaku. Berbohong walau hanya satu kali akan membuatmu terbiasa lama-kelamaan.” Tatapannya ganti menghunusku. Aku tak berani beradu pandang dengannya lebih lama dan memilih untuk menunduk.
🌼
“Kau yakin akan tinggal di sini?” tanya Arya tak yakin. Ia berkacak pinggang sembari mengamati tanah pinggir kali yang menjadi bakal rumah Pranaja.
Karena Pranaja tak paham bahasa Jawa Kuno dan Arya tak paham bahasa Indonesia, akulah yang menjadi penerjemah dan perantara mereka bercakap-cakap.
“Kau bisa tinggal di pemukiman Mleccha yang lebih layak. Pekerjaanmu juga bakal jelas.” Arya masih bimbang.
“Mleccha itu apa lagi?” Pranaja menyeletuk padaku.
“Pemukiman para warga asing,” jawabku.
Pranaja terburu-buru menggeleng. “Aku takut ketemu orang-orang keras dari zaman ini apalagi dari luar negeri. Tidak apa-apa menyepi di sini dengan gubuk yang sempit.”
Dengan kepercayaan diri tinggi, Pranaja menggorok bambu dengan ukuran yang ditentukan Arya. Kemudian suamiku itu terus menggerutu karena Pranaja tak becus menganyam bambu. Sementara itu, aku berteduh di bawah pohon sembari menikmati kelapa muda dan menonton mereka berdebat dengan bahasa masing-masing.
Arya tak membolehkanku membantu, lagi pula itu pekerjaan kaum laki-laki. Perdebatan dengan logat berbeda itu membuatku tergelak kencang, cukup terhibur mengetahui Arya tidak lagi membisu. Mereka terlihat seperti anak-anak yang tengah silang pendapat dan tak terlalu serius menanggapi pertikaian itu. Arya mematahkan stigma tentang betapa keras dan seriusnya pria Jawa Kuno. Nyatanya mereka mempunyai sisi kekanakan juga.


 orenertaja
orenertaja