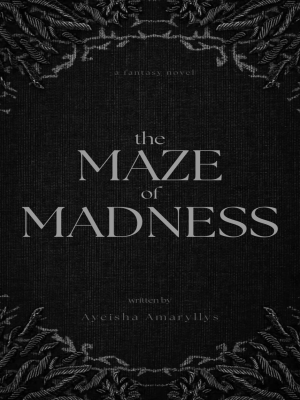"Kau mau ikut ke pasar bersamaku?" Ia alihkan pembicaraan yang tak lagi enak dilanjutkan.
Aku mengangguk antusias. Selama aku tinggal di sini, Emak tak pernah mengajakku pergi ke mana-mana, khawatir kalau aku tersesat karena masih hilang ingatan.
Setibanya di pasar, aku dibuat terpukau oleh masyarakat yang ramah dan saling sapa, juga suasananya terasa berbeda dibanding pasar-pasar di zamanku. Rata-rata perempuan memakai kemban dan rambutnya digelung. Ada beberapa yang memakai alas kaki berbahan dasar kayu maupun jerami. Sedangkan yang laki-laki kebanyakan bertelanjang dada memamerkan kilauan dari keringat mereka yang melumuri tubuh kekar khas pekerja keras.
"Apa yang kau inginkan?" tanya Arya sembari melihat-lihat barang dagangan di kanan-kiri kami.
Aku masih mengamati barang-barang yang tampak antik di mataku. Guci tanah liat yang berukiran tanaman rambat tampak menarik, tapi aku pun kepingin memiliki pernak-pernik perhiasan yang tampak berkilau di antara barang dari tanah liat lain. Sayangnya aku tak punya uang, bahkan aku tak tahu bagaimana rupa mata uang di sini.
"Tenang saja, aku yang akan membayarnya." Arya menginterupsiku untuk cepat memutuskan apa yang akan kubeli, karena kami sedari tadi berdiri diam di tengah jalan.
"Apa kau bisa membaca pikiran orang lain?" Aku berjalan ke arak lapak perhiasan berkilauan yang mengasah mata. Arya hanya tersenyum jenaka dengan pertanyaanku.
Banyaknya desain dari gemerlapnya emas dan permata itu membuatku bingung memilih. Alih-alih tertarik dengan emas yang menyilaukan mata, aku lebih tertarik pada beberapa cincin yang tampak terasingkan di sebelah kiri. Kusambar cincin warna cokelat dengan ukiran Surya Majapahit yang menarik perhatianku karena benda itu berbeda dari cincin kebanyakan yang dipajang.
Aku tersenyum penuh arti pada pemuda yang akan mentraktirku itu dan tanpa banyak kata ia sambar cincin yang sama dan memberikan beberapa keping koin pada penjualnya. Jadilah selain gelang, kami punya cincin yang sama.
"Aku penasaran dengan koin tadi," ucapku seraya memamerkan jemariku yang tampak apik memakai cincin Surya Majapahit.
"Kenapa?" sahutnya sembari mengambil koin dari saku celananya kemudian disodorkannya sekeping padaku. Kuamati lubang persegi pada koin tembaga yang dikelilingi motif kembang wijayakusuma ini, tersenyum mendapat pengetahuan baru.
"Bisa kau jelaskan tentang mata uang ini?"
Arya mengernyit, tapi tetap menjelaskannya, "Itu gobong, salah satu mata uang Majapahit. Hiasannya bervariasi, ada tumbuhan, hewan, juga manusia. Memangnya kau tidak tahu?"
"Beberapa bulan lalu, kepalaku terbentur batu dan hilang ingatan sampai saat ini."
"Kenapa kau tidak pernah bercerita?" Raut wajahnya tampak khawatir, tetapi aku tak suka kalau ada yang menatapku iba seperti itu, padahal aku sendiri tidak kenapa-kenapa.
"Aku ini ceroboh, jatuh ke jurang karena berlarian di dekatnya." Arya menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya mendengar penuturanku.
"Semoga ingatanmu cepat pulih. Aku akan membantu menjelaskan apa pun yang ada di sini jika kau mau, siapa tahu ingatanmu kembali," katanya membuat benakku bersorak. Beruntunglah kalau Arya mau menjelaskan hal-hal yang tidak aku mengerti, jadi tak perlu lagi banyak tanya pada Emak yang tak bisa santai kalau menerangkan.
🌼
Di perjalanan pulang, kami melewati permukiman yang warganya berperawakan asing.
"Arya, mereka bukan asli Jawa?" tanyaku penasaran.
"Ini daerah Mleccha, pemukiman warga selain penduduk asli Majapahit. Ada etnis Cina, Melayu, juga India,"
Aku mengangguk paham sembari mengamati mereka yang berlalu-lalang membawa gerobak maupun tampah yang dibawa di atas kepala. Sepertinya pekerjaan mereka memadai.
Walau belum genap satu bulan aku tinggal di masa ini, aku sudah terbiasa dengan semuanya. Perlahan-lahan aku bisa beradaptasi dan merasa aman tinggal di Majapahit, walau terkadang aku rindu orang tuaku di masa yang ratusan tahun kemudian baru terbentuk.
"Bapamu dulu adalah prajurit?" tanya Arya saat kami melewati bulak— jalan sepi di tengah hutan yang jauh dari perumahan.
"Kata Emak begitu," jawabku apa adanya.
Dulu, waktu pertama kali Emak menjelaskan tentang Bapa, aku terkagum-kagum hingga sekarang karena beliau yang tampak gagah di medan perang tetapi berlagak seperti bocah jika bersama Emak. Beliau gugur saat tragedi Perang Bubat yang memakan banyak korban dari negeri Sunda maupun Majapahit.
Sembari berjalan, aku memandang dengan berbinar cincin yang melekat di jari manisku, dan teringat kalau aku belum berterima kasih pada si pemberi. "Terima kasih buat cincinnya, nanti uangnya kuganti," celetukku. Padahal aku tak tahu bagaimana mendapat uang untuk menggantinya.
"Tidak perlu. Anggap saja hadiah dariku," sahutnya sembari tebar pesona dengan memamerkan senyumnya. Berjalan di jalanan landai membuatku tak merasa lelah hingga kami tiba di rumah.
"Baiklah, lagi pula aku tidak punya uang." Aku nyengir sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal.
Arya tergelak, menepuk halus kepalaku layaknya diriku ini kucing. Aku yang diperlakukan seperti itu hanya bisa menunduk menyembunyikan wajah yang tersipu-sipu tanpa bisa kukendalikan.


 orenertaja
orenertaja