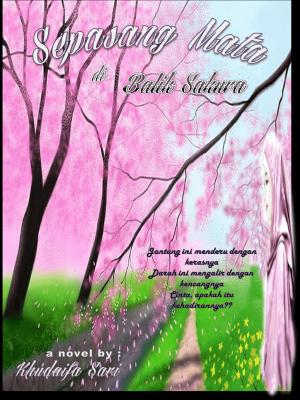Deru ombak bersahutan saling memekik dengan suara-suara lain di bibir pantai ini. Sudah lima belas menit lalu kami bercengkrama dan menunggu. Satu persatu teman-temanku berdatangan dengan berbagai gaya, masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ada yang dulu abai terhadap penampilan sekarang malah sangat fashionable. Ada yang dulu pendiam sudah banyak tata bahasa, entah sejak kapan belajar berkata-kata tanpa jeda. Ada yang dulu sangat sopan berpakaian, bisa kuhitung tak pernah pakai celana ketat kini kerudungnya sudah melilit di leher. Ada yang dulu ratu kecantikan di kelompok kami, ke mana-mana selalu bermake-up, celana kecil ke bagian bawah, baju lebih kecil dari ukuran tubuhnya, kerudung selalu tidak pernah menutupi dada sekarang malah lebih sopan pakaiannya dibanding kami semua. Semua bisa berubah. Bagi yang ingin!
Di dalam saung beratap rumbia dan beralas papan persegi empat, kami berlima duduk melingkar. Sesekali pandanganku menyapu pasir putih dan orang-orang berselancar di antara ombak membesar. Kebanyakan dari peselancar bermata biru dan berambut pirang dengan postur tubuh lebih besar dari tubuh pribumi. Di bibir pantai, para pejalan kaki saling kejar dan penuh canda. Ada juga yang bermain dengan jilatan ombak. Ada pula yang berenang di antara ombak. Ada pula yang duduk-duduk menghadap ke lautan lepas.
Matahari sudah sangat condong ke barat. Hawa panas membuat kulit wajahku terasa begitu kusam. Bisa-bisa warna kulitku segera berubah kembali gelap dalam sekejap. Bukan tidak bersyukur dengan warna kulit yang kumiliki, selama menetap di benua orang-orang berkulit lebih terang aku pun ikut menjadi ikut-ikutan mereka. Ternyata benar, cuaca membawa pengaruh pada tubuhku yang sensitif dan mudah beradaptasi dengan keadaan.
Pantai Lampuuk punya tempat tersendiri bagi kami. Pantai ini selalu saja meninggalkan kesan tidak terdefinisi dalam batinku. Walaupun pantai ini berulang kali menelan korban, tidak mengurung niat orang-orang berlibur bersama teman-teman mereka maupun keluarga. Pantai ini tidak terkotori dengan orang-orang berpakaian tidak sopan, siapa juga tahu negeri ini sudah mengatur tata berpakaian sopan. Beberapa kali aku pernah ikut piknik bersama teman-teman semasa kuliah di tempat wisata Amerika, aku jadi malu sendiri melihat pemandangan yang selama ini hanya kulihat dalam film-film. Perempuan berpakaian sangat minim, hanya menutup bagian penting saja. Laki-laki pun demikian. Di sini, laki-laki peselancar itu yang tak lain warga negara asing mengikuti peraturan negeri ini.
Kelapa muda yang kami pesan terhidang juga di depan kami berlima. Seteguk kelapa muda ini rasanya tidak sebanding dengan kelapa muda di tempat lain. Karena kami di tepi lautan lepas dengan pemandangan yang mahaindah. Lukisan Sang Kuasa tidak mampu membuat mataku berpaling darinya. Belum ada pula pelukis yang mampu menoreh gunung melingkar, lautan biru, pantai putih, deru ombak, saung-saung berjejer rapi, dan matahari yang mulai tenggelam, ke kanvas mereka dengan penuh imajinasi.
Selalu saja. Sifat narsis memuncak begitu Arin mengeluarkan kamera besar miliknya. Kami semua tahu, Arin sang fotografer dalam kelompok kami. Perempuan yang dulu kurus ini lebih beruntung dari kami semua, selesai sarjana langsung terbang ke Australia mengejar pendidikan selanjutnya. Penampilan Arin pun sudah berubah. Arin yang dulu membantai kami yang berpakaian minim dengan nasehatnya kini malah terbalik. Perempuan yang ke mana-mana dengan kameranya itu memang pernah kulihat memposting beberapa foto dirinya di jejaring sosial dengan celana ketat dan berbagai gaya bersama teman-teman lelaki mata birunya di Australia. Setahuku, Arin paling anti dengan celana ketat dan bertegur sapa dengan laki-laki sangat jarang. Kami seperti sama-sama menerima perubahan masing-masing dan tidak ada yang memberi unek-unek akan perubahan ini. Kurasa kami punya pandangan tersendiri akan masalah pribadi. Satu sisi aku berhak menegur Arin yang sudah berubah jauh, sisi lain aku juga harus berada di garis privacy. Aku dan Arin sama-sama pernah tinggal dan berinteraksi dengan orang-orang dari kehidupan Barat yang notabene sangat menjunjung tinggi kehidupan pribadi perindividu. Aku dan Arin jadi semakin jauh saat gerak-geriknya tidak dapat lagi kuterka.
Arin mengajak kami berfoto. Gaya dan tawa membahana saat kami melihat hasil yang tidak sesuai keinginan. Tak sungkan pula Arin meminta laki-laki yang lewat di depan kami untuk membidik tingkah polah kami menghadap ke lautan lepas. Cara Arin bertegur sapa dengan laki-laki pun kurasa sudah dibatas kewajaran. Arin sudah lebih genit, centil dan berjabat tangan dengan laki-laki. Hal yang tidak pernah bahkan ditentang Arin sebelum ke Australia. Kami melihat pemandangan yang tak biasa itu dengan tatapan nanar, Arin bahkan tidak merasa ada yang salah dalam dirinya.
Lalu Tutun, perempuan ini termasuk golongan amburadul dalam kelompok kami. Selama aku mengenalinya baru sekarang aku melihat Tutun berpakaian sesuai perubahan masa. Tutun memang tidak pernah menuruti dunia kecantikan dan keindahan seperti halnya pada perempuan kebanyakan. Penampilan Tutun tidak pernah enak kulihat semenjak awal perkuliahan kami. Tutun selalu tak berbedak, apalagi mengecat bibirnya yang pucat. Baju dan rok yang terkadang perang warna ditambah lagi dengan kerudung yang miring kiri kanan.
Aku merasa senang mendapati Tutun yang sekarang sudah memiliki fashion tersendiri. Wajahnya sudah bermake-up tebal dengan bibir merekah. Tidak menor dan tidak pula pucat. Pas untuk takaran warna kulit Tutun yang lebih gelap di antara kami. Pakaian Tutun pun sudah sangat modis. Tutun memang bukan perempuan yang pakai celana ketat, dari dulu aku pernah melihat Tutun pakai celana, seperti hari ini, celana kain besar mengecil ke bawah yang tak melekat di pahanya berwarna abu-abu, dipadu dengan baju lengan panjang dimasukkan ke dalam dengan motif bunga-bunga kecil warna putih, lalu kerudung warna putih dibuat lebih kreatif bagai model artis di televisi. Tutun benar-benar sudah menjadi bidadari di antara kami dengan tinggi badan di atas kami semua.
Si pendiam Erni sekarang lebih banyak bersuara. Erni termasuk perempuan yang tidak pernah membuang kata-katanya. Bicara apa adanya. Selera humor Erni pun tidak pernah ada semenjak kukenal dia. Erni yang dulu hanya bicara dengan buku-buku sekarang malah lebih semarak dibandingkan kami. Erni yang dulu tak pernah tertawa lepas sekarang malah lebih ceria dari pada kami. Erni yang dulu hanya diam dalam diskusi sekarang malah paling sering mengeluarkan pendapatnya.
Ketiga temanku banyak sekali mengalami perubahan. Dua tahun aku kuliah di Amerika, ditambah dua tahun kami tak saling berpeluk karena kesibukan masing-masing perubahannya sangat terasa. Kupikir dunia maya penuh penipuan, aku tidak pernah percaya saat Arin mengatakan pacarnya seorang laki-laki tinggi dengan postur tubuh gempal dari Belanda. Aku tidak pernah tahu Erni menjadi pembicara ulung di setiap seminar semenjak menjadi asisten dosen. Aku pun tidak pernah diskusi masalah tata busana maupun kecantikan dengan Tutun yang kini sangat paham betul semua perkara perawatan tubuh. Ketiga temanku ini benar-benar membuatku iri akan perubahan mereka. Yang lebih iri lagi, perubahan yang terjadi pada Kazol.
Tidak pernah terpikir olehku ratu kecantikan ini menjadi seorang perempuan yang menghebat suaranya. Sifat dasar Erni sudah diembat Kazol sampai ke akar-akarnya. Kazol yang biasanya lebih banyak bicara malah tips-tips biar tampil cantik dan modis sekarang malah menggangguk saja apa pun yang diutarakan Tutun. Wajah Kazol pun tidak semenor dulu dengan pakaian lebih sopan dibandingkan kami semua. Kazol mengenakan rok lebar, baju panjang selutut lalu kerudung sampai ke perut. Aku tidak menemukan lagi Kazol yang dulu pernah anti dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan khas perempuan. Aku juga tidak menemukan lagi peralatan make-up dalam tas samping Kazol. Sifat Kazol yang dulu sudah diambil Arin dan sifat Arin sudah dilahap Kazol sampai habis.
Orang-orang akan berubah sesuai takaran mau mereka. Aku pun berubah. Sejak dulu aku memang bukan perempuan yang seenaknya saja dengan penampilan. Aku selalu memperhatikan perpaduan antara baju, celana maupun kerudung. Aku juga perempuan yang memakai rok maupun celana. Pakaian yang kugunakan biasa-biasa saja. Tidak mengurasi batas aturan yang sudah ditetapkan negeri kami ini.
Hari ini aku memakai celana katun dengan warna hitam, celanaku hampir sama dengan Tutun, besar dibagian paha lantas mengecil ke bawah. Bajuku pun hampir sama dengan Tutun berwarna putih dengan motif bunga kecil-kecil melingkar di depan dan belakang, hanya saja model bajuku memiliki karet dipinggang jadi tidak perlu kumasukkan ke dalam celana. Dan kerudung kupilih warna mendekati hitam polos, kulilitkan ke leher dan menjuntai ke belakang tanpa kuapa-apakan di bagian atas.
Kami sudah selesai mengabadikan beberapa gaya di depan pantai yang semakin ramai. Sebentar lagi kami akan melihat sunset di balik gunung. Sambil menunggu matahari terbenam kami kembali duduk di saung yang masih tersisa kelapa muda.
“Aku masih belum percaya kamu udah menikah, Er!” kata Arin lebih dengan nada menyindir. Entah apa maksud Arin berkata begitu.
“Semua orang akan menikah lho, Rin!” ujar Erni tak kalah girangnya dibandingkan Arin. “Kamu juga harus menikah, punya suami itu berjuta rasanya,” lanjut Erni sambil melihat kami satu persatu. Kecuali Arin, kami memasang wajah antusias dan harap-harap cemas. Arin tampak tidak bersemangat membicarakan pernikahan, namun entah alasan apa Arin memulai masalah ini.
“Aku masih belum siap, Er!” kata Tutun sambil menggigit bibir bawah.
“Kenapa? Aku yang sudah menikah senang-senang saja, suamiku malah lebih mengerti aku dibanding diriku sendiri. Suami paham aku harus makan apa, kapan aku menyusui, kapan aku masak makanan enak, kapan aku istirahat, kapan aku membaca, kapan aku ngajar, semua sudah diatur suami dari mulai pagi sampai paginya lagi!” tegas Erni penuh semangat. Si pendiam Erni memang sudah terbenam. Mungkin ini salah satu faktor Erni menjadi lebih banyak bicara, karena bahagia, sudah bersuami. Aku makin iri dengan Erni yang mendapatkan suami pengertian dan tidak egois. Teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama, selain Arin yang tidak tertarik dengan tema pembicaraan kami yang sebenarnya Arin buka sendiri bagai moderator tanpa permintaan.
“Aku malah nggak laku-laku, Er!” nada putus asa Kazol membuat kami terdiam. Kulihat Erni mengenggang erat tangan Kazol.
“Jodoh itu punya kita yang cari, sudah ditentukan siapa laki-laki terbaik untuk kita,” mata Erni terbinar.
“Kali saja belum lahir, Er!” nyelutuk Arin membuat kami semua terpana. Arin yang dulu punya segudang referensi dalam berbagai hal masalah agama kini tak pernah mengeluarkan ingatannya itu. Sikap Arin malah cuek saja setelah mengeluarkan kata-kata yang memukul rata. Arin yang duduk di muka, menjuntai kakinya menyentuh pasir kembali memotret pemandangan sore.
Erni tidak menjawab pernyataan Arin. Aku malah mendapati cibiran dari Tutun yang mengisyaratkan Arin tak lagi sama.
“Eh, kalau ada teman suamimu yang baik banget kayak suamimu itu kenalinlah sama kita-kita yang masih sendiri ini,” kata Tutun dengan mimik memelas. Serentak kami menyenggol Tutun dengan mengeluarkan suara protes. Dan lagi-lagi Arin tidak terpengaruh.
“Bereslah, aku akan bilang sama suamiku ya!” kata Erni penuh senyum.
“Tapi aku harus pulang, guys!” ujarku kemudian. Teman-temanku saling pandang. Termasuk Arin yang sedari tadi konsentrasi dengan aktivitas fotografernya.
“Pulang sekarang? Bentar lagilah, sunset belum lagi muncul!” protes Arin.
“Bukan itu, Rin! Maksudku, aku harus pulang ke kampung, tidak lagi di Banda!”
Teman-temanku saling pandang. Keputusanku memang berat, aku sendiri masih belum yakin bisa menyesuaikan diri di kampung. Aku sudah terbiasa hidup di kota besar, belajar dari banyak orang hebat, lalu harus pulang ke kampung dan berinteraksi dengan orang-orang yang tak bersekolah. Bukan aku merendahkan pendidikan mereka, tapi benar kan? Pendidikanku sudah tidak setara dengan kampung halamanku. Entahlah.
“Kenapa harus pulang? Di Banda masih banyak kok kerja untukmu!” ujar Arin. Kali ini lebih antusias. “Aku bisa rekomendasikan dirimu ke beberapa teman di LSM, paling kamu wawancara terus langsung kerja!”
“Atau kamu ngajar di kampus? Aku minta bantu suami cariin jadwal yang pas untukmu,” kata Erni.
Mataku berpaling ke Tutun dan Kazol. Kedua temanku ini memang belum melanjutkan pendidikan mereka karena terhalang tugas kerja. Sebagai pegawai negeri mereka pasti tidak punya masukan berarti untukku. Tutun di salah satu kantor pemerintah kota Banda dan Kazol memilih jadi guru. Kedua temanku ini sama-sama mengangkat bahu tidak ada solusi. Artinya aku harus mempertimbangkan dua pilihan. Ikut tes pegawai negeri aku harus menunggu hingga akhir tahun, itu pun persaingannya antara ketat dan kedekatan dengan pejabat, belum tentu ijazah luar negeri menjamin aku lulus dengan mudah.
Kulirik Arin dari ujung kaki sampai kepala. Aku merasa asing bersama Arin. Aku pun tidak nyaman berada di dekat Arin yang sudah berubah pola pikirnya. Aku tidak menyalahkan pendidikannya di Australia, aku pun tidak mengkambinghitamkan LSM tempatnya bekerja. Arin menentukan sendiri bagaimana dirinya bersikap dan bertingkah laku.
“Rin, aku tidak terbiasa di LSM. Isu-isu perempuan hanya kudengar sambil lalu tanpa kuselami sama sekali. Isu-isu kekerasan terhadap anak pun aku hanya melihat beberapa berita di televisi dan membaca di media. Pengalamanku tidak cukup kuat untuk menjembatani derita mereka menjadi lebih baik. Aku tidak akan paham bagaimana aku memahami dan mau mendengar keluh kesah mereka. Takutnya aku sendiri yang larut dalam masalah mereka tetapi aku tidak bisa mencari solusi, karena aku tidak pernah beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti mereka alami.” Kujelaskan duduk persoalannya pada Arin yang mungkin saja berharap aku mau bergabung dengan LSM, entah LSM apa.
“Kamu tidak harus masuk ke isu-isu itu dong, Nong! Kamu bisa ke LSM yang mengangkat isu lain…,” tampak Arin berpikir keras mencari LSM yang cocok dengan kemampuanku.
“Misalnya?” kejarku.
Arin masih belum menjawab.
“Kamu bisa jadi penyelamat mereka dengan membuat proposal atau pendekatan ke LSM luar, cari donatur susah lho saat ini. LSM luar pada pulang kampung semua dan tinggallah kita yang mencari-cari mereka ke berbagai tempat dengan isu terhangat, kebanyakan memang isu perempuan dan anak. Kamu kayak bukan perempuan saja tidak paham akar masalah yang dialami kaummu sendiri!” Arin malah tidak menjawab pertanyaanku. Aku sendiri bisa menghitung berapa banyak LSM di Aceh, kebanyakan dari mereka hanya mengangkat isu perempuan dan anak serta kesehatan.
“Jiwamu memang di dunia pendidikan, Nong!” kata Erni kemudian. “Kamu kuliah di pendidikan, kamu tentu sangat paham bagaimana cari mengajari anak-anak bahkan mahasiswa akan ilmu yang kamu punya. Kamu ke kampus saja, nanti aku yang bantuin ya!”
“LSM lebih menarik, Nong!” Arin tidak mau kalah dari Erni. “Kamu akan berinteraksi dengan banyak LSM luar yang datang khusus membantu kita, kamu bisa bebas ke luar negeri mencari bantuan agar perempuan Aceh lebih maju dalam berbagai aspek. Kemampuanmu sangat dibutuhkan di LSM, apalagi kamu sangat pintar berbicara, bahasa Inggris sudah tidak bisa diuji lagi, dan kamu punya kepekaan terhadap masalah sampai bisa mencari ke intinya sebelum diselesaikan!”
“Kamu malah akan berkembang di kampus, Nong!” Erni semakin memanas-manasi. “Kamu bisa lanjut pendidikan lagi, kamu selalu bertemu dengan orang-orang hebat di kampus. Ilmumu juga tidak terbuang percuma, tetap kamu praktekkan selama mengajar di dalam kelas dan berdiskusi dengan sesama dosen,”
“Menurutmu orang LSM tidak hebat begitu?” Arin mulai terpancing. “Kamu belum pernah paham ya bagaimana kerja orang di LSM, kami tidak hanya memikirkan angka kredit naik pangkat sampai jadi profesor, kami lebih mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan perut sendiri! Kami mencari uang sendiri ke sana-ke mari dengan modal fakta dan masalah besar di Aceh, bukan hanya menunggu awal bulan ditranfer gaji oleh pemerintah!” rupanya Arin sudah hilang kendali. Aku pun merasa tersinggung dengan ucapan Erni yang penuh penekanan pada kata hebat tersebut. Memang kuakui, orang-orang di kampus hebat, satu sisi lebih hebat dari siapa pun. Tapi aku juga harus membuka mata, orang-orang yang belajar dari pengalaman hidup yang keras bisa jadi hebat. Dalam hal ini, Arin tidak serta merta salah karena membela diri.
Erni tidak memberi jawaban. Erni tahu diri dengan memilih diam. Api menyala membakar amarah di tengah-tengah matahari mulai tenggelam. Kazol dan Tutun rupanya punya cerita tersendiri. Entah mereka mendengar perdebatan hebat kami barusan, entah mereka lupa bahwa kami sedang bersama-sama.
“Ilmuku juga tidak terbuang saat bekerja di LSM!” Arin belum mau kalah rupanya. “Setiap kata buku yang kubaca dan telaah menjurus pada perbaikan kemasyarakatan yang semakin tak terurus. Kalian memang enak, menunggu gaji perbulan walaupun bekerja tidak penuh seperti kami!” rasanya tujuan ucapan Arin tidak lagi pada Erni seorang. Kazol dan Tutun yang merasa terseret masalah terdiam dari bisik-bisik mereka.
“Maksudmu apa, Rin?” tanya Tutun dengan polosnya.
“Hidup sebagai pegawai mudah lho, Tun!” nada suara Arin tidak bisa kudeskripsikan. Dari mata dan mulutnya kutangkap ejekan yang tidak ringan terhadap status pegawai negeri. “Kerja kalian selain tugas yang diemban tentu saja masalah gaji, tunjangan dan kenaikan pangkat. Satu hal lagi, berapa nominal yang bisa kalian ambil di bank untuk buat rumah atau beli mobil. Tidak ada yang salah dengan itu ya, menurutku status kalian yang aman-aman saja. Kalian hidup serba berkecukupan tanpa memikirkan bagaiman nasib anak cucu ke depan. Beda dengan perempuan-perempuan di kampung-kampung yang tidak pernah kalian ketahui nasibnya. Korban konflik, tsunami, bencana alam, bahkan keluarga miskin yang sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Kalian bagian dari pemerintah itu, kalian makan uang dari pemerintah yang tidak kalian bagikan kepada mereka!”
“Kami sudah berzakat, Rin! Jangan sembarangan nuduh begitu!” Kazol menimpali sedikit emosi.
“Aku tahu. Tapi masih banyak kok orang miskin di Aceh ini!”
Arin benar. Seharusnya ketiga temanku menerima fakta yang dibeberkan Arin yang kerjanya melihat dan merasakan penderitaan wajah Aceh yang tak pernah pudar. Sepertinya aku harus menghentikan perdekatan panjang ini sebelum menimbulkan dendam yang berujung pada pertengkaran antara kami.
“Sudahlah. Kupikir ini masalah mengenai diriku yang belum punya pekerjaan. Aku mau have fun dulu beberapa hari ke depan. Pulang ke kampung dan menemani Ibu yang kangen sama diriku katanya. Urusan bagaimana setelah itu, nanti aku kabari kalian lagi. Terima atau tidak tawaran kalian berdua, nanti tetap kukasih tahu. Bagaimana?”
Arin seperti berat hati menerima keputusanku. Erni pun hampir sama.
“Tetaplah di Banda, Nong! Kamu akan menjadi orang hebat di sini!” ujar Erni. Aku tersenyum.
“Aku bisa di mana saja, Er!”
Dalam bisu kami melihat ke lautan lepas. Orang-orang sudah berkacak pinggang di depan matahari yang mulai terbenam. Anak-anak berlarian di gemericik ombak menyentuh bibir pantai. Orang-orang yang punya kamera tidak mau ketinggalan mengabadikan momen paling ini senja ini. Tidak hanya dengan kamera, melalui ponsel pun banyak orang memotret matahari terbenam.
Arin menarik lenganku berlari ke arah matahari yang sedang membulat sebesar dua kali bola kaki. Ketiga temanku mengikuti di belakang. Berulang kali Arin membidik ke arah matahari yang sedang memancarkan keindahan. Sesekali, secara bergantian, maupun bersama-sama kami jadi objek foto Arin. Perempuan ini kuakui lihai betul mengambil angle foto. Kami ikut senang melihat hasil tangkapan kamera Arin. Arin dengan bangga mengatakan dirinya akan menjadi fotografer andal kemudian hari.
Sayup-sayup dari musalla di depan pintu masuk Pantai Lampuuk terdengar suara azan. Tak terasa waktu begitu cepat berlari. Mengejar mimpi-mimpi anak-anak manusia yang semakin tamak akan rasa syukur. Sebagian kecil orang beranjak dari depan lautan lepas dan matahari yang tinggal sabit di atas permukaan laut. Suara azan tidak diindahkan oleh orang-orang dibibir pantai ini. Aku juga sering melihat hal yang sama, aku yang masih sadar akan kewajibanku, mengemasi semua barang dan berangkat ke musalla.
Sampai di depan musalla kecil itu, kami harus mengantre mengambil air sembahyang. Prasangkaku mungkin salah. Masih banyak orang yang mendengar panggilan Tuhannya di senja ini.
***


 bairuindra
bairuindra