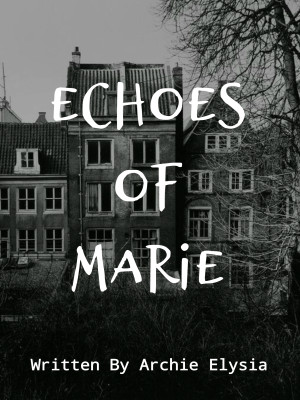Rabu, 24 April 2013.
.
“Nggak sampai Maghrib, oke?” ujar Reni untuk kesekian kalinya.
“Iya, iya. Kenapa kamu jadi takut gini, sih, Ren?” gerutu Angga.
“Keinget cerita Mbah Parjo, ya?” ejek Pandu.
“Nggak! Cuma, nggak tenang aja. Ini, ‘kan, bukan daerah yang kita kenal betul,” sanggah Reni. “Kalau kita nyasar gara-gara udah gelap, gimana?”
“Kita udah ke sana dua kali,” ujar Angga, “ini yang ketiga.”
“Aku baru sekali ini,” sahut Gita mengingatkan.
“Aku inget jalannya, kok. Tenang aja,” ujar Pandu.
“Tenang aja, ada Pandu di sini! Kita nggak bakal kesasar,” sindir Reni, teringat kejadian di hari pertama mereka berada di dusun ini.
“Woi!” protes Pandu.
“Kalau pun Pandu lupa jalan, di sini masih ada Evan,” ujar si pemilik nama, promosi diri. “Sa sudah belasan kali ke sana.”
Mereka berlima berjalan di pematang sawah satu per satu, sementara senja mulai turun. Uji nyali yang sempat batal, sebentar lagi bakal jadi dilaksanakan. Lalu, di mana lokasi yang dijadikan arena? Tempat yang dalam anggapan mereka paling seru di seluruh lereng Merapi:
Parit-parit di dekat Bendungan Senowo.
*
“Ini trik yang aku baca di cerita-cerita detektif,” bisik Pandu pada Angga.
“Sip. Untung Evan ulang tahun di bulan Juni!”
Keduanya tertawa tanpa suara. Mereka akan mengerjai Evan! Hanya untuk bercanda tentunya.
“Masing-masing dari kita berempat,” Pandu memulai arahannya, “berdiri di keempat sudut parit ini.” Ia menunjukkan selembar kertas bergambar segiempat dengan empat titik di tiap titik sudut.
“Urutannya, sesuai kesepakatan kita, yaitu berdasarkan bulan lahir: Angga, Evan, Gita, Reni … dan yang terakhir, aku.
“Angga yang pertama, bawa lilin bernyala, jalan dari luar parit ke sudut pertama di kanan ini. Evan di sisi sudut yang itu, nggak boleh kelihatan sama Angga dan dia juga nggak boleh sampai lihat Angga. Cuma tangan yang boleh kelihatan.”
“Cuma tangan yang megang lilin yang kelihatan?” ulang Reni.
Pandu mengangguk.
“Kedengarannya kok agak horor, ya,” seloroh Angga.
“Penakut!” seru Gita.
Angga langsung merengut.“Aku, ‘kan, bilang agak,” balasnya.
“Lanjut, ya,” sela Pandu. “Evan jalan sepanjang sisi parit ini, terus ke sudut kedua. Di sana, kamu kasih lilinnya ke Gita. Hitung satu sampai tiga puluh dalam hati, lalu pindah posisi ke tempat Gita ini. Gita, kamu jalan ke sudut ketiga, lalu Reni akan terima lilin dari kamu. Kamu juga hitung sampai tiga puluh, lalu pindah. Begitu seterusnya.” Pandu memandangi wajah teman-temannya. “Bisa dipahami?”
Reni dan Angga mengangguk cepat. Evan mengamati gambar Pandu sesaat, lalu ikut mengangguk. Gita melirik Pandu sekilas, lalu tersenyum kecil dan bergumam, “Menarik.”
“Baiklah teman-teman ... ganbatte!” ujar Pandu memberi semangat untuk melakukan yang terbaik, meminjam jargon dari iklan sebuah produk teh khas Jepang yang sedang beken di televisi waktu itu.
Sesaat kemudian, kelima remaja itu telah bersiap di posisi masing-masing. Angga berdiri di muka undak-undakan yang menurun ke parit, cahaya api yang bergoyang-goyang di tangannya menimbulkan bayang-bayang bergerak di wajahnya.
Angga menunggu sampai ketiga temannya membunyikan nada dering ponsel masing-masing, pertanda bahwa mereka sudah siap—Evan sih tidak membawa ponsel karena memang tidak diperbolehkan oleh seminari, tapi karena posisinya paling dekat dengan Angga, jadi tak masalah.
Remaja gempal itu mulai berjalan.
Mentari mulai terbenam.
*
Menunggu.
Menunggu ...
Hah! Lama banget! Kenapa aku dapat giliran hampir terakhir, sih?
Reni gelisah di tempatnya berdiri. Cahaya matahari makin lama makin samar, udara mulai dingin dan, meski di bawah sini tidak ada angin, gadis itu sedikit menggigil. Sebagian besar parit itu tertutup kayu tripleks di bagian atasnya—tidak seperti parit-parit yang ada di perkotaan yang ditutup beton, barangkali karena struktur paritnya sendiri yang rapuh—namun ada beberapa lubang hawa dan mungkin dari situlah udara luar masuk.
Oh, tidak. Ini firasat buruk, batinnya.
Selama tinggal di lereng Merapi ini, Reni belum pernah keluar rumah di atas pukul empat sore. Begitu juga yang lain-lain. Dan saat didengarnya angin bertiup di luar parit, Reni mulai menyesal tidak memakai jaket yang lebih tebal. Dia bisa melihat langit malam yang penuh bintang dari bawah sini. Hampir tepat di atas kepalanya ada satu lubang hawa yang agak lebar, membawa cahaya bulan menjadi penerangan seadanya.
Tunggu. Hari sudah malam sekarang? Tadi, ‘kan, matahari baru mau terbenam ....
Perasaan tak nyaman itu makin menjadi-jadi. Seolah diundang pada waktu yang tak tepat, cerita Mbah Parjo tentang arwah gentayangan orang-orang yang kecelakaan selama mengerjakan bendungan datang kembali ke benak Reni. Dirasakannya organ cernanya mulai bergejolak dan timbul rasa ingin buang air, pertanda dirinya takut. Ia jadi kesal sendiri.
Huuh. Aku nggak boleh jadi penakut! Ia tak tahan membayangkan wajah Pandu yang tersenyum penuh kemenangan kalau melihat dirinya seperti ini.
Sesuatu melintas di atasnya lewat lubang hawa dan seketika itu juga sesuatu yang bercahaya muncul dari kegelapan. Reni tidak bisa menahan diri memekik.
“Ren?” terdengar bisikan. Detik berikutnya, kepala Gita muncul dari balik dinding parit. “Ada apa?” Rupanya Gita yang membawa lilin sudah sampai di sudut itu.
“Nggak apa-apa, Git. Barusan kayaknya ada ... kelelawar.”
Ada ekspresi ketakutan yang sangat jelas di wajah Gita. Ia menyodorkan lilin yang menyala itu kepada Reni, tangannya agak gemetar. “Harusnya aku nggak boleh kelihatan sama kamu. Tapi, udahlah! Terkutuklah Pandu dan peraturan bodohnya!”
“Git ...,” gumam Reni seraya mulai berjalan. “Kalau kamu beneran takut, kembali aja ke atas sekarang.”
“Aku nggak takut!” desis Gita. “Aku tetep ikut permainan ini sampai selesai!”
Ya, aku juga nggak akan kalah di tengah jalan, batin Reni.
Sesaat kemudian, gadis itu sudah sampai di sudut terakhir dan menyodorkan lilinnya. Sebuah tangan meraih lilin itu, dan bayang-bayang bergerak menjauh. Bayangan Pandu kelihatan lebih besar dari orangnya, apalagi cowok itu agak membungkuk lantaran tinggi badannya hampir sama dengan kedalaman parit.
Reni menghitung sampai tiga puluh dan berpindah.
Dari tempatnya berdiri sekarang, ia bisa melihat keremangan yang lebih terang daripada kegelapan dalam parit masuk lewat undak-undakan yang menjadi akses mereka untuk keluar. Dari undak-undakan ke sudut ini berjarak sekitar enam meter, begitu pula jaraknya menuju sudut satunya.
Eh? Sepertinya ada orang yang berdiri di tengah anak-anak tangga itu ...
... Angga?
Memang si Gempal yang menghalangi cahaya dari luar untuk masuk ke parit. Ngapain dia berdiri di situ? Harusnya dia ada di sudut pertama, bukan ...?
Kalau begitu, tidak ada orang di sudut pertama. Sebentar lagi permainan akan selesai, karena dengan absennya Angga berarti tidak ada orang yang akan menerima lilin dari Pandu.
Namun, tidak ada suara apa pun yang menandakan berakhirnya uji nyali itu, Angga tidak bergerak dari tempatnya, dan beberapa menit berikutnya lilin itu kembali disodorkan dari balik sudut oleh Gita pada Reni.
Meski merasa janggal, Reni mengangkat bahu dan menerima lilin itu. Ia berjalan ke sudut pertama, dan di jalan ia punya kesempatan bicara kepada Angga.
“Kenapa kamu malah di sini, Ngga?”
Angga malu-malu menjawab tanpa memandang Reni, “Ehh ... aku ... takut, Ren.”
Reni menyipitkan mata. “Bukannya kamu yang punya ide uji nyali di sini?” Tanpa menunggu jawaban Angga, ia berjalan terus dan tiba di sudut pertama. Tangan Pandu menerima lilin darinya. Reni berhitung lagi.
Kalau dipikir-pikir, aneh juga alasan Angga. Dia dengan entengnya mengakui dirinya takut di hadapan Reni, padahal Gita saja gengsi.
Dan yang paling penting ... bagaimana bisa permainan ini jalan terus dengan hanya empat pemain? Tunggu dulu, logika Reni benar, bukan? Untuk bisa terus, mereka perlu satu orang di tiap sudut, jadi ada empat orang, ditambah satu orang berjalan menuju sudut yang lain ....
Reni menoleh ke arah undak-undakan untuk bertanya pada Angga, tapi yang bersangkutan sudah tak berada di sana.
*
Bunyi nada dering ponsel Pandu yang mengimitasi geram harimau merobek kensunyian di dalam parit. Gemanya terdengar mengerikan dan membuat orang-orang yang masih di bawah buru-buru lari menuju undak-undakan.
Di muka undak-undakan, di luar parit, Evan sudah terduduk sambil terengah. Gita yang berikutnya naik, disusul Reni, dan terakhir Pandu.
“Hiih … seram betul,” seru Evan dengan logat khasnya.
“Evan takut, ya …,” goda Gita, padahal dia sendiri tak kalah pucatnya.
“Ayo ngaku, tadi siapa yang menjerit di putaran pertama?” ujar Pandu sambil memandangi Reni, menggigit bibirnya, seolah menahan ledakan tawa. “Salah satu cewek.”
“Tentunya kamu udah tahu siapa, ‘kan, Sherlock?” bentak Reni, tak mau mengakui ketakutannya tadi.
“Reni kalah …!” sorak Pandu. “Kamu harus mentraktirku di Soto Pak Makmur kalau kita udah balik ke Solo.”
“Iya, iya,” gerutu Reni.
“Apa kriterianya menang atau kalah?” tanya Evan. “Sa juga sempat takut di bawah tadi.”
“Ah, ini hanya pertandingan antara aku dan Reni,” sahut Pandu sok. “Dan aku menang!”
“Kamu sendiri yang bikin alur permainannya,” protes Reni. “Aku juga bisa menang kalau aku yang bikin aturan.”
“Ngomong-ngomong, di mana Angga?” celetuk Gita. Adu mulut Pandu-Reni membuatnya menyadari absennya si Gempal.
“Apa dia masih di dalam e?” bisik Evan.
“Angga!” Pandu memanggil ke arah parit. Tidak ada jawaban. Pandu melirik teman-temannya dengan gelisah.
Reni berseru ke arah yang lain, “Kita sudah selesai, Ngga! Udah, nggak usah takut.” Ia yakin, Angga pasti sudah tidak ada di parit itu. Saat teman-temannya memandanginya dengan heran, ia menjelaskan, “Tadi aku sempat lihat dia keluar, di tengah permainan.”
“Angga keluar?” Pandu tidak bisa kelihatan lebih terkejut lagi. “Kapan?”
Reni mengernyit. “Sebelum putaran pertama selesai. Kamu juga pasti lihat dia di undak-undakan, mestinya kamu ngelewatin dia sebelum aku.”
Pandu menggeleng. “Nggak ada siapa pun di undak-undakan waktu aku lewat.”
“Kalau gitu, Angga udah di luar parit sebelum kamu lewat, dan kembali ke undak-undakan saat giliranku lewat,” ujar Reni.
“Tapi ... Angga, ‘kan, ada di urutan sebelum sa,” ujar Evan sambil berpikir-pikir. “Kalau memang Angga keluar, harusnya lilin itu berhenti di Pandu.”
“Tapi ada yang terima lilin dariku,” bantah Pandu.
“Dan ada yang kasih sa lilin,” lanjut Evan, suaranya melirih.
Gita bergidik. “Siapa ...?”
Keempatnya membisu dengan tegang.
“Hantu ...,” bisik Evan ngeri.
“Jangan-jangan, arwah para pekerja bendungan yang diceritakan Mbah Parjo itu ...,” seloroh Gita.
“Nggak ada yang begituan!” Reni membantah Evan dan Gita, meski wajahnya ikut memucat. Ia berseru lagi, “Angga! Ke sini sekarang dan sudahi lelucon ini!”
Namun, tidak ada yang muncul.
“Ke mana Angga?” desah Evan ketakutan. “Apa dia ….”
“Diculik hantu? Yang bener aja!” Reni bersikeras. “Pandu—” ia berhenti. Remaja laki-laki itu tengah berjongkok membelakanginya, bahunya berguncang-guncang menahan tawa.
Reni berseru gemas sambil mendorong punggung Pandu. “Penipu! Di mana Angga?!”
Pandu tertawa heboh, air matanya sampai keluar. Gita dan Evan saling pandang tak paham.
“Evan ...! Kamu harus lihat wajahmu waktu ngomong ‘hantu’ tadi!” seru Pandu di sela tawanya. “Astaga, Reni jirih! Jirih!!!”
Evan masih melongo saat Gita menendang kaki Pandu dan selepas beberapa detik barulah ia paham akal bulus kawan barunya itu.
Pandu lari terbirit-birit ke arah parit sebelah. “Ampun! He, jangan mengumpat ya, Anak-anak!”
Ia membungkuk ke bawah parit sebelah. “Misi sukses, Bro!” serunya.
Terdengar suara Angga yang menyahut, kedengarannya jauh sekali. Sepertinya ia ada di bawah parit yang satu itu.
“Ya, Tuhan, Pandu,” keluh Evan ketika ia, Gita, dan Reni menyusulnya ke parit itu. “Sa betul-betul takut tadi itu.” Namun, ia tak betul-betul marah pada Pandu. “Bagaimana bisa diatur seperti itu e?”
Senyum bangga terpampang di wajah Pandu. “Jadi begini triknya: Aku jalan dua giliran, giliranku sendiri dan giliran Angga. Dia sembunyi di sini setelah Reni melewatinya di putaran pertama,” terangnya sementara mereka menunggu Angga naik.
“Jadi, tangan yang memberi sa lilin, adalah tangan Pandu? Bukan tangan hantu, ‘kan?” Evan memastikan. Anak itu memang tak pandai menyembunyikan perasaannya. Barulah setelah Pandu mengiyakan, ia tampak luar biasa lega. Kini Evan yang tertawa.
“Kalian betul-betul hebat!” serunya di tengah derai tawa.
Luar biasa kawan baru mereka ini. Tak sedikit pun ia marah karena dikerjai. Ia menganggapnya lucu, itu saja. Pada akhirnya Gita dan Reni ikut tertawa, karena tawa Evan begitu menggelitik dan menular.
“Ngomong-ngomong, jirih itu apa, e?” tanya Evan setelah tawanya reda.
“Penakut,” balas Pandu sambil melirik Reni, yang langsung menoyor bahunya.
“Oh, kita sama, dong, Ren. Hehehe.”
Karena Angga tak kunjung nampak batang hidungnya, Pandu berseru lagi ke parit, “Ngga? Kamu ngapain?”
Angga berseru, tapi suaranya teredam. Memangnya parit yang satu itu sebegitu dalamnya ...?
“Apa kalian denger dia ngomong apa?” Pandu menoleh pada teman-temannya. Semua menggeleng.
“Coba turun aja,” usul Gita.
Pandu menatapnya. “Kita semua turun, kalau gitu.”
Reni mengangkat bahu dan berkata sarkastik, “Silakan duluan, Sherlock.”
*
Keempatnya hampir tiba di dasar parit sebelah, parit yang rasanya sedikit lebih dalam dari tempat uji nyali mereka itu.
“Angga!” Pandu memanggil. “Kamu di mana?”
Parit itu gelap sekali; matahari di horizon belum terbenam betul, meski sedari tadi bulan dan langit malam sudah tampak di atas. Mereka berhenti tepat di undakan terbawah.
“Mana lilin kita tadi?”
“Eh, ketinggalan di parit.” Tentu yang dimaksud adalah parit tempat uji nyali tadi.
“Oh, ya, ampun.”
“Ada yang bawa pemantik, nggak?”
“Bukan aku yang bawa.”
“Ouch! Itu kakiku!”
“Maaf.”
“Lha, siapa yang menyalakan lilin di uji nyali tadi?”
“Angga, ‘kan?”
Semua terdiam.
“Mending kita naik dulu, nggak kelihatan apa-apa nih!” ujar Gita.
Saat itu mereka mendengar Angga berseru, “Oii ... di sini.” Suara itu berasal dari sebelah kanan. Tapi jalan menuju ke sana tak tampak.
“Kamu bawa pemantik, ‘kan, Ngga?” Reni menyahutinya. “Kami di pintu masuk!”
“Aku nggak bawa lilin lain, tapi hapeku ada senternya,” sahut Angga. Tepat saat itu, tampak seberkas cahaya yang sangat lemah, agak jauh dari mereka. “Aku di sini.”
“Jalan ke sini, dong, Ngga!” balas Gita, takut bergerak dalam gelap. Dari tadi tangannya mencengkeram lengan Evan tanpa tahu dirinya membuat remaja laki-laki itu meringis kesakitan. “Di sini gelap gulita!”
“Kalian deh yang ke sini. Ada sesuatu yang ...,” Angga berhenti.
“Ngga?” kali ini Reni yang bicara. Ada yang tak beres di sini, ia bisa merasakannya. “Hape, Git, buka hapemu, paling nggak ada cahaya sedikit.”
Gita membuka ponsel pintarnya. Layar besarnya cukup terang, meski sesekali meredup dan harus disentuh agar tetap memberi cahaya. Ponsel desain baru belum banyak memiliki fitur senter meski sudah ada kamera. Milik Pandu dan Reni sama-sama Blackberry dengan layar kecil, jadi tak akan banyak membantu.
Yah, kadang memiliki hape Nokia keluaran lama seperti Angga ada untungnya juga.
“Hei?” suara Angga terdengar lagi. “Ke sini sekarang, tolong.”
Karena sekarang ada lebih banyak cahaya dari penerangan-darurat-yang-tak-memadai, parit itu jadi cukup terang untuk dilalui mereka berempat tanpa tersandung atau saling menginjak kaki. Mereka memang tidak bawa senter karena tidak mengira bahwa langit akan menggelap secepat ini.
*
Sebetulnya, bagaimana pengalaman Angga sendiri?
Angga berjalan masuk ke sudut pertama di parit uji nyali, lalu sambil menyerahkan lilin pada Evan ia bilang dirinya takut. Evan mengusulkan untuk keluar dari permainan jika Angga memang nggak mau meneruskan. Namun, karena Angga diam saja, Evan nggak tahu apa keputusannya. Karena putaran berikutnya berjalan, Evan mengira Angga sudah menguatkan diri untuk terus.
Sebenarnya Angga langsung kembali ke undak-undakan dan keluar dari parit. Pandu berkata jujur waktu dia bilang nggak ada siapa pun di undak-undakan saat dirinya lewat situ, karena Angga memang ada di luar saat itu. Pandu bersiul-siul dengan nada tertentu sambil lewat, membuat Angga kembali ke pintu masuk parit sesuai perjanjian mereka.
Pandu, yang berjalan ke sudut pertama, tidak berhenti di situ, namun terus hingga ke sudut kedua tempat Evan sudah menunggu Angga. Dengan demikian, Evan mengira Anggalah yang berjalan dari sudut pertama ke kedua dan memberinya lilin, padahal kenyataannya Pandu merangkap giliran.
Angga berdiri di muka undak-undakan, sengaja agar terkena cahaya dari luar, supaya Reni yang ada di sudut keempat dapat melihatnya. Dan saat Reni lewat, Angga mengatakan hal yang sama dengan yang diutarakannya pada Evan.
Kelihatannya Reni nggak terlalu percaya, sesuai dugaannya dan Pandu, karenanya Angga langsung pindah dari parit itu ke parit sebelah yang telah mereka rencanakan sebagai persembunyiannya sampai ada panggilan dengan kata “Bro” oleh Pandu.
Angga berdiri di luar parit selama beberapa saat dan mulai merasa harusnya Pandu yang ada di posisinya sekarang. Ia kini seorang diri, sedangkan bisa saja benar-benar ada sesuatu yang menakutkan di sekitarnya dan diam-diam menerkamnya dalam keheningan malam ....
Tunggu dulu. Angga melihat jam tangannya. Sekarang bahkan baru pukul lima lewat sepuluh, tapi keadaan sekitar sudah seperti pukul setengah tujuh malam di Solo. Apakah matahari memang lebih cepat terbenam di atas gunung? Atau alam sedang mendukung uji nyali mereka kali itu? Atau ada arwah-arwah gentayangan yang ingin menampakkan diri dalam permainan mereka ...?
Tentu saja alasan yang masuk akal adalah yang pertama, tapi Angga jauh lebih tidak berani dibanding Pandu, maka janganlah mencelanya karena ia merasa ketakutan saat ini.
Angga amat sangat nggak mau masuk ke parit itu seorang diri sekarang, tapi tadi ia sudah sepakat dengan Pandu dan ia memang ingin membuat lebih dari satu orang ketakutan di bawah parit yang satu lagi. Sasaran mereka memang Evan, tapi Gita juga cukup penakut. Mungkin Reni yang paling sulit ditundukkan, tapi cewek itu mudah terbawa suasana meski ia berusaha menutupinya. Uji nyali ini pasti akan jadi yang tak terlupakan bagi ketiganya.
Cowok gempal itu buru-buru masuk ke parit sebelah begitu ia mendengar geraman harimau yang mulanya lupa disadarinya berasal dari ponsel Pandu. Permainan sudah berakhir! Angga nyengir sendiri, tak sabar menunggu reaksi teman-temannya.
Ia bisa mendengar Pandu dan Reni memanggil-manggil namanya di luar, tapi tentu saja ia tak boleh keluar sekarang. Bagian yang menarik baru akan dimulai!
Saat itu juga, Angga mendengar sesuatu di dalam parit itu. Agak jauh ke dalam dan rasanya lebih ke bawah dari tempatnya berdiri, seperti suatu benda berat yang jatuh ke tanah pasir, tapi Angga tak yakin. Dinyalakannya senter di ponselnya dengan hati mencelos, tak berani bersuara. Ada siapa di sana? Beranikah ia berjalan dan memeriksa seperti apa yang akan dilakukan Pandu yang selalu ingin tahu?
Suara benda jatuh tadi nggak terdengar lagi dan untuk sekitar setengah menit Angga mematung di situ dengan senter ponsel yang teracung di tangannya sebelum ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia ingin sesekali dianggap lebih cerdas dan berani oleh sahabatnya.
Parit itu aneh bentuknya, tidak persegi empat rapi seperti di sebelah namun memiliki dinding yang miring-miring dan lebih sedikit porsi parit yang tidak ditutupi papan tripleks. Bagus dan tidak bagus, nih. Bagus, karena berarti udara di sini tidak akan sedingin di luar; tidak bagus juga, karena artinya nyaris tidak ada cahaya luar yang masuk.
Angga menyusuri parit itu pelan-pelan dari sebelah kiri pintu masuk. Ia sudah hampir sampai kembali di titik semula ketika ia menemukan sebuah ceruk di dinding, hanya cekungan sebesar ukuran tangan. Dia meraba-raba dan mendapati ceruk itu kosong; pasir di sekitarnya langsung runtuh saat Angga menyapukan tangannya. Dan saat disorotkannya cahaya senter ke tempat lain, Angga menemukan lebih banyak ceruk bahkan di jalan yang sudah dilaluinya tadi. Mulut ceruk-ceruk itu menghadap ke satu arah, itulah mengapa ia tak langsung melihatnya saat berjalan dari arah satunya.
Parit ini jadi kelihatan seperti gua, batinnya.
Saat itu terdengar Pandu berseru, “Misi sukses, Bro!”
Angga menyahuti sambil mematikan senter ponsel dan tiba-tiba saja merasa bersemangat. Permainan mereka berakhir dengan baik! Dan di sini ia menemukan hal yang menarik. Dengan iseng Angga meraba ceruk-ceruk itu satu per satu ke arah jalannya tadi yang berlawanan dengan pintu masuk, semakin ke dalam parit. Saat itu terdengar keributan di undak-undakan pintu masuk; pasti teman-temannya. Angga berseru, “Oi, di sini.”
Suara Reni membalasnya, “Kamu bawa pemantik, ‘kan, Ngga? Kami di pintu masuk!”
“Aku nggak bawa lilin lain, tapi hapeku ada senternya,” sahut Angga sambil menyalakan lagi senter di ponselnya. “Aku di sini,” ujarnya. Tahu-tahu ia mendapati sesuatu di ceruk terdekat, yang tampak berkilau terkena cahaya senternya.
Sebuah ... bros?
Saat Gita menyerukan sesuatu tentang ‘gelap gulita’ di sebelah sana, Angga sudah terlalu terkejut dan ia hanya bisa berseloroh, “Kalian deh yang ke sini, ada sesuatu yang ....”
Mata Angga melebar, ia melongo, berhenti bicara saat samar-samar dilihatnya berkas cahaya lain di belokan di depannya. Remaja itu ragu-ragu. Akankah ia terus memeriksa? Atau menunggu hingga berkumpul dengan teman-temannya? Jelas ia menghadapi manusia dan bukan hantu di tempat ini; tapi siapa yang tahu orang itu baik atau jahat?
“Hei? Ke sini sekarang, tolong,” ujar Angga. Ia mulai takut. Ada apa di dalam parit ini? Apa betul mereka nggak sendirian? Ceruk-ceruk itu seperti buatan tangan yang tergesa-gesa. Pikiran Angga mulai macam-macam lagi.
Saat sesuatu menyambar kepalanya, tak ada pilihan lain bagi Angga kecuali terpekik jerit—ada suara binatang pengerat yang terdengar bersamaan. Setelahnya, kepalanya terasa basah.
*
Keempat remaja yang berusaha menyusuri lorong itu terlonjak kaget mendengar jeritan Angga dan suara binatang.
“Angga?” seru Pandu. Tak ada respons. “Bro?”
“Yang barusan itu ... suara kelelawar, atau apa?” bisik Gita takut-takut.
“Ih, bau apa ini?!” seru Reni. “Apa kelelawarnya baru buang air?”
Tiba-tiba sesuatu menyandung kaki Evan, membuatnya menabrak Reni yang langsung terpekik dan meraih tangan Pandu di depannya hingga ketiganya terjatuh dengan ribut. Gita sendiri ikut kaget karena dari tadi dia berpegangan pada Evan.
“Ahh!”
“Aduuh … memar pantatku ....”
“Ada apa, Van?”
“Jatuh jangan ngajak-ajak dong Ren,” gerutu Pandu. “Ouch.”
Evan meraba-raba tanah dan menemukan sebuah batu yang tertanam di pasir, yang sepertinya merupakan perintang kakinya tadi. “Maaf, ya, Reni, Pandu. Sa tidak lihat benda ini tadi.”
“Nggak apa, Van. Eh, awas! Jangan kamu injak ponselku!” seru Reni pada Pandu.
“Ndu, ini kaki orang, jangan diinjak!” pekik Gita.
“Sori, sori,” keluh Pandu yang kesulitan berdiri sementara kedua cewek itu memakinya. “Barusan tanahnya bergetar, ada yang ngerasa nggak?”
Evan menyahut, “Sa tidak.” Dibantunya Gita berdiri.
“Sedikit, kayaknya,” gumam Reni yang juga berusaha berdiri dibantu Pandu. “Eh, kok, di kepalaku banyak pasir ....”
“Iya, pasirnya kayak rontok barusan! Kalau memang ada gempa, kita harus keluar, ‘kan,” ujar Gita ketakutan.
“Kita ketemu Angga dulu,” pungkas Pandu.
Keributan sesaat tadi telah mengalihkan perhatian semuanya dari Angga. Saat mereka memanggil-manggil kembali, cowok itu tak menyahut.
*
Meski hanya permainan, Pandu puas karena tadi sudah berhasil mengerjai Evan, sekaligus Reni. Apa sekarang Angga ingin berimprovisasi? Mungkin si Gempal mendadak punya ide yang lebih membangkitkan bulu kuduk sekadar untuk lelucon.
Namun, tak lagi tersisa kelucuan setitik pun di tipuan Pandu ketika mereka akhirnya menemukan Angga tergeletak di tanah. Rambutnya basah; bukan oleh kotoran kelelawar, namun oleh darah. Dan, di belakangnya, berdiri seseorang ....


 roux_marlet
roux_marlet