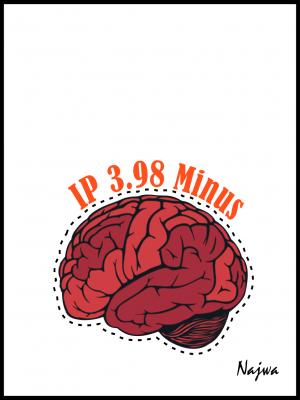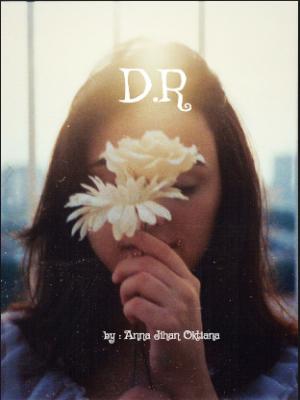Kehidupan ini tersusun atas sekian banyak dikotomi. Aku menggambarkan hidupku dalam tiga varian dikotomi: kehidupan; kematian, kepedulian; pengabaian, serta cinta; benci. Sembari berbaring santai, kuangkat tinggi dan kuamati dengan saksama sebuah pembatas buku. Pemberian cuma-cuma seorang ketua klub di hari kedua masa orientasi siswa yang sedang bersemangat mempromosikan klubnya.
“Amor vincit omnia,” bacaku. Sebaris kalimat yang tertera pada pembatas buku itu; slogan klub literatur.
Terpatri kuat memori tentang bagaimana aku menanyakan arti dari tulisan berbahasa asing tersebut padanya, dan ketika dia menjawabnya, seketika hatiku berdesir. Entah, yang pasti sejak itulah aku tak henti berharap agar setiap hari dapat berjumpa atau sekadar bersilangan jalan dengannya. Namun, aku tak pernah berniat untuk masuk ke klubnya. Aku lebih nyaman mengaguminya dari jauh.
Tiba-tiba seseorang membuka pintu kamarku tanpa mengetuknya lebih dulu, segera aku terduduk di tepi ranjang.
“Kakak, berangkat!” Seusai berkata demikian, anak lelaki berseragam putih-merah itu lekas berlalu. Suara derap kakinya menggema di lorong, disusul teriakan ibu yang memperingatkannya supaya tidak berlari.
“Dasar tidak sopan!” dengusku lantas menyambar ransel biru muda di atas meja belajar.
Jika aku punya seseorang yang ingin kulihat setiap hari, maka aku juga memiliki seseorang yang ingin kuhindari setiap detik, yakni dia yang baru saja menyebutku kakak. Bukan tanpa alasan, justru alasannya nyaris separuh lautan. Dan mustahil kusebutkan satu-persatu. Setelah menutup pintu kamar, aku mengambil sepatuku di rak kemudian memakainya di teras.
“Kok ninggalin sarapan lagi, sih, Kak.” Ibu membuka resleting ranselku lalu memasukkan sekotak bekal.
Begitu tali-tali sepatuku tersimpul rapi, aku beranjak, “Berangkat dulu, Bu.”
“Eh..eh, tunggu.”
Jangan bilang mau barengan lagi.
“Yusuf, ayo cepet sini, Nak. Jangan lupa tasnya dibawa.” Aku menggeram frustasi dalam hati
Dia yang dipanggil Yusuf itu berlari kecil dari arah dapur. Ketika sampai di ruang tamu, ia berhenti sejemang, celingukan. Lantas ia mengambil tas di atas sofa, menyeretnya ke arah ibu.
“Pinternya anak ibu. Tasnya dipakai dulu, ya.” Ibu pun membetulkan cara ‘membawa’ tas dengan menyangklongkan tas tersebut ke kedua bahunya.
Anak itu tak henti menatapku; sesekali tersenyum lebar hingga nampak gigi-giginya yang besar dan lidahnya yang panjang, ditambah air liurnya yang mengalir keluar –ngeces; hatiku semakin meronta dibuatnya.
Menjijikkan.
Kami sedang menunggu bis di halte. Aku menjaga jarak dari dia yang tengah tertawa bersama ibu. Ibu memanfaatkan waktu menunggu dengan mengajarinya berhitung menggunakan jari-jemari. Sungguh bukan sesi itu yang membuatku muak setengah mati, melainkan tatapan simpati dari orang-orang. Meskipun bukan aku obyek yang mereka perhatikan, namun aku tak suka melihat tatapan-tatapan kasihan itu. Selang tujuh menit, bis tujuanku pun tiba. Segera aku berdiri dan melangkahkan kaki.
“Assalamualaikum,” pamitku. Namun belum ada empat langkah, aku mendecak; ibu menyuruh Yusuf membalas salam.
“Wa..alai..kumsa..laamm. Hati-hati, Kakak.”
Tanpa menoleh aku langsung masuk bis. Selain tak suka terhadap tatapan kasihan, aku juga malu. Ya, betapa memalukannya terlahir dari rahim yang sama dengannya.
Perjalanan ini akan terasa membosankan dan melelahkan seandainya sosok itu tak berada di perlintasan yang sama. Dialah yang mampu menanggalkan partikel kotor yang menyelubungi hati, Aeneas Wishama atau Anas; si ketua klub literatur yang menggemari sebuah bahasa yang dianggap telah mati. Setiap berangkat sekolah kami selalu berada di bis yang sama. Di hari yang berbeda, dia pun menggoreskan cerita yang berbeda. Di suatu pagi dia merelakan kursinya untuk seorang nenek. Di pagi berikutnya dia naik dengan tergesa hingga kakinya terantuk; jatuh berdebum. Namun, bergegas dia berdiri; meminta maaf karena mengacaukan pagi hari yang tenteram. Sontak para penumpang tertawa, bahkan pundakku sampai naik-turun. Dan seperti itulah pagiku selalu berwarna karena kehadirannya.
Aku berjalan lunglai menuju halte. Awan mendung seakan mengapung tepat di atas kepala setelah berbicara dengan wali kelas beberapa waktu lalu. Setidaknya tadi itu bukan permintaan yang sulit, ‘membujuk ibu’. Namun, kendalanya adalah parasit yang selalu menempeli ibu ke mana-mana; menyita seluruh atensi dan waktu berharganya. Ibu hanya akan menceramahiku apabila dengan jujur kukatakan sebaiknya ibu sekali saja mengabaikan beban kesehariannya itu.
Makananku tinggal separuh. Sesekali kulirik ibu yang sibuk mengajari anak itu makan sendiri. Merepotkan saja, padahal sudah umur sepuluh tahun, tetapi polahnya masih menyerupai anak usia tiga tahun. Aku berhenti sebentar, mengeluarkan undangan tersebut dari kantong piyama. Lalu kuletakkan di meja, tepat di sebelah piring ibu. Sayangnya, ibu tak menghiraukan; masih fokus pada anak kesayangannya.
“Tolong datang,” ujarku.
“Apa?” Ibu menatapku heran. Kemudian menyadari keberadaan si undangan.
“Ibu usahakan, ya.”
“Harus datang.” Nadaku sedikit meninggi. Aku memandang ibu dengan serius.
Kini ibu sepenuhnya mencurahkan perhatian padaku, “Nanti kita bahas lagi.”
Tatkala malam kian larut; dan anak itu sudah terlelap, aku dan ibu berbicara empat mata. Sesekali kami beradu argumen, hingga puncaknya aku tak lagi dapat menahan diri atas peranku yang selalu mengalah.
“Selalu begitu. Tapi apa? Dia terus yang diprioritaskan. Ibu seakan tak pernah mengusahakan apapun untukku. Amal lelah ditegur terus. Terlihat seperti anak yang tidak pernah diperhatikan orangtua. Apa perlu aku jadi abnormal juga supaya ibu peduli?”
“Amalia! Kenapa kamu tidak mengerti juga?” Mata ibu nampak memerah dan agak berair. “Ibu begini bukan karena kemauan ibu. Tapi karena dia butuh ibu, juga butuh kamu. Seandainya ibu tidak peduli, mana mungkin ibu membelikanmu ini-itu. Lagi pula sudah saatnya kamu berhenti mengabaikan adikmu. Ada kalanya ibu tak lagi dapat bersama dengan kalian.”
Perasaanku campur aduk. Tak tahu harus apa, aku membalik badan dan pergi begitu saja. Menutup pintu kamar rapat-rapat.
Berhari-hari lewat, namun obrolan malam itu masih terngiang. Walau aku berharap sekali ini saja ibu datang, di sisi lain keyakinan akan ketidakhadirannya membuatku memulai hari dengan buruk. Apalagi ini sudah hari keempat dia tidak berangkat menaiki bis yang sama, membuatku bagai menelan pil pahit. Tiba-tiba ponselku berdering. Begitu kuangkat,
“Apa?!” seruku kaget. Terpaksa aku turun dari bis yang telah melaju sekitar 500 meter. Berlari-lari kembali menuju halte.
Dengan napas tersengal, aku sampai. “Kok bisa?” tanyaku kesal.
“Ibu mana tahu akan sakit perut begini. Tolong, ya.”
Aku pun hanya mampu mendengus. Ini benar-benar bencana. Selama perjalanan aku hanya diam. Sementara dia terus ber’wah’ ria memandang keluar lewat jendela. Entah apa yang mengagumkan dengan pemandangan yang itu-itu saja, malah hampir tiap hari dia menikmatinya. Kadang dia berceloteh ini, bertanya itu, tapi aku tak peduli. Biar. Setibanya di sekolah, aku mengantar dia sampai di depan kelasnya. Wali kelasnya menyapaku dengan ramah. Menganggapku kakak yang baik. Aku hanya mengangguk kikuk dan bergegas pergi setelah mengucap salam. Rasanya begitu lega ketika tugas bodoh ini berakhir.
Sekembalinya dari ruang BP, aku mengambil tas dengan lunglai. Benar saja, ibu tidak berubah. Membuatku sangat kecewa padanya, padahal pagi tadi aku telah mengabulkan permintaannya. Mendadak Esca –sohibku- masuk ke kelas yang hanya tersisa diriku disertai napas yang terengah-engah.
“Amal, gawat, gawat. Kak Anas…”
Selanjutnya aku terperangah. Tanpa pikir panjang, aku mengayuh cepat tungkaiku meninggalkan Esca. Rumah sakit yang dia maksud tidak jauh dari sini. Selama berlari aku terus memikirkan perilaku burukku akhir-akhir ini; amat menyesal. Tanpa sadar air mata meleleh di pipi. Kenangan akan dirinya yang kucintai berkelebatan, kian menyesakkan dada.
Analogi roda kehidupan; kadang kita dibawa naik hingga rasanya sungguh menyenangkan, namun tak jarang kemudian kita dijatuhkan sampai berdarah. Itulah yang kudapat setibanya di sana. Bagaimana roda kehidupan dengan tega meruntuhkan segenap kekuatanku. Jika keadaan tidak semenyedihkan ini, tentu aku bahagia dengan kehadiran seseorang di sebelahku. Namun, waktu memang kadang tak sudi berkompromi. Di hari berkabung ini, tumpah ruah sudah tangis di lorong itu.
Pemakaman dilaksanakan seperempat jam lalu. Sekarang aku berhadapan dengan seorang pria di teras rumah.
“Ayah turut berduka. Tapi maaf ayah tidak bisa lama-lama. Kamu jangan khawatir, mulai besok pindahlah ke rumah Bibi Lisa. Dia dengan senang hati menerimamu. Dan tolong jaga Yusuf baik-baik.” Pria itu beranjak undur diri.
Aku bungkam. Sulit memanggilnya ‘ayah’ setelah dia hilang tanpa kabar selama lima tahun ini. Suami macam apa yang membiarkan istrinya bekerja keras seorang diri. Membiarkan ibu menderita padahal dia telah diamanati untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Aku menoleh ketika tanganku digenggam dengan lembut. Dengan senyum di wajahnya yang khas, tatapan mata lugunya memancarkan kasih sayang, menimbulkan perasaan bersalah yang kembali merembihkan air mata.
Tidak pernah kuduga bahwa kepergian orang yang kucintai membuatku mulai menaruh hati pada orang yang kubenci. Enam bulan sudah menetap di rumah Bibi Lisa. Banyak pelajaran yang kuterima, tak sedikit pula perhatian yang kuberikan padanya, Yusuf. Kini aku hampir setiap hari mengantar anak itu ke sekolah. Sepulang sekolah, kami berjalan bersisian. Melewati jembatan dan sawah-sawah. Tapi, arus hari ini tidaklah mengalir lancar. Kami dihadang oleh sekelompok anak nakal yang hobi memalak. Mereka membentak, mengumpat; kurasakan Yusuf memegang erat lenganku. Karena aku menolak dengan tegas, mereka memberingas. Kami dipukul, ditendangi. Tasku diambil paksa. Isinya dikeluarkan dan dilempar sembarangan. Ponselku diambil dan guyuran receh dari tas Yusuf dipunguti. Aku berteriak, berusaha merampas kembali ponselku. Yusuf juga menggila, melempari mereka dengan kerikil.
“Kakak, hp, kembali.” Dia menunjuk-nunjuk ponselku.
Kami tetap kalah. Mereka kabur. Aku mencegah Yusuf yang hendak mengejar mereka, tetapi dia meronta. Aku membentaknya, menyeret dia pulang. Di depan rumah Yusuf meraung-raung seraya memanggili ibu; Bibi Lisa kelimpungan dibuatnya. Tiba-tiba dia berhenti berulah. Matanya memandang ke atas dengan takjub. Perlahan sesuatu yang dingin menghujam tubuh; gerimis mulai membasahi bumi. Aku dan Bibi Lisa segera berteduh, sedangkan Yusuf menikmatinya dengan bahagia. Jika ibu adalah bagian dari tetesan-tetesan ini, maka terbalas sudah kerinduan Yusuf yang belum memahami arti kehilangan.
Kejutan mencengangkan. Rabu ini Bibi Lisa meneleponku dengan panik. Yusuf hilang. Secara ajaib aku pun merasakannya; berdiri gelisah menunggu bis yang tak kunjung tiba. Esca di sebelahku mencoba menenangkan. Berikutnya dia seolah mendapat siraman ilham.
“Berhenti!” serunya lantang. Dan sebuah motor metic berhenti di depan kami.
Aku berusaha melarangnya berkata macam-macam, namun dia abaikan. “Kak, tolong anterin Amalia pulang, ya. Urgent.”
Seseorang yang membuka kaca helmnya itu nampak berpikir. Ia sekilas menengok arlojinya. Aku yakin dia akan menolak.
“Ya udah.” Tapi aku salah. Dia membuka jok motor dan menyodorkan sebuah helm. Aku menerimanya dengan amat malu, sementara Esca senyum-senyum tidak jelas.
“Pegangan yang erat, ya.” Suaranya mengagetkanku yang tengah berdebar tidak karuan.
Aku hanya mengangguk dengan salah satu tangan menyengkeram kuat ranselnya, sedang satunya pada pegangan jok belakang. Lantas motor meluncur cepat mengarungi jalanan.
“Hati-hati!” seru Esca.
Bila ini kondisi normal, mungkin aku akan bahagia setengah mati sebab enam bulan tidak mendapat kesempatan melihat figurnya. Tetapi seluruh pikiranku hanya tertuju pada Yusuf. Dan bukankah hal serupa juga pernah kami alami? Di mana guratan takdir selalu mengadakan pertemuan di waktu yang tidak pas. Namun, tentu saja hikmah di balik itu semua luar biasa.
Motor berhenti di tempat biasa aku dan Yusuf menunggu bis. Dia membuka kaca helm. Aku turun, melepas helm, lalu mengembalikannya.
“Oh iya.” Aku mengeluarkan sesuatu dari ransel, sebuah sapu tangan.
Namun, dia hanya tertawa ketika aku menyerahkannya. “Ambil aja.”
Aku menatapnya tak percaya.
“Maaf buru-buru, duluan, ya.” Dan dia kembali membelah jalan setelah mengucap salam.
Aku tak bisa larut lama dalam bunga-bunga. Bergegas menuju jembatan dan sawah-sawah yang umumnya kami lewati. Lima belas menit berselang, aku menemukannya; di kelilingi anak-anak yang telah merenggut harta benda kami. Seumpama cheetah berburu mangsa aku berlari. Menerjang mereka dengan mengesampingkan rasa takut. Aku tidak ingin mengulang rasa bersalah. Di mana hari itu aku bagai pandir buta karena alpa dengan mag akut yang ibu derita. Di mana aku duduk di ruang tunggu ditemani Kak Anas yang telah membawa ibu ke rumah sakit karena pingsan di depan halte dekat sekolahku. Kak Anas memberiku sebuah sapu tangan bersulam tulisan Amor vincit omnia. Di sana dia berupaya mengalihkan kesedihanku; menceritakan asal nama Aeneas yang diambil dari nama seorang pahlawan Troya pada mitologi Romawi. Dia juga mengisahkan romantika Cupid dan Psyche yang bagai senjata makan tuan; mencintai seseorang yang seharusnya dibunuh.
Seorang bapak-bapak meneriaki kami, membuat mereka kalang kabut melarikan diri. Aku tak acuh dengan keadaanku sekarang. Yang penting aku mampu melindunginya. Dia yang berusaha mendapatkan ponselku kembali kendati nihil hasil. Dia yang kini memelukku erat sembari mengulang-ulang kata ‘kakak’. Yusuf mendongak, raut piasnya berubah. Dia merekahkan senyum sempurna. Tanpa terasa wajahku basah. Kami kembali bersua dengan air langit. Yusuf melompat-lompat girang. Aku meneteskan air mata bahagia. Cinta menaklukkan segalanya. Umpama darah yang mengalir ke seluruh tubuh, cinta telah menaklukkan rasa benci yang bagai melekat dengan tulang dan daging. Jika hujan mampu sampaikan pesan pada ibu, maka aku akan berkata, “Aku sungguh mencintainya. Dan aku berjanji akan menjaganya hingga berakhir tugasku di dunia.”
~~~


 UNEAfra
UNEAfra