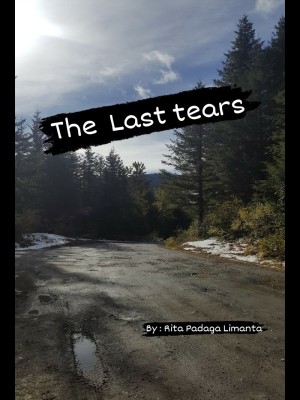Kabupaten Bandung Barat, beberapa bulan sebelumnya.
Kamu tahu jika musim penghujan adalah musim yang baik dan penuh berkah bagi sebagian orang, namun tidak untukku. Musim penghujan adalah musim penuh kesunyian dan kehampaan. Di musim ini, aku terpaksa memilih untuk tetap menenggelamkan diri dalam hiruk-pikuk kehidupan kota: pohon tumbang di jalanan, banjir di selatan, serta angin puting beliung yang meluluhlantakan desa-desa di utara.
Penyebabnya adalah dua dekade silam yang lalu aku pernah menghabiskan musim penghujan dengan berburu siput di belakang sekolah bersama Langit, seorang anak laki-laki blasteran bermata biru. Ia membawaku menyusuri lorong-lorong gelap yang dipenuhi bunga morning glory berwarna ungu cantik. Lorong itu juga dihiasi jaring laba-laba yang membentang dari satu tiang menuju tiang lain. Saat itu, kami sibuk membicarakan hal-hal ajaib: roket, pasir pantai, pohon cemara, gulungan ombak, dan betapa hebatnya ia mengajariku bagaimana cara berdoa pada Tuhan yang tidak berwujud.
Tidak hanya itu, di musim penghujan, aku pernah berjumpa dengamu, pacarku yang sekarang lenyap dan tidak meninggalkan satu pun petunjuk. Aku berjumpa denganmu saat aku masih kuliah dulu, beberapa tahun lalu – aku bahkan lupa. Kamu adalah kakak tingkatku yang mengajariku cara memotret dengan baik dan benar. Kamu mengajariku bagaimana caranya mencintai kata-kata dan menciptakan pundi-pundi dari hal tersebut. Kamu mengajariku bagaimana untuk bersikap jujur kepada diri sendiri dan kamu juga mengajariku untuk mencintai Duran Duran. Kamu adalah cinta sejatiku. Cinta yang memabukkan dan semua hal indah itu telah ditelan hidup-hidup oleh genangan-genangan sisa di cekungan aspal. Kamu pernah begitu menguasaiku di masa lalu.
Di musim penghujan pula, aku harus bergelut dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh kedua orangku. Kamu tentu sudah bosan dengar hal ini, tapi kali ini mereka semakin menjadi-jadi. Papa gagal menjadi anggota dewan daerah padahal ia telah membakar uang milyaran rupiah. Sementara itu, Mama terserang penyakit mental dan memilih untuk pergi menenangkan diri di desa terpencil Pangalengan. Dia menetap di sana dan berbaur dengan warga desa setempat tanpa berpikir untuk kembali ke rumah lamanya bersama kami.
Kalau kamu ada di atas awan sana tengah mengamatiku, kamu pasti merasa sangat ingin membereskan masalah-masalah itu untukku. Iya, kan?
Musim penghujan adalah takdirku, kelahiranku, dan mungkin kelak aku akan meninggal di musim penghujan yang berkepanjangan.
Pada awalnya, aku merasa tidak keberatan karena aku tidak merasakan tanda-tanda cocoklogi pada musim penghujan. Lalu pada musim penghujan selanjutnya, Luna, kakakku, turut meninggalkanku pergi ke Bali. Kamu masih ingat Luna, kan? Dia memilih untuk melanjutkan hidup bersama kekasihnya, Yoga, dan berlatih melukis di sanggar lukis milik keluarga pria itu tanpa berniat untuk melindungiku dari nasib buruk keluarga kami.
Di musim penghujan terakhir, aku benar-benar merasa sangat sendirian.
*
Tapi kali ini adalah musim kemarau berkepanjangan.
Aku sudah berusaha mengubur kenangan-kenanganku bersamamu, Aksara, dan beberapa mimpi tentang kita yang terpaksa harus kumusnahkan. Namun, aku juga letih memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi ingatan-ingatan yang tidak akan pernah meninggalkanku. Mereka hadir, hanya sebatas memori. Beberapa nama orang yang sering kugemakan dalam hati meninggalkanku sendirian dengan wajah dipenuhi tanda tanya. Mereka menyiksaku dan orang lain tidak akan pernah mengerti seutuhnya.
“Turun di depan saja, Pak. Hatur nuhun.”
“Ya, Neng.”
Kabut tipis yang menyelimuti seisi Desa Cukul menyambutku dengan dingin. Kebun teh di sepanjang jalan sudah memutih dan gelap. Sayup-sayup, azan magrib dari toa masjid kejauhan mulai terdengar seperti memanggil-manggil namaku. Pak Agus menuruniku di depan balai desa yang sudah gelap dan sepi. Sekejap saja, mobil bak itu segera berlalu. Aku memandangi mobil yang semakin menjauh itu hingga menghilang di tikungan.
Aku segera berlalu melalui jalan tanah setapak kecil yang pinggir-pinggirnya dihiasi oleh tanaman bunga liar berwarna-warni. Deretan rumah anyam menyambutku dalam keheningan yang beradu dengan suara serangga malam. Rumah di kanan adalah rumah Pak RT. Rumah di kiri adalah rumah Reva, adik kecil yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Rumah di ujung sana adalah rumah Mang Dadan, yang kuanggap seperti Pamanku sendiri karena ia dengan baik hati selalu mengurusi kebutuhan Mama selama tinggal di sini. Aku sungguh merindukan keramahtamahan itu.
Sudah beberapa bulan ini, Mama tinggal di sebuah rumah panggung mungil milik mendiang Bu Tresna, seseorang yang pernah sangat dekat dengan Mama saat ia muda. Mama mengenali almarhumah Bu Tresna sejak berpuluh-puluh tahun lalu saat ia menjalani kegiatan program Bakti Desa dari kampus. Mama sudah menganggap Bu Tresna sebagai ibunya sendiri. Almarhumah tidak mempunyai anak dan cucu, sehingga rumah itu dititipi pada Mama. Kemudian, beberapa tahun setelah kematian Bu Tresna karena gagal ginjal, Mama memanfaatkan rumah berdinding anyam bambu itu sebagai rumah self-healing-nya. Di rumah itu pula, Mama memutuskan untuk menyepi dari kehidupan hiruk pikuk kota dan menulis buku anak-anak. Dan tentu saja, ia bersusah payah untuk melupakan Papa dan tenggelam dalam penyesalan seumur hidup.
Lantas, sebagai satu-satunya anak yang masih memilih untuk berbakti, aku pun memutuskan untuk mengunjunginya minimal sebulan sekali.
Mama menyambutku di pintu rumah dengan tatapan pura-pura bahagia seperti biasanya. Kemudian ia menyuruhku untuk segera masuk karena udara di luar semakin dingin. Parasnya masih tetap sama: rambut pendek sebahu, mata coklat tua, alis tebal, hidung mancung, serta bibir pucat. Ia memelukku sejenak, mencium keningku, dan meratapi tatapanku yang kosong. Daster ungu anggrek favoritnya membuatku menatapnya dengan geli. Saat ia tersenyum, aku dapat mendapati kerutan halus di sudut matanya semakin terlihat tegas. Mama kemudian mengambilkan secangkir teh panas dan menyodori segala kudapan ringan yang ia punya ke hadapanku.
“Gimana harimu? Pekerjaanmu?”
“Baik-baik saja.”
Mama langsung protes, “Serius? Jawaban kamu gitu doang?”
Aku menghela nafas panjang, “Akhir-akhir ini, aku banyak ngeliput event dan dateng-datengin kantor perusahaan,” terangku. “Kabar Mama di sini gimana?”
“Baik,” sahutnya sambil menoleh padaku sejenak. “Mama banyak mengajari anak-anak desa bagaimana cara berhitung, mengarang, bermain boneka. Sekarang Mama jauuuh lebih baik dari pertama kali tiba di sini.”
Aku menatap raut wajah itu, wajah yang sulit terbaca. “Baguslah.”
Lirikanku jatuh pada rak kaca kecil di samping sofa. Beberapa koleksi boneka tangan milik Mama terlihat bertambah. Mungkin ia sengaja memajangnya di lemari kaca kecil ruang tamu agar anak-anak yang datang berkunjung ke rumah ini dapat melihatnya dan tertarik untuk memainkannya. Aku jadi teringat beberapa anak desa yang kurang beruntung itu. Adam, Sidik, Reva, dan Nana. Kurang lebih mereka menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang sama. Yang laki-laki disuruh bekerja ke kebun atau belajar mengemudi mobil bak terbuka. Yang perempuan disuruh menikah muda.
Sejurus kemudian, Mama segera menyentilku kembali dengan nadanya yang datar tapi menjelma menjadi kutukan, “Kamu sudah ngelupain Aksara belum? Kira-kira kamu ada niatan buat menikah nggak tahun ini? Atau kamu lagi dekat dengan seseorang? Kenalin dong, cowok barumu. Bawa ke sini. Mama mau kenalan.”
Bibirku langsung cemberut.
Nyatanya tidak ada satu pun orang di dunia yang dapat memahami betapa aku sangat merindukanmu, bahkan Mama. Sudah kubilang padanya jika aku tidak mudah menerima kehilangan ini. Meskipun diam-diam aku harus terus berupaya melakukan sesuatu, sudah barang tentu kamu tidak akan pernah berhasil tergantikan.
“Hmm?” Mama menodongku lagi.
Aku menyeringai ragu dan menepisnya. “Mama nggak pernah mengajariku bagaimana caranya melupakan,” keluhku. Mama hanya menerawang dan pikirannya pasti bertarung dengan keputusasaannya sendiri. Ya, kami sama-sama memiliki tingkat pertahanan diri yang rendah. Antara aku dan kamu serta antara Mama dan Papa. Hubungan mereka sangat rumit dan berada diambang ketidakpastian. Hal itu sudah bermula sejak bertahun-tahun yang lalu pula.
“Bang Fredi si orang Jakarta itu belum kunjung memberi kabar lagi tentang Aksara?” tanya Mama mengalah.
“Mungkin Bang Fredi juga sudah melupakan Aksara.”
Helaan nafas kami terdengar sangat menyedihkan oleh satu sama lain.
“Aksara nggak boleh membuat kamu kehilangan harapan, Nak.”
Aku menoleh. “Memangnya Mama masih punya harapan dengan Papa? Kenapa sih Mama nggak labrak aja tuh si Kamila?”
“Kamu mau Mama viral di Facebook terus dituduh ngaku-ngaku?”
“Ya, nggak gitu juga, sih.”
“Mama itu pindah ke sini gara-gara Mama ngalah sama Papa. Mama nggak ingin menghalangi dia untuk sukses. Mama nggak ingin…,”
“Stop,” sergahku cepat-cepat. “Pikirkan saja kesehatan Mama. Aku nggak ingin dengar Mama terus-terusan melindungi Papa.”
“Len, coba pahami Papamu.”
“Setelah apa yang dia lakukan dengan Kamila dan meninggalkan kita hingga kacau begini?”
“Kamu merasa kacau?”
“Kurasa yang kacau itu Mama. Makanya Mama ada di sini.”
Wanita itu terdiam membisu untuk beberapa saat. Matanya menatapku sendu. Ada sesuatu yang tertahan di kerongkongannya, tapi ia memilih untuk menahannya.
Setelah teh sudah mulai hangat, aku meneguknya seperti aku menelan kenyataan pahit dengan sekaligus agar aku tidak dapat merasakan kepahitan itu sendiri.
Kemudian kami menyantap makan malam bersama-sama. Ayam goreng, nasi liwet sisa tadi sore, dan sambal bawang. Mama makan sedikit malam ini, sama seperti malam-malam sebelumnya tanpaku. Pipinya semakin jatuh dan tirus, kantung matanya jauh terlihat lebih menghitam dari waktu terakhir kami berjumpa, serta kerutan halus di ujung matanya semakin terlihat jelas di antara cahaya lampu neon. Lihatlah rambutnya hitamnya. Diam-diam, rambut putih tumbuh menghiasi sela-sela rambut hitamnya dan seiring berjalannya waktu, rambut-rambut di kepalanya itu akan menjadi saksi waktu berjalan begitu cepat. Bibirnya kering, seperti padang pasir yang merindukan hujan. Aku tidak tahu mana yang lebih menyedihkan: merindukan bunga yang telah layu ataukah mendambakan bintang di langit.
Menjelang malam, di sela-sela Mama membaca buku Kekerasan Budaya Pasca 1965, ia kembali mengulang wasiatnya, “Len, kalau suatu saat kamu mendapat kabar bahwa Mama meninggal, tolong taburkan makam Mama dengan anyelir merah muda. Tolong.”
Aku hanya memicingkan mata tak percaya dengan apa yang baru saja ia ucapkan kepadaku.
*
Rumah Hampa, beberapa hari sebelumnya.
Musim kemarau begitu kering saat diam-diam Papa membawa seorang wanita ke rumah. Aku tahu, kamu pasti akan sangat membenci tipe pria seperti Papa. Iya, kan? Malam itu aku mendapati mereka berdua duduk berdampingan di atas sofa ruang keluarga sambil asyik menegak anggur. Mungkin mereka sudah mabuk. Papa menatapku seolah-olah berharap agar aku menyapa wanita yang kini bersamanya dengan rendah hati. Tapi aku tidak ingin ambil pusing dan aku pura-pura tidak melihat mereka. Aku segera nyelonong ke kamar sembari menenggelamkan diri dalam lirik-lirik milik Connie Francis yang sengaja di putar keras-keras. You'll know how much this heart of my is breakin' / You'll cry for her the way I cried for you //.
Mungkin diam-diam mereka berdansa dengan laguku itu.
Aku tahu wanita itu. Wanita usia empat puluh tahunan dengan kulit wajah yang masih sangat kencang, poni rambut yang kaku karena semprotan hairspray, serta menenteng tas Hermes. Kamila Jayanti. Wanita itu juga tipe wanita yang kamu benci. Iya, kan? Dia adalah anggota dewan daerah yang kaya raya, anggota partai politik X, pemilik saham perusahaan batubara dengan segudang bisnis properti, seorang dokter selebriti, sekaligus mantan petinggi dinas kesehatan kota. Wanita itu, Kamila pernah mengusirku dengan kasar saat aku hendak meminta klarifikasi terkait kebijakan kontroversial terbaru yang dikeluarkan rumah sakit yang ia pimpin dengan dalih akan pergi mendatangi sebuah rapat penting. Mungkin dia dapat dengan mudah melupakanku karena dia adalah tipikal wanita pejabat borjuis yang sangat sibuk. Ingatannya terhadap wajah dan nama seseorang sangat buruk.
Sementara itu, Papaku adalah seorang dokter kaya raya dengan jam terbang tinggi. Dia kemudian mencoba mencari peruntungan di dalam partai politik yang sama dengan Kamila. Meskipun sudah rugi miliaran saat nyalonin di pilkada lalu, sepertinya Papa tidak akan pernah merasa kapok karena Papa sudah terlanjur dibutakan cinta oleh Kamila. Lagi pula, kenapa seorang dokter malah terjun ke politik, sih? Dengan siapa dirinya sekarang, sudah pasti Papa melupakan saat-saat sulitnya bersama Mama. Kini, perlahan-lahan ia menjelma menjadi duri di dalam keluarga kecil kami.
*
Bahkan, bukan hanya sembarang duri, Papa membuat Mama mencintai kembali masa lalunya. Papa tidak berusaha untuk menggenggam miliknya erat-erat dan tidak pula berusaha untuk melepaskan miliknya. Kaleidoskop itu seperti sengaja ia bikin berceceran di sana-sini tanpa ada niatan untuk menyusunnya kembali secara utuh. Pada akhirnya, Mama memilih untuk kembali berjalan mundur dan menyusuri waktu yang sudah pernah berlalu. Setidaknya, itu yang aku ketahui dari semua surat dan foto yang kudapati dari sebuah kotak usang yang ajaib milik Mama. Surat dengan kisah roman picisan dan puisi-puisi cinta receh dari Aldric untuk Mama.
Aldric, si legenda, dan akan selalu menjadi legenda.
***


 nabillanastyf
nabillanastyf