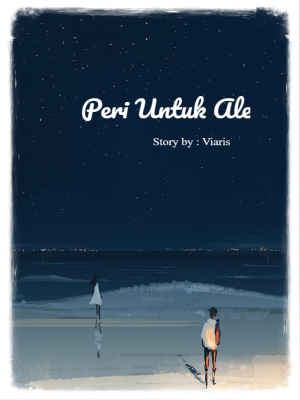Gerimis masih mengiringi ketika Pratiwi duduk bersimpuh di hadapan makam suaminya. Dan ini adalah hari ketiga dari kematian suaminya. Ia sengaja datang sendiri. Tanpa mengajak Revita, Mitty, maupun Bu Surti. Sebab kedatangannya ke makam kali ini bukan sekedar untuk ziarah dan menaburkan bunga tapi ia juga berniat mengutarakan pengakuan atas segala tindakan salahnya selama ini.
Kepergian Gunarto ke hadirat Illahi telah membuka pintu kesadarannya bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, sudah begitu banyak tugas dan kewajiban yang ia telantarkan selama ini. Terlebih tugasnya sebagai seorang ibu yang seharisnya mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayang untuk Revita.
Dengan tangan kiri memeluk erat pusara sang suami, tangan kanannya menaburkan bunga diiringi tetesan air mata.
“Paa, mengapa terlalu cepat kau tinggalkan aku dan Revita, Paa. Mengapa kau mendadak pergi di saat anak kita berhasil meraih prestasi. Mengapa Paa? Tidakkah kau tahu jika saat ini, aku dan Revita sangat membutuhkanmu, Paa. Paa, maafkan segala kesalahanku selama ini. Aku telah begitu lalai terhadap terhadap tugas dan kewajibanku sebagai seorang istri. Aku terlalu sibuk dengan hal-hal yang tak seharusnya aku lakukan. Sekarang aku benar-benar merasa bersalah, Pa.
Tak seharusnya aku menganggap peran, perhatian, dan kasih sayang seorang ibu hanya sebatas insidental moment dalam keluarga. Terlebih untuk anak kita, Revita. Sekali lagi maafkan aku, Pa. Mulai sekarang aku janji akan mencurahkan seluruh waktuku untuk anak kita,” lirih Pratiwi berucap sambil sesekali menyusut air mata di pipinya.
Gerimis masih juga belum reda. Bahkan titik-titik airnya tampak semakin deras. Namun Pratiwi belum juga beranjak dari makam suaminya.
Kini terpampang kembali dalam ingatannya, betapa kerasnya ia menentang keputusan suaminya untuk memindahkan Revita agar tinggal dan sekolah di Blitar. Ia semula menganggap kalau keputusan suaminya itu hanyalah bentuk kemarahan dari serangkaian kekecewaan atas perilaku Revita kala itu. Namun ternyata dirinya salah persepsi.
Baru sekarang ia menyadari kalau keputusan suaminya itu sudah dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan yang matang. Semua demi masa depan Revita semata. Dan sekarang kebenaran itu sudah terbukti. Tinggal dan sekolah di Blitar telah mempertemukan Revita dengan orang-orang yang tepat. Orang yang mengisi perjalanan hidup dengan kasih sayang dan cinta kasih.
Pratiwi serasa mendapatkan satu pembelajaran hidup yang sangat bermakna. Kesederhanaan pola pikir orang desa ternyata jauh lebih luhur dari orang kota yang menganggap materi sebagai prioritas.
“Tidak baik terlalu larut dalam kesedihan. Hidup harus tetap berjalan karena kita memiliki anak sebagai generasi penerus bagi kehidupan kita.” Satu suara tiba-tiba menyentuh telinga Pratiwi.
Kaget, Pratiwi segera mendongak. Seulas senyum manis langsung menyambutnya dari seorang lelaki perlente yang sudah berdiri di sampingnya sambil memegang sebuah payung hitam yang terkembang untuk melindungi tubuh Pratiwi dari siraman air hujan yang semakin deras.
“Septian, untuk apa kau kemari?” tanya Pratiwi yang belum juga berdiri.
Septian yang tak lain adalah ayahnya Dirga itu, sekali lagi tersenyum, baru kemudian menjawab.
“Seperti yang kau lihat, aku datang untuk melindungimu dari guyuran hujan. Aku tidak ingin kau sampai jatuh sakit karena Revita masih sangat membutuhkanmu.”
“Tapi tak seharusnya kau kemari. Nanti kalau sampai ada orang yang tahu justru akan menambah masalah,” sahut Pratiwi yang belum juga mau berdiri.
Lagi-lagi Septian malah tersenyum.
“He he he, kau tidak sedang ada di Surabaya, Pratiwi. Ini Blitar, sebuah kota kecil yang masih relatip sepi. Orang-orang di desa ini tak punya waktu untuk memperhatikan hal yang bukan urusan mereka. Mereka selalu terbuai dengan kehidupan pribadinya yang damai. Apalagi saat hujan begini, mereka pilih menghabiskan waktunya bersama keluarga daripada keluar rumah. Terlebih ke makam seperti ini. Jadi buang jauh-jauh kekawatiranmu yang tak beralasan itu.”
“Tapi tetap saja tak seharusnya kau kemari!” kilah Pratiwi tak mau kalah.
Septian menghela napas sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian lelaki itu berjongkok di sisi kanan Pratiwi.
“Ya memang, tak seharusnya aku di sini. Tapi aku pikir ini adalah saat yang tepat untuk kita bicara tentang hubungan kita selama ini, Pratiwi.”
Hah! Pratiwi tersentak. Matanya yang bulat bening mengerjap-ngerjap memandang lelaki di sampingnya dengan tatapan heran.
“Aku masih dalam suasana berkabung, Septian. Jadi aku harap kau ….”
Belum sempat Pratiwi meneruskan ucapannya, dengan cepat Septian telah memotongnya.
“Kau jangan salah mengerti, Pratiwi. Aku datang menemuimu saat ini bukan untuk membicarakan hari-hari yang telah kita lewati. Tapi sebaliknya aku ingin bicara tentang hari depan kita,” kata Septian penuh keyakinan.
Pratiwi yang sejak awal mengira bahwa kedatangan Septian adalah untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka lantaran ia kini sudah berpredikat janda, semakin tersentak hatinya mendengar ucapan Septian. Sebab meski hingga saat ini ia masih ada rasa dengan Septian yang pernah menjadi kekasihnya ketika mereka bersekolah di SMA yang sama, namun ia tak sudi jika dijadikan istri kedua tentunya.
“Apa maksudmu, Septian? Apa kau tidak melihat, tanah makam suamiku saja masih basah.”
Lagi-lahi Septian tersenyum.
“Kau jangan salah menduga, Pratiwi,” kata Septian lagi.
“Apa maksudmu?”
“Aku yakin kau juga pasti memiliki pemikiran yang sama tentang hal ini.”
“Jangan semakin membuatku bingung, Septian. Memang apa yang ada dalam pikiranmu, hah?! Jika kau kira aku akan segera mau kau nikahi setelah kepergian suamiku, maka kau salah! Salah besar!” tukas Pratiwi sedikit emosi.
“Aku juga tak memiliki pikiran seperti itu, Pratiwi.”
“Lalu apa maksud semua ucapanmu tadi?”
Sesaat Septiam terdiam. Matanya menatap lurus ke pusara yang bertuliskan nama, tanggal lahir, serta tanggak meninggalnya Gunarto. Pengusaha kaya yang beruntung menikahi wanita yang terlanjur lekat di hatinya itu.
“Pratiwi, di depan jazad suamimu ini, aku ingin mengakui kalau apa yang telah kita lakukan selama ini adalah salah. Tak seharusnya kita terbelenggu oleh masa lalu. Meski ketika SMA hingga kuliah kita memang pacaran dan saling mencintai tapi, sekarang keadaan sudah berubah. Kita sama-sama punya anak yang sudah remaja. Bahkan sekarang anak kita satu sekolah, satu kelas, dan juga sempat pacaran.
Apalagi sekarang, anak kita sudah jadi siswa teladan tingkat propinsi, tentu mereka akan teramat malu jika tahu orang tuanya berselingkuh. Karena itu Pratiwi, mulai sekarang mari kita sama-sama fokus mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada anak kita masing-masing selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan.
Kita kesampingkan saja ego dan perasaan kita. Kita dukung langkah positip anak-anak yang sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya. Kita isi sisa waktu hidup kita dengan hal yang bisa membuat mereka bangga karena memiliki orang tua seperti kita.”
“Alhamdulillah Septian, aku juga berpikir seperti itu. Asal kau tahu, keberadaanku di makam pagi ini juga untuk melakukan pengakuan atas langkah kita yang selama ini keliru. Jadi syukur jika kau juga memiliki pemikiran yang sama. Hanya saja kalau boleh aku minta satu hal padamu,” kata Pratiwi sambil menatap Septian dalam-dalam.
“Apa yang kau minta dariku? Katakanlah.”
“Sambil menunggu hingga Revita tamat kuliah nanti, aku harap kau bersedia membantuku mengelola perusahaan yang selama ini dipegang suamiku.”
“Baiklah, aku akan membantumu untuk itu,” jawab Septian tanpa pikir panjang.
“Terima kasih Septian.”
“Sama-sama.”
Septian menepuk-nepuk pundak Pratiwi seolah ia ingin memberikan tambahan kekuatan untuk orang yang selalu tersimpan rapi dalam hatinya itu. Dan tepat ketika hujan sudah mulai berhenti, Septian mendahului melangkah meninggalkan Pratiwi yang masih bersimpuh di hadapan makam sang suami.
Pratiwi kusyuk berdoa di bawah payung hitam yang ditinggalkan Septian untuknya. Besar harapannya semoga hari-hari yang hendak dilewatinya tidak sehitam payung yang kini menaunginya.. Payung yang telah menjadi saksi bisu atas segala pengakuan yang telah ia lakukan di tengah makam pagi ini.


 heru_patria
heru_patria