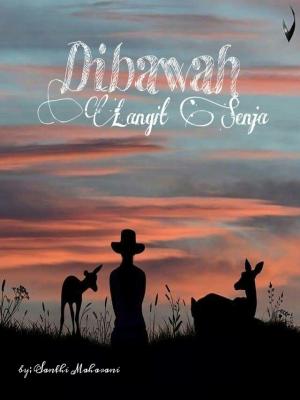“Kalau x pangkat tiga adalah suku banyak, bagaimana dengan angka biasa tanpa didampingi x?”
Telunjuk Deon menekan kacamata. “Angka biasa tetap didampingi x, tapi berpangkat nol. X pangkat nol nilainya satu.”
“Jadi maksudmu angka tiga sendirian berarti tiga kali x pangkat nol atau kata lain tiga kali satu?” Kilia bertanya meminta penegasan.
“Betul sekali!” seru Deon, tersenyum lega karena akhirnya Kilia mengerti. “Jadi nilainya tetap tiga.”
“Menarik sekali topik pelajaran suku banyak ini.”
“Kau orang pertama yang suka membahas matematika, teman-temanku yang lain pada malas semua.”
Kilia berpaling menatap Deon. “Bukannya kelasmu kelas favorit?”
“Favorit pun,” hela Deon sambil kembali duduk. “Banyak pembenci matematika.”
“Hm…” Kilia merenung sebentar. “Fisika? Kudengar kelas XI A juara olimpiade Fisika.”
Sebentar Deon berpikir. Memang sih mereka baru saja mengikuti olimpiade, tapi bukan prestasi yang bisa dibanggakan.
“Juara harapan kedua lebih tepatnya,” Deon mengoreksi dengan lemas. “Perfoma temanku kurang. Sebenarnya saat itu dia lagi banyak pikiran.”
“Lalu kenapa guru menyuruhnya ikut?”
“Masalah menimpanya sehari sebelum olimpiade,” terang Deon. “Tidak bisa dibatalkan lagi.”
“Oh, begitu.” Kepala Kilia mengangguk-angguk mengerti. “Buklankah ada satu mata pelajaran juara umum satu? Aku lupa mata pelajaran apa. Biologi? Kimia? Matematika?”
Deon enggan berkomentar, “Biologi.”
“Siapa pesertanya?” tanya Kilia antusias. Kali ini matanya berbinar-binar menatap Deon.
Tentu saja Deon enggan akan pertanyaan itu. Sebuah pertanyaan menjebak. Gadis itu sudah tahu siapa yang menjuarai olimpiade Biologi, tapi membuatnya seolah-olah belum tahu dan ingin Deon yang menjawab langsung.
“Kurasa kau bisa bertanya pada kepala sekolah,” saran Deon.
Senyum Kilia tersungging sempurna. Terlihat nakal.
“Kenapa kau tidak mau berkata jujur, Deon?” tanya Kilia, bernada sehalus mungkin. “Aku tahu kau yang menjuarai olimpiade Biologi itu.”
“Aku tidak suka mengumbar-ngumbar.”
“Merendah sekali,” Kilia menepuk tangan riang. “Boleh aku tanya sesuatu?”
Alis Deon terangkat tinggi.
“Bukan hal-hal aneh,” Kilia langsung menanggapi. “Aku janji.”
“Ok,” sahut Deon sambil lalu. “Apa yang mau kau tanyakan?”
“Kalau kelas favorit, bagaimana Edward bisa masuk ke kelasmu?”
Sulit untuk dijelaskan. Beberapa saat Deon termenung sambil bersedekap. Tidak mungkin mengatakan Edward pandai padahal selama ini dia selalu membantu sang sahabat mendapatkan nilai-nilai brilian. Walau sebenarnya Edward termasuk cerdas, cuma malas saja.
“Edward itu pintar, tapi sering membuat sensasi dan masalah,” aku Deon tanpa melakukan filter sama sekali. “Tunggu, kau kenal Edward?”
“Siapa yang tidak kenal Edward si pembuat onar?” tanya Kilia balik. “Yah, aku tidak mengerti saja kenapa kau berteman dekat sekali dengannya.”
“Itu…” Deon terdiam sesaat. “Rumit.”
Senyum Kilia kembali tercipta. Raut matanya mengisyaratkan sesuatu.
“Ngomong-ngomong, sebaiknya kau menemui Edward hari ini,” saran Kilia sambil menutup buku. “Sesuatu terjadi padanya.”
Deon mencondongkan badan. “Apa yang terjadi? Dia terlibat masalah lagi?”
“Akan kuceritakan asal kau tutup mulut tidak memberitahunya bahwa aku yang memberitahumu. Ok?”
“Kenapa harus janji-janji belaka?” tanya Deon tidak mengerti.
Sebelah bahu Kilia terangkat. “Aku tak mau berurusan dengannya saja.”
Apakah Edward separah itu? Mungkin sahabatnya itu tidak memperlakukan orang lain sebaik dirinya, mungkin saja. Bisa jadi.
“Baiklah. Aku janji,” Deon menyetujui. “Sekarang beritahu apa yang terjadi dengannya?”
“Dia kena razia klub malam.”
***
“Terlibat masalah apa lagi kau Edward?!” gumam Deon agak geram. “Sudah kesekian kalinya kuperingatkan.”
Satu belokan ke kiri, Deon sampai ke gerbang komplek yang amat mewah. Gerbang itu tinggi, berlapis cat warna keemasan, dan seekor kuda tinggi sedang meringkik di puncaknya. Satu kalimat terpampang pada gerbang itu, “Komplek Citra Asri”.
Salah seorang satpam menghadang. “Datang mengunjungi Edward, Deon?”
“Iya. Apa dia ada, Pak?”
Satpam menoleh ke belakang, memandang sebuah rumah besar di ujung komplek. “Ada. Sayangnya Tuan Besar melarang keras anaknya keluar, kami juga disuruh menangkapnya bila dia mencoba kabur.”
Yang dimaksud Tuan Besar adalah ayah Edward. Seluruh penghuni komplek memanggilnya begitu. Konon Deon mendengar dari ayahnya kalau ayah Edward yang mengagas pembangunan komplek perumahan Citra Asri serta mengurusnya sampai sekarang. Melihat pekerjaan ayah Edward sebagai kontraktor pemerintah, tentu dia mampu melakukan itu. Namun dari tiga anaknya, Edward lah yang tidak beres. Seorang berandal dan selalu kena masalah.
“Wajah Tuan Besar sangat galak,” bisik satpam ngeri. “Kalau kubiarkan Edward lolos, dipecat bukan lagi mimpi.”
“Ayah Edward tidak sekejam itu, Pak,” Deon menenangkan. “Paling palak saja sama Edward.”
“Semoga saja,” harap satpam. “Kemarikan kartu identitasmu, Deon.”
Satpam menempelkan kartu siswa Deon ke layar sensor. Setelah komputer mengucapkan terima kasih secara otomatis, kartu tersebut dikembalikan ke pemiliknya.
“Tolong bujuk tuan muda jangan membuat masalah lagi,” pinta satpam lain, “kalau tidak mau gerbang ini dibuat layaknya gerbang penjara seperti di film-film barat.”
Senyum Deon merekah tidak karuan. “Bapak ada-ada saja.”
Dalaman komplek lebih mewah dari gerbang depan. Jalanan dialasi batu marmer hitam yang mengilap di bawah sinar matahari, pepohonan rindah menghiasi sisi jalan, belum lagi beberapa spot tempat duduk berkanopi dan taman bermain anak-anak. Kondisinya bersih dan rapi. Beberapa petugas berbaju biru putih terlihat berkeliaran mencabut rerumputan, memotong dedaunan pohon, dan melaklukan aktivitas-aktivitas lain. Primadona komplek itu sungguh menarik perhatian, sebuah air mancur berdiameter selebar mobil berdiri kokoh di tengah-tengah komplek. Mendorong air-air ke atas dalam pola searah jarum jam dalam gerakan berirama yang spektakuler.
Berselang Deon sudah sampai di depan gerbang rumah Edward. Setelah menekan tombol bel, Deon diam menunggu dengan sabar. Seseorang bertubuh jangkung berjalan keluar dari balik rumah dengan langkah lebar penuh kepastian. Laki-laki itu berperangai kurus, tinggi, dan berambut tipis putih. Ekspresinya tenang dan santai. Berpakaian batik biru bercorak gelombang-gelombang ombak yang tak selaras dengan cuaca terik.
“Oh, Tuan Deon. Ada yang bisa saya bantu?” tanya laki-laki itu, membuka sedikit gerbang.
“Apakah Edward ada, Pak Gito?”
“Tuan muda ada. Apa anda ingin bertemu dengannya?”
Deon tersenyum. “Ya.”
“Tapi Tuan Besar melarang siapapun bertemu putranya saat ini.”
Kata-kata Pak Gito membuat wajah Deon melemas kecewa, begitu juga wajah Pak Gito. Sedih bercampur ketidaktegaan.
“Sebentar,” celetuk Pak Gito. “Coba kutelepon Nyonya Besar. Pasti dia bisa melunakkan hati Tuan Besar.”
Pak Gito merogoh sebuah telepon genggam kecil dari balik kantung baju. Telepon zaman baholak. Yang katanya anjing pun bisa mati kalau dilempar pakai telepon genggam itu. Jari Pak Gito menekan sebuah tombol lalu menempelkan telepon genggam ke telinga kanan. Suara khas “Tut-tut-tut” berkumandang dalam jeda panjang.
“Nyonya Besar!” seru Pak Gito girang ketika orang di seberang sana menjawab. “Sahabat Edward datang berkunjung.”
Mata Deon hanya menatap gelagat Pak Gito yang terus mengangguk-angguk. Sesekali menyahut membujuk ibu Edward agar mengizinkan Deon menemui Edward dengan berbagai alasan aneh. Salah satunya agar Edward tidak menjadi gila. Cukup astaganaga, tapi sepertinya efektif.
“Mereka mengizinkanmu bertemu Edward.” Pak Gito mulai membuka gerbang lebih besar supaya sepeda motor Deon bisa masuk. “Nyonya Besar minta tolong agar Tuan Deon membujuk anaknya agar tidak berulah lagi.”
Deon menggeleng kepala. “Ini bukan pertama sekali orang-orang menyuruhku membujuk Edward. Anak itu amat keras kepala.”
“Dan beruntung sekali dia punya teman baik seperti anda, Tuan Deon.”
Pak Gito menyuruh Deon masuk terlebih dahulu. Nanti dia menyusul, jadi Deon berkendara dan parkir di depan pintu rumah Edward. Berapa kali pun datang, kesan Deon masih sama. Rumah Edward bergaya Eropa menampilkan kemewahan tiada tara. Berwarna putih bersih dan pilar-pilar tinggi menghiasi hampir setiap sisi bangunan rumah. Itu masih bagian luar, belum bagian dalam. Ketika Pak Gito membukakan pintu, sebuah ruang tamu atau lebih tepatnya sebuah aula menyambut Deon. Beragam barang impor berjejer rapi menghiasi ruangan dari vas bunga bercorak rumit indah, lukisan-lukisan abstrak, jam dinding antik, dan benda-benda lainnya. Namun kursi, meja, dan televisi masih produk lokal. Dulu Edward pernah bilang barang-barang itu punya sejarah berharga.
“Siapa yang main piano?” tanya Deon antusias, mendengar nada-nada piano bertema musik pop menggemai seluruh ruangan saat memasuki ruang tamu.
“Tuan Muda. Sejak sedari pagi.”
“Kupikir abangnya.” Deon menebak salah karena semua abang Edward bisa bermain piano.
Pak Gito menggeleng kepala. “Dua abang Tuan Muda tidak akan pulang untuk lima tahun ke depan.”
“Apa sibuk belajar di luar negeri?”
“Tidak,”Pak Gito menyahut pelan. “Mereka sudah bekerja dan betah tinggal di luar negeri.”
Mulut Deon terkatup. Memang rata-rata orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri enggan kembali. Alasannya banyak, seperti negara luar lebih moderen, kurang diakui di negara sendiri, atau gaya hidup luar lebih enak. Deon bertanya-tanya, jika dia ambil beasiswa di luar negeri, apakah dia mau kembali nanti.
“Sekarang harapan Tuan Besar beralih kepada Edward,” lanjut Pak Gito dengan wajah lesu. “Tapi Tuan Muda tidak sudi. Malah berulah lagi sehingga Tuan Besar marah tak karuan.”
“Nanti kucoba menasehati Edward, Pak Gito,” usul Deon walau ragu dalam hati.
“Semoga saja dia mau dengar.”
Bahkan Pak Gito pun tahu bahwa Edward bebal. Meski tidak berjudi atau makan obat-obatan, tetap saja sahabat karibnya sering terlibat perkelahian, tawuran maupun membuat onar. Kalau bukan karena koneksi dan kekuasaan sang ayah, Edward mungkin saja sudah dijebloskan ke penjara anak-anak dari dulu. Kasus kali ini pun Deon yakin Edward dibantu ayahnya.
Suara piano kian terdengar jelas kala Deon menaiki susuran tangga demi tangga. Kamar Edward di lantai dua, tapi ruangan santai tempat Edward bermain piano berada di lantai tiga. Tiba-tiba saja musik piano Edward berganti genre. Menjadi genre klasik, kesukaan Deon.
“Sepertinya kau tahu aku datang,” kata Deon saat memasuki ruangan lantai tiga.
“Yo, Deon!” seru Edward dari balik piano yang berada di tengah ruangan. “Aku pasang banyak kamera seperti yang pernah kau sarankan.”
“Aku tidak pernah menyarankan apapun,” balas Deon keheranan.
“Kau ingat kamera mini yang kau kasih tahu aku dijual di toko digital tempo hari?” Edward terkekeh sambil masih menekan tuts-tuts piano. “Kupasang di mana-mana. Terima kasih atas usulmu!”
Deon hanya bisa memutar bola mata. “Kenapa kau absen sekolah lagi?”
“Jangan pura-pura tidak tahu, Deon.” Edward beranjak. “Berita cepat menyebar. Kau tidak akan segera datang setelah pulang sekolah begini kalau tidak tahu apa yang terjadi padaku.”
Hela napas Deon terdengar panjang sembari menduduki kursi di samping kursi Edward. Satu-satunya kursi. Mungkin sengaja disediakan Edward untuknya.
“Apa yang terjadi?”
Edward tertawa keras-keras. “Tak usah serius begitu, Kawan. Semuanya aman terkendali.”
“Jika iya, kenapa kau bisa kena tangkap?” Nada suara Deon terdengar lebih ringan. “Kau pernah bilang klub malammu jarang kena razia.”
“Itulah anehnya,” Edward memutar badan dengan alis berkerut. “Polisi-polisi yang menangkap kami menyamar sebagai pengunjung-pengunjung awam. Biasanya penjaga klub bisa tahu kapan polisi akan menggerebek dan bilapun digerebek, pasti kami di dalam sudah diberitahu sebelum polisi sempat masuk.”
“Mereka penegak hukum, Edward,” ketus Deon. “Mereka punya caranya sendiri.”
Edward bersandar santai. “Aku rasa kami dikibus. Seseorang pasti mencari gara-gara.”
“Sebaiknya kau berhenti ke klub malam,” saran Deon, tidak peduli apakah sahabatnya dikibus. “Lebih bagus kau ke mall-mall nongkrong atau duduk-duduk di tepi jalan.”
“Mau ditaruh di mana wajahku, Deon. Anggota geng bakal meremehkanku,” sahut Edward keras. “Lagipula, klub malamku tidak separah yang kau kira.”
Seratus persen Deon meragukan pembelaan Edward. Dulu dia pernah diajak ke klub itu dan beda sama sekali. Cahaya kelap-kelip beragam warna ditembakkan lampu-lampu menyinari seluruh ruangan dalam pola acak-acakan. Membuat ruangan klub terasa kacau balau. Musik-musik begitu keras hingga berbicara pun perlu teriak. Minuman kuning yang dipesan Edward juga nyeleneh. Pahit bercampur asam. Cukup sekali saja Deon mengunjungi sebuah klub malam.
“Baiklah, baiklah,” Deon mengakhiri pasrah. “Kapan kau balik masuk sekolah?”
“Besok. Ayakhu tak bisa menahanku lama-lama di rumah.”
“Beliau marah?” tanya Deon pura-pura bodoh.
Edward berseru,“Terserah. Aku tidak peduli sama sekali.”
“Kau tidak sayang ayahmu?”
Senyum Edward merekah seketika. “Hahaha. Sekarang dia baru peduli padaku karena abang-abangku menolak meneruskan bisnisnya lagi. Aku ini hanya cadangan, tidak lebih.”
Saat itu Pak Gito tiba. Membawa sepiring kue kering dan dua gelas jus di atas sebuah talam besar. Raut wajahnya kelihatan lemas, namun sebuah senyum masih terpampang lebar.
“Terima kasih, Pak Gito,” ucap Deon sopan.
“Sama-sama, Tuan Deon.”
“Pak Gito, tolong ambilkan oleh-oleh papa,” suruh Edward. “Cokelat hitam itu.”
“Tuan Besar berpesan kalau cokelat itu tidak boleh dimakan,” larang Pak Sugito. “Oleh-oleh Tuan Besar untuk teman-temannya.”
Edward hanya tertawa. “Ngak papa, nanti aku yang tanggung jawab.”
“Tapi…”
“Kalau bapak tidak mau, tak apa-apa. Nanti kuambil juga,” Edward berkata penuh kesantaian. “Ambil satu tidak apa-apa untuk dimakan bersama Deon.”
Mau tidak mau Pak Gito pun berlalu dengan wajah masam. Seakan-akan menderita seketika hebatnya.
“Pak Sugito terlalu peduli dengan keluargaku,” ujar Edward sambil menaikkan satu kaki ke kaki satunya. “Padahal bukan urusannya.”
“Jarang-jarang ada orang seperti Pak Gito, Edward.”
“Memang aku berterima kasih, tapi Pak Sugito tahu sangat sedikit apa yang kualami.” Edward mulai sedikit emosional. “Kau sudah pernah dengar ceritaku, Deon. Ayahku mengabaikanku sama sekali. Selalu sibuk saat aku kecil sampai beranjak remaja, kalau pun pulang hanya bertegur sapa layaknya orang asing dan hanya ramah pada abang-abangku. Kenapa aku harus peduli padanya jika dia saja tidak menganggapku ada?”
Pertanyaan terakhir membuat Deon bungkam. Kenyataan realita jauh lebih parah dari bayangannya.
“Ayo kita bicarakan hal lain,” ajak Edward ceria. “ Ada gadis yang chat kamu, kan?”
Deon menuding Edward. “Pasti ulahmu.”
“Kau bilang terserah jadi kusikatlah,” cela Edward. “Berarti ada yang chat kamu, kan? Gimana? Agresif ngak dia?”
Tangan Deon kembali bersedekap. Pandangannya sedikit tertunduk, sulit untuk mengungkapkan karena lari dari ekspetasi Edward.
“Aku ragu,” kata Deon sambil merogoh ponsel pintar dari saku celananya. Ponsel itu diserahkan Deon ke Edward. “Coba kau baca sendiri.”
Seksama Edward membaca isi chat Deon dengan gadis misterius itu. Singkat dan padat. Decakkan lidah Edward terdengar beberapa kali seraya tangannya menggeser-geser layar.
Edward mengangkat sebelah bahu. “Kurasa pertama kalinya dia chat lawan jenis. Padahal dia sendiri banyak dikejar orang.”
“Siapa gadis itu?” Alis Deon terangkat sedikit. “Setidaknya kau harus memberitahuku namanya.”
“Tidak akan, Deon. Gadis itu yang harus memberitahumu atau kau yang bertanya sendiri.”
“Kenapa harus rahasia melulu?” protes Deon.
“Sebab aku hanya membantu kalian berdua. Setelah itu lepas tangan.”
Hanya tatapan sinis yang diterima Edward ketika dia menatap Deon. Memberitahunya kalau Deon tidak mengharapkan semua ini terjadi, tapi bukan masalah bagi Edward demi membantu seorang teman. Lagipula sahabat karibnya itu terlalu mengisolasi diri. Biarkan sekarang sedikit bersosialisasi dengan lawan jenis. Walau di luar dugaan Edward bahwa gadis itu begitu pasif, tidak, menjengkelkan dari gaya chat nya.
“Yah sudahlah.” Edward memutar menghadap piano. “Kau mau aku mainkan lagu apa untukmu.”
“Kau ngak mau belajar? Aku bawa buku catatan loh,” ujar Deon, mengambil keluar sebuah buku notes kecil dari dalam saku celana. “Sudah kuringkas untukmu.”
“Nanti sajalah. Cepat, kau mau lagu apa?”
Kelihatannya Edward memang enggan belajar sama sekali. Buang-buang tenaga memaksanya.
“Lagu barat lama.”
Jari Edward mulai menekan tuts-tuts piano. “Memang seleramu tidak berubah.”
Tiba-tiba teringat sebuah ide bagus terlintas dalam benak Edward. Senyumnya merekah ketika berbalik menatap Deon.
“Bagaimana kalau kau kuajari main gitar?” tawar Edward serius.
Dahi Deon berkerut. “Gitar?”
“Ya. Coba-coba saja.”
Tanpa menunggu persetujuan Deon, Edward beralih masuk ke kamar terdekat dan keluar membawa sebuah gitar dari kayu mahoni. Gitar itu biasanya dipakai oleh pemusik-pemusik terkenal, menurut Deon, pasti harganya luar biasa mahal. Tapi Edward menyodorkan gitar itu dan menyuruhnya memetik senar demi senar. Bukannya menasehati Edward, hari itu Deon malah diajari Edward cara bermain gitar. Deon tidak tahu harus senang atau sedih.


 widdy
widdy