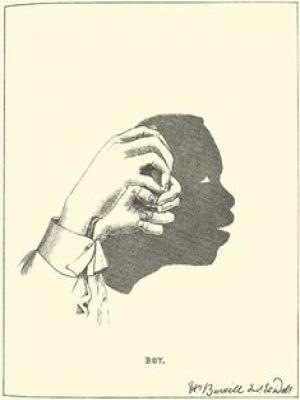Hari-hari berlalu, tapi kini aku dan Gian jadi seperti orang asing. Kami tidak saling bicara jika tidak sedang benar-benar ada perlu.
Hal itu dikarenakan setiap kali hendak mengajaknya bicara, Gian selalu berusaha menghindar. Dia selalu punya sejuta alasan untuk berusaha kabur dari penglihatanku.
Merasa lelah dengan sikap Gian yang selalu menolak ketika diajak bertemu, aku juga balas mendiamkannya. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik untuk kami. Mungkin saat situasinya sudah lebih baik dari sekarang, hubunganku dengan Gian juga bisa ikut kembali membaik nantinya.
Gian mungkin masih banyak pikiran karena persidangan ibunya kini tinggal menghitung hari, maka dari itu dia belum mau kuajak bicara.
Aku tentu memaklumi sikapnya karena aku sendiri juga tidak bisa membantu banyak.
Mama serta keluarga besar Papa minta agar Mbak Yanti dihukum seberat-beratnya, sementara aku hanyalah bocah SMA yang tidak punya bukti, tidak punya kuasa untuk membebaskan Mbak Yanti dari tuduhan yang diterimanya.
“Lu pada udah denger belum?” tanya seorang murid perempuan kepada gerombolannya ketika aku berada di toilet sekolah.
“Denger apa?” tanya yang lain.
“Katanya yang bunuh bokapnya Haira itu emaknya si Gian.”
Aku sedikit terperangah mendengar desas-desus itu. Kubuka sedikit bilik pintu untuk melihat siapa saja yang kini tengah ngobrol di toilet.
“Eh, yang bener?” tanya Bintang. “Kata siapa?”
“Beritanya banyak di internet,” jawab Putri yang merupakan orang pertama yang memulai topik obrolan itu.
“Mana coba liat dong?” kali ini murid perempuan bernama Sekar yang angkat bicara dengan nada penasaran.
“Nih, banyak artikelnya,” kata Putri kepada teman-temannya. “Baca deh, baca.”
“Wah, nggak nyangka gue.”
Aku bingung bagaimana harus menyangkal hal itu. Percakapan mereka yang kudengar dari bilik toilet lama-lama membuatku tidak nyaman.
“Gian sama Haira bukannya pacaran?” tanya Saras kali ini.
“Udah dari lama kali,” kata Putri.
“Kasian Haira nggak, sih, kalau mereka pacaran?”
“Kasian kenapa?” giliran Sekar yang bertanya. “Gian setau gue keliatannya kayak cowok baik-baik.”
“Haira, kan, sultan, terus pacaran sama yang …,” Putri menjeda kalimatnya sejenak. “… you know lah.”
“Jangan-jangan selama ini Haira dimanfaatin sama Gian?” kata Bintang.
“Iya kayaknya. Pasti disuruh bayarin semuanya kalau mereka lagi jalan,” kata Putri. “Lagian, apa, sih, bagusnya Gian? Masih banyak kali cowok yang lebih-lebih dari Gian kalau buat dijadiin pacar.”
“Tau tuh, pake pelet apaan,” kata Saras yang diakhiri dengan suara tawa.
“Udah dibaik-baikin, diterima jadi pacar, eh, sekarang malah emaknya ngebunuh bokapnya Haira,” kata Putri dengan nada mengejek.
“Udah dibaik-baikin sama si Haira bukannya bersyukur, eh malah dibales begini,” kata Sekar yang semakin mendidihkan emosiku.
“Udah nggak modal, sekarang emaknya ngebunuh lagi,” kata Bintang.
“Cocok emang emak sama anak,” kata Saras.
“Sama-sama problematik, ha ha ha!” kata Putri. “Udah, ah, yuk, keluar.”
Ketika mereka semua sudah keluar, aku juga segera keluar. Buru-buru kulangkahkan kakiku sebelum mereka kembali ke kelas.
“Heh, kalian!” teriakku dan langsung membuat mereka berempat segera balik badan.
“Apa, sih, teriak-teriak?” tanya Putri.
“Kalian tadi ngomong apa soal Gian?”
“Kita-kita nggak ngomongin apa-apa.”
“Kalau Gian pacaran sama gue, emang kenapa?” tanyaku dengan nada menantang.
“Lo gila apa teriak-teriak begini?” tanya Putri.
“Jangan berani-berani ya lo ngehina-hina pacar gue.”
“Lo ngomongin apaan, sih?” tanya Putri.
“Lo pikir gue nggak denger obrolan kalian di toilet tadi?” tanyaku.
“Oh, bagus deh kalau lo denger,” kata Putri. “Lo harusnya marah, dong, ke Gian sama emaknya, ngapain masih belain dia?”
“Gian itu nggak kayak yang kalian pikirin.”
Mereka tersenyum meremehkan.
“Daripada ngomentarin orang lain kayak tadi, mendingan kalian pakai waktu kalian buat belajar. Ngerti?” kataku menggebu-gebu.
“Mending suruh tuh pacar lo buat belajar biar nggak tidur mulu di kelas.”
Emosiku semakin memuncak rasanya.
“Oh, kalian ngerasa lebih pinter dari Gian sekarang?” kataku.
Mereka mengedikkan bahu acuh.
“Sekarang gue tanya, who is Steve Jobs?” tanyaku ke mereka.
“Sori, kita ini di Indonesia, pakai Bahasa Indonesia, jangan basa enggres,” kata Bintang dengan nada mengejek.
“Makanya belajar, bodoh, jangan ngerumpi mulu kerjaannya!” kataku.
“Dih,” cibir Putri.
Suasana di antara kami berlima jadi heboh. Murid-murid lain banyak yang keluar kelas untuk melihat apa yang terjadi.
Putri mengambil satu langkah maju, berdiri angkuh di depanku dengan kedua tangan terlipat di depan dada.
Karena tinggi kami hampir setara, aku juga tidak gentar berhadapan dengannya dan balik menatapnya seolah menantang.
Kemudian, tangannya terulur, menjambak rambutku kencang-kencang, membuat murid-murid lain seketika gaduh karena perkelahian kami.
Dengan perasaan yang masih dipenuhi oleh amarah, kulepaskan tangannya sambil kubilang ke dia: Coba saja jambak aku, atau tampar aku sekalian. Aku sama sekali tidak takut bahkan jika mereka berempat akan berbuat anarkis padaku ramai-ramai.
“Gian itu kepribadiannya bagus. Dia emang ranking terakhir di kelas, tapi selalu dapet piala kalau ikut kompetisi piano. Dia nggak kayak kalian, para anak mama yang bahkan nggak pernah punya piala karena bohong ke orangtua kalau ikut les sana sini, padahal duitnya kalian pakai buat main.”
“Lo bilang apa barusan?” tanya Putri.
“Hei, hei, apa-apaan kalian ribut-ribut pagi-pagi begini?”
Semua murid serempak menoleh ke sumber suara, melihat guru kami yang bernama Pak Mulyadi berdiri di ujung lorong dengan wajah garang, kemudian berjalan menghampiri aku dan Putri sambil membawa sebuah penggaris kayu besar di tangannya.
“Apa yang kamu lakukan ke Haira?” tanya Pak Mulyadi ke Putri yang kini menundukkan kepala dalam-dalam.
“Dia duluan, Pak,” jawab Putri.
Pak Mulyadi berdiri di tengah-tengah antara aku dan Putri, menatap kami bergantian. Beliau lalu minta kami berdua untuk sedikit menjauh dari satu sama lain.
“Kamu jangan bohong,” kata Pak Mulyadi.
“Beneran kok, Haira duluan yang mulai,” kata Putri.
“Mana mungkin murid teladan seperti Haira begini yang ngajak berantem duluan?” kata Pak Mulyadi.
“Beneran, Pak. Tanya aja sama temen-temen yang lain.”
Teman-temannya Putri juga menunduk, tidak berani membuka mulut.
Mereka diam karena pasti takut akan ikut dihukum oleh Pak Mulyadi.
Pak Mulyadi kemudian minta murid lain untuk bubar. Mereka semua segera masuk ke kelas masing-masing. Ketiga teman Putri yang tadi bergosip di toilet juga ikut bubar. Sementara itu, Pak Mulyadi minta Putri untuk ke ruang guru setelah ini, tidak boleh masuk ke kelas. Kukira aku juga akan disuruh ke ruang guru, tapi ternyata tidak, aku justru diperbolehkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa.
“Omongan mereka jangan diambil hati, nanti biar Bapak yang hukum mereka.”
“Baik, Pak. Saya ke kelas dulu,” kataku.
Setelah itu, aku kembali ke kelas, kemudian duduk di bangkuku, mengabaikan murid lain yang terus memandangku sejak masuk ke dalam kelas.
“Ra, nggak apa-apa?” tanya Sita.
“Hah? Apanya?”
“Rambutmu mungkin banyak yang rontok.”
“Enggak,” kataku. “Dia tadi jambaknya kenceng, sih, tapi nggak sampai bikin rontok juga kali.”
“Tetep aja. Jadi berantakan semuanya begini,” kata Sita yang kemudian berusaha merapikan rambutku pakai sisir yang dia bawa.
“Makasih.”
“Aku lihat kalian berantem tadi. Kenapa kamu cuma diem aja, sih?”
“Males ngeladenin.”
“Kalau aku yang tadi dijambak, beuh … udah langsung kucekek dia.”
“Serem amat.”
“Biarin, bodo amat. Biar sakit itu tenggorokan, biar nggak bisa julidin orang lagi.”
“Iya deh, terserah.”
“Kita bales dendam gimana?” tanya Sita. “Nanti pulang sekolah, kita cegat dia sama temen-temennya.”
“Ngapain?”
“Ya biar mereka kapok. Biar nggak main jambak rambut anak orang,” jawab Sita. “Yakin deh, yang modelan begitu nggak bakalan kapok habis dihukum sama guru.”
“Males, ah.”
“Halah, males apanya? Aku tau, kamu itu keliatan nggak punya takut ke semua orang. Tapi, aslinya ya begini.”
“Begini gimana?”
“Ya begini, nggak tegaan ke orang lain. Sekali-kali deh, kalau dijahatin sama orang lain tuh lawan balik orangnya.”
“Ya ya ya.”
Lama-lama jengah juga mendengar ocehan Sita.
“Udah, ah, jangan ngelakuin yang aneh-aneh.”
Aku menghembuskan napas malas.
“By the way, omongan mereka tadi nggak usah dipikirin.”
“Iya, tau.”
“Aku juga percaya kalau Mbak Yanti nggak mungkin begitu.”
“Kenapa kamu bisa percaya?”
“Kan, kamu sendiri yang bilang? Lagian, aku juga tau Mbak Yanti itu orangnya gimana.”
“Andaikan semua orang punya pikiran kayak kamu. Pasti nggak jadi begini,” kataku yang kemudian menyenderkan kepala ke atas meja.
Kudengar Sita menghela napasnya.
“Ra,” panggilnya sambil menepuk pelan bahuku.
“Apa?” tanyaku.
“Ada yang mau ketemu kamu deh kayaknya,” katanya. “Dilihat dari mukanya, kayaknya ada yang mau dia omongin.”
“Siapa?” tanyaku.
“Gian.”
“Eh? Gian?”
“Iya, tuh anaknya.”
Aku menegakkan badan. Kepalaku berputar sembilan puluh derajat mengikuti arah telunjuk Sita. Kulihat Gian menatap lurus padaku. Sedetik kemudian dia mengalihkan pandangannya dan beralih mengambil ponsel. Sebuah pesan masuk tertera dalam layar ponselku yang tidak lain merupakan pesan singkat dari Gian.
*****
Setelah bel pulang berbunyi, aku tidak langsung pulang ke rumah.
Tadi pagi, Gian mengirimiku sebuah pesan singkat setelah beberapa hari belakangan kami tidak saling bertukar pesan. Dia bilang mau mengajakku ke suatu tempat setelah pulang sekolah, jadi segera kuiyakan saja tanpa banyak bertanya.
Mesin motor yang dimatikan Gian membuatku sadar bahwa kami telah sampai, kemudian kami turun, kedua mataku menatap sebuah tempat yang sepertinya banyak petugas kepolisian, lalu Gian mengajakku untuk masuk.
“Yuk, masuk,” kata Gian.
Aku ikut dia masuk ke dalam gedung.
Gian kemudian menghampiri seorang petugas kepolisian. Petugas itu lalu meminta identitas kami sekaligus menggeledah barang-barang yang kami bawa. Barulah kami berdua diijinkan untuk menuju ke sebuah ruangan setelah selesai diperiksa.
“Mbak Yanti?” kataku dengan nada tidak percaya ketika melihat Mbak Yanti berjalan menghampiri kami.
“Iya,” jawab Mbak Yanti. “Ini Mbak. Mbak Yanti. Ibunya Gian. Pengasuhnya Rara kalau di rumah.”
“Mbak Yanti selama ini di sini?”
“Iya. Habis ditangkap, Mbak tinggal di sini.”
“Ibu dianggap sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Jadi, Ibu ditangkap terus dibawa ke sini,” kata Gian.
“Sini, duduk dulu,” kata Mbak Yanti.
“Akhirnya, aku bisa ketemu Mbak lagi,” kataku setelah kami bertiga duduk.
“Maaf, ya. Kita ketemunya di tempat yang kayak begini,” kata Mbak Yanti.
“Jadi, Mbak ditahan di sini?” tanyaku.
“Iya,” jawab Mbak Yanti dengan ekspresi sendu.
“Sampai kapan?” tanyaku. “Sampai berapa lama Mbak bakal ditahan di sini terus?”
“Mbak juga nggak tau,” jawab Mbak Yanti sambil menggeleng pelan.
Hatiku rasanya ikut sakit melihat Mbak Yanti memakai baju warna oranye khas seorang tahanan. Raut wajahnya yang tampak lelah menandakan bahwa dia sedang memikirkan banyak hal saat ini.
“Terus, sebelum ini Mbak di mana?” tanyaku, maksudnya aku bertanya ke mana Mbak Yanti menghilang setelah kematian Papa?
“Mbak sewa kos,” jawab Mbak Yanti.
“Kenapa nggak ngasih tau aku, Mbak?”
“Mbak takut,” jawab Mbak Yanti.
“Takut kenapa? Aku tau kok Mbak nggak salah.”
“Kata Gian, kamu ada di sana waktu kejadian?”
“Iya.”
Muka Mbak Yanti seperti sedikit tertegun.
“Kamu lihat semuanya?” tanya Mbak Yanti.
“Iya.”
“Kamu lihat Mbak sama Papamu?” tanya Mbak Yanti. “Kamu lihat kami bertengkar di deket tangga?”
“Iya,” jawabku yang kembali teringat dengan peristiwa mengejutkan pada hari itu. “Aku masuk rumah habis pulang sekolah. Terus, aku lihat Mbak sama Papa di lantai dua.”
“Untung Gian cerita ke Mbak tentang ini. Kalau enggak, Mbak nggak tau lagi harus gimana,” kata Mbak Yanti sambil memandang ke Gian.
Gian justru mengalihkan pandangan seolah malas melihat ibunya sendiri.
“Aku cerita bukan karena mau bantu Ibu,” kata Gian.
“Iya, Ibu tau.”
“Aku cerita demi anak yang dikandung Ibu.”
“Iya, makasih sudah cerita.”
“Gih, sekarang ngomong sendiri ke dia.”
“Iya.”
Setelah bilang begitu, pandangan Mbak Yanti kemudian kembali berpusat padaku, menatap lurus padaku seperti ingin mengatakan sesuatu.
“Rara,” panggil Mbak Yanti.
“Iya, Mbak?” tanyaku yang balas menatap Mbak Yanti dengan ekspresi bingung. Kupikir ini ada kaitannya dengan Gian yang tiba-tiba mengajakku bertemu Mbak Yanti sekarang.
Keheningan menyelimuti kami karena Mbak Yanti tampak ragu-ragu mau bicara.
“Mbak mau minta tolong ke Rara,” kata Mbak Yanti sambil meraih kedua tanganku untuk dia genggam di atas meja.
“Makanya, aku ngajak kamu ke sini,” kata Gian ke aku.
“Mbak udah nggak tau lagi. Sekarang cuma Rara yang bisa nolong Mbak.”
“Aku bisa nolong apa?” tanyaku memandang Mbak Yanti.
“Kamu satu-satunya saksi mata waktu kejadian itu,” kata Mbak Yanti. “Tolong, jadi saksi waktu persidangan Mbak.”
“Jadi saksi?”
“Iya, tolong kamu jadi saksi waktu nanti Ibu disidang di pengadilan,” kata Gian ke aku bagai memohon.
“Aku bisa apa? Apa mereka bakal percaya sama omonganku nanti?” tanyaku.
“Percaya atau enggak, itu biar jadi urusan orang-orang di pengadilan. Yang penting kamu udah bilang jujur ke mereka. Setidaknya orang-orang itu bisa melihat dari sudut pandang lain,” kata Mbak Yanti.
“Tapi, aku nggak punya bukti apa-apa. Semua bukti sekarang tertuju ke Mbak. Susah buat nyangkal rekaman CCTV itu, Mbak. Aku nggak yakin apa dengan adanya aku di persidangan nanti bisa ngebantu Mbak.”
“Kesaksianmu nanti bisa jadi pertimbangan, Ra,” kata Gian.
“Iya, tolongin Mbak,” kata Mbak Yanti ke aku.
“Kamu bilang aja yang sejujurnya terjadi pada waktu itu. Kamu bilang kalau Ibu nggak dorong Papamu, jadi Ibu bukan pembunuh kayak apa yang dibilang sama orang-orang,” kata Gian dengan nada memohon sambil memandang ke aku yang sekarang jadi dilanda oleh perasaan bimbang.
“Terus, kalau nanti ditanya alasan mereka berantem, aku jawab apa?” tanyaku. Mbak Yanti kemudian diam. Gian juga diam.
“Kemarin, Ibu bilang yang sebenernya. Tapi, mereka nggak ada yang percaya,” kata Gian pada akhirnya.
“Jadi, aku juga harus bilang kalau Papa selingkuh?” tanyaku. “Apa aku harus bongkar semuanya?” sambungku.
“Iya, mau nggak mau kamu harus cerita tentang semuanya,” jawab Gian.
“Kalau aku bilang jujur, apa Mama bisa nerima?” tanyaku bagai ke diri sendiri.
“Coba kamu kasih tau Mamamu dulu soal perselingkuhan itu,” kata Gian. “Kasih tau dulu pelan-pelan.”
Awalnya, aku ingin memendam sendiri aib Papa yang selama ini kuketahui, kupikir Mama tidak perlu tahu, karena Papa sudah tiada dan tidak ada alasan lagi bagiku untuk mengungkit hal memalukan tersebut.
Tapi setelah mendengar permintaan Gian, aku jadi bingung lagi, jadi bimbang apakah memang seharusnya Mama berhak tahu mengenai kelakuan buruk Papa atau tidak?
Aku dan Gian kemudian keluar setelah aku mengiyakan permintaan mereka.
“Nanti aku cerita ke Mama dulu,” kataku setelah kami keluar dari gedung yang mengurung Mbak Yanti di dalamnya. “Semoga mental Mama baik-baik aja,” lanjutku.
“Makasih.”
“Iya, sama-sama.”
“Aku lihat kamu tadi berantem pagi-pagi di sekolah,” kata Gian.
“Berantem?” tanyaku. “Oh, yang habis itu ditegur sama Pak Mulyadi?”
“Iya.”
“Habis mereka ngeselin,” kataku. “Pagi-pagi udah ngomongin orang. Pakai jelek-jelekin juga lagi.”
“Memang siapa yang diomongin? Sampai bikin kamu marah begitu?”
“Mereka ngomongin orang yang kusayang. Jadi, aku nggak terima,” jawabku. “Akhirnya, ya gitu deh, kita jadi berantem.”
“Siapa orangnya? Aku kenal?”
“Nggak penting kamu tau dia.”
“Kamu sesuka itu sama dia sampai dibela-belain buat berantem?”
“Iya,” jawabku. “Jangan cemburu.”
“Siapa yang cemburu? Aku?”
“Iya.”
“Aku nggak bakal cemburu.”
“Bagus deh,” kataku. “Kamu nggak perlu cemburu ke dia.”
“Aku nggak cemburu karena aku tau orangnya.”
“Kamu tau? Siapa?”
“Ada lah pokoknya. Aku kenal.”
“Siapa coba? Siapa orang yang kusayang sampai kubela-belain segitunya?” tanyaku. “Coba sekarang jawab.”
“Ciri-cirinya orang itu pasti juga sayang ke kamu.”
“Nah, bener. Siapa kira-kira?”
“Orang itu aku, kan?”
“Eh?” kataku terkejut. “Kok kamu bisa tau?”
“Kan, kubilang kalau aku lihat sendiri kamu berantem.”
“Kamu denger juga?”
“Iya.”
“Kamu denger nggak waktu mereka ngomongin kamu di toilet?”
“Di toilet mana?” tanya Gian. “Toilet perempuan, kan, pasti?”
“Iya,” jawabku. “Denger nggak?”
“Ya enggak lah, ngapain aku nguping di depan toilet perempuan?”
“Oh, syukur deh,” kataku. “Iya, tadi mereka itu jelek-jelekin kamu di toilet. Kebetulan aku juga ada di sana dan aku denger semuanya.”
“Makasih udah belain aku.”
“Iya. Sama-sama.”
Kami sampai di tempat Gian memarkir motornya.
“Habis ini mau ke mana? Mau langsung kuanter pulang? Atau ke mana dulu?” tanya Gian setelah aku duduk di atas motornya, sambil memakai helm yang dia sodorkan.
Tentu saja aku tidak mau langsung pulang dan berpisah lagi dengan Gian. Waktu ini harus bisa kumanfaatkan sebaik-baiknya.
Kubilang ke Gian bahwa aku haus karena cuaca sedang terik, jadi aku minta untuk mampir beli es krim sebelum pulang.
Setelah es krim sudah di tangan, kami duduk di ayunan yang ada di area taman kanak-kanak. Jalanan yang ada di depan kami cukup ramai, mengingat ini sudah hampir sore. Kutebak sebentar lagi pasti akan lebih ramai karena jam pulang kerja.
“Aku bela kamu karena aku sayang kamu, Gian,” kataku.
“Makasih.”
“Iya,” kataku. “Aku sendiri juga nggak terima denger mereka bilang yang enggak-enggak tentang kamu.”
“Kamu keren tadi.”
“He he he. Makasih.”
“Makanya, aku jadi kepikiran buat minta tolong ke kamu.”
“Minta tolong apa?”
“Ya yang tadi, minta tolong buat Ibu. Tolong bela Ibu di pengadilan seperti kamu yang tadi bela aku di depan Putri sama temen-temennya.”
“Kalau itu, aku masih ragu.”
“Ragu karena takut orang-orang di pengadilan nanti nggak percaya omonganmu?”
“Iya.”
“Kan, udah kubilang, nggak perlu ragu.”
“Apa Mbak Yanti sebelumnya nggak bilang kalau dia nggak membunuh?”
“Ibu udah bilang begitu.”
“Terus, apa kata mereka?”
“Jelas mereka nggak percaya,” jawab Gian. “Mereka pikir Ibu sengaja bohong karena nggak mau dipenjara.”
“Mereka aja nggak percaya sama omongan Mbak Yanti. Terus, kalau mereka nggak percaya omonganku juga gimana?”
“Tapi, Ibu sama kamu itu beda.”
“Apa bedanya?”
“Ibu tersangka sementara kamu saksi mata,” jawab Gian dengan pandangan lurus padaku seolah berusaha meyakinkan.
“Ah, iya, bener juga.”
“Makanya, tolong kasih kesaksianmu buat Ibu.”
“Tapi, aku udah bohong sebelumnya.”
“Bohong gimana?”
“Aku bohong waktu diminta keterangan sama polisi,” kujawab.
“Kamu bilang apa?”
“Aku bilang kalau aku nggak tau.”
“Oh, yang mereka dateng habis pemakaman Om Damar?”
“Iya, pas waktu itu.”
“Nggak apa-apa. Waktu itu aku ngerti. Kamu begitu karena masih sedih dan nggak mau bikin Mamamu tambah sedih. Tapi, sekarang kamu harus bilang yang sebenernya, demi anak yang dikandung Ibu.”
“Demi anak itu?”
“Iya.”
“Kenapa demi dia?”
“Aku cuma nggak mau dia nanti lahir di penjara.”
“Kamu sayang sama dia?”
“Mau dibilang nggak sayang, tapi mau gimanapun, aku kakaknya.”
“Aku juga kakaknya.”
“Makanya, tolong bantu Ibu demi adek kita, ya?”
“Oke deh. Aku bakal bantu sebisaku.”
Setelah es krim yang tadi dibeli sudah habis tak bersisa, Gian mengantarku pulang. Ketika sudah tiba di depan rumah, aku turun dari motor Gian dan mengembalikan helm yang dia bawa untukku.
Berat rasanya, membiarkan Gian juga pulang. Apalagi setelah habis ini aku harus cerita semuanya ke Mama.
Tapi aku juga tidak punya alasan untuk tetap menahan Gian agar bisa terus bersamaku hari ini. Jadi kubiarkan dia kembali melajukan motornya hingga menghilang dari pandanganku.
Segera kulangkahkan kakiku menuju rumah dan menemui Mama yang berada di ruang kerjanya ditemani segelas kopi.
“Mama, aku mau ngomong sebentar.”
“Ngomong apa?”
“Mama berhenti ngurusin kerjaan dulu sebentar, bisa?”
“Emang ada apa, sih?”
Mama masih saja fokus ke laptop yang ada di depannya. Memang seperti inilah Mama yang menolak diganggu ketika sedang bekerja.
“Bisa nggak, kalau Mbak Yanti nggak masuk penjara?” tanyaku ke Mama.
“Kamu ini bicara apa?” Mama justru balik tanya.
Aku memutar bola mata malas. Segera kuhampiri meja kerja Mama, lalu menutup laptopnya tanpa ijin.
Mama seperti hendak marah tapi ditahan. Dia memejamkan mata sebentar sambil menarik napas seperti berusaha untuk sabar.
Mama kemudian memutar kursinya sembilan puluh derajat ke kanan. Kepalanya mendongak dan menatapku sambil menyilangkan tangan.
“Ada apa?” tanya Mama dengan ekspresi jengah.
Lalu, aku menarik kursi dan duduk di hadapan Mama:
“Tolong, maafin Mbak Yanti. Jangan biarin dia masuk penjara.”
“Maksudmu apa maafin pembunuh Papamu itu?” tanya Mama dengan raut wajah yang mulai menunjukkan amarah. “Ada apa, sih, kamu tiba-tiba dateng ngomong begini ke Mama?”
“Aku nggak mau Mbak Yanti masuk penjara.”
Suaraku pelan tapi kurasa masih terdengar jelas oleh telinga Mama.
Mama kemudian melepas kacamata yang tadi dipakainya. Dia menatapku baik-baik sambil menahan rasa geram.
“Apa alasannya?” Mama bertanya ke aku dengan nada yang mengintimidasi dan tentu membuat nyaliku menciut.
“Mbak Yanti nggak salah,” jawabku takut-takut karena merasa itu akan membuat Mama marah, jadi kutundukkan kepalaku ketika bilang begitu.
“Dari mana kamu tau kalau dia nggak salah?” tanya Mama.
“Aku juga ada di sana waktu Mbak Yanti sama Papa bertengkar,” jawabku. “Aku lihat sendiri kalau Mbak Yanti nggak dorong Papa dari tangga.”
“Maksudmu?” tanya Mama.
Lalu, kujelaskan pada Mama mengenai detil yang kusaksikan pada hari itu. Kuberitahu mengenai aku yang melihat sendiri Papa dan Mbak Yanti bertengkar hingga Papa meninggal karena tidak sengaja jatuh dari tangga.
Mama tentu terperangah mendengar penjelasan dariku, bahkan sepertinya sampai membuatnya tidak bisa berkata-kata, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan.
“Jadi, begitu ceritanya, Ma. Mbak Yanti sama sekali nggak dorong Papa sampai jatuh.”
“Jadi, Papa bukan dibunuh sama dia?” tanyanya, mentapaku serius karena ingin tahu.
Aku mengangguk sebagai jawaban, sambil berharap semoga Mama percaya dengan omonganku barusan.
Mama kemudian bertanya:
“Tapi, kenapa dari rekaman CCTV kelihatan kalau Papa didorong sampai jatuh?”
“Mereka lagi rebutan hp,” jawabku. “Apa Mama waktu itu inget kalau Mbak Yanti sempet nelepon Mama sebelum Mama dapet kabar kalau Papa meninggal?”
“Ah, iya, Mama inget!” seru Mama.
“Nah, waktu itu Papa nggak mau Mbak Yanti nelepon Mama. Mereka rebutan hp, terus Papa jatuh, tapi di CCTV malah kelihatan kalau Mbak Yanti dorong Papa,” kataku ke Mama. Kuharap setelah ini aku bisa mematahkan tuduhan Mama yang menganggap Mbak Yanti sebagai seorang pembunuh.
“Mama inget, waktu itu kayaknya ada yang mau dia omongin ke Mama,” kata Mama.
“Iya, bener, Ma,” kataku.
“Kira-kira kamu tau apa yang mau dia omongin ke Mama waktu itu?” tanya Mama penuh rasa penasaran.
Setelah memantapkan hati, aku berdiri dari kursi yang semula kududuki, lalu berjalan keluar dari ruangan Mama. Langkah kakiku menuju kamar pribadiku untuk mengambil laptop yang ada di dalam sana. Di laptop itu, terdapat rekaman kamera tersembunyi yang pernah kupasang di penjuru rumah, yaitu kamera yang kugunakan untuk memantau perbuatan Papa dan Mbak Yanti ketika mereka selingkuh di belakang Mama.
Kubawa laptop itu kembali ke ruang kerja Mama, lalu mengganti laptop kerja Mama dengan laptop milikku di atas meja, kemudian kunyalakan laptop itu, kubuka salah satu video yang berisi rekaman perbuatan biadab Papa dengan Mbak Yanti, kuminta Mama untuk menonton, sambil kujelaskan ke Mama mengenai sesuatu yang kini sedang dilihatnya. Sebulir air mata turun membasahi Pipi Mama, membuat hatiku ikut teriris melihatnya.
Memang kejam membiarkan Mama baru mengetahui hal tersebut setelah berlalu puluhan hari lamanya.
“Aku sebenernya dari dulu mau ngasih tau Mama tentang ini.”
“Terus, kenapa baru sekarang?”
“Papa yang ngelarang buat jangan ngasih tau Mama.”
“Astaga, Nak …”
“Aku minta maaf, Ma,” kataku. “Aku sekarang juga jadi nyesel karena dulu nyembunyiin itu dari Mama.”
“Astaga, Tuhan …”
“Maafin aku, Ma.”
“Terus? Habis itu gimana? Apa hubungannya sama kematian Papa?”
“Mbak Yanti hamil.”
“Hamil?”
“Iya, Mbak Yanti hamil anaknya Papa,” jawabku.
“Astaga … Ya Tuhan …”
“Tapi, Papa nggak mau tanggung jawab dan bilang kalau itu bukan anaknya.”
Kulihat tubuh Mama semakin merosot lemas, tenaganya seperti langsung tersedot habis.
“Mama nggak nyangka. Mama bener-bener nggak nyangka Papamu sebenernya begini di belakang Mama.”
“Aku juga sedih waktu tau Papa selingkuh.”
“Jadi, gara-gara itu mereka bertengkar di deket tangga?”
Sebelum melanjutkan, aku mengambil segelas air putih dari dispenser yang ada di ruangan ini untuk membantu membuat Mama sedikit lebih tenang.
“Iya, mereka bertengkar karena Papa malah nyuruh buat gugurin,” jawabku sambil memandang ke Mama.
“Terus?”
“Mbak Yanti ngancem mau lapor ke Mama karena Papa tetep kekeuh buat nyuruh gugurin dan nggak mau tanggung jawab.”
Mama masih dapat mencerna semua penjelasanku dengan baik walau pasti memiliki pikiran yang sedang sangat berantakan.
“Jadi, waktu dia telepon Mama itu gara-gara mau lapor perbuatan Papa? Iya?”
“Iya, Ma.”
“Jadi, yang sebenernya terjadi begitu?”
“Iya, aku saksinya.”
*****
Setelah aku menceritakan semuanya, Mama kemudian keluar ruangan dan berjalan menuju kamar utama, lalu masuk dan menutup pintu. Wajahnya masih sembab karena terlalu banyak mengeluarkan air mata sejak tadi.
Aku juga keluar sambil membawa kembali laptopku, melewati kamar utama dan menuju kamarku sendiri. Hatiku rasanya masih sakit melihat Mama menangis, apalagi tangisan itu disebabkan oleh pengkhianatan suaminya, oleh laki-laki yang dicintai Mama, oleh laki-laki yang telah membersamai kehidupan Mama dalam waktu yang tidak sebentar.
Setelah meletakkan laptop di tempatnya semula, aku merebahkan diri ke atas tempat tidur. Biasanya aku sudah mandi pada jam segini tapi sekarang rasanya belum ingin melakukan apa-apa selain berbaring sambil menata pikiran.
Ketika memejamkan mata, aku kembali teringat percakapan dengan Gian waktu makan es krim di ayunan tadi:
“Tawaranmu buat tinggal berdua di Inggris itu gimana?”
“Tinggal berdua di Inggris, ya?” tanya Gian bagai sedang bicara pada dirinya sendiri. “Memangnya sekarang kamu setuju? Kamu mau?”
“Masih nggak tau. Aku belum nemu jawabannya,” jawabku. “Kamu sendiri jadi nerima kesempatan itu?”
Gian tidak langsung menjawab. Dia diam sebentar sambil menghela napas lelah.
“Aku juga bingung sekarang,” jawab Gian.
“Bingung kenapa?”
“Dulu, aku nerima kesempatan itu tanpa pikir panjang,” jawab Gian. “Aku terima karena waktu itu lagi kecewa sama Ibu dan pengen putus hubungan gara-gara tau Ibu selingkuh sama suami orang.”
“Terus?”
“Nah, sekarang malah ragu.”
“Ragu kenapa?”
“Lihat aja kondisi keluargaku yang sekarang,” kata Gian yang justru memberikan jawaban ambigu.
“Maksudnya?”
“Ibu sekarang ditahan gara-gara dianggep sebagai pelaku pembunuhan. Dia juga lagi hamil. Mau sekecewa apapun, rasanya aku nggak tega ninggalin Ibu.”
“Iya, sih, aku juga ngerasain itu kemarin. Mau sekecewa apapun ke Papa, aku tetep nggak rela waktu Papa meninggal.”
“Apalagi Ibu juga udah nggak punya suami,” kata Gian. “Setidaknya aku harus bisa berguna sebagai anak laki-laki, bukan malah kabur ninggalin dia.”
“Tapi, kamu udah pernah nolak kesempatan kayak gini sebelumnya.”
“Iya, ya?”
“Masa mau ditolak lagi? Lagian, belum tentu kesempatan bagus begini bakal dateng berkali-kali.”
“Aku pikir-pikir lagi nanti.”
“Apapun keputusanmu, semoga itu yang terbaik.”
Jika dipikirkan kembali, memang sulit berada di posisi Gian yang harus memilih antara mengejar masa depan atau tetap bertahan demi keluarga, maka dari itu aku akan berusaha membantunya dengan minta ke Mama untuk memaafkan Mbak Yanti agar Gian bisa tenang mengejar impiannya di negeri orang.
*****
Hidup berdua dengan Gian di Inggris, ya?
Aku senang waktu pertama kali mendengar ajakan dari Gian itu, seperti memberiku sebuah petunjuk bahwa Gian benar-benar serius padaku, tapi tentu pada waktu itu tidak langsung kuiyakan karena menyangkut berbagai hal sehingga perlu kupikirkan secara matang.
Sekarang, semuanya jadi semakin rumit begini.
Entah keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Gian. Kuharap semuanya akan berjalan baik untuk dia. Kuharap dia tidak bertindak bodoh lagi dengan membuang kesempatan yang datang padanya. Setelah kesempatan pertamanya hilang akibat alasan konyolnya yang tidak ingin jauh dariku, kuharap kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kuharap Inggris bisa menjadi jawaban untuk cita-cita Gian.
*****
Esok paginya, gosip tidak menyenangkan kembali menyapa telingaku ketika sampai di sekolah. Hampir semua murid membicarakan hal yang sama, yaitu tentang Gian yang merupakan anak dari seorang pembunuh.
Kejadian antara aku dan Putri bersama teman-temannya kemarin sepertinya tidak memberi efek apapun.
Di sekolah, semua orang terus menerus membicarakan Mbak Yanti dan mengucilkan Gian seolah dia juga ikut melakukan kesalahan yang besar sehingga pantas disingkirkan dari kehidupan sosial.
*****
Gian kurasa jadi pribadi yang lebih pendiam, meski memang dia aslinya tidak banyak omong, tapi Gian biasanya masih berbaur dengan murid laki-laki lain, bahkan saat istirahat dia akan selalu bersama teman-temannya entah main basket di lapangan atau nongkrong di kantin, sementara sekarang dia seperti menjauh dari mereka.
Seperti saat ini misalnya. Di kantin, Gian duduk sendirian, makan bakso yang dibelinya dan duduk di meja paling ujung, sambil memasang earphone yang kini menutupi gendang telinganya, sementara kedua matanya hanya fokus pada makanan di atas meja, sama sekali tidak peduli dengan murid-murid lain yang membicarakannya dari jauh, mungkin ini adalah salah satu cara dia menenangkan diri sendiri agar tidak tersulut oleh gunjingan orang lain.
Ingin rasanya kusumpal mulut mereka semua, agar berhenti membicarakan yang tidak-tidak soal Gian, agar berhenti membuat Gian merasa kesepian karena dijauhi oleh semua orang. Tapi, aku takut jika melakukan keributan lagi, Mama nantinya akan dipanggil ke sekolah.
Yang bisa kulakukan sekarang hanya memandang Gian dari jarak jauh. Ketika hendak mengajaknya bicara, dia masih selalu menghindar. Saat kutanya melalui pesan teks, Gian bilang bahwa dia sengaja menghindar bukan karena marah, melainkan agar aku tidak ikut dikucilkan, tidak ikut digunjingkan oleh orang lain, walau aku sebenarnya sama sekali tidak peduli soal itu, tapi Gian minta aku untuk jaga jarak dulu darinya sementara ini, setidaknya sampai semua kerumitan ini selesai.
*****
Setelah bel pulang sekolah berbunyi, kulihat Gian bangun dari posisi tidurnya dan segera mengemasi buku ke dalam tas. Ketika kelas sudah mulai agak sepi, barulah dia keluar, sepertinya menuju parkiran sekolah, guna mengambil motornya lalu pulang ke rumah. Tapi, Gian justru diseret oleh beberapa anak laki-laki ke belakang sekolah ketika dia sampai di parkiran. Mereka semua yang menyeret Gian sepertinya berasal dari sekolah lain karena seragam kami berbeda.
Saat mengintip dari balik tembok, kudapati Gian justru sedang adu jotos dengan lima murid laki-laki itu di mana salah satu dari mereka adalah pacar Putri yang marah karena menganggap Gian adalah penyebab Putri harus mendapat hukuman dari pihak sekolah.
Gian itu tidak pernah belajar teknik bela diri sama sekali. Tapi dia tetap seorang laki-laki yang mampu melindungi diri sendiri. Dia masih bisa bertahan setelah beberapa kali menerima serangan dari arah yang berbeda-beda. Sesaat aku dibuat salut dan kagum, karena Gian tampak betul-betul keren walau teknik yang dia gunakan itu ngawur dan asal-asalan.
Beberapa menit berlalu dan tidak ada yang datang melerai karena sekarang sekolah sudah benar-benar sepi. Mereka terus adu pukulan, tentu saja tidak seimbang karena Gian harus melawan mereka berlima.
Gian kemudian jatuh setelah kulihat dia sepertinya sudah kelelahan. Wajahnya penuh dengan peluh dan luka lebam di sana-sini. Para pecundang itu, murid laki-laki yang merundung Gian itu, kini mereka kompak tertawa karena berhasil membuat Gian tumbang, berhasil membuat Gian tidak bisa berkutik lagi karena badannya ditahan oleh salah satu dari mereka.
Dalam situasi seperti itu tentu aku sudah tidak bisa terus-terusan diam. Segera kuambil ponsel yang ada dalam saku. Sambil melangkah maju menghampiri mereka, aku menempelkan ponsel ke telinga dan pura-pura menelepon.
“Pak Mulyadi, ada kasus perundungan di belakang sekolah,” kataku dengan suara sedikit keras. Begitu mendengar suaraku, mereka semua langsung berhenti memukuli Gian. Pandangan mereka yang garang sontak beralih padaku, tapi itu sama sekali tidak membuatku takut. Tidak ada yang perlu kutakuti dari para pecundang seperti mereka. Aku tahu, mereka itu beraninya cuma dengan keroyokan seperti ini.
“Awas lu!” kata salah satu dari mereka ke Gian. Tarikan di kerah baju Gian pun dilepas. Mereka kompak bubar sambil menyampirkan tas masing-masing yang semula tergeletak di tanah. Sementara Gian segera kubantu untuk duduk.
“Ngapain masih di sini?”
“Jangan nanya-nanya dulu. Aku bantu kamu ke UKS,” kataku sambil berusaha membantunya berdiri.
Gian menurut, dia terus mengikutiku sampai tiba di UKS. Segera kusuruh dia duduk sementara aku mencari obat merah di kotak P3K.
“Biar kuobatin sendiri,” kata Gian.
“Diem deh.”
“Kamu mending buruan pulang.”
Tidak kuhiraukan perkataannya. Tanganku bergerak dengan hati-hati membubuhkan obat merah di wajah Gian.
“Aku bisa ngobatin sendiri,” kata Gian lagi sambil hendak mengambil alih obat merah di tanganku, tapi segera kutepis.
Kuminta tangannya untuk menyingkir, agar tidak mengganggu pergerakanku yang hendak membubuhkan obat merah.
“Siniin obatnya,” kata Gian bersikukuh.
Aku mendecak kesal dan kutatap dia.
“Ya udah. Pelan-pelan,” katanya kemudian.
Aku mengangguk dan kembali mengobati luka di wajah Gian. Setelah selesai lalu kutiup luka di bagian pelipisnya pelan-pelan. Sementara Gian hanya menunduk dan tidak menolak semua perlakuanku.
Aku bangkit dari dudukku ketika telah selesai mengobati Gian, mengembalikan obat yang tadi kuambil ke tempatnya semula, kemudian duduk lagi di dekat Gian. Kami saling diam dan suasananya jadi benar-benar canggung.
Aku pun memutuskan untuk angkat bicara sambil berdiri di depannya setelah beberapa detik kami terus diam: “Aku pulang duluan.” Kemudian kulangkahkan kakiku keluar dari ruang UKS setelah tidak mendapat respons apapun dari Gian.
Di luar ternyata hujan deras.
Suasana sekolah sudah sangat sepi. Sialnya, aku tidak bawa payung atau jaket atau benda lain yang bisa melindungiku dari guyuran hujan, jadi aku masuk ke dalam UKS lagi dan duduk bersebelahan dengan Gian yang masih di dalam.
*****
Sebenarnya, meski hujan, aku masih bisa pulang sekarang juga. Toh, sopir yang menjemputku sudah menungguku keluar gerbang sekolah sejak tadi. Namun, aku sengaja masuk lagi ke dalam UKS karena ingin memanfaatkan hujan agar bisa berduaan dengan Gian. Sopir yang menunggu di depan sudah kuberitahu bahwa aku akan keluar, tapi nanti ketika hujan sudah reda. Untuk sekarang, aku masih mau berada di UKS karena ada Gian di sini.
Suasana di antara kami hening selama beberapa saat, benar-benar terasa canggung karena kami memang hampir tidak pernah ngobrol belakangan ini.
“Kenapa masuk lagi?” tanya Gian.
“Di luar hujan,” jawabku dengan perasaan antusias karena Gian akhirnya membuka mulut untuk memecah kesunyian. Aku senang karena Gian mau mengajakku ngobrol lagi.
“Padahal, di perkiraan cuaca katanya nggak bakal hujan. Kenapa tiba-tiba malah hujan?” kata Gian bagai bertanya pada dirinya sendiri. “Mana nggak bawa jas hujan lagi,” kata Gian sambil mendesah pasrah.
“Ya udah, tunggu sini aja dulu sampai hujannya reda,” kataku ke Gian dengan maksud agar dia tetap di sini dan tidak nekat menerobos hujan.
“Padahal, tadi nggak mendung,” kata Gian.
“Iya, ya?” kataku setuju.
“Kamu nggak pulang?” tanya Gian sambil menoleh ke aku.
“Kan, masih hujan,” kujawab.
“Memangnya nggak ada yang jemput?”
Aku diam sebentar.
“Ada, sih, tapi tetep aja nanti sampai mobil juga basah,” jawabku.
“Kalau gitu, pakai baju seragamku aja. Pakai buat nutupin kepalamu sambil jalan keluar. Di sini juga kayaknya nggak ada payung.”
Gian kemudian melepas satu demi satu kancing baju seragamnya. Setelah terlepas semua, dia sodorkan baju atasan seragam putihnya itu ke aku, membuatnya kini hanya memakai dalaman kaos putih polos yang pasti tidak cukup menghalau hawa dingin.
“Terus, kamu sendiri gimana? Mau di sini sendirian? Cuma pakai kaos itu? Yakin nggak bakal kedinginan?”
Gian menggeleng. Dia kemudian melipat tangannya di depan dada dengan posisi duduk ditegakkan seperti sok terlihat tangguh.
“Tuh, bulu-bulu di tanganmu pada berdiri semua,” kataku sambil melihat Gian.
Gian tidak merespons. Dia kemudian berdiri dari kursi yang tadi didudukinya. Langkah kakinya berjalan santai mondar-mandir di dalam ruang UKS. Kentara sekali bahwa dia sedang ingin menghalau dingin dengan banyak menggerakkan badan.
“Kamu tuh ngapain? Duduk aja kenapa, sih? Nggak usah jalan mondar-mandir begitu. Kepalaku jadi pusing lihatnya,” kataku.
“Galaknya,” kata Gian pelan tapi tetap menuruti omonganku dan kembali duduk di kursinya semula.
“Udah, duduk diem aja sini.”
Kami saling diam lagi.
“Perubahan cuaca yang nggak menentu kayak gini itu gara-gara temperatur bumi meningkat. Temperatur bumi bisa meningkat juga bukan tanpa alasan. Temperatur bumi meningkat ya karena ada dampak dari pemanasan global. Selain cuaca yang nggak menentu, dampak pemanasan global juga macem-macem. Mencairnya es di kutub, air laut semakin meningkat, perubahan iklim, kebakaran hutan, pokoknya banyak.”
Kulihat Gian diam mendengarkan.
Dari ekspresinya aku tidak dapat menebak mengenai apa yang sedang dia pikirkan. Entah dia paham atau tidak tentang penjelasanku tadi.
“Pemanasan global artinya apa?” tanya Gian dengan wajah super polos dan lugu.
“Kamu nggak tau?”
Gian kemudian diam, entah sedang berusaha mengingat-ingat atau memang tidak tahu sama sekali sehingga enggan menjawab.
“Nih, pakai aja bajumu,” kataku sambil menyodorkan kembali baju seragam Gian setelah dia terus diam dan tidak kunjung menjawab.
“Kenapa dibalikin?
“Bilang aja kalau kedinginan.”
“Enggak. Siapa bilang aku lagi kedinginan? Udah, bawa aja. Pakai itu buat ke depan.”
“Ya udah kalau nggak kedinginan.”
Aku tarik lagi tanganku yang semula menyodorkan baju seragam sekolah Gian, kemudian memakaikannya di tubuhku.
Sejujurnya, aku senang bisa memakai seragam sekolah Gian di tubuhku. Wanginya benar-benar khas Gian sekali. Meski tadi sempat bertengkar dengan anak lain sampai berkeringat, meski sudah dipakai selama berjam-jam, tapi baju seragam Gian sama sekali tidak bau apek, justru wangi parfumnya masih bisa tercium.
Lalu kulihat lagi Gian yang kini tampak sedikit pucat.
“Kamu nggak enak badan?” tanyaku.
“Aku baik-baik aja,” jawab Gian yang kini terlihat kebingungan setelah mendengar pertanyaan dariku.
Aku kemudian menggeser tubuhku agar bisa duduk lebih dekat dengan Gian, lalu kutempelkan punggung tanganku di depan keningnya.
“Kamu demam?”
Rasa khawatirku meningkat setelah merasakan suhu tubuh Gian.
“Masa, sih?” tanya Gian. “Tapi aku nggak ngerasa kalau lagi sakit.”
“Nih, pakai lagi bajumu,” kataku sambil kembali menyodorkan seragam Gian.
“Buat kamu aja orang aku nggak demam,” katanya menolak.
“Nggak usah sok keren deh.”
“Aku nggak sakit, pakai kamu aja bajunya,” kata Gian tetap bersikukuh, melempar pelan seragamnya ke pangkuanku, membuat bajunya kini jadi lecek.
Aku berdecak kesal.
“Belum sempet kena hujan aja kamu udah demam?”
“Aku nggak kenapa-kenapa, Ra.”
“Ini pasti kamu kurang makan sayur, jadi imun tubuhmu nggak kuat.”
“Nah, kan, marah-marah lagi,” kata Gian, lalu mengambil seragamnya dengan gerakan ogah-ogahan. Bukannya dipakai, dia justru hanya menyampirkan seragamnya di atas bahu.
“Orang tadi kusuruh buat pakai,” kataku sambil merebut seragamnya, kemudian berusaha memakaikannya pada tubuh Gian. “Kamu kenapa nggak mau dengerin omonganku, sih?” kataku lagi ketika Gian tetap bersikukuh tidak mau memakainya kembali.
“Orang dibilingain kalau aku nggak sakit.”
Gian terus menolak. Sementara aku terus berusaha agar dia mau memakai seragamnya. Tanpa sadar, kami jadi ribut sendiri di dalam UKS. Gerakan tanganku yang berusaha memakaikan seragam ke Gian membuat jarak wajah kami jadi sangat dekat.
Aku dan Gian sama-sama terdiam dan terpaku dengan tatapan masing-masing.
“Mau tetep berdua di sini sampai hujannya reda?”
Pertanyaan Gian barusan tidak bisa kujawab. Napasku seperti terhenti ketika Gian semakin mengikis jarak.


 nakum18
nakum18