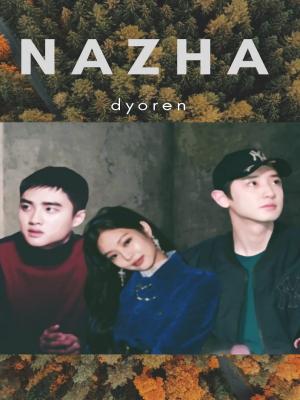Hari ini Senin, aku biasanya berangkat lebih pagi, karena ada jadwal rutin upacara bendera, murid-murid disarankan untuk datang lebih awal dari hari-hari yang lain. Hal itu tentu membuatku harus bangun lebih pagi. Apalagi sekarang tidak ada Mbak Yanti yang akan membantu mengurus keperluanku. Jadi, semua peralatan sekolah selalu kusiapkan sendiri malam sebelum tidur agar besoknya tidak keteteran.
Tapi, saat sudah selesai siap-siap, Gian tidak dapat kuhubungi, bahkan dari semalam, atau lebih tepatnya sejak kami habis dari taman bermain kemarin. Pesan dariku tidak ada yang dibalas, dibaca saja tidak.
Karena waktunya sudah mepet, terpaksa aku berangkat sendiri, dengan rasa kesal karena Gian tiba-tiba mengabaikanku begini. Ketika tiba waktunya melaksanakan upacara bendera, pandanganku mengedar untuk mencari keberadaan Gian yang seharusnya satu barisan denganku. Tapi Gian tidak terlihat di mana pun entah karena telat atau memang sengaja tidak masuk sekolah.
Ternyata Gian lagi-lagi bolos. Tapi Gian tidak biasanya mengabaikan pesanku begini hingga membuatku harus bertanya ke salah satu kawannya yang bernama Samudra:
“Sam, tau nggak Gian hari ini ke mana? Dari kemarin chat dari gue masih nggak dibales juga sama dia.”
“Nggak tau gue. Lagi mencret kali,” jawab Samudra.
“Oh, ya udah deh. Makasih,” kataku dengan nada lesu, kemudian berlalu dari meja kantin yang ditempati oleh Samudra bersama gerombolannya. Mereka kembali asik makan sambil mengangkat kaki ke atas kursi dan ngobrol dengan suara keras.
Aku kembali ke meja yang ditempati Sita. Kulihat dia terus menatap layar ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Kuyakin, pasti dia sedang mengagumi mantan kakak kelas kami yang disukainya sejak beberapa bulan lalu.
Sita baru mengalihkan pandangan saat makanannya sudah datang. Melihatku hanya diam dan tidak pesan makan, dia kemudian bertanya padaku ada apa? Lalu kuceritakan ke Sita perihal Gian. Kuceritakan padanya soal Gian yang mendadak tidak bisa dihubungi setelah kami menghabiskan waktu di taman bermain saat akhir pekan kemarin.
Sita mendengarkan keluh kesahku sambil tetap makan. Dia kemudian diam setelah aku selesai cerita. Pandangannya menerawang ke atas seperti sedang memikirkan sesuatu.
Sita kemudian memberitahuku bahwa mungkin aku sempat membuat Gian sakit hati saat di taman bermain. Katanya, mungkin aku tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang membuat Gian kecewa tanpa kusadari.
Aku jadi diam dan ganti menerawang ke atas setelah mendengar perkataan Sita. Tapi seingatku kami hanya mencoba banyak wahana dan aku sama sekali tidak pernah bicara sembarangan sampai melukai hatinya Gian.
Aku beralih menatap Sita lagi dengan pandangan bingung:
“Kayaknya bukan itu alasannya. Kemarin itu aku sama Gian cuma main, ketawa-ketawa, terus pulang.”
Sita minta aku untuk mengingat-ingat lagi. Dia bilang bahwa mungkin saja aku membuat Gian kecewa lewat perbuatan yang kulakukan.
Aku kemudian ingat dengan tingkahku yang sama sekali tidak mau memegang kamera yang dibawa Gian kemarin. Gian sudah berulang kali minta untuk gantian tapi aku tetap iseng menolak permintaannya sampai kami pulang.
Apa memang benar gara-gara hal sepele itu?
“Kemarin Gian bawa kamera dan minta buat gantian megangnya, tapi aku nggak mau. Masa, sih, cuma gara-gara itu?”
Sita bilang tidak mungkin Gian bisa marah cuma karena itu, pasti ada hal lain, tapi setelah kuingat-ingat, aku dan Gian masih baik-baik saja ketika pulang dari taman bermain. Sita kemudian minta aku untuk langsung menemui Gian saja di rumahnya. Katanya agar semuanya jelas dan tidak membuatku bertanya-tanya sendiri begini.
Aku berencana ke rumah Gian setelah pulang sekolah. Jadi aku pulang dulu untuk ganti pakaian. Mulai hari ini, Mama mengajakku untuk tinggal kembali di rumah, karena seluruh perabotan rumah kami sudah selesai diganti dengan yang baru agar tidak terus-terusan merasa sedih karena ingat kenangan bersama Papa. Aku sebenarnya belum siap karena pasti akan ingat mengenai kematian Papa ketika melihat tangga rumah kami. Tapi, aku dan Mama juga tidak bisa selamanya tinggal di hotel.
Saat pulang ke rumah, polisi kembali datang menemuiku dan Mama untuk memberitahu kami mengenai perkembangan dari kasus kematian Papa. Mereka mengumumkan tersangka pembunuhan Papa yang seketika membuat Mama terkejut:
“Yanti Widati?”
“Benar.”
“Atas dasar apa?”
“Hal itu berdasarkan pemeriksaan CCTV dan keterangan para saksi. Kami kemudian menetapkan Saudara Yanti Widati sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang dialami Saudara Damar.”
“Apa yang dia lakuin ke suami saya?”
“Dugaan sementara saudara Yanti mendorong korban dari lantai dua.”
“Dia yang dorong Mas Damar?”
“Benar.”
“Astaga Ya Tuhan!”
“Saya dengar tersangka juga bekerja di rumah ini?”
“Iya, benar.”
“Kalau begitu, apakah Anda tahu kira-kira motif apa yang mendorong tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban?”
“Saya juga tidak tau, Pak.”
“Karena berdasarkan bukti CCTV yang kami temukan, tersangka dan korban sepertinya sempat terlibat cekcok di dekat tangga.”
Polisi yang datang kemudian memperlihatkan rekaman CCTV kepada aku dan Mama, dan di sana tampak jelas sekali keberadaan Papa dan Mbak Yanti yang sedang adu mulut, sebelum kemudian Papa terjatuh dari tangga, persis seperti apa yang kulihat sebelum kematian Papa. Semuanya terekam jelas dari rekaman CCTV tersebut.
“Kami akan melanjutkan pencarian terhadap tersangka. Perkembangan selanjutnya akan terus kami infokan. Terima kasih.”
Setelah itu, para polisi yang mendatangi kami pamit, kuantar mereka sampai keluar dari rumah, sementara Mama masih terdiam di tempatnya, tampak syok sekaligus tidak percaya terhadap fakta yang baru saja dia terima.
Aku yang sudah menduga hal ini jadi tidak tahu harus bagaimana sekarang, karena aku betul-betul bingung dan tidak terpikir cara apapun untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Mbak Yanti juga pasti tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
Yang bisa kulakukan sekarang hanya berusaha menenangkan Mama yang masih syok di tempat duduknya.
Kudengar Mama kemudian menggumam:
“Apa yang aku nggak tau?”
Aku yang mendengar itu hanya bisa diam.
Mama bisa tambah syok jika kuberitahu mengenai semua alasan di balik pertengkaran Papa dengan Mbak Yanti hari itu.
Lebih baik aku ke rumah Gian sekarang untuk memberitahunya mengenai berita ini.
“Ma, aku keluar.”
Aku segera pergi tanpa menunggu persetujuan dari Mama. Beberapa kali kucoba hubungi Gian, tapi hasilnya nihil, dia masih belum bisa dihubungi, tapi semoga dia ada di rumahnya sekarang, karena aku betul-betul ingin bertemu.
Syukurlah, Gian ada, jadi aku segera mengajaknya untuk bicara di teras, agar pembicaraan kami nanti tidak didengar oleh nenek Gian.
“Kalau kamu mau ngasih tau tentang Ibu yang jadi tersangka pembunuhan Papamu, aku udah tau. Nenek juga udah tau.”
Kedua mataku sontak terbelalak, terkejut mendengar penuturan Gian.
“Kalian udah tau? Dari siapa?” tanyaku.
“Kemarin sore sama tadi pagi polisi ke sini, nyari Ibu lagi,” jawab Gian.
“Apa gara-gara ini kamu jadi bolos? Iya?” tanyaku.
“Iya,” jawab Gian.
“Terus, kenapa kamu nggak bisa dihubungin sama sekali? Kenapa kamu juga nggak cerita ke aku?” tanyaku.
Gian diam sebentar.
“Aku nggak sanggup,” jawab Gian.
“Maksudnya?” tanyaku.
“Aku nggak sanggup ketemu kamu,” jawab Gian.
“Kenapa?” tanyaku.
“Karena aku anak dari perempuan yang sudah berusaha merebut Papa kamu.”
“Jangan ngomong begitu.”
“Aku anak pembunuh yang membunuh Papa kamu.”
“Gian …”
“Aku terlalu malu buat ketemu kamu, Haira,” kata Gian.
“Gi, jangan begini.”
“Aku juga merasa nggak pantes jadi pacar kamu.”
“Kamu jangan mikir begitu.”
“Aku merasa buruk buat kamu, Haira,” kata Gian.
“Gian, dengerin aku.”
Ketika mengangkat wajahnya yang semula menunduk, dapat kulihat Gian yang seperti berusaha menahan tangis.
“Aku selalu lihat kamu sebagai pacarku,” kataku menatap lurus ke Gian, berusaha membuat Gian percaya dengan perkataanku barusan.
“Aku bukan pacar yang baik buat kamu,” kata Gian dengan suara pelan. Raut wajahnya sendu ketika bilang begitu.
Aku segera menggelengkan kepala. Kugeser sedikit kursi yang kududuki agar lebih dekat dengan Gian.
“Aku nggak peduli kamu ini anaknya siapa, yang kutahu ya kamu itu pacarku, Gian,” kataku kemudian.
Sebisa mungkin aku berusaha bicara dengan intonasi lembut, berusaha mengusir perasaan bersalah yang dirasakan Gian.
“Kenapa kamu nggak marah?” tanya Gian. “Setelah semuanya jadi begini, kenapa kamu nggak marah?”
“Aku marah,” jawabku. “Tapi, aku marahnya cuma ke Papa sama Mbak Yanti, bukan marah ke kamu.”
“Harusnya kamu juga marah ke aku,” kata Gian. “Aku anak pembunuh.”
“Kamu bukan anak pembunuh, Gi.”
“Realitanya begitu,” kata Gian dengan suara lebih pelan dan kepala yang semakin menunduk dalam.
“Mbak Yanti memang salah, tapi aku tau dia bukan pembunuh,” kataku.
“Tapi, cuma kamu yang mikir begitu. Orang lain enggak,” kata Gian. “Polisi nganggep ibuku pembunuh. Keluargamu juga pasti mikir begitu. Semua orang nganggep ibuku pembunuh yang udah bunuh Papamu.”
Mendengar Gian bilang begitu, aku tidak tahu harus dengan cara apa aku bisa menenangkan Gian, aku tidak tahu harus dengan kalimat apa aku bisa membuat Gian berhenti menyebut dirinya sebagai anak dari seorang pembunuh, semuanya seolah sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
“Maaf,” kataku.
“Maaf buat apa?”
“Maaf karena nggak bisa bantu apapun,” kataku, merasa bersalah juga karena tidak bisa membantu membuktikan bahwa Mbak Yanti bukan pembunuh seperti apa yang dikatakan oleh para polisi itu.
“Memangnya kenapa kamu bisa mikir kalau ibuku bukan pembunuh? Bukannya kamu lihat sendiri kalau ibuku yang dorong Papamu dari tangga?” tanya Gian.
“Mbak Yanti nggak dorong Papa.”
“Kamu tau dari mana? Apa kamu lihat sendiri kejadian waktu itu? Atau ibuku udah cerita yang sebenernya terjadi ke kamu?”
“Aku lihat sendiri,” jawabku.
“Maksudnya? Kamu lihat sendiri mereka bertengkar dan Papamu jatuh bukan gara-gara didorong sama Ibu?” tanya Gian.
“Iya, aku lihat sendiri,” jawabku. “Aku juga ada di sana waktu itu.”
“Terus, kenapa kamu nggak bilang ke polisi?” tanya Gian. “Kenapa kamu nggak ngasih tau yang sebenernya ke mereka?”
“Kalau aku jelasin semuanya ke polisi, semua orang pasti jadi tau alasan mereka bertengkar itu karena Mbak Yanti hamil anaknya Papa. Mama juga pasti jadi tau. Aku cuma belum siap ngasih tau itu ke Mama karena nggak mau dia makin sedih habis ditinggal Papa.”
Gian kemudian diam, tapi di balik diamnya, kuharap dia mau mengerti, kuharap dia paham dengan alasan yang baru saja kukatakan.
Setelah hening selama beberapa menit, Gian kembali angkat bicara:
“Kepalaku rasanya penuh. Aku masuk dulu.”
“Kalau begitu, aku juga mau pulang,” kataku.
“Hati-hati.”
“Iya.”


 nakum18
nakum18