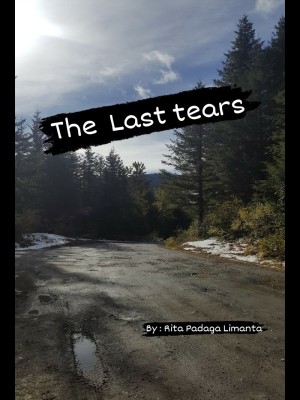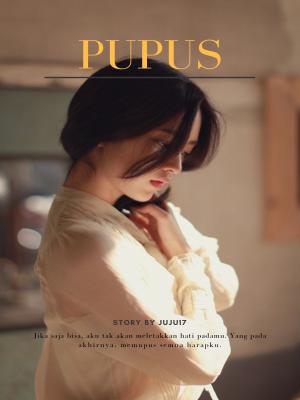Jum’at, 11 Desember. 20.16 WITA
“Happy birthday, Nanaaa! Rara mana?”
Mama memelukku sebentar dengan sebelah tangan, sementara tangan lainnya dengan teguh memegangi kue tart dengan lilin di atasnya. Ia kemudian segera beralih mendekati tempat tidur, pada saudari kembarku yang terduduk sambil mengucek mata. Keberisikan tadi rupanya telah membangunkan Laura.
“Raraaa~ Happy sweet seventeen, Sayang.”
“Ma, ini jam berapa coba? Ngantuk~” Rara, seperti biasa, justru mendorong Mama pelan di pundak. Tetapi ia tersenyum dan merapikan rambut. “Sok-sok ngasih kejutan. Habis liat di Tiktok, ya?”
Mama berdecak, tetapi tidak menyanggah. Ia menarikku mendekat, mendudukkanku di samping Laura.
“Selamat ulang tahun anak-anak Mama yang cantik. Sekarang, berdoa dan tiup lilinnya.”
Aku memejamkan mata. Dan ... aku mulai berdoa.
“Namaku Launa. Besok, 11 Desember, umurku genap 17 tahun. Permintaanku? Hanya satu. Aku ingin ... semua ini hanya mimpi. Aku ingin semuanya kembali seperti semula.”
Lilin ditiup, lalu padam seketika. Bukan olehku. Oleh angin yang berembus kencang dari jendela. Menarikku. Menarikku untuk terbang bersama mereka.
Tubuhku tersentak dan mataku terbuka seketika. Langit-langit putih dan lampu yang terang menyambutku, menyakitkan mata, membuatku secara otomatis memejam kembali dan mengerjap-ngerjap selama beberapa saat, coba beradaptasi dengan intensitas cahaya. Di saat nyaris bersamaan, aroma antiseptik dapat tercium olehku. Tidak salah lagi. Aku segera tahu aku sekarang di mana. Bukan rumah. Bukan kamarku yang hangat. Ini ruangan asing rumah sakit.
Aku bangkit duduk dengan seketika. Dengan seketika pula, merasakan nyeri di bagian belakang kepala, membuatku meringis. Aku memeriksa luka-luka di tangan dan kakiku, sudah diperban semua. Juga, ada perban di kening dan lengan yang aku tidak tahu penyebabnya.
Aku menurunkan kaki, membiarkan telapak kakiku menyentuh lantai yang dingin. Tempatku dirawat sekarang adalah sebuah ruangan yang cukup luas dengan enam buah tempat tidur. Sepi. Tempat tidur di depanku kosong dan tampak hampa. Tetapi, aku dapat mendengar suara pelan dari tempat tidur sebelah, bagian yang tersekat tirai di antara kami.
Kusentak tirai itu tanpa berpikir, berharap itu Laura, Kama, atau Ghea.
Namun harapanku tidak terkabul. Yang menyapaku adalah seorang ibu-ibu tua seumuran nenekku yang sedang menyuapi pria seusianya bubur. Mereka menatapku, sama canggungnya dengan aku yang menatap mereka. Aku lalu meringis meminta maaf dan kembali menutup tirai.
“Maaf, salah orang,” gumamku.
Tepat ketika aku membalikkan badan, terdengar suara langkah dari kamar mandi ruangan. Kepalaku seketika menengok ke arah sumber suara demi menemukan Papa sedang berjalan ke arahku.
“Kamu udah bangun?”
Tanpa sadar, aku menyentuh keningku, rasanya ngilu, terbukti dengan balutan kasa yang kudapati di sana. Anggota tubuh lainnya juga dipenuhi lecet, lebam dan perban di beberapa tempat. Tapi lebih dari itu, aku baik-baik saja.
Aku mengangguk pada Papa. “Mana Mama?”
“Nungguin Rara.”
Ah... rasanya, seakan aku ditarik kembali pada kenyataan. Mimpi yang kualami hanyalah mimpi. Dan kenyataan telah terjadi. Kecelakaan itu ... nyata, bukan bayanganku semata. Apakah ... Ulfi yang jatuh tertidur untuk selamanya di sampingku itu juga benar? Apakah gelang yang terputus dan tubuhnya yang bermandikan darah itu nyata?
Lalu Laura ... aku melihatnya, sekilas. Keadaannya sama buruknya.
Dengan dada berdebar, aku menatap Papa. “Gimana... keadaan Rara?”
Papa tidak segera memberikan jawaban. Ia balik menatapku, dan meskipun seandainya ia tidak mengatakan apa-apa setelahnya, aku segera tahu. Matanya bicara. Kedut kesedihan yang tidak bisa ia tutupi.
“Kritis,” kata Papa beberapa saat kemudian.
Seperti dugaan sedetik yang lalu. Tetap saja, rasanya ada tangan-tangan tak kasat mata meremas paru-paruku hingga sesak. Seolah mereka tidak membiarkanku hidup. Seolah mereka semua menyalahkanku.
Sebelum lamunanku larut kian jauh, Papa meletakkan telapak tangannya di pundakku, meremasnya pelan. “Berdoa aja biar Laura cepat bangun, biar dia selamat...”
Sekali lagi, aku mengangguk. “Yang lain?”
Dalam kediaman Papa yang belum menjawabku, aku berdoa keras-keras dalam hati. Semoga mereka selamat. Semoga mereka semua selamat. Kama, Ghea, Laura. Ulfi. Semoga semua orang baik-baik saja. Semoga semua ini hanya mimpi.
“Sama,” ujar Papa lirih. “Kamu yang mengalami kecelakaan paling ringan.”
Kalimat itu menusukku.
Tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram paru-paru, kini kian menjadi-jadi. Mereka meremas jantungku pula, hati dan semua yang ada padaku. Membuat seluruh tubuhku mati rasa. Membuat setiap persendianku terasa tercabik. Mereka menghancurkanku dari dalam.
Kenapa aku? Kenapa harus hanya aku?
Lalu, satu pertanyaan yang paling mengusikku, yang sejak bangun coba kuredam dalam-dalam ke bawah pikirannya, coba kulupakan akhirnya muncul kembali ke permukaan. Satu pertanyaan, satu kata yang membuat bibirku gemetar ketika mengucapkannya.
“... Ulfi?”
Aku masih ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi, hanya ilusi. Bahwa Ulfi tidak pergi, hanya berada di salah satu ruangan itu, tidak begitu baik tapi masih bernapas. Ya, ya, kuharap begitu. Papa, tolong katakan begitu.
Tapi Papa justru mengambil lebih banyak waktu untuk diam.
Jika sebelumnya aku sudah dapat menemukan kilatan sedih di mata Papa, maka sekarang aku melihat kesenduan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan kesenduan itu menular. Aku meremas pakaian Ghea yang kukenakan dan berteriak dalam hati.
Sekarang jangan katakan. Papa, tolong jangan katakan ...
“Jenazahnya sudah dibawa pulang ke rumah. Besok disemayamkan.”
Lututku lemas. Seluruh tubuhku ngilu. Saat ini, semua yang kuinginkan adalah menangis keras-keras, menjambak rambut dan berteriak sebisanya. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Tidak juga airmata. Aku hanya diam di sana, menyadari bahwa ... semua ini bukan mimpi.
Gelang itu benar-benar putus.
Dan darah Ulfi masih membekas di telapak tanganku.
***
Papa pamit beberapa waktu kemudian. Setelah memastikan aku baik-baik saja tanpa luka berarti, berkali-kali memintaku untuk tinggal di tempat tidur dan memanggilnya jika terjadi sesuatu, ia pun pergi. Ia harus memeriksa Mama dan Laura di UGD. Aku hanya mengangguk menandakan aku mengerti, aku melihat sosoknya menjauh.
Kenyataannya, aku tidak diam di tempat tidur seperti yang Papa inginkan. Sekali lagi aku berjalan, kali ini mengikuti jejak Papa untuk keluar ruangan. Aku tidak bisa diam saja atau aku akan gila. Meski aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kulakukan demi meredam rasa sakit ini? Rasa sakit yang tidak ada hubungannya dengan cedera fisikku. Rasa hampa seolah ada lubang menganga di dalam diriku.
Ruang UGD... aku tidak tahu dimana. Aku hanya berjalan pelan dengan seluruh tubuh yang amat letih dan sakit di tengah koridor, menoleh kanan kiri berharap menemukan sesuatu. Laura, Ghea, Kama, siapapun.
Lalu, tatapanku berhenti pada satu ruangan tidak begitu jauh dari ruanganku. Langkahku juga ikut terhenti. Di sisi kiriku terdapat sebuah ruangan dengan tempat tidur yang lebih sedikit, tempat itu terlihat lebih tertutup tetapi aku masih dapat menengok melalui kaca jendela.
Ghea terbaring di sana.
***
Ghea terbaring sendirian. Infus terpasang di tangannya, gips membelengku leher serta lengan, dan ia belum sadarkan diri. Tidak ada keluarga yang menunggui, dan aku bisa mengerti kenapa.
Anak itu ... telah menjadi yatim piatu sejak lama, orangtuanya terlibat dalam salah satu kecelakaan pesawat. Ia tinggal bersama nenek dan kakeknya, dengan uang warisan yang lebih dari cukup untuk biaya sekolah. Ghea hampir selalu sendirian sehingga kami sering menginap di rumahnya. Kata Ghea, itu adalah satu-satunya waktu dimana rumahnya menjadi berisik, menjadi hidup. Neneknya mungkin bahkan belum menerima kabar ini, Ghea adalah satu-satunya manusia di rumah itu yang tahu cara menggunakan alat komunikasi modern.
Aku mendudukkan diri di samping Ghea. Wajahnya pucat sekarang. Sisa-sisa darah sepertinya telah dibersihkan namun aku dapat melihat bayangannya. Aku dapat membayangkan apa yang menimpanya.Gips di leher dan lengan ... mungkin Ghea telah terjepit, dengan keadaan mobil yang berguling terbalik, jelas kepalanya telah berada di bawah saat mereka mengeluarkannya. Dan sekali lagi, aku menggigil mengingat kejadian senja tadi. Hanya beberapa jam yang lalu namun begitu banyak yang berubah. Begitu banyak yang hilang di udara.
Kira-kira setengah jam kemudian aku melihat pergerakan jarinya, lalu mata yang perlahan membuka. Aku nyaris melompat dari tempat dudukku, ingin berteriak girang, ingin memanggil Ghea, ingin memanggil dokter. Ghea sadar. Ghea sadar! Tetapi semua yang kulakukan adalah diam di tempat, meraih tangannya dan mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru membuka mata.
”Take your time,” bisikku. Dan seakan mendengarkan, matanya terus terpejam.
Lalu, setelah banyak menit yang berlalu dan Ghea telah membiasakan diri dengan keadaan ruangan, aku membantunya duduk dengan hati-hati. Kuraih bantal dan meletakkannya di belakang punggung Ghea agar cewek itu dapat bersandar di kepala ranjang.
Ghea tersenyum lemah menatapku. Eskpresinya yang semula kosong perlahan-lahan memudar. Tanpa diberi tahu, aku tahu bahwa dia sedang diingatkan tentang kilasan-kilasan kecelakaan tersebut. Dan bohong jika ia tidak terguncang. Sementara aku hanya dapat duduk di sana, menggenggam tangannya dengan harap itu dapat menguatkan kami berdua.
Kemudian, setelah kediaman yang cukup lama, pertanyaan yang paling tidak ingin kudengar meluncur dari mulutnya. Ghea membuka bibirnya yang pucat, yang semula terkatup rapat. Kepadaku, ia bertanya dengan suara pelan. “Gimana ... kabar yang lain?”
Parah. Amat parah! Aku ingin meneriakkan kalimat itu. Rasanya mau gila mengingat bagaimana semua yang terjadi dengan begitu cepat justru berputar lambat di memoriku, menunjukkan setiap detail, tiap tetes darah, tiap keping kaca yang pecah, tiap detik menyiksa ketika aku di sana menghadapi Ulfi di detik-detik terakhirnya. Rasanya, kenangan-kenangan yang tidak berhenti berputar di otak ini ingin membunuhku dengan perlahan.
Aku mengeratkan genggaman tangan pada celana jinsku- bukan punyaku, punya Ghea yang ia pinjamkan. Aku ingin menceritakan semuanya, tetapi seluruh kalimat tercekat di tenggorokan.
“Masih dirawat.” Hanya itu kalimat yang berhasil kudorong keluar.
Sementara Ghea menatapku, masih cemas. “Semuanya baik-baik aja kan?”
Enggak. Semuanya enggak baik-baik aja. Laura sekarat, Ulfi pergi, dan aku nggak tahu keadaan Kama. Aku ingin menangis sekarang.
Tetapi yang kulakukan adalah mengulas senyum tipis dan mengangguk. “Ya.”
***
Kemudian, kami tertidur. Efek obat dan mungkin tubuh yang terasa lemah. Atau sebenarnya, hanya Ghea yang tertidur. Aku berbaring di ranjang kosong di sisinya, menatap langit-langit. Tidak ada yang bisa kulakukan.
Seorang polisi datang beberapa saat yang lalu. Mereka mengajukan padaku beberapa pertanyaan, tentang kronologi kejadian atau apakah aku mengingat mobil yang menghantam mobil kami. Untuk yang kedua, aku bahkan tidak tahu mobil apa. Untuk yang pertama, aku hanya menceritakan sejauh yang kuingat.
Aku mulai ragu apakah yang kuceritakan semuanya kebenaran atau sebagiannya adalah halusinasiku saja. Mereka terlalu buram tetapi terlalu nyata. Setiap aku mengingatnya, rasanya seperti dilempar kembali pada kejadian itu hanya untuk mengulang rasa sakit. Aku membencinya.
Mereka juga membawakan tasku dan Ghea. Alat-alat make up yang disimpan cewek itu telah hancur dan ponselnya retak, tetapi sisanya aman. Ada nsedikit noda darah tetapi aman. Aku turut menyalakan ponselku yang juga retak, masih terpasang kabel earphone yang tali-talinya telah putus. Ponsel itu masih berfungsi.
Ponsel itu sekarang kutaruh di atas meja tanpa tersentuh lagi. Benda itu terus bergetar dengan banyaknya pesan yang masuk. Aku tidak tergerak sedikit pun untuk memeriksa. Meskipun biasanya aku selalu memeriksa. Ulfi ... juga. Ulfi tidak bisa berpisah dengan ponsel. Dia punya banyak foto di Instagram dan pengikutnya sudah hampir dua ribu. Sekarang dua ribu pengikut itu akan tahu bahwa tidak akan ada lagi unggahan terbaru dari si pemilik akun. Dan di anatara dua ribu orang itu, apakah ada yang akan cemas? Apakah ada yang akan bertanya-tanya kenapa Ulfi tidak pernah lagi muncul?
Pikiran-pikiran seperti itu memenuhi kepalaku. Hingga sakit.
Aku ingin membuka laman Instagram dan menengok halaman profil Ulfi. Tapi aku takut menangis. Aku ingin menggoyangkan tubuhku agar sadar bahwa semua ini hanya mimpi. Semua ini tidak nyata. Tidak terasa nyata. Aku tidak ingin kenyataan yang seperti ini.
Lalu aku tertidur. Begitu saja.
Aku tahu kebohongan yang semula kusampaikan tidak dapat kupertahankan lama. Karena kemudian, aku terbangun oleh suara tangisan Ghea. Aku mengerjap-ngerjapkan mata beberapa kali, memandangi, memanggil namanya.
“Ghe? Ghea?”
Ia tidak menyahut. Hanya menangis. Di tangannya, adalah ponselnya yang retak itu.
Ponselku di atas lemari masih bergetar, jadi aku menyambarnya. Ada banyak sekali pemberitahuan yang masuk. Tetapi jariku mengusap semuanya agar bergeser. Hingga, mataku menemukan banyak pesan dari grup obrolan kelas. Kali ini aku menekannya.
Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudari kita Ulfi Khalifa tadi sore, sekitar jam 6.30. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.
Ada banyak ucapan belasungkawa setelahnya. Kebanyakan hanya berupa stiker doa atau tulisan copy paste. Sebagian besar mempertanyakan kenapa, bagaimana, dan kekagetan yang tidak dapat dibendung. Membacanya, aku tidak lagi merasakan apapun selain gamang, seolah seluruh emosiku telah tersedot habis.
Aku hanya menatap Ghea di sisiku, masih terisak-isak. Ia tengah memanggil-manggil nama Ulfi.
“Lo jangan pergi duluan Pi... nanti yang nemenin gue saat nggak ada orang di rumah siapa? Nanti yang nyontek sama gue siapa? Nanti yang abisin timun kalau gue makan nasi goreng siapa?” Jeda sebentar. Ghea mengusap aimatanya dengan ujung baju, tetapi isakan dan banjir airmatanya tidak dapat dihentikan. “Yang bikin kita ketawa nantinya siapa, Pi? Itu jugas elo... Jangan pergi, Pi... Di sana gelap. Lo nggak suka gelap. Balik sini sama gue... balik Pi....”
Detik itu juga, airmataku merebak seketika.


 rainaya
rainaya